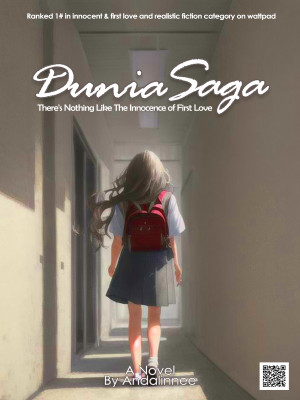Awalnya aku ragu memberikan ponselku pada orang asing, apalagi dia cowok. Memang sih kelihatannya seumuran denganku. Rambutnya yang cukup gondrong tapi rapi membuatku menduga pasti dia masih sekolah. Wajahnya mengingatkanku pada artis remaja yang aku lupa namanya. Tubuhnya kurus dan tinggi menjulang sama seperti Reza. Aku hanya setinggi bahunya. Irisnya berwarna cokelat terang. Berbeda dengan milikku yang segelap malam.
"Oh, nama aku Ale," cowok itu menjulurkan tangannya. "Maaf kalau bikin takut."
"Winda," jawabku bergumam. Akhirnya aku memberikan ponselku. Ale mengambilnya dan memasukan nomor teleponnya.
Ale menunggu nada sambung beberapa saat, lalu mengembalikannya padaku. "Yap, hapeku ilang. Udah nggak tersambung,"
"Kok bisa?" tanyaku.
"Kayaknya jatuh di dalam teater atau mungkin jatuh di jalan. Tadi aku dari toilet, begitu keluar, temen-temenku pada nggak ada. Begitu aku mau hubungi, ternyata hapeku juga nggak ada." ujar Ale sambil menghela nafas.
Saat aku mau bicara, Ale berkata lagi, "Ya udah. Makasih banyak ya, Winda. Maaf jadi ngerepotin." ujarnya lalu bergegas pergi.
Belum sempat aku memasukan ponselku, Reza setengah berlari ke arahku. "Maaf lama. Kayaknya abis ada teater yang bubar jadi toiletnya penuh,"
Aku mengangguk sebagai respon. "Yuk masuk. Teaternya udah dibuka."
"Beli popcorn dulu dong," ajak Reza yang langsung berjalan ke konter makanan.
***
Menjelang magrib, kami sampai di rumah. Reza memarkir mobil ke dalam garasi lalu mengikutiku yang lebih dahulu keluar. Ia membawa beberapa kantong belanjaan berisi donat dan roti yang dibeli di mall untuk ibu, belanjaan sepatu futsalnya, dan ada juga satu kantong dari toko buku milikku.
"Waduh, jangan-jangan uang katering dipakai belanja ya?" canda Ibu ketika melihat kami datang dengan banyak kantong belanja.
"Iya, nih, Bu." Reza mencium tangan ibu. "Kata Winda nggak apa-apa pakai aja uangnya."
Aku menyikut Reza, "Ih! Malah jual nama orang,"
Reza lalu memberikan satu kantong untuk Ibu. Setelah itu aku dan Reza menyandarkan diri di ruang tengah, meluruskan kaki yang sudah pegal karena berjalan di mall.
"Kalian di kamar Winda aja, ya? Bu RT mau ke sini sama ibu-ibu yang lain. Katanya mau diskusiin buat 17 Agustusan sambil mau tanya-tanya konsumsi."
"Di rumah aku aja, yuk, Win." ajak Reza sambil merapikan barang belanjaannya.
Sebelum menutur Reza, aku melihat ke arah Ibu. "Aku di rumah Reza ya, Bu."
"Jangan pulang malem-malem ya!" perintah Ibu.
Reza menyahut. "Iya, Bu. Paling pulangnya pagi." ujarnya terkekeh.
Ibu langsung memutar matanya ke arah kami sambil ikut tertawa kecil. Meski kadang ucapan Reza suka asal-asalan, Ibu tahu kalau itu hanya sekedar bercanda. Lagipula aku tidak akan berlama-lama juga di rumah Reza. Rumah itu terlalu besar untukku.
***
Reza memutar kunci di dalam lubang dan membuka pintu. Rumah Reza yang besar dan kosong langsung membuat nafasku tertahan. Ada perasaan takut dan waswas begitu masuk ke dalam rumahnya. Pernah aku bertanya apa dia tidak takut sering sendirian di rumah dua lantai dengan tiga kamar itu? Tapi dia malah menakutiku dengan rumahku yang katanya 'banyak penghuni dan pernah kosong'. Maksudku, aku saja langsung pergi ke rumah Reza kalau ayah dan ibu harus pergi berdua, misalnya untuk kondangan. Padahal rumahku hanya rumah kecil dengan ruang tamu, dua kamar, satu ruang tengah, dapur, dan kamar mandi.
"Makan, nggak?" Reza menawari. "Indomie enak nih,"
Aku mendecak. "Ya ampun kita kan baru makan."
"Kali aja kamu lapar lagi," ujar Reza. "Terus mau ngapain nih kita? Nonton? Main monopoli?"
Aku menguap sambil merenggangkan badanku. "Aku capek," ujarku sambil menumpuk bantal di sofa ruang tengah. "Nanti bangunin aku jam delapan ya,"
Reza mendengus, "Dih ke rumah orang malah nebeng tidur doang!"
"Ngantuk, Za." ujarku sambil menguap.
"Ya udah tidurnya di kamar aku aja sana." Reza menunjuk letak kamar dengan dagunya.
Aku berpikir sejenak. Membayangkan berada sendirian di kamar Reza yang luas dan berada di lantai dua membuatku merinding. "Temenin ya?"
"Tidur bareng?" Reza menyeringai, tapi dengan cepat aku lempar bantal ke arahnya. Kadang otaknya perlu dibersihkan.
"Ih, maksudnya kamu main PS atau apa gitu di kamar, aku tidur." cicitku. Aku tahu Reza tidak akan pernah punya pikiran untuk macam-macam denganku. Lagipula aku pernah ikutan Karate meski hanya sampai sabuk hijau. Jadi aku masih bisa membela diri.
"Ya udah, iya." ujar Reza. Kami naik ke lantai atas. Begitu sampai di kamar Reza, aku segera menjatuhkan diri ke kasur besar dan empuknya sementara Reza menyalakan televisi dan PS.
***
Rasanya aku belum lama terlelap saat aku mendengar suara ribut dan teriakan. Seketika aku membuka mata dan melihat Beni dan Mansyur sedang bermain playstation dan Reza sedang duduk di ujung kasur.
"Jam berapa ini?" aku meraba-raba sekitaranku untuk mencari ponsel. Waktu sudah menunjukkan pukul delapan malam.
"Za, kan aku bilang bangunin jam delapan!" protesku. Aku harus membantu Ibu menyiapkan pesanan untuk besok.
Masih dengan mata yang tertuju pada layar televisi, Reza menyahut. "Abis kamu tidurnya nyenyak banget. Aku nggak tega banguninnya."
"Bohong," sela Beni. "Dia mah pengen kamu nginep di sini biar bisa tidur berdua." ujarnya dengan tatapan tetap pada layar, sama seperti Reza.
Reza melempar botol minuman ke arah Beni dan menggerutu. Tidak memperdulikan mereka, aku merapikan rambut dan pamitan.
"Jangan main terus, kerjain PR!"
"Matematika? Udah dong," ujar Mansyur dengan bangga. Reza menimpali dengan memaksa untuk pinjam bukunya.
Beni merengut. "Malam Minggu atuh, Win. Masa belajar terus? Uyuhan bisa main PS juga. Daripada di rumah disuruh terus sama Si Mamah."
Aku tertawa kecil mendengar curhatan Beni. Kedua orangtua Beni memiliki kedai pecel lele di dekat rumahnya. Kadang Beni disuruh membantu, apalagi kalau akhir pekan kedai akan lebih ramai dari biasanya.
"Dika ke mana?" tanyaku mengalihkan pembicaraan. Kalau membahas curhatan Beni biasanya tidak ada habisnya.
"Dia mah pacaran." Reza yang menjawab.
"Tuh kan gaya batur mah pacaran. Lah aku di sini sama Reza dan Masnyur mulu." gerutu Beni.
Mansyur mencibir. "Ya makanya cari pacar atuh, Ben! Jangan ngurusin Si Mojang mulu!"
Si Mojang adalah motor bebek kesayangan Beni pemberian turun-temurun dari kakek dan ayahnya. Baru hendak aku menimpali Mansyur, tiba-tiba ponselku bergetar. Aku melihat layar dan ada panggilan masuk dari telepon yang aku tidak kenal. Siapa ini?
"Halo?"
"Hai, Winda ya?"
Aku menjawab 'iya' dengan suara pelan dan kebingungan karena aku tidak mengenal suaranya.
"Aku Ale," aku diam sejenak lalu mengingatnya. Tidak lama kemudian Ale menimpali. "Yang tadi kamu tolong di bioskop? Ternyata handphone-ku nggak ilang,"
***


 nesitara
nesitara