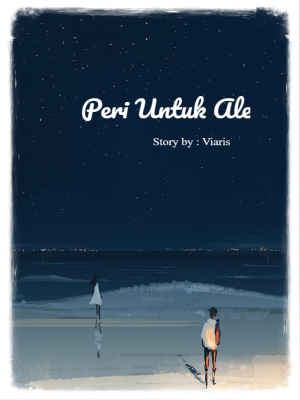Sudah sejak awal ekspedisi ini dimulai aku belum sempat potong rambut, kini panjangnya sudah melebihi batas telinga.
Eoni memintaku untuk potong rambut dan ia bersedia menemaniku, tentu ini kesempatan yang tidak akan aku lewatkan.
“Nanti sore saja, ya? Habis pulang dari lapangan.” Kata Eoni saat makan siang.
Aku mengangguk mantap.
Sudah dua hari ini Pak Jayadi dan Mas Aji tidak ikut ke lapangan, Pak Wicak juga. Kabarnya mereka sedang meninjau situs di kota lain. Tapi entahlah, yang jelas mereka tidak hadir.
Entah dari mana asal-usulnya, kabar mengenai penjarahan mulai menguap memenuhi langit-langit desa, setiap gang dan beranda rumah orang-orang membicarakan topik ini.
Ada yang bilang kalau isi harta di dalam candi itu adalah perhiasan kuno yang memenuhi lubang sumur dangkal yang aku pernah terjerembab masuk ke dalamnya. Pendapat lain juga menyebutkan kalau hartanya tidak banyak, hanya emas, koin dan arca kuno, ada kabar lain yang bilang kalau hartanya hanya satu yaitu sebuah permata merah delima besar yang harganya bisa untuk membeli tujuh pabrik lengkap dengan karyawannya.
Berita-berita semacam itu lalu lalang di pendengaranku, dan semakin membuatku tak bisa tidur. Pihak kepolisian juga kabarnya mulai turun tangan dengan kasus ini.
Jika desas-desus mengenai sebanyak apa harta yang dijarah itu benar, tentu ini bukan kasus yang main-main. Termasuk kejahatan besar, tentu saja.
Dan jika kabar ini tersebar lebih luas lagi, bisa jadi malapetaka akan datang, entah apa yang akan oknum-oknum lakukan pada benda peninggalan purbakala baik yang sudah ditemukan maupun yang belum.
Jujur aku juga dulu pernah ditawari untuk pekerjaan buruk itu, menjadi sejarawan yang memfasilitasi para gembong penjarah besar tentang situs-situs yang kemungkinan masih asli dan belum banyak diketahui, tapi aku sudah pasti menolaknya. Aku ingin punya penghasilan yang ‘enak’ dari pekerjaan yang pasti-pasti saja.
Seiring piring-piring makanan mulai kosong, aku dan Eoni meminta diri untuk pulang paling dulu. Ia akan mengantarku potong rambut. Aku meminjam motor Pak Kadus karena tempat potong rambut yang paling dekat jaraknya 4 kilometer dari sini, ada di desa sebelah.
Aku senang bukan main karena hal ini. Setidaknya akan ada banyak waktu berdua untuk aku dan Eoni.
Namun, semesta sangat sirik dan seolah tidak ingin membiarkan rasa bahagia tinggal di dadaku lama-lama. Tiba-tiba dan entah apa penyebabnya, sudah berjalan lumayan jauh, motor supra tua milik Pak Kadus yang kami kendarai mogok, mesinnya berdecit seperti suara tikus terjepit lubang jebakan. Aku sebentar panik dan memilik menepi di pinggiran.
Bukan kesalahan si motor juga, sepertinya beberapa bulan di sini tubuhku memang semakin bertambah subur saja. Belum lagi aku membawa seorang gadis di bangku belakang. Sudah sejak tarikan gas yang pertama knalpot motor memamg sudah agak sedikit terbatuk-batuk, jalan enggan mati tak mau.
“Kenapa?” Tanya Eoni dari bangku belakang.
Mogok, supra tua ini memang tidak mengenal keadaan sekali, mana hari sudah sore, tak banyak kendaraan yang simpang siur. Kuminta Eoni turun, dan kutarik standar dua untuk menyangga si supra yang rewel ini.
Ada sekitar satu jam lebih aku mengotak-atik mesin si supra, nihil tak ada kemajuan, nampaknya memang ia sedang tidak mau bekerja sama.
Eoni masih terduduk di pinggir jalan, setengah meter di sampingku, terlihat tenang memperhatikan polahku yang kebingungan dengan mesin tua yang ogah-ogahan untuk menyala.
“Apa tempatnya masih jauh?” Tanya Eoni lagi.
“Mungkin satu kilometer lagi. Tak terlalu jauh, kau tahu pasar yang biasa dibuat belanja Bu Dhena dan Bu Nada?”
Eoni mengangguk dibarengi dengan topinya yang bergerak ke atas ke bawah.
“Nah mungkin seratus meter dari pasar.” Jelasku.
Ia mengangguk lagi, paham, “Bagaimana kalau kita jalan saja?”
Itu ideku tadi, namun tentu saja aku tidak tega, mana mungkin aku mengajak jalan kaki seorang gadis di tanah asing yang konturnya naik turun bukit semacam ini.
Belum lagi membayangkan hari yang sudah semakin sore, kemudian gelap dan minim penerangan. Ah itu akan jadi masalah baru lagi.
“Lalu bagaimana dengan motor ini?” Aku tentu tidak bisa membiarkan motor yang bukan milikku ini tergeletak begitu saja di pinggir jalan seperti benda tidak bertuan.
“Titipkan saja pada bapak petani yang sedang memanen sayur di sana itu, kurasa ia tak akan keberatan.” Eoni menunjuk beberapa orang yang nampaknya sedang sibuk dengan karung dan hasil panen, kol dan wortel terlihat tergeletak segar di sana-sini.
Di kebun itu juga ada remaja tanggung yang usianya tentu saja lebih muda dariku. Mereka juga sedang bantu-bantu mengantongi hasil panen.
Aku setuju dengan. Kami pun berjalan menghampiri orang yang Eoni maksud, namun belum tepat kami sampai ke sana.
Aku melihat ada dua orang yang cukup familiar tengah menuju ke arah yang sama dengan kami, tapi berasal dari tempat yang berlawanan, orang itu adalah Pak Jayadi dan Mas Aji. Mereka sudah lebih dulu sampai di tempat petani yang akan juga kami tuju.
Aku dan Eoni saling menatap satu sama lain, isi kepala kami waktu itu sama “Apa yang mereka lakukan di sana dan dengan siapa ia berbicara?”
Mereka terlihat akrab dan sepertinya ini bukan perjumpaan yang pertama saja. Entah bagaimana melihat Pak Jayadi dan Mas Aji membuat langkah kami berdua terhenti.
“Bagaimana?” Kata Eoni, mungkin maksudnya apakah kami jadi menitip kendaraan atau memutuskan untuk menuntunnya satu kilometer lagi.
Aku diam cukup lama, kepalaku sekarang tak hanya memikirkan tentang si supra saja, melainkan dugaan-dugaan lain yang bersangkutan dengan obrolan antara aku, Guna dan Sabang semalam.
Walaupun aku agak sensi dengan Sabang, namun untuk perkara penelitian aku adalah kawan yang loyal baginya.


 littlemagic
littlemagic