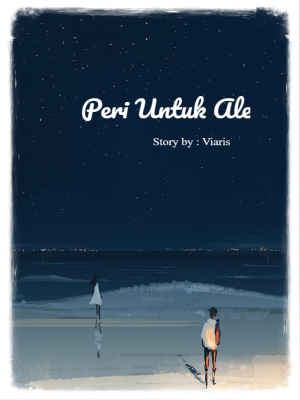Tiang jalan berkarat dan berlumut di sisi-sisi yang berbeda, induk dan anak laba-laba juga terlihat menyemai penghidupan di sudut-sudut yang jarang dijangkau tangan manusia.
Tidak hanya di sana, halte bus juga ramai dengan jaring-jaring tipis yang saling mengait dan menyilang satu sama lain, sepertinya petugas kebersihan terlalu baik hati untuk menggusur rumah mereka.
Ada sedikit rasa khawatir, sebab bus yang menuju jalan besar tempat yang aku tuju sudah mulai langka. Jika tidak dapat bus, tentu tidak lucu jika aku harus bermalam di kota kecil yang dingin ini, aku tidak kenal siapa-siapa kecuali diriku sendiri.
Namun tidak semua khawatir melaksanakan tugasnya, setelah setengah jam menunggu, ada seorang tukang ojek yang nampaknya mengenalku.
“Pak Udi?” Panggilnya. Tentu saja aku tak menoleh, tapi tukang ojek itu masih saja berteriak ke arahku dua kali lagi. Aku masih belum bergeming, aku bukan orang yang ia maksud meski tak ada orang lain lagi yang berada di dekatku.
Tukang ojek itu kemudian mematikan mesin motornya dan menghampiriku, “Bapak mau pulang bareng saya atau masih menunggu orang lain? Jam segini bus sudah jarang yang lewat, adanya nanti jam 7 malam, bus terakhir miliknya Pak Mukidi orang Banyuanget.”
Saat aku menoleh tukang ojek yang sudah paruh baya itu terkejut dan meminta maaf berkali-kali. Ia tentu salah orang.
“Tidak apa-apa, Pak. Salah orang sudah biasa.” Balasku mencoba ramah.
“Saya kira mas ini orang lain, mirip sekali sama teman saya yang tinggal di Sarang Panjang atas, hanya saja mas masih jauh lebih muda.” Tukang ojek menjelaskan.
“Nama bapak siapa? Tinggalnya di mana? Perkenalkan saya Nadif.” Aku mencoba berbasa-basi.
“Panggil saja Pak Onjen, Mas. Rumah saya di Sarang Panjang bawah.”
“Kebetulan sekali saya sedang tinggal di Desa Sarang Panjang juga, Pak. Cuma saya tidak paham itu Sarang Panjang bawah atau Sarang Panjang atas.” Jawabku sambil tertawa ringan untuk mencairkan suasana.
“Owalah begitu, Sarang Panjang memang luas, Mas. Jadi kadang tidak hafal sama tetangga sendiri.”
Aku dan Pak Onjen mengobrol cukup lama, selidik punya selidik ia ternyata adalah kerabat dari Bonu si pemuda desa. Ia juga ikut membantu tim saat ekskavasi pengangkatan batu di hari-hari awal penelitian.
“Jadi Mas Nadif ini sedang menunggu orang atau bagaimana?”
“Saya sedang menunggu angkutan, Pak. Mau pulang.”
“Kalo begitu, sekalian sama saya saja. Saya juga mau pulang. Angkutan dan bus sudah jarang ada kalo jam segini, Mas.”
Tentu saja tidak mungkin aku tolak tawaran tersebut.
Dari atas kendaraan bermotor keluaran tahun 1900-an dengan gas dan asap knalpot yang sudah sangat terbatuk-batuk, lembah dan bukit desa kembali menyapaku, memberi ucapan selamat datang setelah pagi tadi aku tinggal pergi.
Di tengah perjalanan yang penuh dengan guncangan ini, perlahan pikiranku menerawang angan-angan sambil memandangi barisan pepohonan yang samar-samar terhalang awan tipis di kejauhan, kiranya adakah tempat di belahan bumi sana yang bisa menjadi muara atas segala kesal, marah dan bingungku agar segera reda.
Rasa-rasanya dari dulu aku selalu menanganinya sendiri. Entah mengapa sepanjang jalan ini aku terus mengingat kata-kata Maharani saat berangkat tadi, Sejauh apa hubungan Sabang dengan Eoni?
Mungkin maksud Eoni tentang “Memberikan harapan yang sebenarnya tidak ada..” itu berlaku juga bagiku.
Bisa-bisanya aku terjebak dalam hal semacam ini. Sepanjang jalan aku merasa ditertawakan pohon dan diberi predikat sebagai ‘manusia yang tidak bisa belajar dari kesalahan’ karena terus menerus diperbudak oleh perasaan.
Dering ponsel mengakhiri angan dan lamunanku yang semakin lama nampaknya semakin kacau. Pak Bah adalah sebab dari deringnya. Saat panggilan aku angkat, tak ada suara di ujung sana yang menyambutku. Batinku mengumpat, sinyal di sini memang jadi masalah tersendiri.
Aku sempat meminta Pak Onjen untuk berhenti sebentar, aku butuh waktu untuk menggoyang-goyangkan ponsel, barangkali ada sinyal yang menyangkut. Cara ini memang sangat tidak ilmiah, tapi ini adalah satu-satunya cara tercepat yang bisa aku coba, banyak orang juga melakukannya.
Dalam jangka waktu yang cukup singkat mucul pesan yang sama dari tiga orang yang berbeda yaitu Pak Bah, Pak Leo dan Mr. Arief. Sepertinya mereka tahu apa yang tengah menimpaku, sebab tidak kali ini saja aku berurusan dengan satelit.
Pesan singkat itu tertulis, “Nak, jika sempat, carilah sinyal dan segera hubungi aku. Ada kabar penting, ini menyangkut Pram.”
Detak jantungku kembali berpacu, sementara diagram batang penunjuk kekuatan sinyal pada ponsel masih hidup enggan mati tak mau, kedip-kedip seperti lampu kuning yang sudah lewat dari jam 12 malam.
Aku segera meminta Pak Onjen untuk kembali meneruskan perjalanan.
Tak ada satu rekan pun yang tahu kapan aku kembali karena tujuanku kini hanya satu, bukan rumah, bukan lubang ekskavasi, bukan juga batu besar di halaman belakang tempat di mana aku dan Eoni biasa menghabiskan pagi.
Sejujurnya kini aku sedang tidak terlalu peduli dengannya. Tujuanku kali ini adalah bukit yang dapat membuatku merasa dekat dengan orang-orang yang jauh.
Aku diturunkan tepat di kaki bukit Njahe, ada hal yang lebih mendesak untukku lakukan. Namun apa ada, ketika aku sampai di puncak dan diagram batang pada sinyal ponselku mulai membaik, pesan dari operator lebih dulu menyambutku. Ia bilang pulsa dan kuota internetku habis.
Sepertinya takdir belum mengizinkanku untuk dapat kabar penting dari tiga orang penting yang tadi menghubungiku.
Namun aku sudah terlanjur sampai di sana, tempat terbaik untuk memandang senja. Meskipun sendiri, skenario senja tidak akan jadi berbeda, Matahari akan tetap tenggelam dengan cahaya keemasan yang menghambur kemana-mana.


 littlemagic
littlemagic