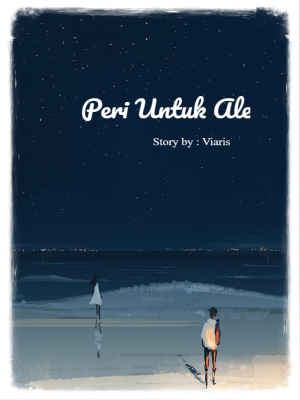Akhir pekan adalah dua kata melegakan dan cocok sekali untuk melegakan kepala. Sebenarnya pagi ini aku berniat untuk lintas alam, sekedar jalan-jalan melihat kebun, ladang dan hutan yang ada di lereng Gunung Dahyang. Guna sudah mengiyakan ajakanku, ia memintaku untuk mengajak serta si Gembi dan kawan perempuan.
Belakangan aku melihat ada yang berbeda dari tingkahnya. Namun rencana itu sedikit terganggu karena Pak Wicak memintaku mengantar Maharani ke kota terdekat, ia harus pulang selama seminggu untuk laporan kampus.
Aku sedikit beralasan di sini. Karena enggan, aku jadi mengira kepulangan Maharani ada hubungannya dengan masalah pada Sabang.
Aih aku tak mau betul ikut campur dengan masalah perasaan mereka. Tapi Pak Wicak memaksa, mungkin karena Dosen yang merekomendasikan Maharani adalah kawan dekatnya, dan aku-lah yang jadi tumbal.
“Sabang, kemari!” Kerah belakangnya kutarik, nampaknya ia mau keluar rumah.
“Oi broo. Ada apa?”
“Kau saja yang mengantar Maharani. Aku mau ikut lintas alam.” Desakku bisik-bisik.
“Ah, tidak. Kau saja, Dif. Kau kan yang disuruh Pak Wicak, bukan aku.”
“Tapi masalah Maharani kan denganmu, bukan aku.”
Sabang terkejut mendengar perkataanku.
Aku juga sama terkejutnya mendengar perkataan sendiri, tak kusangka kalimat itu lah yang keluar dari mulut bodohku ini. Tentu saja Sabang tidak mengira jika aku tahu apa yang sesungguhnya terjadi antara mereka berdua.
“Masalah apa?” tanyanya sedikit kikuk.
“Ah, tidak, tidak. Tapi pokoknya kau saja ya, Bang.” Aku memohon seperti anak kucing yang meminta makan.
Di luar Guna, El dan beberapa teman dari pemuda desa telah bersiap dengan pakaian santai yang lengkap.
“Hey, kalian! Jadi ikut?” Teriak El dari depan beranda rumah.
Sabang cepat-cepat mengangguk, aku juga ingin begitu tapi ada hal lain yang tidak bisa membuat kepalaku bergerak naik turun seperti yang Sabang lakukan.
Begitu tanganku terlepas, sesegera mungkin Sabang melepaskan diri dariku. Ia melambaikan tangan dengan tertawa, sementara aku terduduk lesu menatap datar mereka semua berangkat. Ide lintas alam ini aku yang cetuskan tapi aku sendiri yang tidak ikut. Alhasil aku masukkan kembali air minum dan sepatu lapanganku.
Di basecamp putri, Maharani sudah menungguku. Rasanya malas sekali melihatnya tapi semua itu cukup bisa dimaafkan karena paras Maharani yang memang enak dipandang.
Sebenarnya aku sedikit setuju dengan perkataan Eoni tadi yang menyinggung dugaannya tentang Maharani yang menyukaiku, awalnya kau sempat mengira hal yang sama.
Bukan maksudku terlalu percaya diri atau bagaimana, tapi gadis di sampingku ini memang sedikit menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Ia benar-benar orang yang penuh perhatian, pintar dan serba ingin tahu.
Tapi nyatanya memang tidak semua ‘tanda’ berarti sama dengan asumsi dan dugaan rasa, bisa jadi tanda itu memang tidak ada artinya sama sekali.
Hampir separuh perjalanan kami habiskan untuk diam. Aku bingung bagaimana cara untuk membuka kata, sementara Maharani sama sekali tak mau melihatku, pandangannya tertuju pada sesuatu di luar jendela bus yang entah apa sebenarnya.
“Mau minum?” sekedar basa-basi, aku berterima kasih sekali dengan botol aqua di depanku, setidaknya jadi ada bahan untukku berbicara.
Ia menggeleng, pandangannya tak lepas dari luar jendela.
Bus kami melaju cukup lambat menuruni perbukitan, namun angin yang masuk sudah cukup membuat gaduh suasana di dalamnya. Maharani memutuskan untuk membuka jendela lebar-lebar, membiarkan partikel angin menyapu wajah kami.
“Maafkan aku karena harus merepotkanmu untuk hal seperti ini, Bang.” Untuk pertama kalinya mulut Maharani terbuka dan bersuara setelah puluhan menit berlalu.
“Aku tak paham maksudmu. Aku tidak merasa direpotkan atas apapun.” Tegasku.
“Aku sudah bilang bisa pulang sendiri, tapi Pak Wicak bersikeras melarangnya. Aku pun sudah meminta Kak Gembi dan Kak Eoni untuk menemaniku, namun lagi-lagi Pak Wicak tidak setuju. Entah apa alasannya ia jadi menyuruhmu.”
“Mungkin karena yang menemanimu harus laki-laki. Dari desa ke kota cukup jauh dan jalannya pun sepi. Kau pasti paham.” Aku menjawab sekenanya namun tetap berhati-hati, tak mau membuat suasana hatinya semakin buruk.
Entah perasaan bagaimana yang kini tengah merundung gadis di sebelahku ini. Beberapa kali aku sempat melihat matanya bercaka-kaca namun tidak ada satu pun yang sampai jatuh menetes.
“Bang, aku ingin bertanya sesuatu.” Ucapnya tiba-tiba.
Aku menoleh, raut wajahku berkata silahkan.
“Sejauh apa hubungan Kak Eoni dengan Abang Sabang?” Celetuknya yang membuat mata dan telingaku terkejut bukan main.
Bagaimana bisa gadis ini mengira hal semacam itu? Memang Eoni dan Sabang dekat, tapi kurasa kedekatan mereka wajar, bahkan tidak lebih dari dekatnya aku dengan Eoni.
Aku sempat berdeham beberapa kali sebelum menjawab. Terus terang aku masih saja terkejut seolah pertanyaa tadi terus mendengung di kepalaku, “Aku rasa hubungan mereka tidak lebih dari sekedar teman dan rekan kerja.”
Entah mengapa aku jadi merasa tidak rela karena telah membela Sabang di hari-hari yang lalu, namun batinku segera berbalik, pekerjaan dan perasaan adalah dua hal yang berbeda, aku tak boleh menilai rekan kerjaku secara subjektif semacam itu.
“Semoga saja, aku juga mengharap hubungan mereka tidak lebih jauh dari itu. Apa menurutmu mereka cocok?”
Kepalaku reflek menggeleng berkali-kali, Oi! Bagaimana bisa kau mengatakan mereka berdua cocok! Posisiku saja menjadi terancam setelah mendengarnya.
Namun aku cepat-cepat mengendalikan diri, seperti biasa, seperti rata-rata air, aku tak mau Maharani menangkap kekhawatiranku karena mendengar perkataannya, “Maharani, ada baiknya kau pastikan dulu asumsimu itu dengan orang yang bersangkutan secara langsung, tidak akan terlalu banyak membuat perubahan jika kau bertanya denganku sebab aku sendiri pun tidak tahu. Namun jika boleh saran, sebagai orang awam, aku merasa tidak berhak menilai orang per orang apakah mereka cocok atau tidak, karena sejatinya aku hanya menilai mereka dari luar. Tak pernah aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Bahkan saat aku merasa dekat dan itu bisa dijadikan parameter di mana kita bisa menjadi juri atas sebuah hubungan, aku tetap saja merasa tidak berhak karena kedekatan kami hanya sebatas rekan kerja, bukan saudara atau keluarga. Bahkan terkadang, beberapa saudara dan kerabat keluarga pun tidak sedekat itu untuk jadi bebas menilai.”
Maharani terlihat mengerti dan paham dengan apa yang aku katakan. Sementara aku malah menjadi banyak berfikir karena hal-hal yang aku dengar dan aku ucapkan sendiri.
Seribu diam kembali menyerang kami. Ketika sampai di kota, tak banyak juga yang kami bicarakan, ia segera naik bus lagi untuk menuju tujuan selanjutnya. Dan aku berbalik, kembali ke desa.
Sebelum pulang aku sempatkan diri mampir ke toko untuk membeli perlengkapan dan berapa makanan cemilan untuk kawan-kawan, salah satu cara untuk mengobati lidah yang rindu micin. Kota ini tak terlalu besar, tapi cukup bisa dibilang maju dari pada desa tempatku tinggal selama projek penelitian.
Setidaknya ada dua minimarket dan sentra-kota yang padat dengan lalu lalang manusia. Di sini udaranya juga masih dingin, meskipun matahari juga terasa menyengatnya. Suasana semacam ini jadi meningatkanku pada kota asalku yaitu Nara.
Merasa puas berputar-putar, aku kembali ke halte menunggu kendaraan yang melewati tempat terdekat dengan desa tempatku kembali.
Sinyal di sini cukup bagus, sambil menunggu, aku jelajahi media sosial yang mungkin sudah lumutan karena berminggu-minggu tak dikunjungi pemiliknya. Terus terang, selalu ada saja berita yang membuat pusing ketika membuka medsos, akses informasi di sini tidak seperti di televisi yang ada aturan dan batasannya. Semua orang bebas mengungkap dan mengutip macam-macam trending dan isu terkini. Tapi semakin ke sini, semakin aku merasa banyak juga orang yang menulis fiksi yang difaktakan atau fakta yang seolah difiksikan, susah sekali mencari kebenaran hanya dari satu sudut padang dalam perkara menggunakan medsos.
Mungkin ada setengah jam lebih aku duduk, menunggu bus yang akan mengantarku kembali.
Aku menunggu, untuk kembali.


 littlemagic
littlemagic