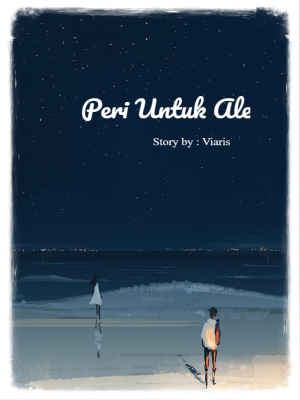Tanpa menunggu ba..bi..bu lagi, segera kupencet menu bergambar gagang telepon pada nomor Zahwa.
“Assalamu’alaikum, Bang.” Suara itu tetap lembut dan sangat sopan menyapa telinga, meskipun percakapan semacam ini sudah jarang terjadi, aku paham betul ini adalah suara Zahwa.
Aku jawab salamnya dengan nada bahagia setelah lama tidak bersua walau hanya versi suara.
“Aku sedang jalan di jembatan belakang rumah, mau ke rumahmu, Bang. Barangkali ibu mau ngobrol juga.”
“Aih, kau memang pandai sekali. Paling mengerti, bahkan sebelum aku memberi tahu lebih dulu.” Aku merasa ada intuisi dan perasaan yang selalu terhubung antara kami berdua.
Di ujung telfon, aku mendengar suara perempuan yang sudah tidak lagi muda memberi salam kepadaku. Ia menanyakan kabarku, pekerjaanku dan rekan-rekan satu timku. Ia juga bertanya apakah makanku enak, apakah tidurku nyenyak, apakah aku ditekan dalam pekerjaanku dan lain sebagainya.
Aku menjawabnya dengan sebenar-benarnya keadaanku sekarang, kabarku baik dan aku menyukai pekerjaanku, aku juga tidur dan makan dengan nyaman. Kadang aku merasa, meskipun umurku sudah lebih dari dua dekade tapi kadang ibu masih memperlakukanku seperti balita.
“Kapan Zahwa pulang, Bu?”
“Kau bisa tanyakan langsung pada orangnya, Nang.”
Dengan suara yang samar-samar Zahwa menjawab pertanyaanku, “Baru tiga hari ini, Bang.” Nampaknya ia tengah melakukan sesuatu, ditelingaku ia terdengar sedikit berteriak.
“Berapa lama di rumahnya?”
“Mungkin dua minggu, aku mau ke ibu kota. Oh iya bang, kemarin aku lihat ada toples unyil isinya kuku-kukumu yang sudah dipotong. Kata ibu, kamu suka menyimpat potongan kukumu kalo habis bersih diri. Agak sedikit aneh dan menjijikan memang, tapi aku mau memintanya sedikit, boleh?”
Telingaku agak berdiri mendengarnya, permintaan Zahwa memang kadang aneh dan tidak penting, tapi itu yang unik dari dia. Jadi selama tidak mengganggu dan merugikan, aku cenderung tidak melarangnya, lagi pula ia anak yang baik.
“Bagaimana pekerjaanmu di Jepang?” Aku menanyakan ini dalam keadaan rambut yang bergerak-gerak ditiup angin. Eoni juga masih duduk di sebelahku. Ia diam sambil memegangi liontin yang tergantung di lehernya dengan tatapan lurus kedepan menatap hijau dari perbukitan yang dekat maupun yang ada di kejauhan.
Zahwa sangat antusias jika aku bertanya sesuatu tentang dirinya. Ia sedang menyelesaikan study starta-2 di negeri sakura. Pendidikan sebelumnnya juga ia selesaikan di sana.
Saat ini ia sedang bekerja untuk sebuah lembaga pemerintah yang bergerak untuk mensosialisasikan masalah kesehatan mental, ia adalah psikolog pribadiku. Jika kami bertemu, keluh kesahku tumpah ruah dan meluap kemana-mana hanya pada satu orang ini.
Ada 30 menit kami mengobrol, setelah itu ganti sesi, gantian ibu yang bercerita dan kembali bertanya tentang lingkungan di sekitarku. Seperti biasa, ia juga menyisipkan pesan-pesan sederahananya yang membantuku melewati banyak hal.
“..semoga kau akan selalu menyukai pekerjaan yang sedang kau lakukan, dan bagaimanapun keadaanmu kau harus selalu bisa mensyukurinya. Satu pesan ibu, Nang. Ingat waktu. Jangan terlena, gunakan itu sebagai ladang kebaikan untukmu.”
“Baik, Bu. Terima kasih untuk nasehat, doa, rencana, kata-kata dan kesempatannya.”
Obrolan tadi seperti boster untukku, rasanya seperti terisi kembali. Aku sampai lupa jika aku kemari mengajak seseorang.
“Maaf kalau lama.” Ucapku dengan nada tidak enak.
Eoni menggeleng, tidak masalah, “Aku paham bagaimana rasanya rindu dan merindukan, meskipun kini aku susah untuk merasakannya lagi.”
Aku diam, aku menangkap sinyal kesedihan di sini.
“Tadi ibumu?” Tanya Eoni cepat-cepat, nampaknya ia tak mau aku membahas ucapannya yang tadi.
“Iya benar, Ibu dan saudara kembarku.”
“Kau punya saudara kembar?” Tanya Eoni, raut dan tatap wajah yang tadinya kosong kini mulai terlihat normal lagi. Ia mungkin antusias mendengar jawabanku barusan.
“Iya, namanya Zahwa. Tapi sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada kami.” Aku memulai ceritaku, “Entah mengapa, sampai sekarang aku tidak merasa jika aku dan dia bersaudara, tapi itulah sesuatu yang dianggap benar oleh orang sekitar, aku harus menerimanya. Aku dan Zahwa terlahir dari orang tua yang tidak pernah kami ketahui, dan seseorang yang barusan aku panggil ibu dalam telfon adalah ibu angkatku. Ia yang merawatku sejak aku lahir, sementara Zahwa diasuh oleh tetanggaku yang oleh Zahwa dipanggil ibu. Jadi kami memiliki ibu angkat yang berbeda, hanya saja ia sejak kecil bermain sering dititipkan pada ibuku, jadi kami memang dekat dari kecil.”
Eoni ternganga mendengar ceritaku, ia sama sekali tidak mengira bahwa lelaki yang duduk di sebelahnya memiliki kisah hidup yang demikian.
“Tadi itu bukan ibu yang benar-benar ibumu?” Tanya Eoni, nampaknya ia agak kesulitan menerjemahkan maksudnya ke dalam kata-katanya sendiri, cara bicaranya sedikit belibet.
“Iya, Eoni. Tapi itu bukan masalah, ialah sosok ibu yang aku kenal sejak aku lahir, merawatku, menyayangiku dan seterusnya akan seperti itu, meskipun aku juga ingin bertemu dan tahu bagaimana keadaan orangtua kandungku, apabila ia masih hidup.”
“Maaf, aku hanya tidak menyangka. Pembicaraan kalian tadi terasa sangat hangat dan itu sama sekali tidak mencerminkan kenyataan bahwa kau adalah anak angkatnya, maaf jika perkataanku menyinggungmu.” Eoni sedikit murung.
“Tidak, tidak apa. Aku mulai paham denganmu, Eoni. Kau bukan orang yang mudah menyakiti orang lain.” Aku harap kau juga tidak mudah menyakitiku.


 littlemagic
littlemagic