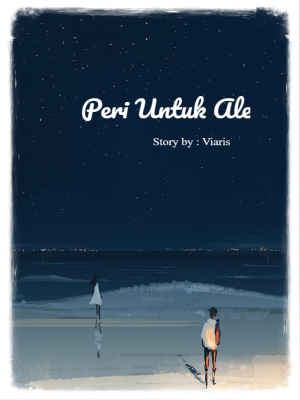Hari kedua dan hari-hari berikutnya tak jauh beda dengan hari kemarin, kami masih bergulat dengan tiang kayu dan tali-temali untuk mengeluarkan batu dari situs ekskavasi. Malamnya pun sama, kembali dengan diskusi-diskusi panjang mengenai jalan keluar mengenai masalah yang tengah dihadapi.
Dan kini sudah Rabu, dua hari setelah Minggu, hari pertama kami datang. Entah mengapa rasanya Rabu dan Minggu punya makna khusus untukku. Mungkin karena salah satu di antara kedua hari itu adalah hari kelahiranku, entah mana yang benar tapi ibu bilang tidak jauh-jauh dari Rabu atau Minggu.
Mungkin Rabu dan Minggu adalah hari yang biasa kita temui. Tapi tepat di hari itu, siapa sangka jika temu, tunggu dan rindu menjadi sangat akrab dan saling berbincang tentang tengah pekan untuk tetap bertahan, serta rekan hari dengan ucapan; terima kasih masih berjuang sampai hari ini.
Seperti pagi kemarin, pagi ini aku kembali duduk di batu di halaman belakang rumah Mbah Kakung bersama gadis cerdas yang misterius ditemani secangkir kopi asli buatan rumahan warga Desa Sarang Panjang. Lembah dan pegunungan rasanya sunyi sekali, tak ada ribut-ribut angin, tak ada bunyi derum mesin kendaraan, yang ada hanya kicau burung yang sesekali menyapa telinga kami.
Di tempat ini ternyata masih banyak capung, tandanya keadaan alamnya masih sehat dan airnya masih cukup bagus, setidaknya begitu kata Eoni. Di bawah kaki-kaki kami juga ramai para kerbau yang sedang sarapan di tanah lapang.
Entah bagaimana mulanya, tapi gadis disebelahku amat menyita perhatianku dengan apapun yang ia lakukan. Mungkin tidak hanya aku, beberapa peneliti lain juga seperti ini.
Setelah kuperhatikan, di leher gadis yang duduk bersamaku ini tersemat sebuah kalung dengan liontinnya berbentuk jangkar kapal berukuran kecil, cocok sekali dengan dirinya.
“Kita tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana cara takdir bekerja,” Ucap Eoni. “Ini hampir sama seperti menjaga anak kecil, dipantau atau tidak, akan ada jatuhnya juga.”
Aku mengengok ke arahnya dengan merasa sedikit aneh namun bercampur kagum, karena secara tiba-tiba ia mengatakan kalimat demikian.
“Maksudku kita sudah berusaha yang terbaik, ketika takdir telah memutuskan untuk menjadikan masalah datang, tidak serta merta itu semua adalah kesalahan kita. Tentang masalah situs ekskavasi yang rusak dan kita harus memulai dari awal, seolah ekskavasi yang pertama tidak ada artinya. Toh itu sudah terjadi dan penyebabnya pun diluar kendali kita. Entah teknologi macam apa yang bisa membawa batu sekian banyak, yang entah dari mana asalnya, dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-seingkatnya sudah mampu menimbun tanah seluas hampir 30x30 meter persegi dengan begitu saja. Aku pusing memikirkan ini. Kau pasti paham bukan, Dif? Ini bukan sepenuhnya kesalahan kita.”
Aku mengangguk, dari kemarin pun aku memikirkan hal yang sama.
“Okelah, masalah tanpa diminta dan ditunggu sudah pasti akan terjadi. Agak kurang adil pula nampaknya jika hal besar bisa didapat tanpa perjuangan yang setara. Tapi yang aku lihat dari rekan-rekan yang lain, yang ada hanya saling murung dan menyalahkan. Mengapa rasanya susah sekali menerima masalah ini dengan sebenar-benarnya kenyataan dan dibarengi usaha terbaik yang masih sempat kita lalukan. Kalau datang masalah hari ini, bukan berarti besok itu kiamat, masih ada waktu untuk mencari jalan keluarnya. Dan untuk menemukan sumber masalah dari kasus seserius ini tidak harus cepat-cepat. Hanya orang bodoh yang menentukan keputusan besar dengan cara terburu-buru.” Kalimat Eoni sama persis dengan apa yang ada dipikiranku beberapa hari ini.
Tapi sebagai junior, aku tentu tidak berani mengatakan hal demikian di depan rekan-rekan apalagi Pak Wicak.
“Mungkin kau berkata demikian karena kau adalah seorang ahli forensik, Eoni. Bukan arkeolog.” Ucapku singkat namun cukup mampu membuat Eoni yang berapi-api itu menjadi diam.
“Ya, aku percaya padamu, Dif. Di antara yang lain, kau memang terlihat paling pintar dan tenang menghadapinya.” Entah apa maksudnya tapi Eoni menjawab demikian.
Kami kembali diam, menatap pucuk-pucuk pinus yang terlihat penyatu dengan hijaunya bukit. Namun tak lama dari itu, Guna memanggilku dan berkata bahwa ponselku berdering beberapa kali.
Sudah kucoba untuk mengangkatnya, namun sinyal di sini sungguh membuat naik pitam. Melihat kegelisahanku, Yua menyarankanku untuk sedikit naik ke puncak bukit. Di sana adalah tempat terbaik untuk mendapat sinyal bahkan akses internet.
Terus terang, aku tak tahu tempatnya, alhasil Yua dan Yui berekenan untuk mengantarku. Mbah Kakung memberi nama yang unik untuk dua cucunya ini.
Sebenarnya, sudah sejak hari pertama aku di sini Yui, si bocil, senang sekali mengikutiku kalau sedang di rumah. Aku ke dapur ia ikut, aku menonton tv dia ikut, aku membuat mie instan dia minta, barulah ketika aku masuk WC aku meminta untuk dia menunggu di luar saja.
Tapi aku kadang terlalu banyak berfikir jadi tidak sempat menanggapi Yui lebih jauh. Usianya baru empat tahun dan senang main mobil-mobilan, beruntung kalau aku berangkat ke lapangan ia belum bangun, jadi tak usahlah dia ikut-ikut juga.


 littlemagic
littlemagic