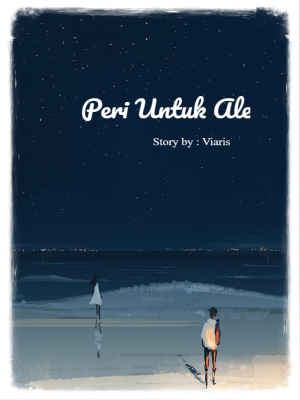Waktu bertambah, tempat berubah, orang-orang berpindah, dan hanya ada satu hal yang tetap di sana yaitu kenangannya. Tak habis pikir olehku melihat bukit yang dulu menyimpan desas-desus menyeramkan kini telah ramai oleh genting dan batu bata. Rumah-rumah berpondasi beton telah mengungkung tanah miring yang telah kutinggalkan sejak empat tahun silam. Lihat, bukit itu diam saja menerimanya.
Dari jendela kamar depan, aku sudah tidak bisa lagi memandangi bentangan alam yang perawan karena telah terhalang dinding rumah tetangga. Pohon beringin besar yang semasa kecil aku takutkan juga telah kehilangan personanya, kini ia tak lebih dari sekedar pohon biasa yang melakukan fotosintesis setiap hari, bukan jadi rumah hantu dan teman-temannya. Wangi kemenyan dan sesajen pun sudah tak ada di sela-sela akar yang mencuat keluar dari dalam tanah.
Namun, mau seperti apapun bentuknya, Nara adalah rumah bagiku. Dua dekade hidupku berlangsung di sana. Setelah empat tahun menimba ilmu di negeri orang, aku sempatkan diri untuk pulang. Menengok Ibu, Lail dan keponakanku, serta Nurdin yang telah menjadi sang kakak ipar bagiku. Beberapa orang tahu, dahulu aku tidak menyukai Nurdin karena dia terlalu baik. Ya memang, ‘terlalu baik’ mungkin menjadi alasan penolakan bagi beberapa orang.
Terlepas dari tetangga ‘manusia’-ku yang semakin banyak, sudah cukup membuat perbedaan yang berarti bagiku, karena dahulu tetanggaku hanya tanaman kol, sawi dan pohon kopi, namun semua hal mengenai Nara masih sama sendunya. Sungai kecil yang mengalir di belakang rumahku masih tetap jernih dan ramai dikunjungi itik dan induknya. Suhu udara di sini pun masih tetap dingin, setidaknya perlu dua pakaian tebal agar tidurku terasa nyaman. Cuaca juga sepertinya masih sama, ia kerap memainkan angin, hujan dan panas semaunya sendiri tidak peduli cucian ibu yang sudah kering atau belum. Nara masih sama, aku yang berubah.
Hanya 2% dari teman-teman kuliahku yang tahu tempat ini, bahkan banyak dari mereka yang baru pertama kali mendengar kota bernama Nara. Tapi selalu aku katakan pada mereka bahwa Nara itu sangat dekat dan nyata bagi siapa saja yang benar-benar ingin tahu, ia bukan sekedar karang-karangan yang dibuat hanya untuk membuat orang sedikit senang. Entah mereka percaya atau tidak, tapi aku telah mengatakan yang sesungguhnya.
~~~
Mungkin beberapa orang akan sulit mencernanya, namun semenjak Ibu Eni memberitahu nama Ibu kandungku ~yang telah meninggal sejak aku lahir, aku tak sedikit pun membuat jarak darinya. Mau bagaimana pun, Ibu Eni adalah sosok ibu yang telah merawatku dan mengenalkan dunia yang begini adanya. Kata Ibu, “Nama perempuan hebat itu adalah Alina”. Cantik sekali nama itu, bisa jadi Alina adalah nama terkeren yang ada waktu itu, batinku.
Aku kira nama yang hits waktu itu tidak jauh-jauh dari Sumarno, Siti, Sutati. Suliah, Surahman dan yang mirip-mirip. Dari bisik-bisik yang sudah tidak lagi disembunyikan dariku, kudengar “Alina” adalah sosok peremuan yang baik, ramah, cerdas, pandai memasak dan membuat sajak. Namun sebanyak apapun deskripsi yang disebut orang-orang tentangnya, ia masih saja misterius bagiku. Tidak ada kata-kata yang sanggup menerjemahkan raga dan rasa secara utuh.
Kabar Ibu Eni sudah lebih sehat dari dahulu, apalagi dengan cucu barunya, terus terang anak Lail memang sangat lucu dan menggemaskan. Cabang bayi menjadi hiburan luar biasa bagi ibuku.
Ibu juga masih sering pergi ke ladang untuk sekedar menengok apakah hama ulat menyerbu tanamannya atau tidak. Sebenarnya pekerjaanku sekarang sudah lebih dari cukup untuk mengidupi kami berdua, belum lagi Laila yang rutin mengirim ibu bingkisan setiap minggu walaupun kini ia telah punya rumah sendiri.
Sudah berkali-kali kubujuk ibu agar di rumah saja, tapi ia bilang ia bekerja dan mengunjungi ladang bukan karena ia butuh uang, melainkan karena memang hanya itu yang bisa ia lakukan. Ibu tak suka berpangku tangan di rumah dan membiarkan ladangnya diurus sepenuhnya oleh orang lain. Baginya, menyiangi rumput juga hiburan.
Kini ibu di rumah tidak sendirian meskipun Laila sudah pindah sejak dua tahun lalu. Ada seorang anak tetangga bernama Izah, ia adalah seorang gadis manis yang tuna wicara. Izah biasa membantu ibu melakukan pekerjaan rumah, pekerjaan apa saja ia lakukan, termasuk memasak, mencuci baju, menyiram tanaman, mengelap jendela dan masih banyak lagi.
Meskipun tak pernah mengatakan apapun, ibu merasa komunikasinya dengan gadis itu berjalan lancar dan ibu senang ditemani Izah sepanjang hari yang baru akan pulang apabila senja tiba atau ketika orang tuanya memanggil. Aku mengenal gadis itu dengan baik, meskipun ia adalah tetangga baru kami.
Tidak sedikit yang bertanya padaku tentang saudara kembarku, Zahwa. Aku yakin kini ia baik-baik saja dengan pendidikan dan pekerjaannya di sana. Pertemuanku dengannya selama empat atau lima tahun ini sangat bisa dihitung jari. Kalau ia libur, aku kuliah dan bekerja. Kalau aku libur, dia masih di Negeri Sakura.
Waktu tak pernah merestui kami. Terus terang tak banyak yang bisa aku ceritakan karena aku memang tak lagi banyak tahu tentangnya. Tidak seperti dulu. Ada yang aku kecewakan akan hal ini, tapi ya sudahlah, seperti yang aku bilang di awal, manusia pasti berubah.
Ada hal yang perlu diketahui, sebenarnya aku tak terlalu percaya dengan kenyataan bahwa aku dan Zahwa adalah saudara kembar, maksudku kami memang banyak kemiripan dan saling memahami satu sama lain. Tapi terlepas dari itu, aku merasa darah yang mengalir dalam pembuluh kami tidak berasal dari satu sumber yang sama. Naluri manusiaku mengatakan hal demikian, tapi lagi-lagi ya sudahlah. Tak ada yang bisa aku lakukan selain menerima kenyataan dan kejadian yang dianggap benar oleh sebagian banyak orang.
Kembali ke Nara sama saja membuatku kembali mengingat masa lalu, tentang kejadian-kejadian lampau yang telah dan belum aku selesaikan.
Cukup sulit bagiku untuk menerima bahwa aku mempunyai dua ibu dan dua ayah di usiaku yang sudah seperlima abad. Mereka adalah dua pasang yang berbeda. Yang kadang membuatku tidak terima, Tuhan tidak mengijinkanku untuk menatap langsung mata kedua orang tua kandungku barang satu menit saja.
Selepas kejadian beruntut empat tahun lalu, aku sempat mengalami kebingungan selama berbulan-bulan, awalnya memang aku coba menerima, namun setelah usaha yang aku lakukan untuk meyakinkan diri sendiri tidak menghasilkan apa-apa, dari situlah aku sering melamun dan mempertanyakan diri sendiri, untuk apa dan siapa aku hidup. Merasa tidak lengkap sebagai manusia. Memang itu bodoh, namun seperti itulah yang terjadi dahulu.
Tapi aku masih beruntung, setidaknya aku tetap mendapatkan sosok orang tua yang menyayangiku sepenuhnya, meski setengah dari umurku saat ini aku juga kehilangan salah satunya. Ayah yang merawatku meninggalkanku saat usiaku 12 tahun. Aku sudah hafal dengan perasaan kehilangan, namun selalu rapuh tiap kali mengalaminya kembali. Seperti tidak bisa belajar dari yang lalu-lalu.


 littlemagic
littlemagic