Gelanggang langit sore memberikan sinar merah keemasan ke seluruh lembah dan bukit yang secara pasrah menerimanya.
Sinar itu membuat semuanya jadi oranye termasuk juga halaman rumah yang kami sebut sebagai taman.
Ia tak luas dan penghuninya pun bukan bunga-bunga mahal dengan harga jutaan dolar.
Tapi aku yakin cinta yang ada di sana tidak akan sanggup ditebus oleh orang paling kaya di seluruh jagat Nara.
Tamanku masih ramai dengan bunga-bunga kesukaan Ibu dan Lail, mereka telaten sekali menyiramkan air setiap pagi dan sore hari, menyiangi rumput liar yang tidak diinginkan, dan memberinya pupuk yang baunya membuat mata pedih jika dihirup lama-lama.
Entah mengapa perempuan sangat suka merawat hal yang tidak menghasilkan uang seperti ini.
Tapi aku belajar dari mereka bahwa tidak semua hal adalah tentang uang, ada yang lebih penting, eksklusif, dan istimewa.
Seperti kataku tadi, cinta di sini mahal, konglomerat tidak sanggup membelinya.
Jupri mengantarku pulang saat halaman rumah sudah gelap.
Cahaya lampu yang redup berusaha memaksimalkan kekuatan yang ia punya untuk menciptakan sinar dari pergerakan elektron.
Aneh sekali, tak ada balasan salam yang menyambutku pulang, dan sesaat baru aku sadari jika aku tidak menemukan sepeda motor kerjaku di teras depan.
Otak dan dadaku seketika kejang, ke mana motor ini pergi jika bukan aku yang membawanya?
Lail tidak bisa mengendarai motor gigi, ia sejak awal hanya mau naik motor matic.
Tidak mungkin Ibu, jangankan membawanya, memboncengku saja ia takut.
Aku menghambur ke kamar dan menggerayangi meja yang biasa kugunakan untuk belajar. Tidak aku temukan kunci motorku di sana.
Kemudian di ruang tengah, di cantolan dekat jendela, tempat di mana kami sekeluarga biasa menaruh kunci rumah dan sejenisnya.
Nihil hanya ada satu kunci silver untuk membuka pintu depan. Jupri memandangku dengan heran tanpa tahu apa yang terjadi padaku.
Kini keringatku sudah sebesar biji jagung, menempel di jidat dan punggung.
Ketika sampai di dapur, kulihat Ibu tengah duduk, hanya menatapku dan tidak mengatakan apa pun.
"Bu, di mana sepeda motor Nadif?" Detak jantungku sudah kehilangan kendalinya, rasanya ia tengah memompa darahku di luar kemampuan biasanya.
Ibu hanya diam, menatapku kosong dan tetap tidak mengatakan apa pun, Ibu kenapa?
Sejak dua hari yang lalu, Ibu memang mengeluh pusing, perutnya sakit dan terus batuk-batuk.
Sesekali Ibu juga berkata bahwa mulutnya terasa pahit untuk mengecap makanan apa pun.
Aku masih menunggu reaksi Ibu dengan menanyakan hal yang sama dua kali.
Dan ketika aku mendekat, ibu berdiri dengan galak. "Waktu kemarin kamu tidak pulang, kamu ke mana saja, Nak?" tanya Ibu, dengan raut wajah yang marah tapi matanya berair.
Aku tidak mengerti, apa yang membuat Ibu terlihat begitu marah? Aku belum menjawab pertanyaan Ibu.
Dan semakin aku diam, semakin wajah Ibu memerah menahan tangis dan amarah. Entah apa yang tengah dipendamnya saat ini.
"Tadi siang ada orang datang kemari, ia menyampaikan surat katanya dari kantor." Entah siapa yang datang pada hari itu, tapi ia bukan pembawa berita baik.
Ibu menangis seharian karena kabar yang mereka bawa.
Kata Ibu, ada dua orang lelaki, yang satu bertubuh kurus dan memakai kacamata bulat, satu yang lain berbadan medium dengan dada yang tegap serta tatapannya yang tegas.
Sayang sekali Ibu tidak sempat menanyakan nama mereka.
"Ibu tidak sudi punya anak pemabuk!" suara Ibu tercekat di akhir kalimat.
Aku tertohok bukan kepalang, siapa yang pemabuk? Jupri yang berdiri di belakang kami ikut terkejut, matanya membelalak mendengar apa yang Ibu ucapkan.
"Dari kecil dididik dengan agama, disuruh ngaji yang rajin, supaya tidak kesasar, tapi begitu besar lupa semua. Ibu kira dengan kamu yang sudah semakin besar, kamu sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang dilarang. Tapi ibu salah, ibu salah besar."
"Kenapa Bu? Siapa yang mabuk? Demi Allah Nadif tidak pernah melakukannya."
"Jangan bawa nama Allah untuk kesaksian sebuah kebohongan." Suara ibu timbul tenggelam dengan nada sesenggukan yang tidak kuasa aku dengar, seumur-umur aku belum pernah membuat Ibu menangis di depan mataku dengan aku sendirilah yang menjadi penyebabnya.
Dengan genangan air mata yang meluap-luap, Ibu memberikan aku surat beramplop coklat dengan cap kepolisian di pojok kanan bawah.
"Mereka membawa ini, surat panggilan pemeriksaan untuk karyawan kantor tempatmu bekerja. Ibu tidak terlalu fasih dalam membaca, tapi lihat, di deretan ini ada namamu, ibu yang pertama kali menuliskan namamu di atas kertas saat kamu baru berumur satu minggu, mana mungkin ibu tidak bisa membacanya di sini. Kamu dicurigai ikut pesta dan mengonsumsi barang haram, Nak."
Ibu menangis lagi, "Siapa yang mengajarimu? Kamu ibu izinkan bekerja jauh dari rumah untuk dapat pengalaman dan kenalan yang baik, bukan yang seperti ini."
Beberapa hari yang lalu, ditemukan paket berisi sabu seberat 30 gram di kantor.
Tidak ada alamat pengirim ataupun penerima, tidak juga ditemukan di gudang penyimpanan barang.
Sabu itu ada di ruang karyawan tempat kami makan-makan semalaman suntuk.
Tapi demi apa pun aku tidak tahu menahu soal barang haram ini.
"Itu bukan Nadif, Bu. Aku hanya ikut makan-makan saja malam itu. Tidak lebih."
Entah pembelaan yang bagaimana, yang bisa Ibu terima, aku memang tak punya bukti bahwa aku tidak ikut-ikutan, tapi selembar kertas yang di tangan Ibu dari kepolisian belum jelas kebenarannya.
"Apa yang membuat ibu yakin kalau kamu tidak terlibat pada malam itu?"
Aku diam, aku takut perkataanku yang sembarangan malah memperburuk keadaan.
"Tidakkah kamu tahu bagaimana perasaan ibu saat tetangga bertanya tentangmu yang dikabarkan menggunakan narkoba pada ibu? Ibu malu, Nak. Malu."
Ibu terus berbicara dengan linangan air mata yang ke mana-mana, mengalir sampai dagu membuat kerudungnya basah.
"Jangan dengarkan apa kata tetangga, Bu!" Ibu yang tadinya terhenyak, kini terkejut mendengar suaraku yang seolah membentak.
Aku belum pernah berbicara dengan nada yang lebih tinggi darinya. Jangankan membentak, menatap matanya saja aku takut jika sedang dimarahi.
Entah apa yang merasuki aku kini. Semakin aku dewasa, bukan menjadi alasan untuk semakin merasa bisa melawan orang tua karena keadaan yang merasa hampir setara.
Itu pesan Ayah dulu. Tapi aku sungguh kehilangan diriku dan apa yang aku pegang kini.
"Tinggalkan pekerjaanmu, Nak. Jauhi lingkungan yang tidak membuatmu jadi lebih baik. Pergilah dari mereka yang membuatmu menjadi bukan seperti dirimu. Tinggalkan pekerjaanmu, Nadif."
Hatiku getir mendengarnya, aku melakukan semua ini untuk ibuku.
Aku banting tulang, kepanasan, kehujanan, rela kelelahan di jalanan selama berjam-jam dan itu kulakukan setiap hari, hanya untuk Ibu.
Tapi apa yang aku dapat kini? Sebuah kecurigaan dan larangan seolah aku anak baru besar yang semua-muanya masih diatur orang tua.
Kubanting pintu saat itu juga, dan kutarik Jupri yang kebingungan di ruang tamu.
Laila baru pulang dari lemburnya kebingungan kala melihatku yang tengah bersitegang dengan Ibu yang air matanya belum kering.
Tak ada yang kukatakan, aku hanya ingin pergi jauh dengan rasa percaya yang tidak penuh dan kecewa karena apa yang telah kuusahakan mendapat penghargaan yang demikian.
Aku kecewa sekali.


 littlemagic
littlemagic



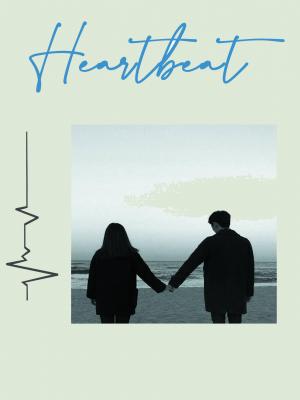








I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog