"Apa yang aku pikirkan?" ucap Pak Bah mengulangi pertanyaanku, "Aku selalu berpikir, Nak. Sepertinya aku tak pernah memberi jeda pada pikiranku untuk tidak memikirkan sesuatu."
Ia menjawabku, namun matanya tidak bergoyang dari pandangannya yang memeluk jalanan.
"Aku telah pergi mengelilingi bumi walaupun belum seluruhnya, mengunjungi kota di seperempat dunia. Tapi aku tetap masih suka berjalan, mengunjungi tempat asing yang baru, dan akan selalu seperti itu."
"Mengapa demikian, Pak? Bukankah tinggal dan menetap lebih menenangkan hati karena kita sudah tidak perlu pergi dan mencari-cari lagi?"
"Mengapa demikian? Aku juga tidak tahu. Sebenarnya bukan tempat atau tujuan baru yang aku tuju, aku hanya menyukai proses berpindahnya. Nak, bukan pergi yang menjadi tujuanku, melainkan pulang kepada tempat yang selalu satu. Sebuah tempat yang kini tidak ada lagi di dunia ini. Dan salah satu cara agar aku bisa pulang, maka aku harus pergi."
Entah apa yang menarik dari jalanan yang pinggirannya hanya dihuni pohon, sungai, perkebunan warga, dan tanah tinggi ini.
Mata Pak Bah tidak sedikit pun meninggalkan jendela bus.
"Sesuka itu aku pada perjalanan, Nak. Satu lagi yang ajaib tentang perjalanan dan perpindahan adalah, kita bisa tidak melakukan apa-apa, tapi kita tidak sedang membuang waktu, karena perjalanan adalah sebuah proses menunggu untuk sampai ke tempat yang akan kita tuju."
Aku tidak tahu bagaimana nikmat dan seninya karena aku belum mengalaminya sendiri.
Tapi dengan melihat Pak Bah, mendengar caranya bercerita, aku seperti bisa sedikit merasakan dan membayangkan kira-kira seperti apa rasanya.
"Dulu, waktu kekasihku masih menemaniku di dunia ini. Aku selalu merindukan rumah dan tak sabar untuk cepat-cepat pulang, menemuinya. Tapi setelah ia pergi menemui-Nya, sang Maha Pemilik Segalanya, aku jadi paham bahwa seluruh tempat pulang di bumi ini adalah semu. Ada satu tempat di mana kita akan pulang dengan sebenar-benarnya pulang. Aku belum tahu rasanya dan tidak tahu bagaimana tempatnya. Tapi kini kekasihku telah di sana. Semoga ia tidak kesepian menungguku."
Aku terhanyut dengan ucapan yang keluar dari lisan lelaki berusia lebih dari setengah abad ini.
"Pak Bah, apa aku boleh bertanya sesuatu?". Tanya Nadif sambil mengusap pelipisnya.
"Tanyakanlah, seluruh manusia bebas dan merdeka untuk bertanya, tapi tidak untuk mendapatkan jawaban." Ungkap Pak Bachrudin pelan.
"Apa Pak Bah percaya dengan cinta pandangan pertama?" Saat ini pikiranku tertuju pada putrinya.
"Masa mudaku keras, Nak. Tidak sempat memahami hal yang seperti itu. Tapi karena kau bertanya, jawabanku, mungkin tidak. Aku rasa, aku tidak percaya dengan hal demikian…"
Aku hendak mengelak, tapi Pak Bah seperti belum selesai dengan kalimatnya.
"Manusia itu sangat banyak, mereka mempunyai otak sendiri-sendiri. Mereka punya jalan pikiran yang berbeda-beda ketika ditanya tentang cinta. Definisi cinta bagiku, mungkin berbeda dengan definisi cinta menurut bapak-bapak yang mengemudikan bus reot ini. Hati-hati dengan cinta pandang pertama, Nak. Aku telah mengalami banyak macam rasa seumur hidupku, mulai dari rasa senang, sedih, terharu. Rasa-rasa itu sama seperti rasa cinta. Bukan berarti cinta tidak istimewa, tapi rasa-rasa yang lain juga istimewa. Senang itu istimewa, sedih juga begitu. Jangan cinta melulu yang diurusi, seolah menjadi ihwal paling penting di seluruh jagat dunia. Tapi mau bagaimanapun itu, bagiku cinta adalah kebiasaan. Ia dijahit pelan, sebenang demi sebenang, kemudian menjadi rajutan, lama kelamaan menjelma menjadi sebuah kain kehidupan yang panjang. Seperti kataku tadi, hati-hati dengan suka pada pandangan pertama, sebab yang sejati biasanya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang simpel tapi tidak sederhana."
"Dulu aku pernah belajar ilmu termodinamika tentang entropi. Katanya, semakin reaksi terjadi secara spontan, maka ketidakteraturannya akan semakin tinggi. Lalu cinta yang disebabkan karena pandangan yang sekejap itu, apa benar itu cinta atau hanya bentuk lain dari nafsu dan rasa penasaran belaka?"
Aku diam.


 littlemagic
littlemagic











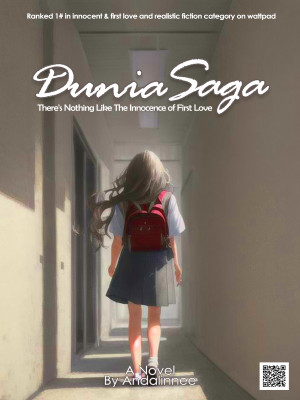
I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog