Tiba hari bertemu malam. Entah mengapa aku tak bisa tidur, padahal sudah seharian bekerja, bertemu banyak orang, berkeringat sampai bau kecut, tapi kalau malam masih saja susah tidur.
Mungkin mataku menutup, pura-pura mau tidur, tapi pikiran tetap saja kelayapan. Kalau saja ada turnamen kejuaraan orang paling susah tidur aku bisa mendaftar jadi kontestannya.
Dahulu, semasa SMP, sekolah pernah diliburkan sebulan penuh karena wabah penyakit menular sedang melanda Nara.
Kami dilarang keluar rumah, apalagi mampir ke rumah tetangga. Virus itu menyebar secara mengerikan, bisa lewat sentuhan tangan, bersin, batuk, dan kabarnya juga bisa menyebar lewat udara.
Banyak orang yang meninggal karena virus kecil yang ukurannya tidak sampai setengah milimeter itu.
Tapi Zahwa bukan tipe anak yang mau diam, dia merajuk bukan main minta jalan-jalan.
Karena Bu Widi pusing, akhirnya Zahwa diselundupkan dari pintu belakang rumah supaya tidak dilihat tetangga dan mengetuk pintu rumahku.
Bu Widi percaya rumahku aman. Virus tidak senang main-main di kebun.
Betapa terkejutnya Ibu, Zahwa datang dengan mulut tertutup masker, memakai jas hujan padahal hari sedang cerah, bersepatu boots, lengkap dengan sarung tangan.
Aku hampir tidak mengenalinya. Bu Widi berbisik-bisik, bilang ingin menitipkan Zahwa karena ia tak mau disuruh tinggal di rumah saja.
Ibu mengangguk dan buru-buru melepas kostum Zahwa yang mirip kepompong.
Zahwa adalah anak yang cerdas, sudah sejak kecil ia memiliki pikiran yang tidak sama dengan anak-anak lain.
Kami berdua bermain di teras rumah saat hari mulai mendung, dan ia bercerita padaku;
“Bagaimana bisa orang percaya bahwa yang tertiup dan kemudian kita rasakan ini adalah angin? Ia bahkan tidak terlihat sama sekali. Bagaimana jika ternyata yang tertiup dan kita rasakan ini adalah kentut atau gas beracun, kita mengira angin dan baru menyadari setelah mencium baunya.”
Aku mengangguk dan kemudian menggeleng, setuju tapi tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ia berkata lagi;
“Bagaimana bisa orang menyebutnya gerimis? Bisa saja air yang berjatuhan itu ternyata adalah kelakuan burung-burung yang bermain genangan air yang terjebak di talang rumah, bentuk rintiknya tak beda jauh.”
Aku mengangguk dan menggeleng lagi, tidak terlalu setuju tapi tidak memiliki kalimat untuk menyanggahnya. Kemudian ia berkata lagi;
“Bagaimana bisa orang percaya bahwa bumi adalah satu-satunya planet yang ada penghuninya?”
Aku masih menunggu ucapannya yang selanjutnya yang ternyata sudah selesai. Baru kemudian aku menggeleng tapi aku menjawab, “Karena di planet lain tidak ada air?”
“Memangnya air untuk apa?” tanyanya dengan nada polos.
“Sumber kehidupan, manusia bergantung dengan air,” jawabku seadanya.
“Bagaimana jika manusia di sana sumber kehidupannya bukan air, bisa saja benda lain yang tidak ada di bumi. Beda rumah beda penghuni, beda planet apalagi.” Jelas beda sekali, maksudnya begitu.
“Tapi belum ada penelitian yang membuktikan keberadaannya, Wa.” Aku mengeluarkan argumen seadanya lagi.
“Belum ada, bukan berarti tidak ada. Bang, bagaimana kamu bisa tahu kalau di kepalamu tidak ada kutu?”
Jidatku mengernyit heran. “Gatal-gatal?”
“Bisa jadi iya, bisa juga tidak. Semisal Bang Nadif kutuan, mungkin awalnya akan gatal-gatal, lalu Ibu akan mencari kutu-kutu itu tapi tidak menemukan. Lalu Ibu menyimpulkan bahwa di kepala Abang tidak ada kutu. Sampai berhari-hari Abang masih merasa gatal, sampai akhirnya Abang memutuskan untuk pakai sampo terbaik agar jika benar itu kutu, ia akan mati. Baru setelahnya gatal itu reda, apa yang seperti itu bisa serta merta menandakan bahwa di kepala Abang tidak pernah ada kutu?”
Aku menggeleng untuk kesekian kali.
“Bisa jadi ada, tapi memang tidak pernah ada yang menemukan. Sehingga akhirnya dibilang tidak ada. Penghuni planet lain juga begitu, peneliti hanya belum menemukan jadi bilangnya tidak ada. Dan yang seperti itu tidak bisa diartikan absolut, tidak ada. Bisa jadi ada tapi memang belum ditemukan, atau mereka memang sengaja tidak ingin kita temukan.”
“Jadi kamu percaya kalau Alien itu ada?”
“Kalau Alien itu adalah makhluk aneh, tukang culik, dan pakai piring terbang yang ada cahayanya, aku tidak percaya. Tapi jika Alien itu adalah makhluk sederhana yang tinggal dan hidup menjalani hari-harinya di tempatnya berada. Jawabannya adalah aku belum tahu, aku tidak bisa memutuskan apakah aku percaya atau tidak. Tapi jika dipersentasekan kepercayaanku dengan makhluk luar bumi itu, mungkin 75% percaya dan 25% tidak.”
“Cari aman.” Aku terkekeh.
Ia juga tersenyum dengan mata bulan sabit dan wajah sendunya. “Iya, aku hanya tidak suka dengan orang yang kekeh dengan pendapatnya yang kaku, mutlak, dan tidak boleh diganggu gugat bahwa makhluk di luar bumi itu tidak ada. Menurutku kurang bijaksana.”
Kutatap ia yang melamun, tidak jelas memandang apa. Matanya seperti menerawang jauh, dan aku tidak mengerti di mana pangkal ujungnya.
“Mungkin aku akan sepenuhnya percaya jika ada manusia yang telah menghabiskan seumur hidupnya untuk berkeliling galaksi dan luar angkasa, menyambangi planet-planet, menyapu debu angkasa yang bernama nebula, hingga pada suatu ketika ia kehabisan bekal serta kehausan, kemudian ia singgah di suatu planet untuk meminta air. Dan entah dari mana asalnya, ada sebuah sumur yang isinya sulfur, bukan air. Ia kemudian memilih kembali ke bumi dengan tenggorokan kering, dan menyimpulkan di tempat itu tidak ada air maka tidak ada kehidupan. Salah satu alien yang melihat keheranan, mengapa makhluk asing tadi tidak jadi minum padahal ia terlihat membawa botol dan sangat kehausan. Apakah sulfur yang lezat itu memang bukan seleranya?”
Aku tertawa terbahak-bahak mendengar perkataannya barusan.
“Abang paham maksudku?” tanyanya.
Aku mengangguk masih dengan tertawa. Mungkin maksudnya di planet sana tidak ada air, karena memang tidak dibutuhkan. Mereka lebih butuh sulfur untuk hidup, air bisa jadi adalah benda asing yang berbahaya bagi mereka. Jadi tidak ada air bukan berarti tidak ada kehidupan.
“Dari dulu memang imajinasimu berbeda sekali, Wa.” Dan kami tertawa bersama-sama. Hal apa pun jika sudah masuk ke kepalanya, kemudian diolah sedemikian rupa, hasilnya akan jadi istimewa, setidaknya untukku.
Aku rasa ia punya bakat yang tidak banyak orang lain punya, meskipun aku tak tahu sebutannya apa.


 littlemagic
littlemagic




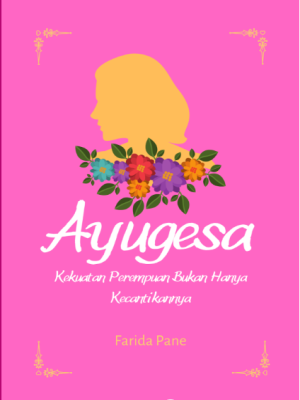







I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog