Semua dimulai sejak jembatan kecil dibangun di belakang rumah kami. Jembatan itu menghubungkan pekaranganku dengan halaman belakang rumah Zahwa.
Memang tak besar, hanya cukup dilalui satu mobil atau dua sepeda motor yang saling berpapasan.
Jembatan itu dibangun untuk memudahkan akses penduduk di Bukit Randu Gunting ke Kota Nara, sebuah kota kecil di pegunungan Jawa bagian pelosok yang sudah patut kami sebut kota karena listriknya yang berlimpah serta pasarnya yang sangat ramai, pusat jual beli masyarakat dari berbagai desa dan distrik tempat kami tinggal terpusat di Nara.
Jangan bayangkan Nara sebagai kota seperti Jakarta, Semarang atau Surabaya, ia tidak sebesar itu.
Tak ada gedung bertingkat ataupun pasar swalayan. Koperasi Toserba sudah merupakan yang terbaik.
Waktu itu usiaku masih enam tahun, Zahwa mungkin lima. Aku tak terlalu paham berapa usianya, yang jelas tidak jauh dariku. Jarak rumah kami tidak sampai seratus meter, namun terhalang kebun sayur dan sungai kecil.
Zahwa tinggal di tepi jalan raya ramai, akses transportasi angkutan utama dari desa-desa menuju Nara lewat depan rumahnya, sementara rumahku ada di kaki bukit, bertetangga dengan wortel dan sawi.
Pada musim tertentu keluargaku juga berdampingan dengan jagung atau ketela pohon. Tetanggaku yang paling pasti hanya pohon kopi, ia tidak pernah ditanam bergantian, cukup sekali dan berbunga sepanjang tahun.
Jembatan itu membuat Ibu jadi mudah ketika ingin membeli sabun cuci piring atau tepung tempe goreng di warung, karena di pinggir jalan raya banyak pertokoan kecil, salah satunya adalah rumah Zahwa.
Ibu Zahwa, selain menjahit, ia juga berjualan di toko yang menjual sembako serta jajan anak-anak, sementara ayahnya bernama Pak Akbar, yang mana adalah seorang kepala sekolah, yang sudah sejak kecil aku takuti.
Mengenai takut ini, entah apa alasannya, mungkin karena dahulu kalau aku ikut Ibu berkunjung ke rumah Bu Widi -Ibunya Zahwa- sering susah diajak pulang.
Alhasil Ibu sering juga bergurau tentang Pak Akbar yang galak dan tak suka anak nakal.
Ibu tak jarang dimintai tolong oleh Bu Widi untuk mengasuh Zahwa, semisal sedang ditinggal ke kota untuk berobat Pak Akbar. Zahwa tak boleh ikut karena merepotkan dan suka meminta yang tidak-tidak ketika di rumah sakit.
Melihat Zahwa yang akrab dengan ibuku, Bu Widi sangat senang. Tak hanya Zahwa, Bu Widi juga menitipkan kakak Zahwa yang bernama Dilan jika pergi di hari selain Sabtu dan Minggu. Kami sudah seperti saudara.
Zahwa adalah anak perempuan yang usianya sepantaran denganku, yang pertama aku kenal.
Biasanya aku hanya bermain dengan Laila -kakak perempuanku- atau dengan Nurdin, itu pun jarang, karena rumah kami terpisah tiga ladang yang ditanami sawi.
Di kaki bukit Randu Gunting hanya ada sembilan rumah yang letaknya saling berjauhan, sisanya ladang dan perkebunan. Cukup menyenangkan tinggal di sini, suasananya sangat tenang dan banyak hal bisa dilakukan tanpa takut akan mengganggu tetangga.
Meskipun terkadang sedih juga ketika abang tukang bakso atau siomai lewat di jalan raya sana dan aku hanya bisa mendengar suaranya, karena mau berlari sekencang apa pun jika si tukang bakso tidak sedang berhenti, aku pasti ketinggalan.
Pernah pada suatu hari, Laila menangis minta membeli es tung-tung, dinamai begitu karena memang sang penjual sengaja memakai lonceng berbunyi tung-tung untuk memanggil pembeli, tukang es hanya lewat di jalan raya sana.
Ibu sudah sekuat tenaga mengejarnya, namun memang belum rezeki, es tung-tung itu sudah pergi lebih dahulu. Berbeda denganku, dahulu Laila tak senang tinggal di sini.
Semasa kecil ibuku senang sekali mengepang rambut Zahwa dan memandikan kami bergantian.
Aku tak suka main masak-masak, namun hanya dengannya aku mau melakukan hal tersebut, bukan karena gombal, tapi rasanya gembira saja bisa bermain dengan gadis bermata seperti bulan sabit ini.
Lagi pula mana ada anak usia enam tahun di zamanku yang tahu “gombal”.
Tak jauh dari masa-masa itu, kisah lain yang aku ingat adalah tentang Zahwa yang takut dengan pohon randu alas yang tumbuh besar di kebun tetangga.
Letaknya memang jauh, namun karena ukurannya yang besar, aura gagahnya terasa hingga kemari. Katanya, jika hendak tidur ia suka membayangkan belasan Kunti bermain di dahan dan menerbangkan daun keringnya.
Aku jadi ikut membayangkan, lumayan mengerikan.
Dia juga suka mengarang cerita tentang ayam hutan yang tidak tahu apa-apa sedang mematuk tanah di sela-sela akar pohon besar itu, tiba-tiba saja salah satu belalai akar melilit kaki si ayam hutan dan menariknya dengan secepat kilat.
Saking cepatnya, si ayam hutan sampai tak sempat berkokok ataupun meminta tolong ayam lain. Ayam itu tak pernah terdengar rimbanya lagi.
Daripada mempercayainya, aku lebih memilih untuk mengiyakan saja meskipun aku tahu ia berbohong. Namun, kuakui imajinasi gadis itu memang sungguh luar biasa. Ucapannya juga, di balik bibir yang tipis, terdapat lisan yang menarik meski kadang tak realistis.
Semasa sekolah dasar saja ia sering menjuarai lomba mengarang bebas dan mendongeng. Mungkin karena semenjak kecil ia suka berimajinasi yang tidak-tidak.


 littlemagic
littlemagic










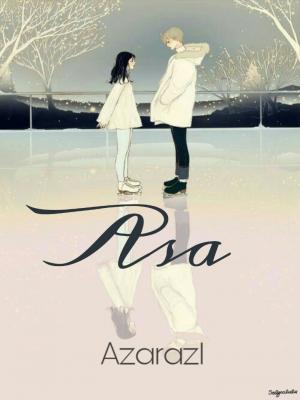

I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog