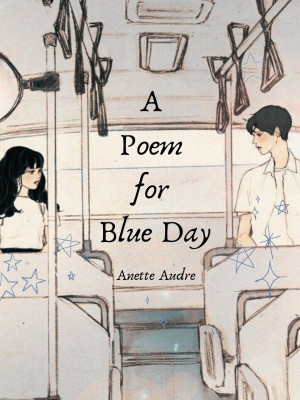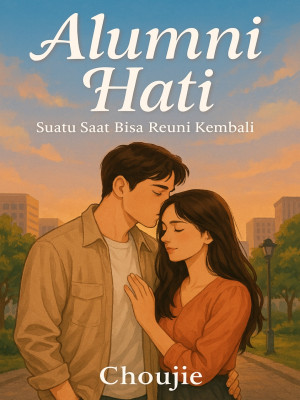“VAREN!”
Varen menghentikan langkahnya, begitu juga Septhian yang ada di sandingnya. Beralih memandang gadis bersurai hitam lakan dengan satu alis yang terangkat tinggi.
Irena—si pemanggil— membungkukkan raganya sejenak, mengatur napas selepas berlarian ke sana-kemari. Ia memburu Varen, tetapi lelaki itu terus melangkah pergi guna menghindari kerumunan para siswi kelas X—nan terus mengusiknya di sela praktik olahraga mereka.
“Kalau gak mendesak, gue—"
“Ini mendesak!” potong gadis itu.
Varen mendengkus singkat. Melangkah mendekati Irena yang masih dalam keadaan terengah-engah.
“Kenapa? Lo gak bawa bekel?”
“B-bawa, kok.” Irena menyengir. Berasak menegakkan tubuhnya, menentang iras Varen yang melantarkannya makin berbunga-bunga.
“Terus apaa?”
Varen mencoba bersabar. Lebih-lebih mengingat titah Ilona—selaku Ibunda Irena— untuk menjaga Irena selama berada di luar mansion mereka.
Irena kian meringis. Sampai kalakian, ia menarik sisi jas kanannya lantas mengambil satu barang dari sana.
“Buat lo. Ucapan selamat datang!” seru Irena. Menyodorkan kotak kecil berwarna merah muda yang dicekal dua tangannya—yang Varen duga berisi jam tangan— tepat di depan wajah lelaki itu.
Varen berdecak lirih. Menarik kotak itu dan setelahnya tersenyum. “Ini ada aji-ajiannya buat melet gue, 'kan? Ketawan, lo!”
“Sembarangan!”
Varen terkekeh, tangannya ia anjurkan. Hendak mengacak rambut Irena seperti biasanya, seperti sediakala—tetapi anehnya urung begitu saja.
“Kenapa? Iren sampo-an, kok.” Varen tersenyum singkat. Bukannya memilih untuk melanjutkan aksinya, ia justru hanya menatap manik mata Irena. “Kenapa?!”
“Sorry, Ren. Nanti cewek gue salah paham.”
Irena menelan salivanya. Terus mengamati sepasang netra Varen tanpa berkedip barang sedetik. Keheningan menyapa keduanya.
“H-halah, bercanda lo gak lucu!” Irena segera memukul dada hangat lelaki itu. Namun, tak seperti dugaannya, Varen tak juga tergelak ataupun menyengir. Melainkan terdiam dengan wajah datarnya.
"... L-lo—”
“Iya, Iren. Kan gue udah bilang.”
Irena menggeleng cepat. Tidak ingin percaya dengan ungkapan seperti itu. Terlebih, ini Varen. Cowok konyol yang selalu tak bisa serius.
Namun, mengapa tatapan Varen seolah memaksa Irena mempercayainya?
Ain Irena berkaca-kaca. Hatinya perih bak ditusuk ribuan serpihan kaca, sesak memenuhi dadanya. Isak lirih yang terdengar menyakitkan keluar dari bibir merah mudanya.
“Gue duluan, ya? Makasih 'selamat datang'nya.”
Varen melangkah pergi. Seolah tak mau peduli dengan Irena yang masih membatu di tempat. Ditenggelamkan oleh lara lantaran ucapannya sendiri.
Lengan Irena terkepal kuat. Menentang Varen maupun Sephtian lurus-lurus tanpa mengejap. Amarahnya membuncah, irasnya kentara mematikan. Ia berambisi untuk membunuh siapapun itu, yang menghalangi langkahnya untuk mendapatkan Varen.
🌻
Lana menguap serta menggeliat singkat selepas mendengar bel yang sukses membuatnya terjaga. Anak-anak berhamburan keluar kelas, kontan melengangkan kelas. Akhirnya, istirahat yang dinantinya tiba juga.
Dua netranya mengerjap guna menyesuaikan cahaya yang masuk. Membenarkan posisi kacamatanya yang miring. Kemudian, setelah indra penglihatannya sukses terbuka, ia menemukan Candra yang tengah tersenyum tipis.
“EH? Gue ngiler lagi?”
“Enggak.”
Lana buru-buru meraba permukaan mulutnya. Senang karena sungguh tak menemukan cairan bau yang mungkin dihasilkan oleh mulutnya sendiri.
“Tunggu di sini dulu, ya? Tapi kalau kalian mau pergi ke kantin dulu, nggak apa-apa,” ujar Lana. Tak enak jika senantiasa membuat Candra juga Irena repot untuk menungguinya.
“Gue sama lo.”
“Oh ya, Irena?”
“Udah pergi.”
Lana mencelang sekejap. Merasa aneh akan kenyataan Irena pergi tanpa mereka, malar-malar belum pamit padanya. Apa ada satu atau suatu fakta yang Irena sembunyikan darinya?
“Kemana?" Entah mengapa Lana merasa tidak tenang.
“Irena nemuin Varen.”
“Va-varen?”
Candra menganggut. Menciptakan puluhan pertanyaan memenuhi benaknya.
“Sejak kapan? Kok gak pamit sama gue?”
“Kurang lebih tiga puluh menit lalu.”
“Hah?”
“Dia bolos dari pelajaran Pak Gani.”
Lana menyengguk singkat. Kembali melayangkan pertanyaan lain, “Alasannya?”
“Lupa kerjain tugas.”
“Varen-nya?”
“Jamkos.”
Lana menghela napas. Sebal akan kebiasaan Irena yang kerap seenaknya. Bahkan ia mengesampingkan pelajaran yang cukup penting bagi masa depannya—Matematika. Namun, memang pertemuan apa yang membuat dara itu belum kunjung kembali hingga kini?
“Gak perlu khawatirin dia. Nih, catet PR dari Pak Gani sekalian ngulur waktu.”
“Makasih, Can.” Lana mengeluarkan pulpennya. Perlahan, tangannya mulai menulis kata demi kata meski seluruh pikirannya terarah pada Irena yang entah ada di mana.
🌻
“Lo ....”
“Apa?” sewot Varen.
Septhian menghela napas, memutuskan untuk bungkam. Mungkin ini berat juga baginya—bagi Varen. Laki-laki itu terlihat tak baik-baik saja sehabis membuat hati Irena sukses retak.
“Trus lo mau suruh gue gimana lagi? Ini cara paling halus buat Irena mundur,” desis Varen. Terus menggerakkan tungkai untuk menaiki anak-anak tangga menuju rooftop diikuti Septhian. Sahabat sekaligus penasihat barunya.
“Lo kenal Irena gak, sih?” pekik Septhian mulai tak tenang.
“Lo bercanda?” pekik Varen balik.
“Maksud gue, lo udah kenal dia dengan baik belum, sih?! Gimana kalau dia bunuh Lana?” Septhian menatap netra Varen tajam-tajam. Takut keadaan lebih runyam dari kelihatannya.
Mendengar itu Varen bergeming, cukup lama. Dan setelah ia sadar dari lamunannya, dia menggeleng samar, “Gak bakalan.”
“Kata siapa?” Septhian mempercepat langkahnya, mendahului Varen dan berdiri di hadapan laki-laki tersebut.
“Gue,” ketus Varen.
“Ren!”
“Hish, iya gue tahu! Gue gak mungkin tolak dia mentah-mentah, 'kan?” kesah Varen.
“Lo ...." Septhian menghentikan ucapannya, netranya terbelalak, “Jangan bilang lo—“
“Iya. Gue gak pernah berniat kenal Irena lebih jauh. Sebisa mungkin gue menghindar dari dia. Karna gue tahu ... dia suka sama gue.”
Septhian menggeleng cepat. Dugaannya ternyata tak pernah meleset.
“Kenapa? Mau cap gue lebih jahat dari Irena?”
Septhian mendesah. Ia lekas terduduk di salah satu anak tangga dan memandang langit—dari balik atap kaca— yang tampak sangat biru dan cerah saat itu. Keheranan, Varen mengamati gerak-gerik Septhian yang terpaku pada dirgantara nan adiwarna.
“Kalaupun gue jadi lo, mungkin gue lakuin hal yang sama.”
Varen membuang napasnya perlahan. Rasa lelah di kedua kakinya baru terasa sekarang.
“Lo harus hati-hati, Ren. Irena itu bisa jadi ranjau suatu hari nanti.”
“Gue tahu.”
“Yang perlu lo tahu ... lo udah ada di tengah ladang ranjau yang Irena lempar. Kita gak tahu kapan, yang pasti suatu hari lo bakal kena ranjau itu. Lo harus hati-hati.”
🌻
“Haiii! Irena, ya?” sapa Vena hangat. Perempuan itu membelai lembut kepala Irena yang hanya mengangga. Menatap Ibunda Varen saksama.
“Tante operasi plastik, ya? Cantiknya kebangetan,” kisik Irena yang menyebabkan seluruh orang yang ada di ruangan itu tertawa lepas. Menertawakan kepolosan Irena yang menyebalkan sekaligus menggemaskan.
“Hush, Irena! Kamu, inii ....” desis Ilona yang sesekali masih tertawa.
“Eh, Irena ... kamu mau temen, nggak?” tanya Vena, ia menunduk di hadapan Irena yang sudah mengatupkan mulutnya.
“Gak, tante. Iren sukanya nge-game. 'Temen' itu nyebelin. Kalau game enggak.”
“Kalau game kalah, bukannya nyebelin?” ujar Vena, masih sama lembutnya.
“Tetep, temen itu nyebelin.”
“Emangnya kamu punya temen?” tanya Ayah Irena, Norman setengah tertawa.
“Gak ... tapi kata kakak, temen itu nyebelin. Kakak sering curhat kalau temennya suka nakalin dia,” jawab Irena masih bersikeras dengan gagasannya.
“Eh, tapi kalau Varen, enggak!” ujar Vena cepat-cepat.
“Varen?”
Mereka bertiga kompak mengangguk.
“Mau ketemu, enggak sama Varen?”
Irena yang mendadak penasaran, menganggukkan kepalanya. Hingga Vena lekas menarik tangannya, membawa gadis itu memasuki kediamannya lebih dalam lagi.
“Tunggu sebentar, ya? Varen biasanya lagi molor.”
Irena manggut-manggut, membuat Vena tak ragu untuk lekas berlalu.
Lantas, gadis mungil itu hanya berdiri menunggui Vena di tengah-tengah lorong menuju lantai dua—tak melakukan apa pun. Sampai tiba-tiba saja, di sela kesepiannya, muncul anak lain dengan cokelat di seluruh bibirnya, tampak berlepotan.
“Maaf, Ma. Varen habisin coklatnya. Enak.”
Irena—gadis molek itu mematung. Tercengang memandangi Varen yang berpijak tak jauh darinya. Sedangkan Varen, yang masih menjilati jarinya nan berlumuran coklat, mulai menoleh ke arahnya. Yang rupanya bukan Ibundanya.
Kala manik mata mereka bertemu, Varen menyengir lebar.
“Ooh, kamu Rena, ya? Yang katanya suka asal ceplos?—Eh, bukan aku yang bilang! Mama kamu sendiri, hehe.”
Irena masih membatu. Memegang dadanya yang mendadak merasa sangat senang, malu, dan ... canggung?
“A-aku Irena!”
“Varen!”
Mereka pun saling jabat tangan dengan erat. Irena tak peduli meski sadar lengan basah itu telah menggapai tangannya.
Irena mengusap kristal bening yang terus menjatuhi pipinya, itu meleleh. Kelopak netranya jadi menghitam akibat maskara dari bulu matanya sukses luntur. Turut sembap dalam sekejap. Gadis itu kembali menggeram kesal. Menghantam wastafel kaca itu dengan kepalan lengannya. Menangis tertahan di sana.
Mengingat kenangan yang pernah dilaluinya dengan Varen; membuat napasnya tertahan, membuat dadanya kembali sesak. Dia benci ini, ketika Varen seperti melupakan semua yang pernah mereka alami. Melupakan segala kama yang coba ia singgir.
Irena menggelengkan kepalanya berulang kali, berupaya mengatur napas.
Tidak. Tangisan itu bukan tanda menyerahnya. Melainkan suatu tanda bermulanya sebuah perang. Ia betul-betul bersedia habis-habisan untuk mendapatkan Varen yang telah lama dicintainya. Dicintainya sejak kali pertama bersua.


 aneylarevaa_
aneylarevaa_