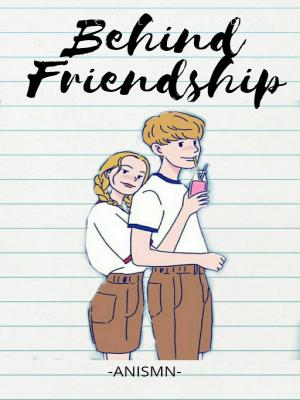“Yang udah jadian mah, kayak ada manis-manisnya. Iya nggak, Gan?” celetuk seseorang, saat Danika mengeluarkan motor untuk ke kampus.
“Kalian ngapain di sini? Aku sibuk, mau berangkat kuliah.” Danika mendapati Karla dan Gani sedang menatapnya dengan penuh keanehan.
“Harusnya kalo udah pacaran itu dianterin pacarnya, Ka. Kayak aku, nih. Ke kampus dianterin Gani.” Karla kembali berucap, membuat pipi Danika memerah.
“Pacar apaan? Aku nggak–”
“Pagi, Ka. Ka-kalian kok di sini?” Ravi gelagapan menyadari kehadiran Karla dan Gani sepagi ini di depan rumah Danika.
“Wah, pangerannya dateng tuh, Ka. Sapa juga, dong!” Lagi-lagi Gani melancarkan godaan. Dia memang sudah mengetahui status hubungan Danika dan Ravi sejak semalam. Ya, siapa lagi yang memberi tahu jika bukan dari Esa dan Jaka.
Selain Gani, Karla juga sudah mengetahuinya. Rasa-rasanya, rahasia apa pun yang terjadi di antara mereka selalu terbongkar dengan cepat, padahal Danika dan Ravi sudah sepakat untuk menutup rapat hubungan mereka.
Mendengar keributan di luar, Bunda dan Ayah akhirnya keluar dan mendapati para sahabat Danika di sana. “Kalian ke sini pagi sekali. Ayo, masuk. Kita sarapan dulu, yuk!” Bunda membuka pagar dan mempersilakan dengan begitu ramah.
“Aduh, nggak usah deh, Bun. Mereka pasti udah sarapan di rumah masing-masing.” Danika menghalangi ketiganya, terlebih Gani dan Karla agar tidak masuk rumah.
“Lho, kamu nggak boleh gitu, Ka. Udah, yuk, masuk sini.” Jika Ayah yang sudah bicara, Danika tidak bisa memprotes lagi. Dia pun mengangguk dan menyingkir dari pagar.
“Sarapan gratis,” bisik Karla, menggoda. Danika hanya mendengkus melihat mereka masuk, sementara dirinya berkacak pinggang sekaligus membuang napas kesal.
“Awas aja, aku bales kalian.” Danika kembali mengomel dan memasukkan motornya yang sudah setengah keluar pagar.
Tiba-tiba, ada yang berteriak, “Danika! Oi!” seru seseorang. Danika menoleh, dia terbelalak saat mengetahui Esa dan Jaka berboncengan menuju rumahnya. Cepat-cepat Danika masuk dan mengunci pagar agar keduanya tidak bisa masuk. Dari kejauhan, teriakan Esa masih terdengar sangat jelas. Danika berlari ke dalam rumah, membuat orang-orang yang ada di sana menatapnya heran.
“Kenapa, Ka?” Ayah menatap heran, disusul tatapan Ravi yang sulit diartikan.
“O-oh, enggak, kok. Ayo kita sarapan. Hari ini aku ada jadwal pagi, takut kesiangan ke kampus.” Sebisa mungkin Danika bersikap biasa saja. Jantungnya berdegup cepat, takut jika Esa dan Jaka akan bersikap lebih gila lagi.
“Kenapa, Neng?” Karla berbisik. Kebetulan, posisi duduk mereka bersampingan.
“Nggak apa-apa. Udah, lanjut aja makannya. Buruan!” Piring yang berada di hadapannya mulai diisi nasi dan lauk-pauk. Belum sempat nasi itu masuk ke mulutnya, terdengar panggilan dari luar. Kan, apa aku bilang! batin Danika.
“Nah, itu suara Esa!” ucap Karla, menatap Gani dan Ravi.
“Ka, bukain pintunya.” Ayah angkat bicara selepas meneguk air minumnya.
“Jangan. Biar Bunda aja. Pasti kamu ngerjain mereka, ya? Usil, nih,” kata Bunda, bangkit menuju pintu. Tanpa sepengetahuan yang lain, Danika dan Ravi saling bertatapan cemas. Sepagi ini sudah dihadapkan dengan kejadian-kejadian konyol. Wajah Ravi begitu pasrah akan apa yang terjadi selanjutnya.
“Ayo duduk, ikut sarapan sama yang lainnya,” titah Bunda sekembalinya dari depan. Di belakang Bunda sudah ada Esa dan Jaka yang tersenyum semringah.
“Kok ada kalian juga, sih? Apa kita janjian?” celetuk Jaka, berdiri di samping Gani. “Danika tadi kabur, Bunda. Padahal kita udah teriak-teriak panggil dia. Iya kan, Sa?”
“Bunda, Bunda. SKSD banget, maneh![1]” gerutu Danika, melotot ke arah Jaka. Baru saja bertemu Bunda sehari, sudah berani memanggil begitu.
“Iya, Bunda. Eh, Bunda yang ngundang mereka?” tanya Esa, kecerewetannya mulai kumat.
“Udah, nanti aja ngobrolnya. Berisik banget sih, kalian berdua!” Pagi ini tekanan darah Danika mendadak tinggi sejak kedatangan Gani dan yang lain. Bunda pun memberikan kursi dan piring tambahan untuk Esa dan Jaka. Sikap Bunda memang selalu ramah kepada siapa saja. Bunda juga sudah menganggap sahabat-sahabat Danika itu seperti anaknya sendiri.
“Sekarang Esa kerja di mana?” Ayah menyandarkan punggung seraya menyeka sudut bibirnya. Sarapan Ayah sudah habis paling pertama.
“Aku kerja di supermarket, Om.” Esa tersenyum, menyendok beberapa potong perkedel jagung kesukaannya. Sejak dulu, dia menyukai perkedel jagung apalagi dimakan dengan nasi hangat dan ditambah sedikit garam. Ah, makanan itu selalu mengingatkannya pada mendiang Ibu.
“Semoga lancar ya, kerjanya. Kalo kamu di mana?” Ayah seperti wartawan yang sedang menginterogasi orang-orang yang memasuki wilayahnya. Giliran Ravi yang ditanya, tatapan Bunda beralih serius pada Danika. Bukan hanya Bunda, bahkan Gani pun ikut-ikutan menatap serius.
“Ravi masih kuliah, sama kayak Danika, Om. Kan dulu satu angkatan sama anak Om ini, terus satu kelas, lagi.”
“Satu cinta juga.” Sekonyong-konyong, Karla menyahut ucapan Ravi. Otomatis semua pandangan tertuju padanya. Bunda yang sudah memahami ucapan Karla hanya tersenyum simpul.
“Maksud kamu Ravi pacaran sama Danika?” selidik Ayah, menatap Ravi dan Danika bergantian. “Bagus, itu. Biar Danika lebih feminim lagi. Om merestui kamu sama Danika, Rav.”
Aliran darah Ravi terasa berhenti hanya dalam hitungan detik. Dia tidak tahu harus berkata dan bersikap bagaimana lagi saat ini. Wajahnya memerah, tak terkecuali Danika yang diam seribu bahasa. Tak sedikit pun terlintas di pikiran kalau hubungannya dengan Danika itu akan direstui begitu cepat oleh ayah Danika.
“Tapi kalian harus selesaikan kuliah dulu. Jangan menikah saat pendidikan belum selesai. Begitu sih, harapan Ayah. Bunda pasti setuju sama ucapan Ayah, kan?” Mata tegas Ayah terjatuh pada Bunda yang langsung mengangguk dengan senyuman masih menghias sudut-sudut bibirnya.
“MENIKAH?” seru Danika dan Ravi bersamaan.
“Ciee, udah kompak gitu. Akhirnya Danika dan Ravi married! Makan besaaarr.” Esa memeluk Ravi di kursinya, membuat yang lain tertawa karena tingkah konyol Esa yang mirip anak kecil ketika mendapatkan undian lotre.
“Jangan lama-lama, buruan dilamar. Nanti keburu digebet orang.” Gani terkikik melihat wajah Danika yang merah padam. Dia tahu, Danika sangat malu, tetapi di sisi lain hatinya juga sedang berbunga-bunga. Cepat atau lambat, Danika dan Ravi akan segera mengakhiri kegengsian mereka masing-masing.
***
Obrolan dengan sang ayah barusan, membuat Esa tertunduk sedih di kamarnya. Hari ini setelah merecoki rumah Danika bersama yang lain, mereka memang menghabiskan waktu di tempat biasa berkumpul, sekalian memperkenalkan tempat itu kepada Jaka dan Gani yang sudah cukup akrab dengan K’DER. Sejenak, Esa menatap pigura foto ibunya di dekat tempat tidur. Kerinduan itu begitu menusuk-nusuk hati Esa, sampai dia memeluk pigura dan menangis.
Orang lain melihat Esa sebagai sosok yang selalu ceria. Akan tetapi, jauh di dalam hatinya ada segerombolan kesepian yang meluluhlantak kekuatannya. Ketika sedang bersama K’DER, kesepian itu memang dapat diatasi sangat mudah. Namun, jika sudah berada di kamar sendirian seperti sekarang, Esa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Orang kesepian, tidak memiliki ibu lagi, dan dihadapkan dengan permintaan ayahnya untuk menikah lagi.
Esa tak bisa berkata-kata banyak hal ketika ayahnya mengutarakan keinginan itu. Dia hanya mengangguk-angguk, meski seluruh celah kebahagiaan di dalam hati yang kadung mati itu semakin seperti rongsokan tak berarti. Sekuat tenaga dia tidak menangis di hadapan ayahnya karena tak ingin membuatnya bersedih.
Sejak Bu Lala meninggal, Esa tak pernah terpikir memiliki sosok ibu tiri. Baginya, saat ada ayahnya di rumah saja itu sudah cukup. Namun, mungkin lain hal dengan apa yang Pak Idan pikirkan. Rumah yang didominasi kesepian itu bak gua tak berlampu. Esa tersesat dalam gelapnya sunyi, begitu pula Pak Idan. Bagaimana bisa dia merestui kemauan ayahnya jika hatinya tak pernah mau hal itu terjadi? Esa kalut dengan kehidupannya sendiri.
***
Mata Pak Gio berkaca-kaca mendengarkan cerita Ravi dengan saksama. Di sampingnya, Bi Deuis juga terlihat beberapa kali menyeka sudut mata. Dua bulan selepas obrolannya dengan ayah Danika tempo hari, telah berhasil meyakinkan hati Ravi untuk segera melamar Danika. Walaupun ada syarat yang harus dilakukan, hal itu sama sekali tidak menjadi persoalan. Toh, Ravi hanya akan melamar Danika dahulu, menyelesaikan kuliah, lalu menikahi gadis pujaannya. Impian sederhana, tetapi mampu membuat dadanya sesak menahan haru.
“Ayah seneng dengernya. Akhirnya kamu nggak ragu lagi sama perasaanmu sendiri. Kapan kamu akan melamar Danika, Rav?” tanya Pak Gio, menyentuh pundak anak sulungnya.
“Secepatnya. Ayah harus sembuh, Ayah harus kuat demi aku, demi Ayah sendiri.” Sesegera mungkin Ravi memeluk ayahnya. Dia terisak begitu pilu, melarutkan tangis kebahagiaan dan kesedihan yang bercampur menjadi satu.
Hatinya bahagia karena sebentar lagi akan menepati janji pada Karla untuk melamar Danika, meskipun di sebagian lain ada sedih karena sudah tak ada sosok ibu di dalam kehidupan Ravi. Ravi hanya bisa memeluk di dalam doa, bercerita melalui setiap harapan sederhananya setiap kali merindukan Bu Oki. Hidup tanpa sosok ibu seakan berjalan di dalam gua tanpa penerang. Gelap, sunyi, dan menakutkan.
“Makasih karena Bibi udah ngizinin Ravi tinggal di Jogja waktu itu. Ravi nggak akan ninggalin Ayah lagi, Bi.” Kali ini pelukan Ravi beralih pada wanita yang sudah begitu banyak berkorban untuknya. Ravi bersyukur masih memiliki Bi Deuis, meskipun dia tak lagi mendapatkan kasih sayang murni dari seorang ibu.
“Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, ya. Jika nanti kamu resmi melamar Danika, itu artinya kamu memiliki satu tanggung jawab untuk jaga dia sebagai calon istri.” Bi Deuis menyeka sudut-sudut matanya yang tak kuasa lagi menahan tangis sejak tadi. Keponakannya itu sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang sebentar lagi akan mempunyai calon istri.
“Jangan lupa, jadi anak yang baik untuk ayahmu juga, ya. Kakak yang bisa diandalkan oleh Sandi,” lanjut Bi Deuis mengusap kepala Ravi penuh kasih sayang. Setidaknya setelah ini Bi Deuis akan lebih tenang menjalani hari-harinya di Yogyakarta.
“Makasih banyak, Bi. Ravi akan selalu ingat nasihat Bibi.” Ravi mengecup pipi bibinya, sudah seperti kepada ibu sendiri.
Di lain tempat, Danika menatap takjub sebuah dokumen yang berada di tangannya saat ini. Lembar kerja sama menerbitkan buku itu didapatkannya sekitar satu jam yang lalu, melalui kurir pos. Tiga hari yang lalu, dia memang mendapatkan surel balasan dari pihak penerbit yang menyatakan jika naskah novel kirimannya akan diterbitkan. Sungguh, mimpi Danika selama ini akhirnya akan terwujud.
Tangan yang gemetar itu mulai mengisi setiap bagian yang harus diisi untuk kelengkapan proses penerbitan. Di bagian tanda tangan, Danika bergeming sebentar. Pikirannya menerawang ke masa di mana berulang kali penolakan didapatkan. Siang dan malam merevisi naskah tersayang, lalu mengirimkannya ke penerbit hingga penantiannya terbayar sekarang.
“Ini buat Bunda, Ayah, dan K’DER.” Sebuah tanda tangan dicantumkan pada bagian materai. Tak lupa dia menuliskan nama lengkapnya dengan begitu rapi.
Kontrak itu kembali dimasukkan pada amplop cokelat, lalu di bagian depan diisi dengan alamat penerbit bersangkutan. Dada Danika terasa sesak, tak kuasa menahan haru yang menjalar di seluruh pembuluh darahnya. Cewek si pilot origami itu sebentar lagi akan dikenal banyak orang melalui karyanya.
***
Sejauh mata memandang hanya menyuguhkan cincin berkilauan. Di sebuah pusat perbelanjaan, Ravi sedang membeli cincin yang akan diberikannya kepada Danika. Dia mendapatkan tambahan uang dari Bi Deuis, sebelum wanita yang begitu memedulikannya itu harus segera kembali ke Yogyakarta karena tidak bisa meninggalkan toko lebih lama.
Kali ini, Ravi tak pergi seorang diri. Dia sengaja mengajak Esa untuk menemaninya membeli cincin, walau sejujurnya Ravi sedikit ragu dengan pilihan Esa. Sejak tadi mereka berkeliling, tak ada satu pun pilihan Esa yang benar. Sahabatnya itu malah mengajak Ravi membeli batu akik dengan alasan agar Danika lebih terharu di hari lamarannya.
“Aku nyesel ngajak kamu, Sa. Ide kamu buruk banget,” oceh Ravi, masih berjalan mendahului Esa.
“Harusnya kamu bersyukur karena aku rela bolos kerja cuma buat nganterin kamu ke sini. Udah, deh. Sekarang ikut aku, yuk!” ajak Esa, menyejajarkan diri dengan Ravi. “Kalo kali ini amsyong lagi, aku pulang.” Esa sedikit mengancam, tetapi wajahnya memang menunjukkan keseriusan.
Ravi pun berjalan mengikuti Esa dengan langkah sedikit cepat. Beberapa toko perhiasan mereka lewati begitu saja, hingga Ravi mendesah berulang kali sambil terus mengikuti Esa yang berjalan santai. Sekitar lima menit berselang, Esa berhenti di salah satu toko perhiasan. Tokonya memang tidak begitu besar, tetapi Esa meyakinkan Ravi jika kualitas perhiasan di sana sudah tak perlu diragukan lagi.
“Mbak, saya mau lihat cincin buat lamaran teman saya ini. Ada, kan?” tanya Esa, meliarkan pandangan ke sekitar toko.
“Oh, sebentar.” Pelayan itu menunduk dan sedikit berjongkok, lalu menunjukkan sepasang cincin indah.
Secepat mungkin Ravi merasa tertarik dengan cincin yang baru saja ditunjukkan. Dia menyelidik cukup intens tanpa mengatakan apa-apa. Di sampingnya, Esa tersenyum memberi isyarat agar pelayan tadi segera membungkus cincin tersebut.
“Ngomong apa, kek. Diem mulu,” ujar Esa sambil menyenggol Ravi cukup keras.
Ravi terkesiap, cincin yang sejak tadi digenggamnya kini secara tak sadar dilepaskan begitu saja. “Cari yang lain, yuk. Cincin itu pasti mahal, Sa. Duit aku pasti kurang.” Ravi berbisik, tetapi Esa tidak memedulikannya.
“Ini cincinnya, ya. Ini totalnya.” Pelayan itu menyerahkan kotak cincin lengkap dengan tagihannya.
“E-eh, Teh. Kok main bungkus aja, sih?” protes Ravi. Peluhnya bercucuran menuruni pelipis, sedangkan Esa masih saja tak acuh.
“Biar aku tambahin. Nih,” seru Esa mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. “Makasih ya, Teh. Yuk, balik.” Esa bergegas meninggalkan toko tersebut seraya membawa cincin yang sudah dibayarnya tadi. Ravi terpekur melihat sikap Esa yang aneh karena tiba-tiba mau membayarkan cincinnya segala. Sampai di parkiran, mereka tetap tak saling bicara satu sama lain. Ravi duduk di bagian kemudi, sedangkan Esa di jok samping.
“Toko itu langganan ibuku. Dulu waktu Ibu masih ada, aku sering nganterin ke sana. Makanya aku berani jamin kalo kualitas barangnya bagus.” Tanpa diminta, Esa membuka penceritaan.
“Soal uang tadi, anggap aja itu sebagai denda karena dulu aku udah berusaha merusak kebahagiaan kamu sama Danika. Aku udah janji sama diri sendiri, apa pun yang terjadi nanti, aku akan selalu ada buat bantu kamu, bantu Karla, Danika, dan yang lainnya. Nggak perlu aku kasih alasannya lagi, kan?” Tatapan Esa masih tertuju pada jalanan di depannya.
“Makasih banyak, Sa. Aku nggak tau harus bilang apa lagi. Kamu emang sahabat terbaik.”
“Aku nggak sabar nunggu hari bahagia kamu sama Danika, Rav. Kalian harus sama-sama terus, ya.” Esa memalingkan wajahnya pada kaca samping.
Sejak tadi, dia memang merasakan kesulitan menahan gejolak di dada sampai akhirnya air mata itu sedikit pecah. Ravi tidak menjawab dan tetap fokus mengemudi. Perjalanan hari ini begitu berkesan bagi Ravi. Semesta memang tak pernah salah mempertemukannya dengan Esa. Dulu, mereka memang pernah berselisih paham, tetapi bukan berarti kesetiakawanan keduanya memudar begitu saja.
“Rav, bisa anterin aku ke makam Ibu, nggak?”
“Oh, oke.” Kemudi Ravi sedikit dipercepat. Tanpa bertanya pun, Ravi sudah tahu di mana pemakaman Bu Oki. Kedua pemuda itu sudah seperti saudara, saling mengetahui satu sama lain, tak jarang berbagi apa pun yang dimiliki.
Sepuluh menit berlalu, mereka sampai di tempat pemakaman Bu Oki. Tadinya Ravi ingin ikut serta ke dalam, tetapi Esa mencegahnya. Ah, Ravi tak ingin berdebat dan memilih menunggu di dalam mobil. Selama menunggu Esa kembali, Ravi membuka beberapa pesan grup yang sejak tadi tak henti membuat handphone-nya bergetar. Grup K’DER GJ, nama baru persekutuan mereka setelah Gani dan Jaka ikut serta di dalamnya.
Jaka:
Aku ga sabar liat Danika pake kebaya. Hahahaha.
Danika:
Gandeng!
Lagian siapa juga yang mau pake kebaya? Haro pisan!
Karla:
Lah, jgn begitu, dong. Kan itu hari special.
Nanti aku dandanin, deh!
Tapi jgn lupa bayarin ketring kalo nanti aku sama Gani nikah.
Wkwkwk.
Jaka:
Eh, si Esa, Gani, sama Ravi ke mana, nih?
Kalo Ravi mah, pasti lagi atur nafas karna sesak mau lamaran. Awas bengek!!
Ravi tertawa sendiri membaca deretan chat konyol itu. Mereka seakan tak pernah kehabisan cara untuk terus menggodanya dengan Danika.
Ravi:
Kangen, Jak?
Sibuk nyari dana buat lamaran, euy.
Pinjeminlah.
Karla:
Dih, naon, pinjem-pinjem.
Danikaa! Kamu jgn mau dilamar Ravi klo duitnya hasil minjem, apalagi minjem dari si Jaka.
Danika:
Pipis di terminal lw panjang ge bayar ya, Kar. Kes lagi, nggak ada minjem-minjeman.
Sedang asyik berbalas chat, Esa kembali dengan wajah sedikit muram. Setelah mengantarkan Esa pulang, Ravi juga berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Dia tidak ingin mengganggu suasana hati Esa yang dirasa sedang kurang baik.
Sekembalinya ke rumah, Esa teringat permintaan Pak Idan semalam. Orang yang disayanginya itu meminta izin untuk menikah lagi. Jauh di dalam hati, Esa terpukul ribuan kali. Dia belum siap menerima kehadiran ibu tiri di dalam kehidupannya. Akan tetapi, jika menolak keinginan ayahnya, Esa takut melukai hati sosok yang sudah sabar menjaganya selama ini.
Itulah alasan mengapa sejak tadi Esa tak begitu ceria. Bukan hanya sedih karena kembali mendatangi tempat favorit ibunya, Esa juga memikirkan permintaan sang ayah yang terasa sangat berat. Batinnya tertekan, jiwa yang kukuh itu larut dalam kebimbangan tak tentu tujuan. Esa tak berani menceritakan hal ini kepada siapa pun, termasuk para sahabatnya. Dia sudah cukup menyusahkan mereka dan untuk saat ini, biarkan jiwanya sendiri yang menguatkan diri.
Langkah gontai itu diseret menuju ruang tengah. Esa bergeming, menatap lamat foto keluarga di sana. Wajah Bu Lala tersenyum penuh kebahagiaan, sehingga mengundang tangis yang sulit ditahan bagi Esa. Dengan posisi yang masih berdiri, Esa membiarkan air matanya terjatuh bebas. Semalang inikah nasibnya?
“Kuat, Sa. Jangan nangis, jangan lemah kayak gini!” rutuknya, menjambak rambut frustrasi. Cepat-cepat Esa menyeka air mata dan melanjutkan langkahnya ke kamar. Saat melewati kamar orang tuanya, Esa melihat sang ayah sedang duduk di atas sajadah. Tangannya terangkat, suara permohonan sekaligus merengek terdengar begitu jelas. Batin Esa kembali porak-poranda. Dia sudah keterlaluan pada ayahnya sendiri karena tak menjawab apa-apa saat dimintai izin.
Ayah, maafin aku. Esa memelas dalam hati dan sesegera mungkin berlari ke kamarnya.
Sosok yang kuat akan jatuh ketika hatinya terluka. Esa yang selama ini dianggap keras kepala pun bisa menangis sesenggukan karena persoalan hidup. Baginya, ujian yang diberikan saat ini sama besarnya dengan kepergian Bu Lala tempo hari. Esa tidak kuat, hatinya hancur perlahan.
***
Hampir satu jam berlalu, lagu yang sama itu terus menyemarakkan telinga Esa. Lagu milik Andmesh berjudul “Hanya Rindu” seakan mewakili perasaannya saat ini. Esa benar-benar merindukan sosok ibu di rumah, wanita yang dengan sepenuh jiwa selalu melakukan apa pun untuk dirinya dan sang ayah.
“Bu, kalo aja Ibu masih ada di sini, mungkin Esa nggak akan ngerasain kesepian kayak sekarang. Esa nyesel, Bu. Kenapa dulu waktu Ibu masih ada, Esa lebih banyak waktu di luar daripada di rumah sama Ibu.” Esa berbincang dengan dirinya sendiri. Lantunan lagu Andmesh pun masih terus diputar olehnya.
“Bu, Ayah pengen nikah lagi. Esa harus apa, Bu? Esa nggak bisa gantiin Ibu di rumah ini sama siapa pun. Tapi Esa juga kasihan sama Ayah. Esa tau, Ayah kesepian di rumah, Bu. Esa bingung.” Esa duduk memeluk lututnya sendiri dengan perasaan tak karuan. Ingin rasanya berteriak pada semesta, lalu mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuasa.
[1] Kamu


 yulitriyuliani
yulitriyuliani