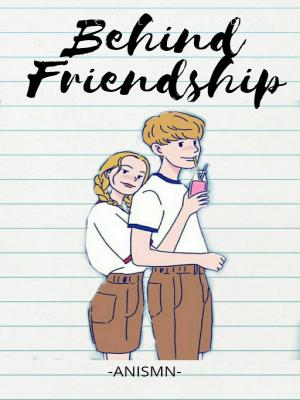Sejauh mata memandang, lukisan-lukisan bergaya seni mahal itu terpajang dengan rapi. Orang-orang hilir mudik, mulai dari hanya sekadar melihat-lihat, memotret, atau saling bernego untuk mendapatkan harga terbaik. Sesekali di antara mereka ada yang berbisik, memperbincangkan sebuah lukisan. Benar-benar malam yang ramai.
Sejak tadi, Karla hanya mengikuti Esa tanpa bertanya atau sekadar ikut berkomentar. Mood-nya sedang tidak bagus, apalagi dia menyadari jika yang dilakukannya tadi adalah kebodohan. Tak seharusnya Karla menampar Gani dan mengatakan tak mau melihat cowok itu lagi di hadapan Danika dan Jaka. Bukankah hal itu akan menambah perkara saja?
“Sa, haus, nih. Beli minum dulu, yuk!” ajak Karla, akhirnya bersuara lagi setelah hampir lima belas menit berkeliling di pameran.
“Kita ke minimarket aja, ya. Sekalian aku mau ngambil uang.” Esa tertegun menatap Karla dan menunggu jawabannya.
Karla menyetujui tanpa berkomentar apa-apa lagi. Esa menuntun Karla melewati kerumunan orang yang semakin malam malah semakin ramai. Setahu Esa, pameran ini akan dibuka sampai pukul sembilan malam. Jadi, tidak mengherankan kalau beberapa di antaranya memilih datang selepas pulang bekerja.
Keduanya berhenti di sebuah minimarket sekitar kawasan Asia Afrika. Karla memesan minuman kaleng dan menunggu di luar, sedangkan Esa bertugas membelinya ke dalam. Selama menunggu Esa, Karla mengedarkan pandangannya ke sekitar jalan. Lampu-lampu menyala menerangi jalan, kendaraan tak henti melintas di hadapan. Belum lagi orang-orang yang memilih berjalan kaki di sekitar trotoar, menambah semarak pusat kota malam ini.
Perlahan Karla mengeluarkan handphone dari saku celana. Dia mendapati beberapa WhatsApp yang dikirimkan oleh Danika dan Gani. Senyum kecutnya mengembang, tetapi untuk saat ini dia tak berhasrat membalas pesan-pesan itu.
“Nih, Kar. Kita di sini aja dulu atau kamu mau aku anterin pulang?” Esa datang membawa beberapa camilan yang diwadahi tas kain. “Motor kamu masih di depan minimarket tempat aku kerja. Nanti aku anterin ke rumah, ya,” lanjut Esa seraya membuka minuman kaleng miliknya.
“Sa, aku keterlaluan nggak, sih?” Karla mendongak, menatap wajah Esa cukup cemas. “Tadi aku ke rumah Gani. Ternyata Gani dan Jaka itu sepupuan, Sa.”
Esa tersedak minuman yang baru saja sampai di kerongkongannya. “Gani sama Jaka? Kok bisa? Terus, apa masalahnya?” Minuman kaleng itu ditaruh di meja, lalu tangannya dilipat di dada. Siap mendengarkan cerita Karla mengenai Gani dan Esa.
“Kamu tau nggak, ada orang yang selalu kirim puisi sama Danika?” tanya Karla, memulai pembahasan. Esa menggeleng.
“Setiap kali kirim puisi sama Danika, orang itu pake inisial RG. Sampai akhirnya Danika cerita sama aku soal itu. Entah kenapa, aku tiba-tiba inget sama Gani, Sa.” Tubuh Karla sedikit melorot dari kursi yang didudukinya.
“Terus kenapa?”
“Ternyata pengirimnya emang Gani. RG itu inisial Raihan Gani. Iya, si Gani. Aku nggak terima sama sikap Gani, Sa. Selama ini dia dibantu Jaka buat kirim puisi-puisi itu,” paparnya, kembali menunduk.
“Kamu cemburu, Kar?” Pertanyaan ini seakan sulit lolos dari kerongkongan Esa. Denyut luka yang dulu pernah dirasa saat mengetahui Karla dan Gani menjalin hubungan, kini seakan kembali datang.
“Huum, aku cemburu. Seharusnya Gani cuma kasih puisi itu buat aku, bukan buat Danika. Meskipun aku paham, tujuan akhirnya biar Danika kasih tau aku soal puisi-puisi itu. Tapi aku tetep nggak terima.”
Rumit. Esa mendesah kasar mendengar cerita Karla. Otaknya saat ini sedang merangkai beberapa kalimat yang mungkin bisa menjadi jalan tengah bagi mereka. Ada kekhawatiran yang membuncah dalam benak Esa, kalau-kalau urusan hati itu akan menjadi bom yang meledakkan keakraban K’DER seperti sebelumnya.
“Kar, aku yakin, Danika nggak mungkin menyikapi puisi Gani secara berlebihan. Aku tau gimana Danika, Kar. Kamu juga pasti tau dia, kan? Kita sahabatan udah lama, udah saling paham gimana sifat masing-masing. Aku rasa kamu kayak gini cuma karena rasa cemburu itu. Kamu masih sayang ya, sama Gani?” Genggaman hangat diberikan Esa, sekadar agar Karla tak merasa canggung ataupun ragu saat menceritakan perasaannya saat ini. Esa tak ingin memaksakan kehendak hanya demi kebahagiaannya seorang diri.
“Sejujurnya ….” Ada jeda cukup lama, hingga yang terdengar hanya deru kendaraan di jalanan. “Sejujurnya aku masih sayang sama Gani, Sa. Ma-maafin aku.” Raut wajah Karla berubah cemas. Tak dapat dimungkiri jika dia takut melukai perasaan Esa.
Senyum simpul terlihat di wajah Esa, sebelum akhirnya berkata, “Nggak usah minta maaf. Waktu kita di basecamp itu kan udah sepakat satu hal. Apa pun yang terjadi, kita harus kompak. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak sama aku, Kar. Kamu berhak bahagia atas pilihanmu sendiri. Meskipun aku nggak bisa milikin hati kamu, tapi seenggaknya aku bisa jadi tempat berbagi buat kamu. Ya kayak sekarang.” Demi apa pun, Esa tengah bertengkar dengan perasaannya sendiri. Kalimat yang terdengar bijak itu memang diucapkannya dengan tulus, semata-mata demi kebaikan semua orang.
“Makasih udah ngertiin aku, Sa. Aku harus minta maaf sama Danika dan Gani. Kamu anterin aku ke rumah Gani sekarang, ya,” pinta Karla, sedikit tidak enak hati. Esa hanya mengangguk, lalu menggenggam tangan Karla menuju motor yang terparkir di sana. Genggaman tangan itu terasa hangat, meski ada hati yang membeku karena luka, rasa, dan seluruh harapan yang harus terkubur sia-sia; Karla tak pernah ditakdirkan untuk Esa.
***
Sepanjang perjalanan menuju rumah Gani di Ujung Berung, Esa berpikir keras tanpa henti. Konsentrasinya dalam mengendarai motor sedikit buyar setiap kali ia menatap Karla melalui kaca spion. Seandainya dahulu dia lebih berani mengatakan perasaan itu pada Karla, mungkin urusannya tak akan semenyakitkan ini. Karla memang pantas mendapatkan Gani, cowok yang lebih dewasa dibandingkan dengan Esa. Namun, mengapa rasanya masih saja sulit untuk menerima kenyataan?
“Di sebelah mana, Kar? Aku kan udah lama nggak pernah ke rumah Gani.” Esa bertanya dengan sedikit memekik agar terdengar.
“Nanti di depan, kamu belok kiri aja, Sa,” jawab Karla, tak kalah berteriak. Sesuai petunjuk, Esa segera berbelok ke arah kiri hingga beberapa meter dari sana, Karla memintanya untuk berhenti. Saat ini di depan mereka sudah terlihat sebuah rumah bercat putih milik Gani. Karla turun dari motor, disusul Esa yang mengikutinya dari belakang.
“Lho? Kalian ngapain di sini?” Sebuah suara mengejutkan keduanya.
“Jaka!” seru Esa, memukul si pemilik suara tadi yang ternyata adalah Jaka.
“Hei, Jak.” Karla menyapa ragu. Rona di wajahnya sudah cukup membuat Jaka paham.
“Ah, Karla. Kenapa tadi siang pergi gitu aja? Kasihan Danika kan, dia jadi pulang naik ojol.” Jaka berdecak, mengamati wajah Karla yang penuh dengan kecemasan.
“Mau ketemu Gani? Yuk, masuk. Dia ada di dalem, kok. Galau seharian gara-gara tadi siang kamu begitu sama dia. Konyol banget kalian itu.” Jaka menggiring Karla dan Esa untuk masuk menemui Gani. Cowok yang baru saja membeli nasi goreng itu tersenyum sendiri, membayangkan kejadian apa lagi yang akan dilihatnya nanti. Tentunya antara Gani dan Karla.
Persis seperti ucapannya, di sana Gani sedang duduk sendirian. “Sana, samperin Gani. Nggak usah takut, dia nggak gigit, kok,” canda Jaka agar ketegangan di wajah Karla sedikit berkurang.
“Temenin aku, Sa.” Pandangan memohon diarahkan Karla pada Esa.
Akhirnya, Esa sepakat untuk menemani Karla menemui Gani, sedangkan Jaka bergegas ke dalam rumah. Dia sudah tidak sabar menikmati nasi goreng sambil menonton drama ala-ala FTV yang akan segera dimulai. Jail sekali pikiran Jaka itu!
“Gan,” sapa Esa, memulai pembicaraan.
Gani pun menoleh dan bangkit. “Esa? Karla?”
“Aku ke sini cuma buat nemenin Karla. Dia bilang, ada sesuatu yang harus disampaikan,” katanya, mendorong Karla agar lebih dekat dengan Gani.
“Karla, ada apa?” Kening Gani mengerut, lalu berjalan menghampiri Karla yang masih saja tertunduk. “Kamu nangis karena sikap bodoh aku itu, kan?”
“Aku minta maaf, Gan. Nggak seharusnya aku bersikap kayak tadi siang. Aku gitu karena–”
“Karena salah paham. Kamu berpikir kalo aku berusaha deketin Danika lewat puisi itu kayak yang aku lakuin sama kamu dulu. Padahal kan nggak begitu. Kamu cuma salah paham aja, Kar,” potong Gani, perlahan mendekati Karla kemudian memeluknya. Esa yang berdiri di sana hanya bisa tersenyum getir menyaksikan dua hati yang pernah dia pisahkan, sekarang malah semakin tak bisa saling kehilangan.
“Kalian harus balikan. Kalo kalian anggap aku ini ada, kalian harus balikan. Tapi jangan balikan cuma demi aku. Aku udah rela kalian bersama lagi. Aku rela, kok,” papar Esa, suaranya sedikit bergetar. Dia memang sedang menguatkan diri agar air matanya tidak terjatuh. Walau sebetulnya, kesedihan sudah mendesak sejak menginjakkan kaki di rumah Gani.
“Bro! Kamu keren banget! Respek,” bisik Jaka yang tiba-tiba datang. Esa hanya tersenyum miris mendengar ucapan Jaka yang terdengar begitu spontan. Aku sakit, Kar! katanya dalam hati.
Gani melepaskan pelukannya dari Karla, lalu berjalan ke arah Esa. Pelukan haru antara Esa dan Gani pun terjadi. Dua orang yang sama-sama menginginkan tempat di hati Karla, tetapi salah satu dari mereka harus mundur penuh ketegaran. Segala sesuatu memang tak selalu sama dengan apa yang diharapkan. Setidaknya, Esa menyadari bahwa saat ini dia sudah melakukan hal benar.
***
Sandi terpekur memperhatikan Ravi yang tidak seceria biasa. Tidak hanya murung, Ravi juga sering mengurung diri di kamar. Sudah beberapa kali Sandi berusaha membujuk Ravi agar mau mencoba sedikit saja memaafkan diri sendiri. Ah, benar! Ravi terluka oleh masa lalunya. Dia merasa menjadi orang yang jahat karena membiarkan ayahnya menanggung beban sendirian.
“Seharusnya aku nggak pergi ke Jogja! Seharusnya aku nggak egois!” Ravi frustrasi sendiri mengingat tingkahnya saat itu.
Handphone yang ditaruh di tempat tidur berdering. Berulang kali benda pipih itu berbunyi, tetapi tak menarik perhatian Ravi sama sekali. Ravi masih asyik dengan perdebatannya sendiri sambil duduk memeluk lutut di balkon kamar. Namun, dering yang kesekian kali berhasil membuat Ravi bangkit dan segera meraihnya. Ravi membanting handphone itu ke sembarang arah dengan penuh emosi. Selang beberapa saat, dia menangis tersedu memanggil-manggil sang ibu. Kegaduhan yang dibuatnya itu berhasil membuat Pak Gio dan Sandi berlari ke kamar Ravi.
Hati Pak Gio teriris dan merasa bersalah karena sudah memberi tahu hal yang seharusnya hanya menjadi rahasia saja. Sandi terisak, memeluk Ravi sangat erat. Dia tidak menyangka jika kakaknya akan sejatuh ini saat tahu bagaimana kondisi ayah mereka selama dirinya berada di Yogya.
“Ayah, maafkan Ravi. Maaf, Ravi sudah menjadi anak durhaka buat Ayah. Seharusnya Ravi selalu ada buat Ayah,” ujar Ravi, suaranya bergetar hebat. Tubuh yang biasanya berdiri kukuh itu, kini tak ayal seperti pohon tua yang akan mati dalam hitungan waktu.
“Jangan minta maaf, Rav. Ayah nggak pernah menganggap kamu sebagai anak durhaka. Enggak sama sekali, Rav. Ayah sayang sama kamu dan ayah juga yakin kalo kamu sayang sama Ayah. Iya, kan?” Air mata sosok paruh baya itu mengalir. Sungguh, rasanya tidak kuasa melihat si sulung terus-terusan menyesali apa yang sudah terjadi.
Sejatinya, tak pernah ada orang tua yang rela melihat anak mereka terluka. Jangankan terluka, susah sedikit saja, hati orang tua akan perih dibuatnya. Itu pula yang dirasakan Pak Gio, apalagi posisinya saat ini harus berperan ganda sebagai ibu sekaligus. Beban Pak Gio sudah cukup besar, tubuhnya semakin ringkih, dan penyakit itu tak pernah absen menggerogoti diri. Pak Gio sungguh sosok yang hebat, setidaknya dia masih bertahan dan terlihat kuat saat kematian merenggut wanita terkasihnya; ibu.
***
Kondisi Ravi yang menyedihkan, akhirnya sampai juga di telinga K’DER, termasuk Jaka dan Gani. Mereka menyesalkan mengapa Ravi tak pernah menceritakan keadaannya itu.
San, gimana kondisi Ravi sekarang? Apa dia masih nggak mau keluar kamar?
Danika mengetik pesan, lalu mengirimkannya kepada Sandi. Di hadapan Danika saat ini sudah ada Karla, Esa, Gani, dan Jaka. Mereka sepakat akan menemui Ravi selepas Magrib nanti.
Ya, begitulah, Kak. Tapi tadi sempet ngobrol sebentar sama aku. Kak … bisa ke sini buat temuin Kak Ravi?
“Hah!” Danika mendesah membaca balasan dari Sandi. Pandangannya menerawang ke sudut jalan yang ramai tetapi terasa sepi baginya.
“Kenapa, Ka? Apa ada kabar terbaru?” seru Gani, menajamkan tatapannya, tetapi Danika menggeleng dengan cepat.
“Aku kira hidup si Ravi nggak akan semalang sekarang. Semenjak ibunya nggak ada, dia emang agak lain,” jawab Karla, menyandarkan punggung. Saat ini, mereka sedang berada di sebuah kafe di bilangan Wastukencana.
“Iya, aku juga mikirnya gitu. Jadi sekarang kita ke sana aja, ya? Aku nggak tega biarin dia kayak gitu, sih.” Esa ikut berkomentar, disambut anggukan dari yang lainnya. Danika sendiri tidak banyak berbicara lagi. Pikirannya kalut membayangkan Ravi di sana, seolah-olah ikut berada di posisi cowok itu.
“Yuk, cabut. Udah kelar azannya.” Gani bangkit, disusul yang lain. Mereka pun meninggalkan kafe dan berharap semesta akan memberikan sedikit kekuatan lagi bagi Ravi.
***
Kehangatan bercampur air mata, begitu nyata terasa di ruangan cukup besar milik Ravi. Saat mereka sampai, Ravi tengah duduk di balkon seraya memandang langit Kota Bandung. Handphone yang dibantingnya tempo hari, masih terlihat menyedihkan di atas nakas. Esa, Gani, dan Jaka terlebih dulu memeluk Ravi, memberikan keyakinan jika semua yang terjadi bukanlah sesuatu yang perlu disesali sedalam ini. Ravi tidak bersalah atas sakit yang diderita ayahnya. Dia juga tidak bersalah ketika memutuskan menyelesaikan sekolah di Yogya bersama bibinya.
Di ambang pintu kamar, Karla memeluk Danika cukup erat. Matanya terasa berat menahan air mata yang sejak tadi sudah berdesakan membentuk perkumpulan. Di sisi lain, Danika hanya mendesah beberapa kali mengingat-ingat cerita Sandi mengenai kondisi ayah dan keadaan Ravi setelah tahu bagaimana kenyataannya.
“Aku mau ngomong sama kamu, Rav.” Suara Danika berhasil mengalihkan perhatian Ravi. Tatapan mereka beradu, Ravi tak menyangka jika hari ini dia akan berurusan dengan Danika. “Jadi cowok itu jangan payah kayak gini!” cetus Danika. Walaupun ucapannya terdengar tegas, sebetulnya hati Danika tak kuasa menahan ledakan kesedihan yang menerpa.
“Aku udah tau keadaan ayah kamu! Sandi udah cerita semuanya sama aku, sama yang lain. Tapi, kamu bodoh kalo kayak gini. Apa kamu mau menyia-nyiakan kesempatan jaga ayah kamu lagi, ha? Harusnya kamu mikir, Rav! Kamu nggak boleh menyalahkan diri terus-menerus. Kamu nggak boleh kayak gini, RAVI GANENDRA!” Cara bicara Danika menggebu-gebu, hingga orang-orang di sana menatapnya takjub.
“Aku nggak mau lihat kamu kayak gini, Rav. Aku sayang sama kamu.” Danika tertunduk, buliran air mata benar-benar pecah di hadapan Ravi. Kontan saja yang lainnya saling berpandangan, apalagi saat mendengar Danika mengutarakan perasaannya.
Dada Ravi sesak melihat Danika menangis. Seumur hidup, dia memang tak menyukai ketika ada seseorang yang menangis di hadapannya. Ravi bangkit dan memeluk Danika yang masih berdiri di sana. Dia membiarkan sosok terkasihnya itu meluapkan tangis yang mengiris perasaan.
“Aku juga sayang sama kamu, Ka,” bisik Ravi, semakin membuktikan jika perasaannya pada Danika tak pernah berubah sama sekali.
Hati siapa yang tak tersentuh oleh keduanya? Esa yang dulu pernah mati-matian menghalangi hubungan mereka pun tak bisa menyangkal jika dia terharu melihat Ravi dan Danika. Air mata Esa luruh seiring dengan egois yang tak lagi menguasai hatinya. Esa banyak belajar tentang dirinya sendiri melalui orang lain, melalui sahabat-sahabatnya.
“Kemarin aku nonton adegan romantis Gani sama Karla. Sekarang malah Danika sama Ravi. Lah, aku kapan?” celetuk Jaka, benar-benar merusak suasana.
“Berisik banget si Jaka, ya!” Esa menjitak kepala Jaka.
***
Kejujuran yang sudah dilakukan Danika pada diri sendiri dan Ravi, benar-benar seperti ledakan semangat baru dalam hidupnya. Selama ini Danika menyadari jika dirinya terlalu berusaha baik-baik saja, padahal sebetulnya dia hancur berantakan. Apalah artinya terlihat baik-baik saja di mata orang lain, kalau pada nyatanya hanya menghancurkan diri sendiri? Bodoh!
Danika nyengir menyelesaikan tulisannya hari ini. Tepat di bagian akhir lembar kerja itu, dia menuliskan “TAMAT” dan mulai mempersiapkan hal lain agar tulisannya bisa dikirim ke penerbit. Harapannya, cerita yang dia tulis bisa menginspirasi banyak orang, hingga membuat siapa pun yang membacanya ikut hanyut ke dalam alur cerita. Jika dihitung-hitung, Danika nyaris menulis cerita itu selama satu tahun. Waktu yang tidak sebentar, karena dia juga harus mengurus kuliahnya.
“Aduh, rajin banget kamu, Ka.” Bunda menghampiri Danika dan mengelus kepalanya, kemudian kembali berkata, “Ayo, makan dulu. Nanti dilanjut lagi,” katanya, beranjak duduk di tempat tidur sambil terus mengamati putri kesayangannya.
“Hehe, iya, lagi rajin nih, Bun. Oh ya, Bunda tau nggak? Ayah Ravi sakit, lho.” Danika menatap Bunda penuh kesedihan.
“Oh ya? Sakit apa?” Raut penasaran begitu tercetak jelas di wajah Bunda.
Danika pun bangkit menghampiri bundanya sambil berucap, “Kanker sel plasma, Bun,” desah Danika.
Ayah Ravi didiagnosis mengidap kanker yang menyerang sel plasma, yaitu salah satu jenis sel darah putih pada sumsum tulang penderita. Untuk saat ini, penyebabnya memang masih belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, pertumbuhan sel plasma abnormal (myeloma) dapat berlipat ganda dengan cepat dan melebihi pertumbuhan sel normal, lalu menghasilkan antibodi yang justru merugikan bagi tubuh. Dalam dunia kedokteran, penyakit ini disebut multiple myeloma. Bunda terkesiap mendengarkan penuturan Danika. Terbayang di benaknya, kondisi Ravi pasti buruk kala mengetahui sang ayah tidak baik-baik saja.
“Kalian harus kuatin Ravi, terlebih kamu, Ka. Bunda tau, hati kamu ini menyayangi Ravi melebihi dari seorang sahabat. Benar, kan?” Tangan lembutnya menyentuh dada Danika. Mengisyaratkan kalau hati anaknya itu benar-benar terpaut pada Ravi.
Danika pun mengangguk, lalu memeluk Bunda dengan erat. Keduanya larut dalam kehangatan, seakan perang dingin yang pernah terjadi itu hanyalah omong kosong belaka. Di dalam pikiran Danika, muncul beberapa hal yang ingin dilakukan untuk Ravi. Semoga dia bisa menjadi penguat Ravi, hingga tak lagi merasa diri paling bersalah.


 yulitriyuliani
yulitriyuliani