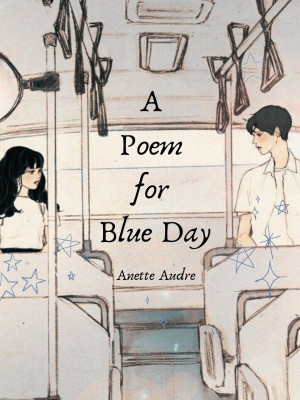“Bagaimana? Ada kendala dengan tugasnya?”
Sunyi. Seisi kelas hanya menunduk, sementara kau bertopang dagu, menatap papan tulis tanpa ekspresi. Sesekali kau melirik tugas yang diberikan guru satu minggu lalu—menulis dengan topik “Impianku”.
“Ada yang mau menceritakan impiannya?” Suara Bu Ina, guru Bahasa Indonesia, memecah kesunyian. Masih tak ada yang bersuara. Menulis saja sudah sulit, dan sekarang harus menceritakannya? Akankah ada yang tertarik mendengarnya?
Mungkin tidak.
Namun, nyatanya, kini kau menatap Bu Ina datar dengan tangan mengacung, kemudian meninggalkan tulisanmu di meja dan maju ke depan. Dua detik kemudian, puluhan pasang mata menatapmu ingin tahu, menantimu bicara.
“Baiklah, jadi apa impianmu?” tanya Bu Ina, mencoba memancingmu untuk mulai bercerita.
“Aku ingin menjadi seperti Raditya Dika.”
Hanya satu kalimat.
Kau menemukan impianmu di usia delapan tahun—menjadi penulis.
*
“Apa impianmu?”
Kau hanya diam, sementara jemarimu masih terus menari-nari lincah di atas kibor laptop.
“Hei,” panggil laki-laki itu. “Kau harus menjawab saat ada seseorang bertanya.”
Kau menoleh dari laptopmu dan menatapnya tepat di mata. Tampaknya kau teringat dengan pertanyaan yang sama, yang diajukan padamu saat berusia delapan tahun.
“Aku ingin menjadi seperti Raditya Dika,” ujarmu datar. Jawaban yang sama seperti dua belas tahun lalu.
“Penulis?” tanyanya, yang lebih terdengar seperti sebuah pernyataan. “Mengapa?” Ia mencondongkan tubuhnya ke arahmu dan berujar, “Apa karena itu sedang tren? Kau tahu, akhir-akhir ini banyak yang ingin menjadi penulis dengan ekspektasi menjadi terkenal dan menghasilkan banyak uang.”
“Terkenal dan uang itu hanya bonus.”
“Bukan itu?” Laki-laki itu menatapmu dengan salah satu alis terangkat. “Lalu, apa maksudmu ingin menjadi seperti Raditya Dika?”
Kau mengangkat bahu acuh tak acuh. “Itu hanya istilah yang kubuat sendiri.”
Ia mengernyit bingung, tetapi kemudian ia mengangguk dan kembali bertanya, “Jadi, mengapa kau menjadikan penulis sebagai impianmu? Padahal, kau tahu, ‘kan, sebagian besar orang Indonesia tidak suka membaca.”
“Apa harus ada alasan untuk memiliki impian?”
“Kata orang, selalu ada alasan di balik segala sesuatu.”
Salah satu sudut bibirmu terangkat. “Aku tak pernah benar-benar memikirkannya. Aku hanya melakukannya.” Kau terdiam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, “Aku terlalu sering melakukannya, hingga akhirnya aku mencintainya dan menjadikannya sebagai impianku. Duniaku.”
Laki-laki di hadapanmu terdiam, sepertinya sedang berusaha mencerna apa yang baru saja kaukatakan. Kau menutup laptopmu dan kembali buka suara, “Masih ada banyak hal yang bisa kucapai dengan tulisan-tulisanku. Bisa dikatakan, ini ialah impian yang tak pernah usai—selalu bisa berkembang lebih dan lebih lagi. Impian seumur hidup, mungkin?”
“Kau benar-benar menyukainya?”
“Aku mencintainya,” koreksimu. “Aku tak pernah tanggung-tanggung ketika mencintai sesuatu, atau juga seseorang, kau tahu?”
Ya, kau hanya mencintainya. Itu saja.
Karena menulis adalah duniamu.


 amandajgby
amandajgby