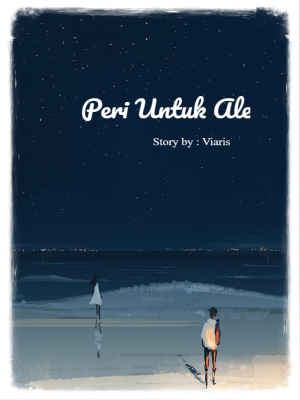“Apa pun yang kau pikirkan, itulah jawabannya.”
Jonatan menatapku dengan dahi berkerut. “Jawabanmu itu ambigu,” ujarnya. “Katakan dengan benar. Kau menyukainya atau tidak?”
Aku hanya diam dan mengangkat bahuku acuh tak acuh.
Melihat reaksiku, lelaki itu bergumam, “Kau menyukainya.” Ia mengusap dahinya yang basah oleh keringat, menyandarkan punggungnya ke sandaran bangku, dan berkata, “Tapi dia tidak menyukaimu,” ujarnya. “Kau tahu, kau itu erotomania. Kau memang menyukainya—jangan membantahnya—dan kau mengira ia menyukaimu, padahal tidak sama sekali. Ia hanya memanfaatkanmu,” katanya lagi. Ia menghela napas sebelum akhirnya melanjutkan, “Kau bisa percaya padaku, Eirene. Kau tahu itu, bukan?”
Aku hanya diam, mencoba untuk mencerna kata-katanya. Ia juga diam, sibuk dengan pikirannya sendiri, dan keheningan pun menyusup dengan leluasa di antara kami. Keheningan yang nyaman dan menenangkan.
“Jo,” aku memanggil sahabatku itu.
Ia hanya melirikku. Aku pun melanjutkan, “Apa aku harus melupakannya?”
“Terserah kau saja.”
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba memenuhi paru-paruku dengan udara segar di sore hari ini, dan mengembuskannya pelan. “Apa yang spesial dalam dirinya?”
“Kenapa kau bertanya padaku? Seharusnya kau lebih tahu perasaanmu sendiri,” ujarnya datar. Matanya menatap lurus-lurus ke arah danau yang ada di depan kami.
Aku hanya mengangkat bahu, sama sekali tidak ingin merespon kata-katanya. Melihatku yang hanya diam, Jonatan menoleh dan menatapku. “Sebenarnya, aku sangat penasaran,” katanya. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, “Apa yang begitu spesial dalam dirinya, sehingga kau begitu menyukainya seolah tak bisa—atau tak ingin—melihat siapa pun lagi?”
Aku menatap danau yang ada di depan kami lurus-lurus, mengangkat bahuku acuh tak acuh, dan berkata, “Apa pun yang kau pikirkan, itulah jawabannya.”
***
Siapakah teman terbaik yang pernah kau miliki dalam hidupmu?
Jika kau bertanya siapa teman terbaik yang pernah kumiliki, maka kesepian adalah jawabannya.
Ya, aku tahu, ini memang terlihat aneh. Tak ada satu pun manusia di dunia ini yang ingin berteman dengan kesepian, bahkan jika diberikan miliaran uang sebagai imbalannya. Tapi nyatanya aku telah berteman, bersahabat karib dengannya selama hampir empat tahun.
Aku bertopang dagu angkuh, menatap langit malam dari jendela kamarku, sama sekali tak peduli dengan dinginnya angin musim gugur yang seakan mencoba menggelitik wajahku. Sesekali aku menghela napas, lalu mengembuskannya perlahan. Kata-kata Jonatan, sahabatku, masih terus terngiang-ngiang di telingaku sejak sore tadi. Harus kuakui, Jonatan memang benar. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku benar-benar menyayanginya—laki-laki itu. Mencintainya. Bahkan walaupun ia hanya melihatku ketika ia membutuhkanku. Walaupun—menurutku—itu bahkan jauh lebih menyakitkan daripada tak pernah dilihat sama sekali.
Kata orang, sangat sulit untuk melupakan cinta pertamamu. Ya, laki-laki itu adalah cinta pertamaku. Katakan saja aku ini bodoh. Aku memang bodoh, aku tahu. Terlalu bodoh karena menjadikan orang sepertinya sebagai cinta pertama. Terlalu bodoh untuk mengharapkannya tetap ada di sampingku di saat ia mencintai gadis lain.
Ah, dasar. Cinta memang mampu membuat seseorang buta, bukan?
Aku tersadar dari lamunanku ketika tiba-tiba ponselku berdering. Jonatan.
“Kau belum tidur?”
“Belum,” gumamku, tetap memandang langit malam di depanku dengan tatapan kosong.
“Biar kutebak, sekarang kau pasti sedang berdiri di depan jendela kamarmu dan memandang langit malam, bukan?” sahutnya dari seberang sana. “Katakan jika aku salah.”
Tanpa kusadari, seulas senyum tersungging di bibirku. Ia mengenalku dengan sangat baik. Bisa kubayangkan ia mengatakannya sambil tersenyum jenaka.
“Eirene, apa kau masih di sana?” suaranya kembali terdengar, menyadarkanku dari lamunan.
“Ah, ya,” gumamku
“Apa yang sedang kau pikirkan, hm?”
Aku menggeleng, masih dengan seulas senyum di bibirku.
“Eirene?”
“Ah,” gumamku, tersadar bahwa ia tak mungkin bisa melihat gelenganku. “Bukan apa-apa.”
Kudengar Jonatan mendesah perlahan sebelum akhirnya berkata, “Jangan pikirkan dia,” ujarnya. “Buang-buang waktu saja.”
Aku mengerjap beberapa kali, lalu melangkah ke tempat tidurku, dan duduk di sana sambil memeluk guling dengan tangan kiri—masih dengan ponsel di tangan kanan. “Aku tidak memikirkannya.”
Kali ini Jonatan mendesah keras. “Sampai kapan kau mau terus berbohong padaku?” ujarnya. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, “jangan memikirkannya lagi. Buang-buang waktu. Tidak ada gunanya. Kau juga tahu dia hanya memanfaatkanmu, bukan?” Ia kembali terdiam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan dengan serius, “akan ada seseorang yang menyayangimu sama seperti rasa sayangmu padanya, bahkan mungkin lebih dari itu,” katanya. “Jadi, hentikanlah.”
Aku hanya diam, mencoba mencerna semua perkataannya.
“Tak usah terlalu memikirkan kata-kataku,” Jonatan kembali buka suara. “Istirahatlah. Jangan terlalu sering melihat langit malam dari jendela. Udara malam tidak baik untuk kesehatanmu.”
Aku hanya menggumam sebagai jawaban, kemudian ia berujar, “Aku akan menutup telepon, oke? Selamat malam.”
Aku meletakkan ponselku di nakas samping tempat tidurku. Kupeluk gulingku lebih erat dari sebelumnya, kupejamkan mataku perlahan, lalu mendesah. Aku benar-benar tidak tahan untuk tidak memikirkan kata-kata sahabatku tadi.
Yah, sebenarnya aku benci—bahkan sangat benci—untuk mengakui ini, tapi nyatanya lagi-lagi aku harus mengakui kalau dia benar. Tak ada gunanya. Buang-buang waktu. Tapi tetap saja, aku tahu hatiku memberontak terhadap kata-katanya.
Ah, dia datang lagi. Aku tahu dia pasti akan datang, terutama di saat-saat seperti ini. Layaknya angin, kehadiran sahabat baikku itu dapat kurasakan dengan mudah meskipun ia tidak tampak. Mungkin itu karena pertemanan kami yang sudah terjalin cukup lama. Dan kini, salah satu sudut bibirku terangkat ke atas, seolah menyambutnya dengan senang hati.
Aku tahu, aku dikelilingi banyak orang yang menyayangiku dengan tulus. Aku mengetahui fakta itu dengan baik, dan aku menghargainya. Namun tetap saja, rasanya percuma saja berinteraksi dengan mereka. Aku tidak pernah bisa mengusir rasa sepiku, bahkan ketika aku hanya sekadar mengobrol dengan salah satu dari mereka. Atau malah mungkin aku tidak ingin mengusirnya? Entahlah, aku tidak tahu. Aku hanya mengetahui satu hal: rasa sepi itu tetap ada dan takkan pernah pergi meninggalkanku, dan tak ada satu orang pun yang mampu mengusirnya. Kecuali dia.
Hanya dia yang mampu mengusir rasa sepiku tanpa bekas. Aku benar-benar merindukannya, sungguh. Kehadirannya sudah lebih dari cukup untukku. Namun, kerinduanku padanya sepertinya tak akan pernah terkatakan.
Meski begitu, aku hanya ingin bersamanya. Laki-laki itu.
Heaven Christie.
***
“Lama sekali dia,” gerutuku pelan seraya membalik halaman novel yang sedang kubaca.
“Roti cokelat kesukaanmu.”
Aku tertegun, menatap sebungkus roti cokelat yang terletak tepat di sebelah kakiku. Aku pun mendongak, dan kulihat dia berdiri di depanku.
Jonatan Williams.
Aku mendengus, kemudian berkata, “Kenapa kau lama sekali, huh?”
Jonatan tidak menjawab, hanya menyunggingkan seulas senyum sebagai permintaan maaf. Ia lalu duduk di bawah pohon yang sama dengan gadis itu, di sisi yang berlawanan.
“Ah, aku selalu suka tempat ini,” desah Jonatan ketika melihat apa yang ada di sekitarnya. Taman yang luas dan dipenuhi dengan rerumputan, jalan-jalan setapak, dan pohon-pohon yang besar dan teduh. Suasana taman di sore hari ini tidak terlalu ramai. Selain mereka berdua, hanya ada beberapa orang yang bersepeda dan jogging di jalan setapak, dan ada juga yang duduk-duduk santai di tengah rerumputan, entah itu berpiknik atau memanggang barbeque.
“Apa yang kau baca, hm?” tanya Jonatan. Matanya masih terus memandang ke depan. “Apa yang begitu asyik di dalam buku itu sampai-sampai kau seakan lupa bahwa aku ada di sini?”
“Ini novel. Kau tidak akan mengerti apa yang asyik dari ini,” sahutku, masih fokus dengan novelku. “Bacaanmu hanya komik detektif yang membosankan itu, kau tahu?”
Diam-diam, Jonatan tersenyum. Ia selalu senang menggoda Eirene di saat gadis itu sedang membaca novel seperti sekarang. Menurutnya, Eirene terlihat begitu menggemaskan ketika digoda.
“Berhentilah membaca,” kata Jonatan lagi. “Temani aku, sebentar saja.”
“Kau bisa menunggu. Aku sudah sampai di pertengahan cerita, dan ini benar-benar seru,” kataku ringan, masih terus membaca.
“Novel tentang apa?” tanya Jonatan lagi, merasa penasaran.
“Apa, ya?” aku berpikir-pikir. “Cinta tak terbalas.”
Mendengar jawaban sahabatnya itu, Jonatan terdiam. Keheningan pun menyusup di antara mereka. Bagi Eirene, itu adalah keheningan yang nyaman, namun tidak bagi Jonatan. Ia teringat dengan percakapannya dengan Eirene semalam.
“Eirene.”
“Apa?” sahutku seraya menyelipkan pembatas buku di halaman terakhir yang kubaca, menutup novelku, dan beralih ke sebungkus roti cokelat dari Jonatan. Aku benar-benar lapar, sungguh.
“Kau.. apa kau masih sering memikirkannya?” tanya Jonatan ragu.
Aku tertegun sejenak, lalu akhirnya buka suara, “Kenapa kau bertanya?”
“Hanya ingin tahu saja,” sahut Jonatan ringan, padahal ia tahu hatinya dipenuhi rasa penasaran yang teramat sangat.
“Kau juga tahu kalau dia masih memiliki tempat di hatiku, Jo,” sahutku. Seketika rasa sakit kembali menyeruak masuk dan menggores hatiku.
Jonatan mengembuskan napas pelan, menyandarkan kepalanya di batang pohon, lalu memejamkan matanya. Sampai kapan kau akan seperti ini?
“Kapan kau akan melihatku?” tanya Jonatan lirih.
Aku mengernyitkan dahi, tak mengerti dengan maksud ucapannya. “Aku selalu melihatmu."
Jonatan bangkit dari duduknya, lalu menghampiriku. Ia duduk di depanku dan berkata, “Kapan kau akan melihatku?” ulangnya—kali ini dengan penekanan di setiap kata—sambil menatap mataku dengan sangat serius.
Aku menatapnya dengan tatapan bingung. Aku benar-benar bingung, sungguh. Mengapa ia masih bertanya kapan aku akan melihatnya ketika ia bahkan sudah berada tepat di depanku?
Jonatan menghela napas. “Eirene, dengarkan aku baik-baik,” ia terdiam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, “kau selalu melihat laki-laki itu. Kau selalu menunggunya, merindukannya, dan mengharapkannya,” ujarnya. “Tapi, kenapa kau tidak pernah, tak pernah sekali pun melihatku?”
Seakan baru tersadar akan sesuatu, mataku melebar ketika mendengar kata-katanya. Aku baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika ia kembali buka suara, “Aku selalu melihatmu, Eirene. Aku selalu menunggumu. Tapi, selama ini yang kau lihat hanyalah dia, dia, dan dia. Heaven Christie,” katanya. “Kau tak pernah sekali pun memalingkan wajahmu darinya. Kau selalu merasa terluka, tapi kau terus melihatnya. Sampai kapan kau mau terus-menerus seperti ini, Eirene? Kapan kau akan melihatku?”
“Jonatan,” gumamku, tak tahu apa yang harus kukatakan.
Jonatan menatap mataku dalam, lalu berkata, “Izinkan aku mengobati lukamu, Eirene. Aku tidak ingin melihatmu terluka lebih lama lagi. Biarkan aku mengobati lukamu. Aku ingin selalu bersamamu, menemanimu, menjagamu, dan melindungimu,” katanya dalam satu tarikan napas. “Jadi, apa kau mau?”
Aku hanya diam, tak merespons kata-katanya. Kutatap mata lelaki itu, dan ia membalas tatapanku dengan tatapannya yang dalam dan menenangkan.
Baru kusadari, lelaki inilah yang selalu ada di sampingku. Ia selalu berusaha membuatku tertawa, menjadi pendengar yang baik, dan selalu siap untuk meminjamkan pundaknya, ketika aku ingin menangis. Ia selalu berusaha menjagaku dan melindungiku dengan caranya sendiri. Di sampingnyalah aku selalu merasa aman dan nyaman. Kuingat lagi pelukannya yang hangat dan menenangkan, yang seolah selalu ingin mengatakan, “Semuanya akan baik-baik saja, dan akan selalu baik-baik saja.” Dan selama ini, aku selalu menutup mataku akan kehadirannya, dan justru mengharapkan seseorang yang bahkan tak bisa diharapkan.
Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Aku terlalu sibuk dengan Heaven dan sedih karenanya, sementara ada seseorang yang juga merasa sedih karena aku. Aku tak pernah melihat apa yang ada di dekatku, dan malah melihat apa yang tak bisa kugapai. Kenapa aku baru menyadarinya?
Kulihat Jonatan masih menatapku dengan tatapannya yang dalam dan menenangkan itu. Ia terlihat begitu tenang, namun aku tahu, ada banyak hal tersembunyi di dalam hatinya. Persahabatan kami selama tujuh tahun lebih dari cukup untuk membuatku mengetahui bahwa ada sesuatu yang selama ini selalu ia tahan, dan kini ia tak sanggup menahannya lagi.
Aku memeluknya erat. Mendadak aku merasa ingin menangis, dan seketika air mataku mengalir deras dan membasahi baju laki-laki itu. Kurasakan tubuh laki-laki itu menegang karena kaget, namun aku tak peduli. Aku justru memeluknya semakin erat, seolah tak ingin ia terlepas dari genggamanku.
Aku melepaskan pelukanku. Jonatan menatapku lembut dan berkata, “Aku tahu, aku memang bukan dia. Aku mungkin tidak bisa menjadi sepertinya. Tapi, aku akan berusaha menjagamu dengan caraku sendiri,” ia menghela napas dan mengembuskannya perlahan sebelum akhirnya melanjutkan, “Kau bisa percaya padaku, Eirene. Kau juga tahu itu, bukan?”
Aku mengangguk, dan Jonatan kembali menarikku ke dalam pelukannya. Bisa kudengar dengan jelas suara detak jantungnya. Benar-benar hangat, nyaman, dan menenangkan.
“Jangan menangis lagi. Kau terlihat sangat jelek ketika menangis,” ujarnya lembut. Aku pun mengangguk dalam pelukannya sebagai jawaban.
“Aku menyayangimu. Aku sangat mencintaimu, Eirene Gabriella.”


 amandajgby
amandajgby