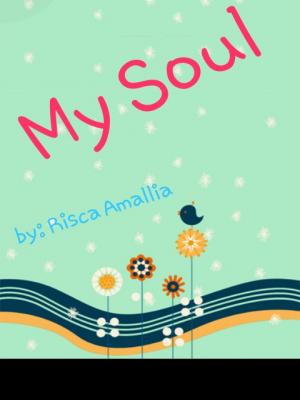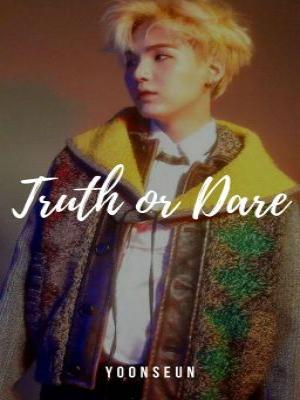Loneliness
Loneliness,
is a fire,
which I hold close to my skin,
to see how much pain I can stand,
before running to the water
--Atticus--
B r i a n
Gue tersenyum sambil menatap kotak hitam pipih yang sedari tadi gue tempatkan tepat di depan muka gue. Tangan gue bergerak-gerak sok asyik. Sejujurnya, bersamaan dengan pergerakan gue tadi, ada sesuatu dalam hati gue yang tertahan, pun begitu di pelupuk mata gue—gue ingin menangis, gak salah lagi. Bukan karena gue secengeng itu kuota gue habis untuk video call, tenang saja, di sini ada wifi yang berjalan dua puluh empat jam khusus untuk mahasiswa kampus ini.
“Abang! Kapan mau pulang?” Tanya adik gue—Hisyam—sambil memamerkan gigi-giginya yang dua tahun lalu masih ompong. Walaupun mereka lahir dan dibesarkan di Aceh, bahasa sehari-hari yang mereka gunakan tetap Bahasa Indonesia. Ya, wajar saja, di keluarga gue, hanya abu yang biasa berbahasa melayu, mamak adalah orang Jawa, dan mereka akan berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia.
Walapun gak jarang Bang Ijul dan Sena meledek gue, “Yan, kok lo ngomong gak kayak Upin-Ipin, sih?” Tanya Sena. Selanjutnya mereka cekikikan sendiri ketika Bang Ijul bertanya, “Sen, lo tau kagak angkatan darat di sana disebutnya apa?”
“Apa emang, Bang?”
“Laskar hentak-hentak bumi,” selanjutnya tawa Bang Ijul yang tengil menyertai.
“Hahaha anjir! Udah kayak lagu TK, ‘Siapa yang senang hati tepuk tangan? Siapa yang senang hati hentak bumi?’ Lu suka kayak gitu gak, Bang, dulu?” Tanya Sena balik. Dia tertawa-tawa sampai muncul rona-rona merah di wajahnya.
“Aing gak pernah TK masa,”
“Heuu pantesan gak bisa baca!”
“Mana adaaa? Masa gue kuliah kagak bisa baca!” Bang Julian menoyor Sena yang tetap diakhiri dengan tawa-tawa itu. “Lagi, Sen, lagi, bahasa melayunya merayap apa?”
“Apa, Bang?” Tanya Sena bingung.
“Bersetubuh dengan bumi!”
“Demi apa?” Sena bengong sesaat kemudian dia tertawa-tawa lagi. Sementara itu gue hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika dua bocah gede itu menertawakan bahasa daerah gue. Kurang ajar, ya. Bisa gue laporin ke bapak presiden, terus nanti mereka diangkat menjadi duta bahasa.
Ya gitu, kan?
Kadang gue berpikir juga, Indonesia ini memang aneh. Ketika negara lain menghasilkan duta-duta dari lulusan perguruan tinggi bergengsi, Indonesia malah menjadikan seseorang yang melakukan kesalahan sebagai duta. Terus lagi, fenomena-fenomena di Indonesia tuh kadang gak masuk akal buat gue, masa orang main tiktok yang gue pikir gak ada faedahnya sama sekali bisa terkenal? Sementara gue? Gue yang melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat tetap aja gak dikenal. Pindah ke mars gue lama-lama.
Tapi bagaimana pun, Indonesia adalah tempat gue lahir dan dibesarkan. Maka, gue harus cinta Indonesia. Apalagi sekarang gue ada di Bandung. Kalau kata Bang Ijul, Bandung itu diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Siapa tahu gue juga bisa tersenyum terus kan kalau gue tinggal di Bandung?
Sayangnya gue belum punya alasan untuk tersenyum.
Hehe.
Alah, jijik banget gue.
“Bang!”
Suara dari handphone gue kembali membawa gue ke alam sadar. Kenapa gue jadi mikirin si Sena sama Bang Ijul sih. “Kamu maunya Abang pulang kapan?” Tanya gue. Dijawab dengan kening yang berkerut dari dahi Hisyam, “Kalau Abang bisa pulang aja, yang penting Hisyam bisa lihat Abang setiap hari!” Jawabnya.
Gue menghela napas. Ada beberapa macam perasaan yang kini gue rasakan; sedih karena ingin segera pulang, tapi I have nothing, bahagia karena keluarga gue mengerti dengan keadaan gue, dan bingung, sebenarnya apa yang harus gue lakukan? Gue sudah memikirkannya berkali-kali untuk kerja sambilan, tapi gue gak tahu apa yang cocok untuk gue.
“KAK CHILA!”
Suara Hisyam mengeras, membuat gue melepas earphone tiba-tiba hanya untuk melihat bayangan Chila di layar. Dia sudah berdiri di belakang gue sambil berdadah-dadah ria, “Hisyam! Kakak kangen, deh,” ujar Chila sambil tersenyum.
“Gak akan kedengeran begee,”
“Ya, santai aja, begee,” Chila merebut handphone gue dan memasangkan earphone di telinganya dengan semena-mena. Merasa terancam—buset udah kaya apaan aja—gue segera mengambil handphone tersebut dan mematikan sambungan video call. “Ih jahat banget sih lo, gue kan cuma mau ngobrol sama adek lo!”
“Gue tahu lo mau ngomong yang enggak-enggak, kan?”
“Gak! Buset, suudzhon banget si Bapak,” Chila memonyongkan bibirnya. Beberapa detik kemudian, ekspresinya kembali berubah menjadi ceria. “Makan kuy.”
“Makan apaan?”
“Hmmm, soto Bu Anih?”
“Gak mau ah gue, banyak lemaknya.”
“Ya udah, ayam penyet, deh?” Tawar Chila.
“Gak ah, pedes.”
“Lo cowok apa cewek sih? Makan aja pilih-pilih, nanti kalau lo sakit berabe. Gue nih yang berabe, temen-temen kos lo mana mau ngurusin lo,” ujar Chila keras. “Lo sih gak pernah baik-baik sama mereka, makanya mereka gak peduli sama lo.”
“Heh, itu mulut suka sembarangan ngomong ya, mana ada mereka gak peduli sama gue? Gini-gini gue tuh teman terbaik bagi mereka,” jawab gue. “Eh tapi, cieee lo perhatian banget sama gue, gue suka deh.”
“Idih, mau lo doang,” Chila berjalan beberapa langkah mendahului gue. Ya, walaupun gue sok-sok menolak tawaran makannya—yang gak dia bayarin, kita bayar masing-masing—sebenarnya gue ingin makan juga, itu hanya taktik gue biar dia merengek-rengek minta ditemani makan dan berakhir mentraktir gue.
Ya, sayangnya ramalan gue salah.
Sorry not sorry nih, gue bukan Dilan.
Lagipula kadang ramalan dia tuh aneh, “Aku ramal kita akan ketemu di kantin.” Ya iyalah ketemu, kecuali kalau Dilan sama Milea puasa berjamaah. Suka aneh-aneh aja tuh orang. Dan lebih anehnya lagi, ketika gue nonton di bioskop—sama siapa lagi kalau bukan sama Chila yang sudah merencanakan menonton ini jauh-jauh hari—cewek-cewek dari baris A sampai baris paling depan teriak-teriak setiap Dilan bergerak satu sentimeter.
Mohon maaf nih ya, para penggemar Dilan.
Tapi, gue merasa gue lebih fantastis dari pada dia.
“Chilaaa buset lo gendut-gendut jalannya cepet amat!” Gue misuh-misuh sambil mengejar Chila yang mungkin sudah berada seratus meter di depan gue. Jangan salah, si Chila ini gendut-gendut juga atlet lari seratus meter saat dulu kita SMA. Pantes aja dia udah seratus meter di depan gue.
Langkah gue terhenti ketika melihat dia sedang berbicara sambil tersenyum-senyum dengan seorang laki-laki yang lebih tinggi dari gue—dan tentu saja lebih tinggi dari Chila. Melihat ekspresi dari kedua belah pihak, sepertinya yang dia bicarakan bukan hal penting, karena di setiap akhir percakapan selalu diikuti dengan tawa mereka.
Laki-laki itu memakai kemeja yang dimasukkan ke dalam celana bahannya, tangannya membawa tumpukan kertas, dan laki-laki itu berkacamata. Kalau gue lihat-lihat sih, kayaknya dia anak kedokteran? Mana mungkin si Chila punya teman anak kedokteran yang rapi macam pangeran begitu?
Eh sorry, yang kaya pangeran itu gue.
Gue ralat.
Mana mungkin Chila punya teman anak kedokteran yang kaku seperti itu?
“Halooo!” Gue menghampiri mereka berdua, yang berakhir dengan tatapan aneh dari laki-laki di depan gue. Muka-mukanya bukan muka ramah, setipe dengan Sena atau Jhordan. Tapi gue rasa, gue harus tahu siapa laki-laki yang tertawa-tawa dengan Chila beberapa saat yang lalu ini. Jadi, kalau dia memiliki niat jahat, gue gak segan-segan buat mematahkan leher dia. “Gue Brian.” Gue merangkul Chila.
Kedua alis mata laki-laki itu tertaut. “Pacar lo?”
Chila menatap gue sinis kemudian melepaskan rangkulan gue dari bahunya. Gue berakhir mengernyit karena biasanya dia gak berlaku sejahat ini. Mohon maaf nih gue agak lebay, tapi biasanya dia mau-mau aja gue rangkul di depan umum. Katanya biar gak kelihatan jomblo-jomblo amat. “Gak. Temen gue,” jawabnya cepat. “Anak ilmu komunikasi.”
Laki-laki itu mengangguk, lalu mengulurkan tangannya ke arah gue. “Gue Raka,” ujarnya sambil tersenyum, lantas gue langsung menyambut uluran tangannya. Kemudian pandangannya beralih ke arah Chila, “Lo udah makan?”
Gue mendelikkan mata. Lah, lah, lah, ada apa ini? Kok baru ketemu udah ngajak makan? Gue yakin sih si Raka ini memang baru ketemu Chila tadi. Nih ya, gue tuh udah hapal siapa-siapa aja temennya Chila dari bayi sampai sekarang, dan gue gak pernah tahu kalau Chila punya teman yang—buset—parfumnya kecium dari jarak lima meter ini?
Modus operandi apalagi ini.
“Belum,” jawab Chila lagi sambil tersenyum-senyum jijik. Heh, apa-apaan dia, ngomong sama gue aja nyongor, ini sok-sok senyum lagi.
“Ya udah kita makan, ehm… kalau soto Bu Anih gak mau, ya? Cewek biasanya gitu, bilangnya lagi diet,” ujar Raka itu, kemudian mereka tertawa.
Halah, cewek kayak Chila mana peduli soal diet. Yang ada nih sebentar lagi dia teriak-teriak, “GAPAPA! BAWA AKU KESANA KAKANDA!” Sampai si Raka ini menatap dia histeris dan kabur. Sesuka itu dia sama soto Bu Anih yang airnya berkilauan karena penuh dengan lemak. Percayalah, hanya gue yang kuat berhadapan dengan Chila.
“Ehehe, iya, banyak lemaknya soalnya,” jawabnya. “Gak baik buat metabolism tubuh, ya?”
Gue salah.
Gue yang kini menatap histeris pada Chila.
Apa?
Apa dia bilang?
“Kamu benar-benar anak teknik pangan yang teladan, ya,” puji Raka.
“Ahahaha, bisa aja,” jawab Chila sambil tersipu.
Apa?
Anak teknik pangan yang teladan? Dia bego apa gimana, sih? Anak teknik pangan itu belajar produksi pangan, bukan belajar gizi. Ini bocah mau-maunya lagi digombalin dengan isi yang salah dan tidak berbobot. “Chila, kita mending makan aja di soto Bu Anih, kan tadi lo pengen banget sampai hampir musuhin gue?” Ujar gue, kemudian menatap Raka dan Chila bergantian.
Chila memelototi gue dan menyikut gue keras. “Gak, kita makan…”
“Salad?” Tawar Raka. “Lo gak ada kelas lagi, kan? Kita bisa makan di luar,” tatapannya beralih pada gue. “Lo juga ikut, kan?”
Gue mengalihkan pandangan gue ke arah Chila sebelum menjawab. Gak, Chila gak pernah tahan makan tanpa nasi. Biasanya, kalau gue ajak dia makan bakso, dia masih menganggap itu bukan makan dan akan melanjutkan makan nasi di tempat kos—tapi jarang begitu, karena uang kita pas-pasan, makanya gue kalau ngajak Chila makan, akan langsung membeli nasi dan lauknya, karena makan dua kali adalah keborosan. Lah ini salad? Mana harga salad tuh…
“Ok. Di mana?” Jawabnya antusias.
Really? “Chil?” Tanya gue memastikan.
Chila tersenyum dan kemudian meninggalkan gue untuk menuturi langkah Raka. Gila. Kata orang, kadang jatuh cinta membuat seseorang gak menjadi dirinya sendiri.
And I see it.
***
C h i l a
Lo pernah tahu cerita-cerita klasik tentang seorang gadis yang miskin, lalu bertemu dengan pangeran yang gagah, kaya raya, dan baik hati? Hm, mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan dongeng yang menceritakannya dengan plot yang berbeda-beda—tetapi pada akhirnya seperti itu. Mereka bersama dan hidup bahagia.
Dalam hidup gue, mana ada cerita begitu. Yang ada, sehari-hari gue ditemani seorang cowok tengil yang hobi menenteng tas selempangnya kemana-mana, sering memakai topi atau kupluk untuk menutupi rambutnya yang berantakan seperti tarzan, dan kelakuannya…
Naudzubillahimindzalik.
Sangat jauh dengan pangeran impian gue.
Tapi, seorang Chila tidak pernah putus asa begitu saja, apalagi ketika menemukan secercah harapan di siang bolong seperti ini. Siang yang terik memang kadang membuat para mahasiswa malas untuk sekedar keluar dari kampus—apalagi jika nantinya mereka akan ada kelas lagi. Satu-satunya alasan gue mau keluar dari gedung FTIP adalah karena gue gak ada kelas lagi plus gue sangat lapar.
Tempat nongkrong terbaik gue—dan Brian tentunya—di saat lapar seperti ini adalah warung soto Bu Anih plus warung-warung lain yang berjejer di sebelahnya. Letaknya sangat strategis, jadi kalau lo mau makan soto terenak di kampus ini, lo mesti antri bisa hampir satu jam.
Gue sih gak masalah.
Soalnya Brian yang antri, gue tinggal duduk.
Tapi entah kenapa ya tuh bocah tiba-tiba gak pengen makan di sana. Sok-sok takut lemak lah, sejak kapan dia memperhatikan dan mengurus badannya? Sejujurnya, gue berterima kasih juga, karena dengan dia yang malas-malasan mengantar gue, akhirnya gue bertemu dengan pangeran gue.
“Eh?”
Tanpa sengaja modul-modul praktikum yang gue bawa di dekapan jatuh karena seseorang di depan gue berjalan terburu-buru. Sontak gue berteriak kaget—dan prihatin karena modul gue jadi lecek dan kotor—kemudian langsung mendongak untuk melihat siapa yang menabrak gue.
Sayangnya, gue gak bisa memaki.
Bagaikan adegan slow motion yang diberi animasi bunga bertebaran dan berjatuhan ditambah dengan musik Tiba-Tiba Cinta Datang by Maudy Ayunda, gue mendongak dengan dramatis hanya untuk melihat laki-laki yang…. WOY INI MAHASISWA ATAU PANGERAN DARI NEGERI AWAN?
Lo bayangin coba, ternyata di Bandung Kota Kembang ini terdapat mahasiswa seganteng Guanlin dan seberwibawa Ahjussi Goblin, gila-gila.
“Gak apa-apa? Maaf ya, gue tadi gak lihat,” katanya sambil merapikan berlembar-lembar modul gue. “Aduh ini jadi agak kotor.”
Gak apa-apa. Gak apa-apa modulnya kotor, asal kamu yang mengambilnya. Biar aku nanti mempelajarinya sambil menutup mata dan tersenyum karena ada bekas peganganmu di sana. “Eh iya gak apa-apa, itu aku juga yang salah.”
“Aku?”
Gue gelagapan. Anjir, kenapa mulut gue kayak gini sih. “I—iya, gue yang salah hehehe.”
Pangeran itu tersenyum sambil memberikan modul yang sudah ia usap berkali-kali agar lebih bersih. “Lo anak teknik pangan?” Tanyanya sambil meneliti muka gue. “Chila, wow your name is so cute.”
Gue tertawa, sudah gak tahu seberapa banyak rona merah yang bertebaran di muka gue. “Nama gue Rakasa Lukas, anak kedokteran. Panggil aja Raka. Kebetulan gue tahun ketiga dan udah mulai menyusun skripsi. Hngg, karena skripsi gue menghubungkan pangan dan kesehatan, lo mau bantu gue?” Tanyanya sambil tersenyum.
Jangan tersenyum, Bang. Adek bisa meleleh. Ditanya seperti itu, gue berasa ditanya, “Kebetulan gue gak punya pacar, lo mau jadi pacar gue?”
Dan sepersekian detik kemudian gue menjawab, “MAU!” Tanpa berpikir dua kali. Hingga Raka—atau mungkin gue harus memanggilnya Kak Raka?—tertawa-tawa melihat tingkah gue dan mungkin mengira gue gila.
Ah, memang gue gila setelah melihatmu, Bang.
Dan di saat seperti itu lah si bocah tengil datang sambil merangkul bahu gue dan merusak kebahagiaan pangeran skripsi gue ini. Gak peduli gue, mau bantui skripsi kek, mau bantuin cuci mobil, bahkan bersihin bandara aja gue mau, kok.
Untung aja Brian gak mengikuti langkah gue untuk menuju restoran yang akan dituju Raka. Yah, walaupun salad is not my daily food, but, why not? Setidaknya gue harus berkelas di depan pangeran gue ini.
“Temen lo itu anak ilmu komunikasi? Yang tadi?” Tanya Raka sambil menatap gue lamat-lamat. Gue gak tahu apa yang ada di pikiran dia ketika melihat wajah gue masih menatap kosong semangkuk salad. Kenapa….isinya…sedikit amat. Tapi masa bodo, lah. “Iya, kenapa?”
“Kayaknya anaknya jago ngomong….,”
“Hahaha, emang ya, Brian tuh ngomong terus kerjaannya. Kenapa emang?” Tanya gue lagi.
Raka tertawa dan membalas, “Gue ada lowongan pekerjaan, jadi penyiar. Papa gue sih yang suruh cari, kira-kira dia mau gak?” Tanyanya dengan tatapan yang tajam. Tatapannya sudah seadem ubin masjid, membuat gue berkedip berkali-kali. “Beneran? Kebetulan tuh dari kemarin dia pusing cari kerja sambilan. Nanti gue kasih tahu, ya!”
“Siap!” Jawabnya lagi, masih tertawa. “Lo semangat gitu ya orangnya? Lucu.”
Apa….katanya….bisa tolong slow motion-kan untuk gue?
***
B r i a n
“Yan…,”
“Hm.”
“BRIAN, SADARLAH!” Bang Ijul mengguncang-guncangkan bahu gue dramatis. Sesaat kemudian gue tersadar kalau nasi ayam katsu gue sudah penuh dengan saus yang sedari tadi botolnya gue pencet. “Janganlah kau membayangkan sedang menekan-nekan…”
“Bang! Jangan jorok, ya?”
“Gue gak bilang yang jorok-jorok?” Ujar Bang Ijul keras. “Lo sih pikirannya kotor,” jawabnya.
Saat ini, gue sedang makan di kantin FIB—fakultas Bang Ijul—yang konon katanya makanannya enak-enak. Sudah hampir satu setengah tahun gue kuliah di sini, dan baru pertama kali makan di FIB. Alasannya karena mana mau gue makan salad yang harganya lebih dari dua kali nasi ayam katsu gue? Ogah banget. Dan satu-satunya orang yang sedang free untuk gue ajak makan bareng hanyalah Bang Julian.
“Tumben,” lanjut Bang Ijul. “Maneh kok tumben nyamperin aing, biasanya makan bareng si Cilok.” Mulutnya penuh dengan bakso yang dia pesan, sampai-sampai gue takut baksonya meluncur ke kerongkongan tanpa sempat dikunyah, kemudian besoknya headline koran-koran menampilkan mahasiswa yang tewas setelah keselek bakso. “Telan dulu, Bang, telan.”
“Berantem sama si Chila?”
“Hahaha, mana ada gue berantem sama dia, Bang,” jawab gue.
“Terus?”
“Terus apa?”
“Muka lo kayak orang patah hati,” jawab Bang Ijul, kemudian terkekeh beberapa saat. “Gak deng, kayak nahan boker. Atau muka patah hati lo sama kayak muka nahan boker?”
Gue mendengus kesal mendengar pertanyaan sekaligus pernyataan Bang Ijul. Berkatnya, gue jadi ingat bagaimana Chila dengan teganya meninggalkan sahabatnya ini demi semangkuk salad. Cih, salad-salad apaan, mending juga lotek pakai nasi atau lontong. Gak. Gue tuh gak patah hati, gue sih terserah Chila mau sama jalan sama temennya yang mana, tapi masalahnya tuh orang yang namanya Raka itu kan belum jelas asal-usulnya?
[Chilaaa]
Bri, lo gak merana kan ditinggal gue? Ada yang mau gue omongin sama lo btw, soal kerja sambilan.
Gue memandang handphone gue, lalu segera memasukkannya lagi ke dalam tas. Mood gue sudah hilang sejak tadi, mungkin chat itu masih belum gue bales sampai nanti. Lagian si Chila pasti mau nawarin kerja sambilan aneh-aneh, atau cuma bercanda doang. Tau dah ah, pokoknya gue sedang gak mood untuk berbicara apapun.
“Bi! Nasi ayam katsunya satu lagi ya, dibungkus,” ujar gue, disambut dengan anggukan dan jempol wanita paruh baya yang sejak tadi menopang dagunya sambil tertawa-tawa sendiri memandang handphone di depannya. Tau deh lagi lihat apa. Jangan bilang…
“Eh buset! Lo akan membuang nasi ayam saus lo dengan semena-mena?”
“Bang, jangan dramatis.”
“Tapi itu harganya tiga belas ribu, lo mau ganti gitu aja gara-gara banyak sausnya?” Tanya Bang Ijul.
“Gak, itu buat Chila.”
Bang Ijul manggut-manggut, kemudian menyeruput kuah baksonya dengan nikmat. Tapi kenikmatan itu akhirnya terdistraksi dengan kedatangan seorang perempuan cantik dengan rambut panjang yang tiba-tiba berhenti di depan meja tempat gue dan Bang Ijul makan.
Waw.
Inikah teman Bang Ijul?
Kenapa Bang Ijul gak bilang kalau di FIB banyak mahasiswi-mahasiswi secerah masa depan gue ini? Gue hanya bengong ketika dalam beberapa menit pertama Bang Ijul belum sadar akan kehadirannya dan perempuan itu juga agak bimbang—entah karena canggung atau memang bukan orang yang senang menyapa. “Maaf, Teh, cari siapa?” Tanya gue, kemudian nyengir.
Wajah perempuan itu menampilkan ekspresi kaget, disusul dengan Bang Ijul yang mengangkat pandangannya dari mangkuk bakso yang sudah kosong. Kemudian, yang Bang Ijul lakukan selanjutnya hanya helaan napas panjang.
“Julian,” panggilnya.
Oh, nyari Bang Ijul toh ternyata. Ya, siapa tahu kan nyari gue?
“Maaf gue dulu pernah…”
Hm, bau-bau masa lalu nih. Tapi kenapa Bang Ijul gak pernah bercerita bahwa masa lalunya seperti bidadari jatuh dari surga seperti ini? Oh my God, gue lama-lama bakal jadi Dilan juga. Maafkan aku yang sudah menistakanmu di awal tadi.
“Gue kayaknya udah bilang,” jawab Bang Julian. “Jangan temui gue lagi. Gue udah maafin lo, lo mau bilang apa pun gak ada ngaruhnya buat kita…”
Jir, serem juga Bang Ijul. Wah ada apa ini? Berasa menjadi nyamuk yang luar biasa mengganggu, sebaiknya gue cabut saja dari tempat ini. Apa ini alasan Bang Ijul galau kemarin-kemarin? “Bang, gue cabut, ya. Ke kosan.”
Tanpa menghiraukan panggilan-panggilan dari Bang Ijul—yang sebenarnya sudah mengajak gue untuk pulang bareng—gue berjalan meninggalkan FIB. Sorry, Bang, kayaknya gue gak usah ikut campur.
***
J u l i a n
“Yan! Tunggu gue!” Gue memanggil-manggil Brian yang tubuhnya mulai tidak terlihat dari kantin fakultas gue. Untuk beberapa saat gue hanya terdiam dan mencoba mengalihkan pandangan gue dari sosok di hadapan gue. Oryza, lo mau ngapain lagi ke sini?
“Julian, gue gak lagi ngomong sama meja,”
“Gue gak mau ngomong sama lo,” jawab gue cepat.
Oryza menghela napas dan kemudian menahan tangan gue. “Please ikut casting The Mask.”
“Buat jadi pasangan lo?” Tanya gue, kemudian tertawa. “Atau buat jadi bahan hinaan papi lo lagi?” Mungkin gue terdengar sarkastik dengan mengucapkan kalimat itu. Tapi, memang itu kenyataannya. Memang selama ini gue menjadi bahan hinaan mereka yang gue sudah simpan dalam-dalam hingga ia datang lagi ke dalam hidup gue.
Oryza menatap gue dengan mata yang berkaca-kaca. “Sebenarnya apa yang Papi gue bilang kepada lo waktu itu?”
“Lo ini gak tahu atau pura-pura gak tahu?” Tanya gue. Kini memberanikan diri menatap matanya. “Gak usah pura-pura bego, Za. Gak usah pasang tampang innocent. Gue tahu kalau lo tahu semuanya.”
“Gue bener-bener gak ngerti,”
“Tolong tanya aja sama papi lo yang punya segalanya itu,” gue menghela napas, kemudian melepaskan tangannya yang masih menahan tangan gue. “Oryza, gue gak akan ikut The Mask, jadi sekali lagi gue bilang, jangan muncul lagi di hadapan gue.”
Oryza kembali menahan tangan gue. “Tapi ini pemeran utamanya dua orang, gak seperti dulu.”
“Mau dua orang, mau tiga orang, mau berapa pun, selama ada lo, gue gak bisa,” gue kembali melepaskan tangannya—yang kali ini lebih lemah. “Bukan gak bisa, tetapi gak mau. Gue gak mau harga diri gue dijatuhkan begitu saja untuk ke sekian kalinya.”
Gue mulai melangkahkan kaki meninggalkan kantin yang sebenarnya sangat ramai, tapi entah kenapa dunia seperti diam, hanya menyisakan gue dan Oryza di sana. Gue kira dia akan membiarkan gue pergi begitu saja, sampai akhirnya suaranya memasuki pendengaran gue, “Gue masih sayang sama lo, Julian.”
Untuk beberapa saat gue menghentikan langkah gue. Jantung gue berdetak lebih keras dari biasanya, sementara itu, darah mulai mengalir ke bagian-bagian kulit gue, terutama ke bagian muka, hingga gue merasakan sensasi panas mengalir indah.
Mengalir indah untuk sesuatu yang tidak indah.
“Emang lo pernah benar-benar sayang sama gue?” Tanya gue tanpa berbalik. Gue gak pernah mau melihat mukanya yang penuh drama. Semenjak kejadian itu, gue gak pernah mau lagi percaya pada dia, terutama ketika gue tahu apa yang dia lakukan berbeda dengan isi hatinya.
Gue hampir menertawakan diri sendiri ketika tidak ada jawaban dari seorang Oryza. Yang gue dengar hanya semilir angin yang berhembus cukup kuat siang ini. Entah apa yang akan terjadi, mungkin hujan akan segera turun atau justru angin ini adalah pembawa panas yang tak berkesudahan.
“See? Lo gak pernah benar-benar sayang sama gue,” gue tertawa hampa. “Iya, ini bukan salah lo. Ini salah gue karena pernah sayang sama seseorang yang bahkan gak punya hati.”
Kali ini gue benar-benar meninggalkan Oryza di sana. Tanpa gue tahu, dia masih menatap punggung gue yang menjauh dan perlahan air mata keluar dari sudut matanya. Suara lirih sempat keluar dari mulutnya, “Maafin gue, Yan. Tapi sekarang, gue benar-benar sayang sama lo.”
Kaki gue melangkah lebih cepat dari biasanya, menembus angin yang semakin kencang, hingga gue sadar hujan mulai turun. Setelah sampai parkiran, gue segera masuk ke dalam mobil hanya untuk berdiam dan memandang setir. Sesaat gue sempat berpikir untuk keluar dan memberikan jaket gue kepada Oryza yang masih gue lihat keberadaannya di tempat yang sama, tapi untuk apa?
***
O r y z a
Baby I just love you so much
But I guess it wasn’t enough
Can I see you once again
Cause I’m dying from this pain oh
Take me out of the way
Never thought I would be one to cry
But you were always there standing by my side
In our pictures you and I in love until we die
Now imagining that we would be ones to say goodbye
Tangan gue meraba-raba bagian tepi tempat tidur untuk menghentikan lagu yang sedang terputar dari handphone gue. Oke, mungkin eyes, nose, and lips tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan gue saat ini. Tapi, entah kenapa beberapa bagian liriknya membuat gue terdiam dan merenung, hingga gue akhirnya muak pada diri gue sendiri.
“Tolong tanya aja sama papi lo yang punya segalanya itu.”
Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di dalam pikiran gue, berputar-putar membentuk pusaran angin yang siap memecahkan kepala gue kapan saja. Gue bukan pura-pura gak mengerti, karena pada dasarnya gue memang gak tahu. Yang gue mengerti adalah memang yang gue lakukan dulu itu sangat salah.
Gue berpacaran dengan Julian hanya agar gue bisa menghentikannya ikut casting. Tapi soal Papi, gue gak pernah tahu apa yang dia lakukan saat itu hingga Julian sangat membenci gue seperti saat ini.
Seandainya gue sadar kalau gue benar-benar jatuh cinta pada Julian saat itu, seandainya gue gak pernah memaksakan ego gue, yang mendekati dia hanya untuk menjadi pemeran utama dalam daftar mimpi gue, mungkin gue gak akan menghancurkan mimpi orang lain yang sudah dibangun baik-baik.
Tapi toh waktu itu gue yang menang saat casting pemeran utama? Dia marah kepada gue karena dia sadar kalau gue gak menyukai dia setulus itu atau….dia marah karena kalah? Tapi, bukankah itu wajar dalam sebuah kompetisi?
“Julian, besok casting bakal dilaksanain,” sore itu entah kenapa lebih cerah dari biasanya. Siluet jingga menghiasi langit, memberikan pemandangan yang tidak biasa. Saat itu, gue dan Julian selesai berlatih dialog di rooftop sekolah—tempat favorit anak-anak untuk bolos pada zamannya. “Gue kok takut, ya.”
“Loh kok takut? Kan saingannya cuma gue?” Julian tertawa, matanya yang sipit bertambah sipit. Dan saat itu, gue gak mau mengakui kalau sebenarnya gue sudah hanyut dalam senyuman dia bahkan sejak pertama kali kita bertemu. “Atau lo takut kalau gue bakal menjauh kalau gue kalah sama lo?” Tanyanya lagi.
Saat itu gue gak mengiyakan—ya, kemungkinan itu memang bisa terjadi, tapi itu bukan saatnya memikirkan perasaan ketika karir gue diujung tanduk. Gue lebih takut kalau gue kalah dari dia saat itu, karena so far, dia sangat-sangat bagus ketika latihan. Maka gue hanya menjawab, “Hahaha iya.”
Sorry gue bohong waktu itu.
Sorry gue mikirin diri gue sendiri waktu itu.
“Janji deh, siapa pun yang menang di antara kita, kita tetep seperti ini. Ya?” Julian mengacungkan jari kelingkingnya, disambut oleh gue yang masih membisu yang pada akhirnya tetap membalasnya. “Menurut gue, gak masalah kita mau menang atau kalah di sini. Namanya juga kompetisi, kalau lo menang, berarti lo memang lebih bagus dan lebih layak. Kenapa gue harus menjauh? Gue kalah secara terhormat.” Jelas Julian panjang lebar.
Masalahnya gue sangat gak mau kalah, saat itu.
Peduli setan dengan kompetisi, bagi gue, saat itu adalah saat yang tepat untuk gue melangkah maju.
Tapi, saat pengumuman pemeran dikeluarkan dan gue pemenangnya, kenapa dia bahkan gak mau melihat poster itu sama sekali? Dia bahkan hanya berjalan melewati gue ketika dia sendiri yang membuat janji-janji di atas rooftop itu.
Noted.
Dia-berjalan-melewati-gue.
Tanpa satu pertanyaan pun, tanpa satu ucapan selamat pun, dan dia menghilang tanpa pesan dari hidup gue. Gue mungkin masih bisa melihat Julian berlari-lari di koridor sekolah, menjahili teman ceweknya, atau makan makanan kesukaannya di kantin. Tapi, gue gak pernah melihat dia tersenyum untuk gue lagi.
Apa dia sadar kalau gue jadian dengannya hanya agar bisa mempengaruhi dia untuk gak ikut casting?
Tapi, kenapa dia gak sadar kalau gue sudah berada pada titik sayang saat dia meninggalkan gue begitu saja?
Dan kenapa dia gak sadar kalau dia sudah melupakan janjinya pada gue saat itu?
Gue masih belum tahu jawabannya. Dan saat dia mengeluarkan kalimat baru lagi, “Tolong tanya aja sama papi lo yang punya segalanya itu.”. Mungkin ada sesuatu yang memang terjadi dan gak gue ketahui?
***
J u l i a n
Sosok orang-orang berotot—yang mungkin lebih tua hanya beberapa tahun dari gue—menghampiri gue di ujung jalan buntu. Jalan buntu itu gak memungkinkan gue kabur dari serangan yang mendadak ini. Gue juga bukan atlet taekwondo dan sejenisnya, sehingga yang gue pikirkan adalah gak mungkin gue bisa melawan mereka, kecuali kalau gue ingin berakhir ke akhirat sana.
Samar-samar gue mendengar mereka meneriakan banyak hal, hingga akhirnya sosok dengan pakaian serba hitam datang, membuat orang-orang tersebut menepi dan memberi hormat. “Jangan coba-coba buka mulut, terutama di hadapan Oryza.” Begitu saja orang berjas itu pergi, meninggalkan sekotak uang di hadapan gue, menyisakan orang-orang berotot itu untuk terus menghantamkan tangannya ke arah badan gue.
Tolong, gue sakit.
Tolong, gue menyerah.
Gue gak akan memperjuangkan lagi kalau memang sesakit ini.
Samar-samar, gue mendengar teriakan cukup keras.
Semakin keras.
Semakin keras lagi, hingga akhirnya gue kembali ke alam sadar. “Panjul! Jul! Bangun! Lo kenapa?” Perlahan gue membuka mata gue dan melihat sosok Yoga tengah menggoncang-goncangkan bahu gue dengan panik.
“Bang Ijul, gak apa-apa, kan? Gue jadi pengen nangis, nih, liatnya,” Sena berdiri di ambang pintu sambil menghentak-hentakkan kakinya. Sementara itu, keempat anak lain juga sedang berada di kamar gue, mukanya berkerut-kerut khawatir.
“Bang, kenapa, sih? Mimpi apa sampai kayak gitu?” Tanya Dennis, beberapa kali dia menghela napas untuk menenangkan dirinya. “Abang sampai keringetan gitu, teriak-teriak pula, kita jadi takut Abang kenapa-kenapa.”
Gue bangkit dari tempat tidur. Kepala gue sangat pusing, Dennis benar, keringat dingin bahkan bercucuran di dahi gue. Ah, mimpi itu lagi. Setelah sekian lama gue gak memimpikan kejadian itu, sekarang mimpi itu datang lagi, lebih jelas dan nyata dari sebelumnya.
Seperti…benar-benar terjadi dua kali.
“Gak apa-apa, kalian tidur gih,” ujar gue pelan. “Gue cuma mimpi buruk aja.” Pandangan gue beralih ke arah jam dinding yang menunjukkan waktu tengah malam. Lucky me untuk menemukan mereka sebagai teman-teman gue. Kalau mereka gak peduli dengan gue, mungkin gue akan tetap terjebak dalam mimpi itu sampai pagi, hingga rekaman dari seluruh kejadian benar-benar terputar kembali.
“Lo benar-benar baik-baik aja, Bang?” Tanya Jhordan. “Jangan lupa baca doa sebelum tidur, biar gak mimpi buruk lagi. Bang Ijul istirahat lagi aja, kayaknya badannya agak panas gitu ya, Ka?” Jhordan melirik Cakka yang disambut dengan anggukannya.
“Abang tadi hujan-hujanan? Ngapain sih, Bang? Kan naik mobil?” Cakka malah misuh-misuh sambil memberikan kompres air hangat ke Yoga.
Yoga menghela napas. “Ya udah kalian bocah-bocah tidur aja, biar gue yang ngurus,” ujar Bang Yoga. “Awas kalau pada telat bangun pagi.” Ucapan Yoga rupanya disambut anggukan oleh para bocah yang kemudian mulai melangkahkan kakinya menuju kamar masing-masing walaupun tatapannya masih mengarah pada gue prihatin.
Gue menghela napas lega, “Ga,”
“Hm. Diem lo jangan gerak-gerak,” Yoga menampis tangan gue yang berusaha memegang dahi. “Semakin lo gerak-gerak, semakin banyak air yang bakal gue guyurin ke pala lo.”
Gue mendengus,“ Ga, kalau mimpi buruk masa lalu tiba-tiba menghantui lagi, menurut lo apa yang bakal terjadi?” Tanya gue.
Yoga menghentikan aktivitasnya dan menaruh kain putih yang sedari tadi dia pegang di dahi gue. “Gue…gak yakin. Mungkin karena masa lalu lo ada di dekat lo kembali?”
Gue terdiam, tatapan gue menegang. Seandainya saja Oryza gak kembali muncul dalam kehidupan gue, mungkin mimpi buruk itu gak akan datang kembali. “Santai, Bro. Gak lah. Itu mah gara-gara lo-nya aja yang gak berdoa tadi. Ditambah lagi, lo lagi sakit, pasti pikirannya melayang kemana-mana.”
“Semoga ya, Ga.”
“Emang siapa yang lo takuti bakal kembali lagi?”
“Seseorang…,” jawab gue, lalu menghela napas. “Dari masa lalu.”
Yoga mengernyit, kemudian setelah merasa menemukan jawabannya, dia sedikit tersenyum. “Oryza?”
“Not her.”
***


 adillazulfana
adillazulfana