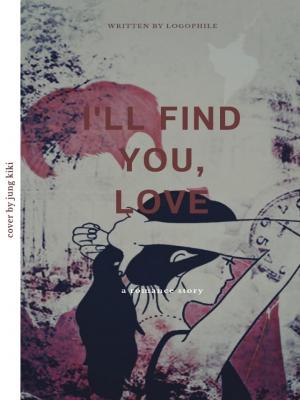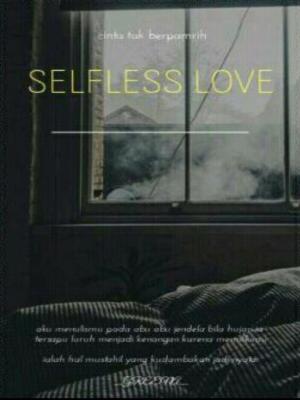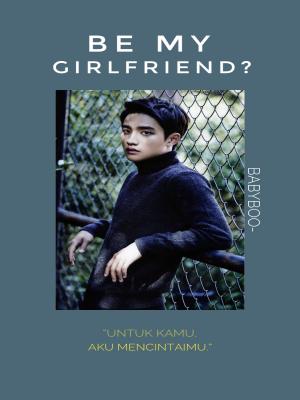Silence
It took me a while
To realize
That everything can be said
In a silence
Y o g a
Sinar matahari sudah masuk menyelusup melalui celah-celah gorden yang terbuka. Menyadari ini sudah cukup siang, gue terlonjak. Parah nih, telat shalat subuh. Sementara gue mengerjap-ngerjapkan mata untuk mengembalikan kesadaran, gue menyadari bahwa Julian sudah tidak ada lagi di tempat tidur.
Semalaman gue menemani Julian di kamarnya, udah so sweet belum? Habis kalau gue tinggalin, gue takut dia bakal teriak-teriak lagi kayak orang kesurupan dan mukanya itu jelas-jelas menampilkan ekspresi yang takut setakut-takutnya. Gue gak tahu dia bertemu apa dalam mimpinya, tetapi, mengetahui itu bagian dari masa lalu dia, kemungkinan besar itu bukan hantu.
Julian mungkin sering cekcok dengan ayahnya soal masa depan, tapi cekcok mereka hanya cekcok kecil sebatas sindir-sindiran, dan ayahnya pun hanya meminta Julian untuk membuktikan pilihan hidupnya saat ini tanpa menjatuhkan. Ibu Julian juga sangat mendukung dengan apa yang Julian pilih saat ini, jadi gue rasa masalahnya bukan datang dari keluarga. I guess.
Secepat kilat, gue menuju kamar mandi dan segera melaksanakan shalat subuh yang telat—mungkin udah masuk waktu dhuha. Parah banget gue, untung aja sekarang hari Sabtu dan kuliah libur. Tapi melewati bagian kosan tadi, gue rasa maison de rêve sangat sepi? Masa sih belum pada bangun? Oke, Jhordan adalah pengecualian. Tapi biasanya, si Brian udah ngasih makan di kolam kecil depan kosan, atau Sena yang sedang olahraga—entah joget—di ruang tengah.
“Hello my sunshine!”
Gue tercekat melihat pemandangan langka di depan gue saat menuju dapur. Sosok perempuan berambut panjang dengan celemek mencolok mata tengah tersenyum dan melambaikan tangannya pada gue.
A—apa tadi dia bilang?
My sunshine?
Sejak kapan…
Walaupun kata itu gak pernah dia ucapkan semenjak dia berpacaran dengan gue, tapi kata itu sempat menimbulkan rona merah di pipi gue dalam beberapa detik. Hingga akhirnya gue tersadar, gue gak boleh begini.
Pandangan gue beralih pada Julian yang ternyata sudah berada di sana—mungkin sejak tadi—dengan tatapan kok-dia-bisa-ada-di-sini? Alis gue mengangkat meminta penjelasan, tapi Julian hanya mengangkat bahunya, yang mungkin dapat diartikan sebagai mana-aing-tahu? Kemudian ia lanjut memotong-motong bumbu di atas talenan.
“Ada apa, Ditas?” Tanya gue, menarik salah satu kursi makan dan duduk di sebelah Julian. Tanpa menunggu jawabannya gue bertanya pada Julian, “Lo udah baikan?”
“I’m ok,” jawab Julian sambil terkekeh. Kemudian, setengah berbisik, dia mendekatkan wajahnya ke telinga gue. “Gue gak tahu siapa yang izinin dia masuk ke sini. Tau-tau pas gue mau masak, dia ada di belakang gue,”
“Tapi sejak kapan dia berinisiatif datang ke sini…”
Ditas tiba-tiba berbalik dan menaruh sepanci besar sup. “Kalian kok ngomongin guenya sambil bisik-bisik?” Kemudian dia tertawa. Gue menggaruk kepala gue yang tidak gatal. Ini…dia habis kesambet petir kali ya, kemarin? Kemarin kan hujan gede banget.
Semenjak insiden percakapan gue dan Ditas lewat handphone Cakka, gue hampir gak pernah berhubungan sama sekali dengan Ditas. Bahkan, jika gue biasanya menemukan dia di sudut koridor atau di depan masjid, kemarin-kemarin gue justru gak bisa menemukan dia.
Bukan berarti gue ‘mencari’, tapi rasanya semesta bekerja sama dengan gue. Karena, dengan gak adanya dia di sepanjang jalan akan lebih mudah buat gue untuk melupakan dia. Alon-alon asal kelakon. Yang penting usaha.
Penasaran dengan bagaimana percakapan itu berakhir?
Percakapan telepon itu seharusnya tidak pernah berakhir, gue yang memutuskannya sebelah pihak ketika gue gak mampu menahan tangis lagi—ditambah lagi saat itu Cakka sudah bangun dari tidurnya, atau mungkin sebenarnya dia tersadar ketika gue berbicara dengan Ditas.
Dan kita belum putus karena percakapan itu berakhir begitu saja.
Semenjak itu, gue kira dia sudah menyerah. Bagus kalau memang iya. Gue gak perlu lagi repot-repot mencari cara agar dia capek dengan semua kelakuan gue, gue gak perlu lagi berusaha menghindar setiap bertemu dengan Ditas, dan gue harus benar-benar siap merelakan dia untuk orang lain yang sudah disiapkan keluarganya.
Tapi, sejak kapan dia mempunyai inisiatif untuk mendatangi tempat kos gue?
Ditas meletakkan mangkuk di depan Julian. “Julian, kan? Gue denger lo sakit kemarin, kayaknya sup ini enak buat lo. Terus, biar gue aja yang lanjut masak. Lo berdua duduk aja.” Ujar dia sambil tersenyum, disusul dengan anggukan dan tampang cengo Julian yang kemudian menerima sup itu dengan senang hati.
Beberapa kali Julian memandang gue dan mengangkat alisnya heran. Ya, sama, gue juga heran. Sudah berapa tahun gue pacaran dengan Ditas? Mungkin sudah hampir dua tahun, dan baru kali ini gue menyadari sesuatu.
Ternyata gue gak tahu apa-apa soal Ditas.
Gue gak tahu apa makanan kesukaannya, gue gak tahu warna kesukaan dia, gue gak tahu tempat apa yang ingin dia kunjungi, gue gak tahu tempat favorit dia, gue gak tahu hobi dia apa, dan bahkan gue gak tahu kalau dia bisa memasak seperti ini.
It feels like we are stranger to each other.
Bahkan untuk mengobrol dan melihat wajahnya sedekat ini terasa sangat canggung untuk gue. Beberapa saat gue terdiam, kemudian mengambil mangkuk dan menuangkan sup ke dalamnya. “Lo…dalam rangka apa ke sini?” Tanya gue lagi. Seingat gue, gue gak ulang tahun, dan gak ada siapa pun yang berulang tahun hari ini di maison de rêve.
“Loh emang gak boleh ke tempat kos pacar gue?”
“UHUK!”
Gak, itu bukan gue yang keselek. Karena sekarang Julian sedang megap-megap dan tangannya bergerak menuju gelas yang sudah berisi air, lalu dia meminumnya cepat. Gue bisa tahu sekaget apa si Panjul. Gue gak pernah membawa Ditas ke sini, dia dan anak-anak lainnya hanya tahu bahwa pacar gue bernama Ditas dan tahu wajahnya hanya dari foto-foto di handphone Cakka—percaya atau tidak, Cakka sering sekali berfoto dengan Ditas.
“Lo…gak apa-apa?” Tanya gue prihatin melihat Julian yang kemudian menarik napasnya panjang dan bangkit dari kursi. “Gue kayaknya gabung aja sama anak-anak yang lain. Mungkin lo berdua butuh bicara.” Ujar Julian, kemudian menepuk-nepuk bahu gue. “By the way, thanks for the soup.”
Ditas mengangguk-angguk, pandangannya beralih ke arah gue, membuat gue gelagapan dan gak tahu harus berbicara apa ketika Julian mulai menjauh dari meja makan dan meninggalkan dapur.
“Eh—eh Panjul! Emang bocah pada ke mana?” Tanya gue.
Julian hanya menoleh sepersekian detik, kemudian menjawab sambil terus berjalan, “Tau tuh, tadi pagi ada rame-rame di gang depan. Gue kesana, ya. Oh iya, maison de rêve kosong, kalau lo mau keluar jangan lupa dikunci.” Kemudian Julian tersenyum mengejek. “Selamat berbaikan.”
Gue memandang Ditas pelan dan dramatis. Ya, habis, mau gak dramatis gimana kalau suasananya seperti ini? Jujur, mungkin dalam dua tahun hubungan kita, kita bahkan gak pernah jalan berdua kecuali makan bareng di kantin FISIP? Itu pun bisa dihitung dengan jari frekuensinya. Gue dan dia terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan sekarang….gue dan Ditas hanya berdua di sini?
“Kenapa lo tiba-tiba ke sini?” Tanya gue pelan, memecah keheningan yang hampir lima menit menguasai seluruh ruangan. “Bukanya gue udah bilang untuk gak perlu peduli lagi sama gue dan jalani aja kehidupan lo?”
Ditas tersenyum masam, kemudian duduk di hadapan gue. “Kata siapa gue peduli sama lo?”
“Ya?”
“Gue peduli sama diri gue sendiri,” jawab Ditas pasti. “Karena gue gak bisa jauh dari lo. Atau mungkin, karena sebelum gue benar-benar gak ada di kehidupan lo, gue harus membuat kenangan sama lo.”
“Kenapa?” Gue terkekeh. “Bukannya bagus kalau kita gak punya kenangan? Kenangan itu cuma bisa bikin sakit.”
“So, lo gak mau gue sakit?”
“Ya. Pergi dari hidup gue tanpa menyisakan apa-apa di memori lo itu bagus, Tas. Lo bisa menjalani kehidupan lo tanpa teringat dengan gue,” jawab gue.
Ditas menghela napas. “Bagaimana dengan lo? Apa lo juga ingin hidup tanpa kenangan dari gue?”
“Kalau itu yang terbaik, kenapa enggak?”
“Lo benar-benar ingin gue pergi, ya?”
Gak, gue gak ingin lo pergi.
Gue menghela napas, kemudian menatap matanya tajam. “Ya, di luar sana ada tempat dan seseorang yang lebih baik lagi buat lo.”
Ditas mengangguk-angguk. “Gue memang akan pergi.”
“So, do it.”
“Biarkan gue membentuk kenangan indah bersama lo. Cukup hari ini,” jawabnya cepat. Matanya menatap gue sungguh-sungguh dan penuh ketegasan, tidak ada garis-garis berkaca-kaca yang biasa orang perlihatkan ketika akan terjadi perpisahan. “Seenggaknya gue punya ‘momen’ bersama lo.”
Ditas kemudian tersenyum, membuka celemeknya dan menaruhnya di atas kursi makan. Tangannya merogoh handphone-nya dan menaruhnya pelan. Kemudian telapak tangannya terulur ke arah gue. Gue mengernyit, “What did you think?”
“Handphone lo,” Ditas menghela napas. “Kita jalan tanpa handphone.”
***
“Lo…lo suka main kayak gini?”
Ditas mengernyit, “Kenapa emang?” Tanyanya pelan. “Oh, did you think these are too childish?” Kemudian dia tertawa, melanjutkan kembali kesibukannya pada layar kotak di depannya, jari jemarinya sibuk menari di atas keyboard. Sementara itu, tampaknya tokoh jagoan Ditas masih berjaya di game tersebut.
“Ng—gak sih,” jawab gue ragu. “Gue kira—“
“Makanya, lo jangan suka berasumsi sendiri,” Ditas menoleh ke arah gue, jarinya secara otomatis menekan tombol space pada keyboard-nya. Kemudian tanpa kita sadari, jarak kita sangat dekat, hanya terpisahkan oleh dua pegangan kursi yang kini telah menempel—gue gak pernah sedekat ini dengan dia, I guess. Matanya menatap gue pelan, “Lo mungkin mengira gue hidup seperti tuan putri. Ya, benar. Tapi bukan berarti gue gak suka diajak ke tempat seperti ini.”
Gue tidak menjawab, hanya memandang Ditas pelan, sebelum ia membuka mulutnya kembali. “Asumsi lo bikin kita tambah jauh.”
“Ditas…”
Ditas melepas headphone-nya, menggantungnya pada batas-batas yang berada di internet café tersebut. Kemudian dia menepuk bahu gue pelan. “This is enough. Kita harus pergi ke tempat ke dua.” Ditas bangkit dari tempat duduknya untuk berjalan mendahului gue.
Gue tertegun beberapa saat hanya untuk menghasilkan kerutan-kerutan di dahi gue. Perlahan-lahan sebuah rasa hangat menjalar di dada gue, dan sebuah senyuman tipis terangkat. Sebuah perasaan yang gak pernah muncul dalam diri gue—dan sangat sulit didefinisikan—tiba-tiba saja sudah mengisi hati gue.
Cukup lama kita berada di internet café ini, hampir empat jam, karena sekarang sudah menunjukkan pukul satu siang, mengetahui hal itu, Ditas segera mengajak gue ke tempat selanjutnya, hingga beberapa menit kemudian, gue sedang menyetir menuju tempat yang ingin dia datangi.
Cukup jauh, mungkin akan sampai dalam waktu lebih dari dua jam. Awalnya, gue gak tahu akan secanggung apa gue dan dia di dalam mobil berdua, tapi nyatanya pandangan gue gak bisa terlepas dari Ditas yang terus-terusan tersenyum. Gue rasa…dia senang. Dan buat gue, itu cukup.
“Ditas.”
“Hm.”
“Lihat gue,” ujar gue pelan, membuat kepalanya perlahan menoleh dan menatap gue gamang. “Ditas, lo lagi sama gue. Gue bukan jalanan yang lo tatap terus menerus dari tadi.”
Ditas terkekeh. “Gue selalu lihatin lo setiap hari, Ga. Itu udah jadi makanan gue. Tapi biasanya lo menghindar, sejak kapan lo pengin gue lihatin?”
“Sejak tadi,”
Ditas menghela napas, kemudian senyum kecil tersungging di bibirnya. “Kenapa baru sekarang?”
Karena gue baru tahu ternyata melepas lo pergi gak semudah itu.
“Because you’re three times more cute now.”
Ditas kembali tersenyum, menciptakan rona merah di pipinya. Sesaat kemudian, Ditas kembali mengalihkan pandangannya pada jalanan. Entah apa yang dia pikirkan, tapi kini pandangannya kosong. “Ditas, kamu beneran mau pergi?”
“Iya,”
Gue mengangguk-angguk. Dia memang harus pergi—pun gue yang menyuruhnya pergi. Pergi agar dia gak terikat lagi pada gue dan membuat hidupnya menjadi semakin rumit. Ditas pasti sudah cukup pening dengan perjodohan itu, dan itu akan sangat sulit jika gue tetap mempertahankan dia untuk berada di sisi gue.
Tapi dari dalam hati yang terdalam, gue gak ingin dia pergi.
“Kenapa lo melakukan ini semua seakan-akan lo mau pergi jauh?” Tanya gue lagi. “Lo hanya pergi dari gue, bukan pergi dari hidup lo.”
“Karena lo adalah hidup gue, Ga.”
Ditas menjawabnya cepat, tanpa ragu sedikit pun. Matanya menatap nyalang ke arah gue, membuat jantung gue sejenak serasa berhenti, tenggorokan gue tercekat, dan yang gue lakukan selanjutnya hanya menghela napas panjang dan merutuki diri sendiri di dalam hati.
Hampir satu jam kita diam-diaman. Dia hanya memandang langit dari jendela, sementara gue berusaha fokus menyetir. Pikiran gue melayang jauh, berusaha menemukan memori-memori ketika gue dan Ditas bersama.
Gak ada.
Hampir gak ada.
Gue benar-benar gak pernah melakukan sesuatu bersama dia.
“Yoga, gue selalu suka langit sore. Ya, walaupun ini masih peralihan dari siang ke sore—karena ini masih jam tiga sore—gue senang karena gue melihatnya bersama lo,” Ditas mengambil jeda beberapa saat. “Dari awal kita jadian, gue kira kita akan seperti pasangan lainnya,”
“Maksud lo?”
“Ya, sering bareng-bareng, pergi ke tempat-tempat romantis, makan di pinggir jalan sambil nikmatin udara dingin malam, dan lain-lain. Like a couple,” Ditas terkekeh. “Terlalu childish ya, keinginan gue? Tapi itu memang apa yang ingin gue lakukan, Ga. Dulu, saat pertama kali kita jadian, gue ingin mengajak ke tempat yang akan kita datangi saat ini.”
“Terus kenapa lo gak ajak gue?”
“Lo sibuk, semua orang tahu itu.” Ditas menghela napas. “Lo sibuk sama orang-orang di sekitar lo, urusan kuliah lo, organisasi, dan lain-lain. Do you think I can disturb you? Bahkan menarik perhatian lo pun gue gak bisa, Ga. Gue sudah mencoba selama dua tahun ini tapi…lo gak pernah melihat gue.”
Gue tercekat beberapa saat, “Gue kira lo gak ingin semua orang tahu tentang kita.”
“Hobi lo itu emang berasumsi, ya?”
Gue tersenyum kecil, padahal dalam hati gue merutuki kelakuan gue. “Kita udah sampai.” Gue mengalihkan topik pembicaraan, mematikan mesin mobil dan keluar. Udara sejuk, semilir angin, serta semburat jingga menyapa gue saat turun.
Pantai.
Kata mereka, melihat sunset di sini sangat indah. Ditas chose the right place. Dia tiba-tiba mendekati gue, menarik lengan gue dan menggandeng gue. Ok, slow down your heartbeat, Ga. Gue gak pernah tahu kalau Ditas adalah orang yang seterang-terangan itu untuk menggandeng cowok di tempat umum.
Gue dan dia berakhir duduk di tepi pantai, menyewa tikar yang cukup besar, ditemani dengan es kelapa muda yang masih berada pada buahnya. “Ga, gue sayang sama lo.”
Gue menghela napas panjang. “Gue kira enggak.”
“Lo udah bisa dapat rekor MURI sebagai orang yang paling sering berasumsi untuk kejadian-kejadian di sekitar lo,” jawab Ditas lagi. She’s so smart, as smart as how she beat my word. “Dulu gue sering ke sini, sama Papa. Papa gue sering banget ajakin gue main, dan ini adalah tempat favorit gue dulu, waktu kecil. Tapi gue gak pernah ke sini lagi.”
“Kenapa?”
“Semakin gue besar, Papa semakin sibuk, Papa punya jabatan yang semakin tinggi, hingga seperti sekarang. Dia gak ada waktu buat gue lagi, gue sendirian dan kesepian. Mama juga wanita karir yang mungkin baru pulang tengah malam pas gue tidur. Gue jarang ngobrol lagi sama mereka,” jawab Ditas.
“Kenapa lo gak coba ke sini sendirian?”
Ditas terkekeh. “Lo tahu? Gue berjanji sama diri gue sendiri untuk datang ke sini dengan orang yang benar-benar spesial buat gue. Gue kira, gue akan ke sini setelah kita jadian, tapi ternyata kita ke sini ketika kita akan berpisah.”
“Menurut lo gue orang yang spesial?”
“Apa menurut lo gue gak menganggap lo seperti itu?”
“Ya,” gue tersenyum singkat, gak perlu gue katakan lagi, gue memang sudah merutuki diri gue sendiri atas asumsi-asumsi yang sudah gue buat. Cakka benar, mengobrol sebenarnya adalah jalan keluar yang paling tepat. Berbicara satu sama lain, bertukar pikiran, hingga tidak ada asumsi-asumsi gak pasti yang gue pikirkan.
“Pertama kali gue ketemu lo, gue serasa melihat pangeran berkuda tau gak?”
Gue tertawa. “Hahaha. Really? Lebay banget, lo.”
“Lo keren, ketua angkatan saat itu, dari cara lo ngomong, lo itu orang yang cerdas,” Ditas melanjutkan. “Dan gak salah kalau lo banyak banget penggemar yang rela ngantri buat nanya-nanya ke lo. Dan…”
“Dan?”
“Suatu hari ketika lo menolong gue dari cuitan kakak tingkat yang gak berkelas itu, lo bukan lagi pangeran berkuda gue!”
“Tapi?”
“Calon suami idaman gue,” Ditas tertawa. Gue sempat tertegun untuk mencerna perkataannya beberapa saat, dia menganggap gue suami idaman dia ketika gue kira hanya diri gue yang menganggap Ditas adalah perempuan yang sempurna?
“Hidup lo lebay juga ternyata, gue baru tahu,” jawab gue, mencoba menyembunyikan rona merah di wajah gue. “Pas pertama gue ketemu lo, gue melihat lo sebagai bintang.”
“Bintang?”
“Iya, terlalu bersinar, tapi letaknya terlalu jauh,” jawab gue. “Sulit untuk digapai. Gue aja sempet shalat istikharah buat meyakinkan diri gue sendiri untuk nembak lo atau enggak. Tapi anehnya, jawabannya iya. Gue nembak lo, Tas. Lo jadi pacar gue, tapi…”
“Tapi setelah kita pacaran, justru kita semakin jauh. Itu kan yang mau lo bilang?” Tanya Ditas. “Lo hidup atas dasar asumsi lo, dan gue juga begitu. Gak ada yang bisa diselesaikan dengan asumsi. Coba kalau kita sering ngobrol dari dulu, gue gak menganggap lo sibuk atau lo gak menganggap gue sibuk, kita pasti sering cerita. Kita pasti gak semakin jauh kayak gini.”
“Is it too late?” Gue bertanya dengan nada yang bodoh. “Ah, you don’t have to answer. You must go for someone else.”
Ditas memandang langit yang semakin menampakkan semburat jingganya, hingga tidak ada lagi warna biru yang tersisa. “Hidup di tengah keluarga kaya raya terkadang gak sepenuhnya menyenangkan, Ga. Gue kesepian, gue harus hidup pada aturan Papa, termasuk soal pasangan.”
“Lo udah ketemu sama orang itu?”
“Siapa?” Tanya Ditas dengan kening berkerut. “Ah, that boy. Yes, I have. Dia ganteng, tinggi, masa depannya cerah—terutama untuk tiga sampai empat tahun ke depan, pinter juga, dan gue rasa dia tipe orang yang peduli, I guess?”
Sesaat setelah mendengarnya, bagian dalam tubuh gue serasa ada yang patah. Ah, kenapa sih gue. Padahal gue yang memang menyuruh dia pergi kepada cowok itu, tapi kenapa ternyata melepaskan gak semudah itu? Maaf gue jadi galau sendiri seperti ini, tapi…“Glad to hear that. Semoga lo bahagia nanti.”
“Semoga, Ga.”
“Kayaknya lo udah sangat siap untuk pergi dari gue?”
“Lo yang membuat gue terbiasa, Ga,” jawabnya sambil menepuk-nepuk puncak kepala gue, membuat gue sesaat terdiam. Kemudian, Ditas segera menarik tangannya dan tersipu. “Sorry, that’s only for the first and the last time.”
“It’s ok,” jawab gue sambil terkekeh, mencoba menormalkan kembali detak jantung gue yang tidak beraturan. Rambut gue dan dia sama-sama melambai, terbawa angin sore. Beberapa saat gue berpikir dan menerka, kira-kira respon apa yang akan dikeluarkannya jika gue…. Ah, gue terlalu banyak menerka.
Perlahan gue mengambil sejumput rambutnya dan menyisipkannya ke belakang telinga Ditas. “I’m sorry.”
“Untuk apa?”
“Untuk gak berusaha membuat kenangan sama lo sebelumnya,” jawab gue. “See? Kita gak punya foto berdua, kita bahkan baru bisa mengobrol dengan benar….sekarang. It’s too late if I say I don’t wanna let you go, because you must go.”
“Yoga, makasih udah menjadi suami idaman gue selama ini…”
“Tolong jangan bilang itu,” jawab gue sambil menyeka air mata yang tiba-tiba turun mengalir di pipi gue, dan di saat bersamaan gue juga melihat hal serupa di wajahnya. “Tolong jangan bilang itu, gue jadi geli sendiri.”
“Hahaha, dasar ya lo,” Ditas menoyor gue, tetapi dengan tawa sekaligus isakannya. Gue merengkuh dia ke dalam pelukan gue. “Sorry, this is for the first and the last time. Gue ternyata sayang sama lo, dan ternyata melepas lo pergi sesedih ini.” Lanjut gue.
Ditas masih terisak hingga air matanya mungkin sudah membasahi baju yang gue kenakan. Bahunya bergetar hebat dan yang bisa gue lakukan hanya ini. “Jadi… kita putus?” Tanya Ditas dengan suara yang kurang jelas karena dia masih berada di pelukan gue.
Gue memejamkan mata beberapa saat, mengambil keputusan yang gue kira akan gampang gue keluarkan, tapi ternyata tidak. “Ya, kita putus,” jawab gue sambil mengelus punggungnya. “Don’t forget to be happy, with him.”
“I wish.”
Rasanya sakit dan aneh ketika pergi di tengah sesuatu yang baru dimulai.
***
C a k k a
Baru Sabtu pagi ini maison de rêve heboh oleh teriakan Bang Jhordan—yang biasanya bangun tengah hari seperti orang mabuk yang berpegangan pada dinding dan menuju dapur untuk mencari makanan yang tersisa. Saking hebohnya, bahkan manusia yang tidurnya cuma di hari-hari weekend seperti Bang Sena ikut-ikut keluar untuk mencari penyebab teriakan Jhordan itu.
“Paan sih? Selalu aja lo yang bikin weekend gue berantakan!” Bang Sena mengacak-acak rambutnya yang sudah acak-acakan, kemudian memandang keluar jendela hanya untuk melihat Babeh Rahmat sedang bergosip dengan pemilik-pemilik kos di sekitar sana. “Lo nyuruh gue nonton gosip?”
“Kagak bege, itu tuh ada keributan gitu tadi. Tiba-tiba orang-orang lari ke arah sana,” Bang Jhordan menunjuk arah barat dan masih melongok-longok, memastikan bahwa yang dilihatnya tadi gak salah.
Gue mengernyit heran memandang pemandangan hari Sabtu yang biasanya sangat tenang berubah menjadi sangat heboh. “Itu orang-orang pada ngapain deh? Tawuran?” Tanya gue tanpa meminta jawaban dari abang-abang yang tiba-tiba sudah berkumpul ribut di belakang gue.
Bang Dennis membuka handphone-nya sambil mengerutkan dahinya. “Guys…”
“Eh liat-liat itu tuh si Jona anak kos putri sebelah, kan?” Tanya Brian, matanya menyipit memastikan. “Wah bener ternyata!”
“Emang kenapa, Yan?” Seakan mendapat informasi hebat, semua orang menoleh ke arah Brian.
“Gak, kalau pagi-pagi ternyata seksi juga, ya, dia,” jawab Bang Brian, kemudian tertawa-tawa. Disambut dengan toyoran dari abang-abang lainnya sambil mengeluarkan makian-makian terhadap bang Brian.
“Guys, gue manggil kalian loh tadi….”
“Maaf gak minat mendengarkan teori psikolog,” jawab Jhordan cepat. “Kesana aja gimana? Penasaran gue.” Ujar Bang Jhordan, matanya menatap kita lamat-lamat untuk meminta persetujuan. Warga-warga yang sebagian besarnya anak kos masih berlalu lalang di depan kos menuju arah barat, mulutnya mangap-mangap, sepertinya sedang bergosip ria.
“Bang, kalau misalkan itu cuma topeng monyet, sia-sia keringat kita,” ujar gue diikuti anggukan yang lainnya. Hm, memang banyak pengikut gue ini.
“Teman-teman, tadi gue lihat di grup whatsapp itu ada kasus pembunuhan di kos putra gang depan…,” ujar Bang Dennis, membuat keadaan hening seketika. Bang Sena dan Bang Jhordan saling bertatapan, sementara itu gue sibuk berpikir. Jadi, pembunuhan itu memang benar-benar ada, ya?
Bang Sena berbicara terbata-bata. “Lo serius? Pembunuhan di kos putra? Putra?”
“Iya, makanya dengerin gue dulu kenapa, sih,” Bang Dennis yang gak pernah marah jadi misuh-misuh sendiri, sementara itu Bang Jhordan—yang tadi menampik omongan Bang Dennis—terkekeh. “Hehehe, sorry, gue kira lo mau berpidato. Ngomong-ngomong, itu dari grup whatsapp mana? Tar hoax lagi. Sia-sia energi gue dipake kaget begini.”
“Grup whatsapp komplek,” jawab Bang Dennis tenang.
Bang Brian menutup mulutnya dramatis. “Demi what? Lo masuk grup yang isinya bapak-bapak kos bongkotan sama ibu-ibu yang hobi bergosip ria pas belanja sayuran itu?”
Dennis nyengir, “Disuruh Babeh Rahmat, katanya siapa tahu warga komplek butuh pencerahan dari gue,” ujarnya, membuat yang lain menggeleng-gelengkan kepala heran, ada-ada saja Babeh Rahmat.
Tapi sesi-sesi tertawa itu berakhir dengan keheningan lagi, gue sendiri merasa bulu kuduk gue naik dan merinding. Gue ini bukannya gak pernah mendengar kata pembunuhan, tapi mengetahui itu sangat dekat dengan tempat gue berdiri saat ini….rasanya agak ngeri juga. Biasanya gue senang membaca-baca buku detektif, atau menikmati berita di koran pagi tentang kasus seperti itu, tapi gue hanya akan terkejut sebentar, penasaran, dan melupakannya.
Tapi coba bayangkan kalau itu ternyata benar-benar ada di dekat kita?
Di-dekat-kita.
Mendengarnya aja gue merinding. Itu artinya, si pembunuh juga ada di sekitar kita, kan? Masalahnya dia sama-sama manusia, ya mana mungkin gue bisa tahu siapa yang berpotensi jadi pembunuh atau bukan?
“Si—siapa yang jadi korbannya?” Tanya Bang Jhordan, yang gue kira akan biasa saja mendengarnya.
“Rajasa Lukas,” jawab Bang Dennis, masih menatap handphone-nya gamang. “Dia anak kampus sebelah, katanya. Gue sendiri gak pernah ketemu dia sih kayaknya.”
Gue mengernyit dan mencoba berpikir, “Kok rasanya namanya familiar ya buat gue?”
Bang Sena menoleh dan memastikan, “Masa, sih? Lo lebih sering gak keluar kosan dibanding kita-kita.” Gue mencoba memastikan memori gue, tapi tampaknya memang benar-benar familiar. Di mana, ya, gue melihat atau mungkin mendengar nama dia?
“Beneran anak kampus sebelah?” Tanya gue.
Bang Dennis mengangguk, “Yo-i. Katanya sih begitu. Atau kita mau ke sana aja cari-cari tahu?” Sepertinya usul Bang Dennis bukan usul yang bagus, tapi patut dipertimbangkan. Gue menelusuri raut muka abang-abang gue ini dan pada akhirnya mereka manggut-manggut setuju.
“Bang Yoga! Bang Ijul! Kita ke sana yak, lihat yang rame-rame!”
“HEH MAU KEMANA?”
Dengan berakhirnya kalimat itu, kita berlima menuju ke sumber keributan dengan heboh. Oke, ralat, gue gak heboh. Yang heboh justru Bang Sena dan Bang Jhordan yang sepertinya sudah penasaran setengah mati dengan apa yang mungkin terjadi. Bahkan satu langkah mereka merupakan dua langkah gue. Giliran tadi aja takut-takut, sekarang malah pecicilan.
“Excuse me? Maaf kalian gak boleh terlalu dekat,” sesosok wanita, ngg—mungkin bukan, tetapi seorang gadis yang berpakaian layaknya orang biasa menghadang jalan Bang Sena dan Bang Jhordan yang sudah berada beberapa langkah di depan gue. Hal itu membuat keduanya mengernyitkan dahi dan bertanya, “Sorry, lo siapa? Kita cuma mau lihat.”
Perempuan itu menyodorkan sebuah name-tag yang membuat keduanya terkejut, “Lo? Polisi? Sekecil ini?” Tanya Bang Sena dengan muka kaget sambil menunjuk-nunjuk perempuan yang ada di hadapannya.
“Bunga.”
“Ya?” Tanya Bang Jhordan.
“Nama gue Bunga,” jawab perempuan itu.
Mata Bang Jhordan menyipit beberapa saat, kemudian saling bertatapan dengan Bang Sena. “Gue gak nanya nama lo?”
Perempuan itu mendengus, kemudian berbalik. “Teknisnya, kalau kalian ingin tahu apa yang terjadi, kalian harus bertanya pada polisi, bukan para warga yang menceritakan kejadian ini dengan banyak bumbu.” Ujarnya kemudian berjalan beberapa langkah meninggalkan mereka berdua.
Gue melangkah maju menerobos Bang Sena dan Bang Jhordan, membuat keduanya terkaget-kaget. “Sorry, Kak Bunga?” Tanya gue pelan, sekaligus merutuki diri sendiri karena gak tahu harus memanggil dia dengan sebutan apa. Bu? Neng? Teh? Mbak? Satu-satunya alasan yang membuat gue berani untuk memanggilnya adalah perihal nama itu.
Rajasa Lukas.
Yang entah kapan dan di mana, rasanya gue pernah mendengarnya. Beberapa kali, bahkan.
Perempuan itu menoleh, memancarkan sorot matanya yang dingin. Kulitnya pucat, matanya tegas, tapi di satu sisi terpancar rasa lelah dari sana. “Ya?” Tanyanya. Sesaat segala sesuatu tentang polisi itu membuat Cakka tercekat, namun ia akhirnya kembali membuka mulutnya untuk berbicara. “Korbannya…Rajasa Lukas?”
Perempuan itu menghela napas, kemudian mengangguk. “Lo kenal? Kalau kenal, gue bisa tanya-tanya sama lo.”
Gue menggeleng. “Disebut kenal sih enggak, tapi rasanya gue sering dengar namanya. Apa satu fakultas dengan gue, ya?”
“Rajasa Lukas sepertinya gak sekampus dengan lo,” jawabnya cepat.
“Loh dari mana lo tahu kampus gue?” Tanya gue heran, memastikan sorot matanya tidak berbohong. “Lo sering ngikutin gue, ya?”
“Rajasa Lukas adalah anak kampus teknik itu,” jawab Bunga sambil memutar bola matanya. “Dan gue rasa lo bukan muka-muka orang yang pantas masuk ke sana.” Ujarnya.
Omongan polisi muda yang mengalir begitu saja tanpa berpikir dan tanpa jeda itu membuat gue mengepalkan tangan. Oh, bagus ya, polisi zaman sekarang ternyata melakukan pelecehan hati dan perasaan orang. Kalau aja dia bukan polisi, udah gue gampar dari tadi.
“Ok, then,” jawab gue sambil memunculkan seringai. “Tell me about him.”
“Him?”
“Rajasa Lukas dan kenapa dia bisa seperti itu.”
“This place is not appropriate to talk about something like this,” ujarnya. “Mind to treat me a bowl of meatball?”
***
Gila, gila, gila. Bisa dibilang kejadian yang menghampiri gue beberapa minggu ke belakang ini adalah kejadian luar biasa yang membuat orang biasa akan kejang-kejang menghadapinya. Gue kira, nasib sial gue bertemu dengan orang aneh akan berhenti sampai Jihan. Tapi ternyata, ada orang yang lebih aneh lagi yang meminta ditraktir di pertemuan pertama gue dengan dia.
“Gue rasa gue gak perlu manggil lo dengan sebutan ‘Kak’?”
“Up to you.”
“Gue harus menunggu berapa lama lagi?”
“Lo nungguin gue?” Tanyanya, tatapannya beralih dari semangkuk bakso yang gue belikan untuk dia ke arah muka gue. Masih sama, tanpa ekspresi.
Eh, buset sumpah, ya, terus gue di sini dari tadi ngapain kalau bukan menunggu dia bicara? Tapi gue hanya menarik napas dan membuangnya kembali. Gue harus baik-baik pada orang yang akan memberikan banyak informasi. “Gak, gue nunggu tukang baksonya tutup.”
“Hahaha, gak lucu.”
“Gak ngelucu, sorry.”
“Tapi tadi keliatannya lo berusaha ngelucu?”
Gue mendengus. “Gue kesini bukan untuk berdebat dengan lo, orang yang baru gue kenal beberapa jam lalu, Bunga.” Ujar gue. “Lagian gue gak percaya lo polisi ketika kayaknya lo seumuran Abang gue?”
“Gue lulusan termuda dari akademi kepolisian,” jawabnya datar. “Jadi lo gak kenal Rajasa Lukas?” Tanyanya, kini mencapai poin yang ingin gue dengar.
“Tadi lo udah ngatain gue kalau gue gak pantes masuk kampusnya dia, sekarang lo masih nanya lagi?” Tanya gue sebal.
Bunga merogoh sakunya, kemudian menaruh sebuah foto di atas meja. “Kalau begitu, lo pasti kenal dia. Rakasa Lukas.” Jawabnya sambil menunjuk-nunjuk foto itu. Jari-jarinya mungil dan lentik, membuat siapa pun yang bertemu dengannya tidak akan menyangka bahwa dia adalah seorang polisi.
“Raka…sa Lukas?” Gue mengernyit beberapa saat, kemudian terkejut. “Jadi mereka kembar?”
“Menurut lo?”
“Kalau gue lihat fotonya, iya gue kenal!”
Bunga memandangi sekitarnya, kemudian menjitak kepala gue. “Gak usah berisik, Dek.” Matanya kini melotot dan membuat gue memelankan suara gue. “Dia kakak tingkat gue, sering jadi panitia di acara-acara yang melibatkan maba. Makanya, gue kenal.” Jawab gue. “Terus kembarannya benar-benar mirip sama dia, ya?”
“Iya.”
“Tunggu-tunggu,” gue mengernyit. “Dari mana lo tahu kalau gue kenal sama kembarannya?”
Bunga mendengus. “Apa gue perlu menjelaskan? Ternyata lo anak kedokteran yang cukup lemot juga, ya.” Ujarnya. “Satu, di antara teman-teman lo yang berisik tadi, cuma lo yang tertarik untuk menanyai gue soal Rajasa Lukas. Gue berpikir kalau lo mungkin mengenal salah satu di antara keduanya, makanya lo tertarik. Dua, lo sudah pasti gak mengenal Rajasa Lukas, karena, ya, muka lo gak pantes masuk kampus sana, as simple as that. Maka dari itu, kemungkinan lo anak kedokteran, dan lo mengenal kembarannya, bukan Raja.”
Gue mengangguk-angguk. Ya, kalau gue pikir-pikir, dia pantas juga jadi polisi di usia muda, karena analisisnya gak bisa disebut jelek. “Lo pikir ada anak kedokteran yang mukanya bego apa?”
“Ada,” jawab dia. “Lo.”
Gue mati-matian menahan emosi karena dia menyebutkannya dengan datar. “Terus, kenapa lo gak tanya-tanya soal Raja ke kembarannya?” Tanya gue lagi.
“Tuh kan, bego.” Bunga lagi-lagi mendengus. “Kalau gue udah ketemu kembarannya ngapain gue harus tanya-tanya lo begini?” Ujarnya, kini nada bicaranya meninggi.
“Ya, lo gak bilang kalau kembarannya gak ada!”
“Lo tahu apa soal Raka?”
“Gue gak tahu apa-apa, dia cuma kakak tingkat gue. Oke, menurut cewek-cewek, dia mungkin ganteng karena setahu gue selalu banyak orang yang memandang dia dengan pandangan yang beda,” jawab gue. “Ya, selebihnya, gue gak kenal dekat.”
“Dari reaksi lo tadi, berarti lo benar-benar gak tahu kalau dia punya kembaran,” dia mendesah pelan. “Menurut lo dia orangnya baik?”
“Ya, I think?”
“Kemarin dia masih masuk kuliah?”
“Hm, iya,” gue berpikir beberapa saat. Kemarin, gue sempat melihat dia pagi-pagi di kampus, sedang membeli batagor dan duduk sendirian di sudut kantin FK. Like usual, dia selalu makan sambil membaca sesuatu dari laptopnya. Bukan berarti gue adalah pemerhati dia hingga gue tahu kebiasannya, tapi, eksistensi dia di FK ini gak bisa ditolak, setiap orang yang gue temui setidaknya akan berbicara satu kali tentang dia dengan gue. “Tapi, kemarin kan gue mabim…”
“Mabim?” Keningnya berkerut.
Gue menghela napas. “Mabim itu ospek jurusan.”
Bunga mengerucutkan bibirnya. “Ooo, gue kira nama kendaraan,” jawabnya santai. “Terus?”
“Raka itu orang yang berdedikasi tinggi dalam kepanitiaan,” ujar gue. “Jadi kalau lo merasa dia yang membunuh kembarannya, sepertinya lo salah. Dia gak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu.”
“Gue gak menuduh dia? Gue hanya sedang mencari dia,” jawabnya. “Lo belum lanjut soal mabim lo itu.”
“Biasanya dia akan menjadi sesuatu yang mencolok seperti…. MC? Atau sebagai moderator, dan sebagainya. Tapi gue gak melihat dia kemarin,” jelas gue. “For your information, mabim gue dilaksanakan pukul enam belas sampai pukul delapan belas. Tapi, paginya gue sempat bertemu dengan dia.”
Bunga mengangguk-angguk dan tampak berpikir.
“Lo gak nanya teman-teman satu kosnya? Tanya kalau siapa tahu mereka memang gak melihat Raka, atau justru sebelumnya melihat Raka tapi tiba-tiba hilang?” Tanya gue heran.
“Mereka gak tinggal di tempat yang sama,”
“Maksud lo? Mereka gak sekos?” Tanya gue. “Gue aja sama Abang gue gak mau tinggal terpisah, apalagi ini, sama kembaran sendiri?”
“Jangan samakan hidup lo dengan hidup orang lain,” jawabnya sinis. “Raka dan Raja memang kembar, tapi mereka gak dekat. Raja tinggal di tempat kos, tapi Raka tinggal di apartemen, sendirian. Raja cenderung mudah berbaur dengan orang dan senang hidup sederhana, tapi berbeda dengan Raka, ia kebalikannya. Apartemennya bisa dikatakan adalah salah satu apartemen terbesar yang pernah gue lihat, barang-barangnya pun nyentrik dan unik.”
“Mereka anak orang kaya, I guess?”
“Ya, mereka anak dari direktur utama Adikusuma group,”
“UHUK!”
“Lo gak makan, jadi seharusnya lo gak tersedak.”
“Perusahaan apa tadi lo bilang? Adikusuma?”
Bunga mengangguk-angguk. Perusahaan itu mengingatkan gue akan seseorang, Kak Ditas. Orang tua Kak Ditas adalah salah satu dari tiga keluarga yang memiliki perusahaan itu, bahkan ayahnya—sebagai anak tertua di keluarga Adikusuma—menjabat sebagai presdir di perusahaan pusat yang mengatur berbagai bidang.
Agak sulit dibayangkan kalau ternyata dunia ini benar-benar sempit, bahkan orang-orang di sekitarnya harus terhubung dengan jalinan benang tersebut. “Gue mengenal putri presdirnya sangat baik. Dia pacar kakak gue.”
“I’m not interested.”
“Gue cuma cerita!”
“Tapi yang lo harus tahu adalah dia baru saja turun dari jabatannya kemarin-kemarin,” jawab Bunga.
“Ke—kenapa?”
“Menurut lo kenapa orang itu harus turun dari jabatannya ketika dia sedang dalam masa kejayaannya?”
Gue mendengus. “Lo membuat kepala gue pening dengan memikirkan hal-hal seperti ini.”
“Lo memang bego ternyata.”
“Gue gak bego!” Sergah gue cepat.
“Then, think it by yourself,” begitu saja Bunga bangkit dari kursinya, lalu kemudian berjalan beberapa langkah sebelum akhirnya berbalik. “By the way, thanks for your information and that meatball.” Kemudian dia melanjutkan langkahnya, keluar dari kedai bakso ini menuju arah yang tadi.
Gue berpikir berkali-kali. Kira-kira, kenapa papa Kak Ditas harus turun jabatan ketika dia sedang berada dalam masa kejayaannya? Selain mungkin karena sakit parah—menurut gue ini gak terjadi, karena tampaknya keluarganya baik-baik saja—bisa juga karena terjerat kasus tertentu?
Seperti…
Korupsi?
Ah mana mungkin, seenggak dekatnya Kak Ditas dengan papanya, gue tahu dari dia kalau papanya orang baik. Maka, hal itu gak mungkin terjadi. Mungkin saja gue harus menanyakan secara langsung pada Kak Ditas nanti.
Gue bangkit dari tempat duduk, membayar bakso, dan berniat keluar dari kedai sebelum akhirnya tanpa sengaja melihat seseorang yang gue cukup kenal tengah duduk di sebelah tempat sampah, di depan sebuah tempat kos yang kosong karena penghuninya pasti sedang terkena sindrom heboh. Jaraknya hanya beberapa rumah dari tempat kejadian perkara—hampir sama dengan kedai bakso ini.
Orang itu merokok, sambil menatap nanar—sepertinya ke arah kerumunan yang masih sama ramainya. Ngapain dia di situ?
***


 adillazulfana
adillazulfana