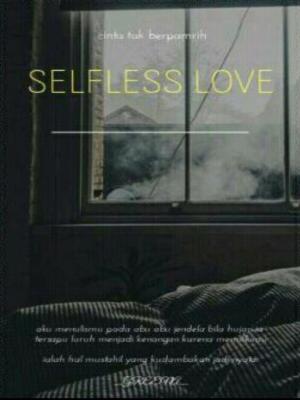Ada suatu waktu ketika Oci berkunjung ke rumah Risa tanpa memberi kabar terlebih dulu, alhasil menangkap basah Risa yang sedang merokok di jendela kamarnya. Bagaimanapun, Oci tidak terlihat terkejut maupun jijik, melainkan tertawa-tawa dan meminta Risa segera memadamkan rokoknya.
“Jadi selama ini kamu musuh dalam selimut,” gerutu Oci main-main sambil mengibaskan tangan berusaha menepis bau yang, tidak peduli meski jendela sudah dibuka lebar, tetap meliuk di dalam ruangan. “Kamu ‘kan tahu aku alergi asap rokok.”
“Aku tidak tahu kamu mau datang,” gumam Risa malu, lantas menggerus ujung rokoknya kuat-kuat ke bekas kaleng biskuit yang dialihfungsikan menjadi asbak. Ya, dia tahu Oci alergi asap rokok, karena itulah dia selalu memastikan dirinya menyembunyikan barang-barang serta pakaian yang sekiranya akan dekat dengan Oci. Berlama-lama dia memandangi Oci yang masih mengibaskan sebelah tangan sambil terbatuk-batuk, kemudian beringsut ke nakas dengan tidak nyaman. “Aku yakin ada Cetirizine di sekitar sini ...”
Oci menghentikan tangan Risa. “Aku tidak apa-apa.”
“Tapi alergimu.”
“Nanti kalau sudah terasa tidak enak, baru aku pergi dari sini.” Oci mencengir lebar. “Omong-omong, ini pertama kali aku melihat kamu merokok.”
“Karena memang tidak ada yang tahu selain Ibu. Lagi pula, siapa yang mau dekat-dekat dengan anak ingusan yang merokok seperti bapak-bapak.”
Oci menariknya supaya duduk di ranjang bersamanya. “Aku mau,” kata Oci sungguh-sungguh, senyumnya melembut. “Apakah perlu kukatakan kalau kamu jadi kelihatan ...”
Derum mobil yang muncul di ujung jalan segera saja membuyarkan lamunan Risa. Dia mencondongkan badan ke depan dengan berpegangan pada kosen jendela, menyadari bahwa itu memang Land Rover milik Hanan. Kalau dia murid teladan, sudah pasti dia akan berlari menyongsong lelaki itu dan mencium tangannya, tapi rasa-rasanya gadis yang menghabiskan waktu membolos dari sekolah dengan merokok sesiangan sudah tak pantas disebut murid.
Dia sekadar memandangi mobil itu melipir sampai sangat dekat dengan pagar. Ada jeda selama sekitar dua menit ketika Hanan duduk di dalam mobil, sebelum lelaki itu keluar dan mengurai tubuhnya yang jangkung. Bahkan dari lantai dua, dia masih terlihat sangat besar, pikir Risa seraya menghela substansi rokok dan mengembuskannya ke udara.
Entah apakah baunya merebak sampai bawah, atau Hanan memang punya radar terhadap keberadaan Risa, lelaki itu lantas mendongakkan kepala. Senyum lebar seketika terbentuk di bibir Hanan, kemudian dia melambaikan sebelah tangan.
“Apakah saya harus ke atas, atau lebih baik kamu yang turun?” seru Hanan. Selama ini Risa hanya pernah mengobrol dalam jarak dekat, sehingga suara keras lelaki itu sedikit mengejutkannya. Tidak terlalu berat, tapi tidak sangat ringan; suaranya kuat dan jernih.
“Saya lebih suka kalau Bapak pergi,” Risa berseru balik. Hanan tertawa sambil menggeleng-geleng.
“Saya akan naik, kalau begitu.”
Risa membelalakkan mata. “Jangan! Saya yang turun.”
Hanan tertawa lagi dan melenggang menuju pintu pagar, sedangkan Risa dengan hati-hati menyeimbangkan rokoknya yang masih tiga perempat di kosen jendela, kemudian bergegas keluar. Ketika dia tiba di ruang tamu, Hanan sudah menunggu di depan pintu dengan senyum lebarnya.
“Halo, Risa,” kata lelaki itu. “Tumben ibumu tidak ada untuk menyambut saya.”
“Ibu arisan.”
“Ah, begitu. Boleh saya masuk?”
Untuk ukuran orang yang tidak tahu malu ikut-ikutan menangis, Hanan jelas memahami adab bertamu. Risa mengedikkan dagu ke arah sofa-sofa yang tertata. “Masuk saja.”
Hanan duduk di tempat yang kemarin: sofa ganda yang terlihat seperti kursi berlengan untuk satu orang jika didudukinya. “Jadi, kamu sudah membuka-buka pelajaran yang saya berikan kemarin?”
Risa melesakkan punggung ke sandaran sofa. “Belum.”
“Saya sudah menduganya, makanya saya bawa hadiah lain untuk kamu.” Lantas, Hanan membuka ritsleting ransel dan mulai menggeledah isinya. Ada gemelotak benda-benda padat saling bertumbuk, lalu gemerisik kantong plastik. Risa menggaruk kulit kepala dengan frustrasi.
“Berapa kali saya bilang, Pak, saya tidak akan berangkat ke sekolah hanya dengan mendapat hadiah.”
“Itu karena kamu belum tahu. Nah, ini dia.” Hanan mengeluarkan selembar papan keras berukuran A3 serta wadah tertutup kecil. “Kamu suka main puzzle? Saya bawakan puzzle buat kamu, lumayan untuk menghabiskan waktu kalau kebosanan di rumah.”
“Saya punya banyak hal yang bisa saya lakukan selain main puzzle,” dengus Risa, dengan skeptis memandangi wadah berukuran tempat bekal yang diletakkan di meja. Tampaknya entah bagaimana Hanan berpikir dengan memasukkan semua kepingan ke dalam wadah dan tidak mengizinkan Risa melihat gambar aslinya terlebih dahulu akan membuat permainan lebih seru.
“Selain merokok seperti lokomotif uap di kamar?” tanya Hanan, tapi sambil tersenyum, alhasil pertanyaannya tidak terdengar seperti sindiran. Risa mengepalkan tangan, meremas rambutnya. “Coba jelaskan, Risa, kenapa kamu mulai merokok?”
Nada membujuk Hanan terdengar amat menjengkelkan di telinga Risa. Dia menjatuhkan kedua tangan ke tempurung lutut. “Saya kepingin jadi anak keren.”
“Anak keren,” ulang Hanan, seolah baru pertama kali mendengarnya dan perlu mencicipinya dengan lidah sendiri. Dia agak mencondongkan badan ke depan, kedua siku menumpu paha, dan menatap Risa penuh ketertarikan. “Saya tidak pernah melihat kamu sebagai tipe pemberontak. Apakah kamu memerlukan pengakuan dari orang lain untuk jadi anak keren?”
“Tidak, dorongan itu berasal dari diri sendiri. Waktu itu saya keluar dari rumah setelah bertengkar dengan Ayah, kemudian saya melihat beberapa pengemudi ojek merokok bersama dan mereka kelihatan keren serta tenang.” Risa merasa aneh bercerita pada wali kelasnya ketika tidak seorang pun tahu alasannya memulai kebiasaan buruk tersebut, tapi bisa jadi Hanan memerlukan semua ini untuk mengisi jurnal pribadinya atau hal klise yang bodoh semacam itu. Lagi pula, dia sedang tidak ingin mengarang-ngarang cerita.
“Lalu? Bagaimana kamu bisa beli? Kamu masih di bawah umur.”
“Tidak ada yang bertanya soal umur kalau beli di toko kelontong. Lagi pula, sejak kecil saya sudah disuruh beli rokok oleh Ayah. Penjualnya sudah hafal.”
Hanan mengangguk-angguk. Orang polos yang berambisi menjadi guru sepertinya pasti tidak paham, pikir Risa. Berani bertaruh Hanan adalah tipe orang yang benar-benar mengurangi laju kendaraan menjadi lima kilometer per jam sesuai spanduk yang ditulis menggunakan cat semprot di gang-gang kecil. Mungkin dia sekarang sedang memutar otak bagaimana cara menyuluh Risa tentang bahaya merokok; mungkin besok dia akan bawa seluruh perlengkapan eksperimen biologi yang menunjukkan bahwa nikotin dapat menodai paru-paru dari kapas.
“Bagaimana kalau kita mulai menyusun ini?” Sehingga, tak ayal Risa terkejut dengan tawaran Hanan yang melenceng begitu jauh dari bahasan awal. Tanpa menunggu jawabannya, Hanan membuka tutup wadah dan membiarkan kepingan-kepingan mungil longsor ke meja. Warnanya didominasi merah dan jingga. Hanan mulai memilih keping-keping itu, mencari bagian sudut. “Saya perlu semalaman untuk menyelesaikannya. Mungkin kamu bisa lebih cepat dari saya.”
“Apa Bapak berharap saya akan menyelesaikan puzzle kalau buku pelajaran saja tidak saya sentuh?”
“Kalau pelajaran tidak kamu sentuh, mungkin kamu lebih suka mengerjakan permainan. Logikanya begitu,” sahut Hanan ringan dan meletakkan satu kepingan di sudut kiri atas. “Sini, tolong bantu saya.”
Risa mengerang keras, tapi akhirnya tetap beringsut ke ujung sofa dan merunduk, mengamat-amati tumpukan keping puzzle. Jantungnya melorot saat menemukan seraut muka rata di salah satu keping. “Demi Tuhan.” Dia terbelalak menatap Hanan. “Bapak tidak mengerjai saya, kan?”
“Tidak, jangan khawatir,” kekeh Hanan, meraih kepingan itu dari tangan Risa dan menguburnya di balik keping-keping yang lain. “Ini pemandangan dari jepretan foto. Mungkin si pembuat sengaja mengeblur wajah orang-orang yang gambarnya tak sengaja terambil demi menjaga privasi.”
“Saya tidak mau mengerjakan ini malam-malam dan harus memelototi muka rata untuk mengetahui di mana letaknya,” gerutu Risa.
“Kamu selalu bisa meletakkannya terakhir,” sahut Hanan. “Hidup juga seperti itu jika diibaratkan bingkai puzzle. Ada banyak yang perlu dipetakan, ada banyak yang harus diletakkan di tempat yang benar. Hanya karena kamu takut terhadap satu kepingan, bukan berarti kamu tidak bisa menyelesaikannya.” Hanan mendongak membalas tatapan Risa, lantas tersenyum. “Pelan-pelan saja, lama-kelamaan kamu akan mendapat gambaran.”
Risa membuang muka. “Oleh sebab itu, Bapak seharusnya tidak datang ke sini setiap hari.”
“Justru sebaliknya, Risa. Saya bisa memakai kekerasan dan ancaman kalau ingin mengembalikan kamu ke sekolah, apalagi dengan tamparan yang sempat menghantui tidur saya di malam hari.” Hanan tersenyum penuh arti. “Tapi tentu saja itu tidak bisa saya lakukan. Ini yang saya sebut sebagai pelan-pelan; semua orang punya cara mereka sendiri untuk pelan-pelan.”
“Berarti Bapak tidak akan keberatan kalau saya tidak kembali ke sekolah sampai waktunya lulus? Karena Bapak tadi bilang semua orang punya cara sendiri untuk pelan-pelan,” tantang Risa, tapi Hanan hanya tersenyum.
“Kalau kamu tidak keberatan saya berkunjung sampai waktunya lulus, tentu saja.”
Risa memberengut. Seharusnya sejak awal dia tahu bahwa memasang puzzle akan jauh lebih baik ketimbang berbicara dengan Hanan. Dia memutar-mutar salah satu kepingan yang ada di tangan. Terlihat seperti sebagian sayap burung, tapi secara kebetulan dia menemukan bagian burung yang lainnya. Selama beberapa menit, dia hanya fokus merekonstruksi burung camar tersebut.
“Risa,” panggil Hanan.
“Ya, Pak.”
“Oci tahu kalau kamu merokok?”
Meskipun tidak ingin, Risa mendapati dirinya harus mengambil jeda sejenak sebelum menjawab, “Tahu.”
“Oh, kalian benar-benar bersahabat baik. Apa katanya?”
Suasana sore itu kembali merebak dalam ingatan Risa. Angin mendadak berembus kencang, mengelepakkan gorden dan menerbangkan ujung-ujung rambut Oci yang menyentuh bahu; baunya seperti sedikit rokok bercampur parfum stroberi. Sinar matahari membanjiri kamar serta mengempas bagian belakang kepala Oci, menjadikan helaian rambutnya tampak seperti warna tembaga dan menyembunyikan senyumnya dalam siluet gelap.
Oci bergerak sedikit, Risa dapat melihatnya, tapi semakin banyak pergerakan menyebabkan citra sahabatnya sepenuhnya buyar dan digantikan raut muka Hanan yang masih menanti jawaban. Risa mengalihkan pandangan kembali ke papan di atas meja.
“Tidak bilang apa-apa. Bukan sesuatu yang penting.”
Hanan sekadar menggumamkan satu silabel tanda mengerti, padahal Risa memerlukan serentetan cerocosan tanpa makna untuk dapat mengusir rasa yang menghantui ujung-ujung jari serta ruas-ruas tulang belakangnya. Mustahil dia mempertahankan ketenangan jika dikelilingi keheningan yang semakin mengobarkan kegelisahan panas di setiap jengkal kulitnya.
Kenapa dia memikirkan sore itu? Kenapa, di antara sekian banyak hal yang dapat diingatnya dari Oci, dia justru mengenang helaian rambut Oci yang berayun dan memendarkan cahaya emas?
“Risa,” panggil Hanan lagi, dan Risa baru menyadari pergelangan tangannya telah berada di genggaman Hanan. Dia memandang kosong jari-jemarinya yang gemetar, helaian rambut yang rontok ikut berguncang di telapaknya. “Maafkan saya, Risa. Mengingat Oci pasti masih terasa berat untukmu.”
Risa menggertakkan rahang, mengepalkan tangan kuat-kuat dan menariknya dari pegangan wali kelasnya. “Guru laki-laki macam apa yang menyentuh muridnya. Astaga. Ibu saya bisa menangis kalau melihat ini.”
Hanan tidak menanggapi provokasinya; lelaki itu sekadar memandanginya lekat-lekat. Risa melingkari pergelangan tangannya sendiri menggunakan tangan yang lain, mengusap-usap kulit yang masih mengingat tekanan serta suhu jari-jemari Hanan.
“Saya tidak begini hanya karena mengingat Oci,” gumam Risa, tidak sanggup menanggung keheningan yang entah bagaimana terasa seperti kesalahannya sendiri.
“Lantas?”
Risa merapatkan bibir, menolak menjawab—menolak mendengar jawabannya sendiri. Hanan mendesah pelan, lalu mengumpulkan kepingan puzzle yang masih teronggok di meja dan memasukkannya kembali ke wadah.
“Maaf, tampaknya saya belum berhasil memahami perasaanmu. Saya akan pulang. Kalau ada waktu, selesaikanlah puzzle ini dan coba buka-buka pelajaran yang sudah saya berikan kemarin.”
Satu hal yang dipelajari Risa dari Hanan adalah lelaki itu selalu memaknai ucapannya. Hanya dalam waktu tiga menit, lelaki itu sudah berdiri di teras dan mengenakan sepatu, sedangkan Risa berdiri di ambang pintu tanpa tahu harus mengatakan apa.
“Besok kamu mau diberi hadiah apa?”
“Tidak usah,” kata Risa. Dia sedang menunduk, akibatnya dapat melihat Hanan pelan-pelan menurunkan sebelah kaki yang tadinya diangkat untuk mengenakan sepatu.
“Apakah sebaiknya saya tidak usah pulang, setidaknya sampai ibumu selesai arisan?”
Risa mendengus, kemudian mendongak, siap untuk meluncurkan kata-kata bernada sinis, tapi ekspresi serius di wajah Hanan menghentikannya. Wajar jika lelaki itu prihatin—atau setidak-tidaknya agak jijik—setelah dua kali mendapati Risa menjambak rambut seperti hendak menggunduli kepalanya sendiri. Padahal, tidak seorang pun bahkan ibunya mengetahui kecenderungan yang muncul semenjak kepergian Oci.
“Saya lebih suka suka sendirian,” kata Risa, mau tidak mau melembutkan suaranya. “Bisa merokok dengan bebas seperti lokomotif uap.”
Ekspresi yang melintas di wajah Hanan selama sepersekian detik sempat membuat Risa terperenyak. Haru, sedih, atau justru kasihan? Momen berikutnya, bagaimanapun, sekali lagi Hanan menyunggingkan senyum lebarnya yang biasa.
“Begitukah? Saya merasa kasihan pada paru-parumu, tapi kamu pasti menganggap saya cerewet.”
“Saya cukup kagum ternyata Bapak menyadari itu.”
Hanan tertawa dan memasukkan kedua tangan ke saku celana. “Tawaran saya masih berlaku. Besok kamu ingin dibawakan apa?” Dia memiringkan kepala ke samping dengan lagak berpikir. “Mungkin kita bisa main monopoli atau ular-tangga, mana yang paling kamu sukai? Secara pribadi saya lebih suka ular-tangga karena tidak rumit. Di sisi lain, monopoli akan membuat kamu—”
“Apa pun itu tidak masalah,” sela Risa bosan. Apakah dia sungguh-sungguh sempat berharap mendengar cerocosan Hanan? “Toh pada akhirnya saya tidak bisa mencegah Bapak datang ke sini.”
“Memang benar. Kalau begitu, kamu tunggu saja kejutan dari saya,” kata Hanan, lalu mengedipkan sebelah mata. Sebagai balasan, Risa memutar bola mata. Hanan tertawa. “Saya senang melihatmu kembali baik-baik saja.”
Risa tahu apa yang diimplikasikan Hanan. “Jangan anggap saya penyakitan.”
“Sama sekali tidak seperti itu. Tapi, Risa.” Tangan kanan Hanan dikeluarkan dari saku celana dan terulur mendekati kepala Risa. Kalaupun lelaki itu memutuskan menyinggungkan jemari pada satu atau dua helai rambutnya, Risa tidak akan bisa merasakan sentuhan seringan bulu tersebut. “Saya yakin sekali kamu bisa berhenti melakukan ini. Tampaknya sangat menyakitkan.”
“Saya tidak mau,” jawab Risa tanpa ragu, sejenak membekukan gerakan tangan Hanan yang sudah ditarik dari kepalanya. “Momen ketika saya sepenuhnya pulih dan bisa berjalan maju, artinya saya sudah meninggalkan Oci sendirian jauh di bawah tanah sana.”
Dan artinya dia sudah memaafkan dirinya sendiri, yang mana mustahil dilakukan. Tapi Risa tidak mengatakannya. Tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak dipahami Hanan.
Hanan tertegun. “Apakah kamu berniat melanjutkan hidup seperti ini selamanya?”
“Siapa tahu, kalau itu perlu.”
“Tapi tidak ada yang memerlukannya,” kata Hanan serius. “Risa, satu-satunya yang diharapkan semua orang di sekitarmu adalah melihatmu pulih seratus persen. Saya yakin Oci juga lebih senang kalau kamu berbahagia.”
Lucu bagaimana Hanan berbicara seolah-olah memahami gejolak perasaan Oci hanya sesaat sebelum hidupnya berakhir. Semua orang berbicara seolah-olah mereka adalah perwakilan isi pikiran Oci. Padahal, tidak seorang pun tahu.
“Sampai besok, Pak.”
“Tunggu—”
Risa bergegas menutup pintu dan berlari ke lantai dua, kemudian masuk ke kamarnya dengan membanting pintu. Akan tetapi, kamarnya yang berbau rokok hanya mengingatkannya pada Oci, pada sore itu, sehingga Risa cepat-cepat mengeluarkan kepalanya ke jendela, berusaha meredakan gejolak perasaan yang merambati punggung serta tengkuknya, menjalar ke depan dan akhirnya menelan seluruh tubuh.
“Risa!”
Risa membuka paksa matanya yang entah sejak kapan tertutup rapat. Dia melihat Hanan berdiri di sebelah mobil dan menaungi mata menggunakan satu tangan untuk melawan pancaran matahari sore yang ganas.
“Besok kita tidak akan membahas itu lagi, saya janji. Karena itu, maafkan keteledoran saya.”
“Bapak kebanyakan bicara,” seru Risa, kemudian memunggungi jendela dan merosot hingga duduk bersimpuh di lantai.
Entah kenapa pemandangan kamarnya tampak sangat mencekik, jadi Risa beranjak keluar dari kamar untuk mengambil puzzle yang masih ada di ruang tamu.


 zaky
zaky