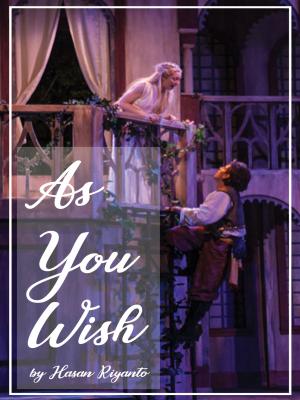[ EVAN ]
"JADI, EVAN, GIMANA UN kamu kemarin?" tanya Dokter Arni-onkologis[1] anak yang biasa menanganiku-dengan nada yang biasa dipakai untuk berbicara dengan anak berumur lima tahun. Aku, yang dari tadi sibuk menonton film Doctor Strange di TV kabel kamar rawatku, baru ngeh kalau aku diajak bicara waktu beliau menggengam tangan kiriku yang diinfus. (Ini, BTW, adalah rawat inapku yang kedua selama libur kenaikan kelas.) "Kamu rencananya mau ngelanjutin SMA di mana?"
Tangan kananku, yang nggak diinfus, sedang memeluk boneka gajah maskotnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Theresia yang kudapat waktu kemoterapi pertama di sini. Yang membuat aku semakin kelihatan seperti bocah yang kebetulan saja kelewat bongsor. Dengan wallpaper motif kebun binatang dan segala macam dekorasi yang membuat ruangan ini lebih mirip kamar anak-anak ketimbang ruang rawat inap, sangat mudah bagi dokter-dokter dan perawat-perawat untuk lupa kalau umurku hampir enam belas tahun. (Secara teknis sebenarnya sih baru lima belas lebih dua bulan, tapi aku nggak pernah suka menyebut diriku sebagai "anak berumur lima belas tahun". Umur lima belas, nggak kayak enam belas, kesannya terlalu nanggung.)
Sebenarnya menurutku nggak etis nanyain pertanyaan yang menyangkut masa depan-kayak mau ngelanjutin SMA dimana dan semacamnya-kepada seorang anak yang hidupnya nggak lama lagi, namun aku menjawab, "Di Adiwiyata," yang merupakan nama SMA swasta yang letaknya nggak jauh dari pusat kota.
Aku sengaja nggak nambahin, seharusnya saya masuk sekolah bola di Jakarta tapi nggak jadi. Semua orang yang ada di ruangan ini tahu kenapa. Dulu, sebelum diagnosis dan kemoterapi dan obat-obatan yang namanya bahkan nggak bisa kueja, aku sempat menjadi kapten tim sepakbola di SMP-ku. Aku nggak pintar matematika dan nggak bisa dengan cepat menghafal ibukota semua negara di Eropa Timur, tetapi aku jago bermain bola. Cuma itu satu-satunya yang membuatku stand out di antara anak-anak lain. Aku nggak mau dikenal sebagai sekedar salah satu dari bocah-bocah SMP ingusan biasa yang banyak berkeliaran di sekolahku. Dan dengan bermain bola, se-enggaknya aku kurang lebih punya sesuatu yang bikin aku beda dari anak-anak lain.
Sayangnya, semuanya harus berakhir dengan diagnosis, kemoterapi, dan obat-obatan yang namanya bahkan nggak bisa kueja tadi. Beberapa bulan yang lalu, Dokter Arni bahkan memberitahuku kalau kaki kiriku sudah 50% nggak berfungsi, sehingga mau nggak mau aku terpaksa keluar dari tim.
Meski demikian, main bola bagi seorang Evan Alamsyair harus tetap jalan (walaupun aku seringkali merasa sakit tiap kali memaksakan diri berlari-after all, boro-boro lari di lapangan, untuk jalan saja aku pincang), dan hal inilah yang aku ceritakan ke Dokter Arni. Pasien yang kurang ajar memang, apalagi Dokter Arni-lah yang waktu itu melarangku main bola. Tetapi anehnya, Dokter Arni nggak berkomentar apa-apa. Beliau hanya memandang Mama dan Papa, yang hari itu datang menjengukku, dengan tatapan khawatir. Kayaknya beliau mau mengganti topik pembicaraan.
Papa, yang orangnya to-the-point dan nggak suka berbasa-basi, tahu kalau Dokter Arni sedang berusaha untuk nggak mengatakan apa yang sebenarnya beliau mau katakan. Beating around the bush. "Bu," ucap Papa dengan nada tegas, "Saya nggak suka basa-basi kayak gini. Tolong kasih tahu saja anak saya ini kenapa." Papa menunjukkan raut wajah yang biasa beliau gunakan tiap kali komplain ke kepala sekolah mengenai nilai raporku, raut wajah yang akan membuat siapa saja langsung patuh. Papa selalu dapat apa yang beliau inginkan.
Dokter Arni kembali menatapku. Dengan amat berhati-hati, beliau meminta, "Saya...boleh minta izin keluar sebentar? Ada yang mau saya bicarain sama papa-mama kamu." Kemudian, Dokter Arni beralih ke Papa. "Uhm, Pak Heru, Bu Lydia, bisa kita bicarakan ini di luar?" Aku ada feeling kalau sebenarnya Dokter Arni mau menambahkan, saya nggak yakin kalau Evan siap buat mendengar semuanya langsung. Satu lagi bukti kalau Rumah Sakit Ibu dan Anak Theresia memperlakukanku kayak anak kecil.
Maka begitu mereka bertiga keluar dari kamar, aku diam-diam bangkit dari tempat tidur dan lompat-lompat dengan satu kaki (kaki kanan, tentunya) ke arah pintu depan supaya aku bisa nguping. Dengan tangan kiriku yang diinfus dan tangan kananku yang memeluk boneka gajah dan segalanya.
"Jadi, Bu, bahkan saya sendiri kaget, lho, begitu melihat hasil PET scan-nya Evan." Itu suaranya Dokter Arni, yang entah kenapa lebih terdengar kayak bisikan.
"K-kenapa memangnya, Dok?" Ini Mama. Aku hampir bisa membayangkan Mama menutup mulutnya dengan kerah jaket turtleneck yang hari ini beliau pakai. Kebiasaan Mama tiap kali beliau merasa cemas.
Aku bisa mendengar Dokter Arni menghela napasnya sejenak. "Kankernya," perempuan berumur tiga puluhan itu mulai angkat suara, "sudah bermetastasis, Bu. Dalam kata lain, menyebar ke mana-mana. Coba Ibu lihat sendiri." Kini aku bisa membayangkan Dokter Arni menyerahkan hasil PET scan-ku tadi pagi, yang menggambarkan bagaimana sel kanker dalam tubuhku sudah menyebar ke mana-mana, kayak bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Hening sejenak. "Kemungkinan Evan bisa survive dalam situasi seperti ini bisa dibilang sangat kecil."
"Nggak. Nggak mungkin." Papa, yang sudah amat terbiasa mendapatkan apa yang beliau mau, memang paling nggak bisa menerima kenyataan yang sering kali nggak sesuai dengan yang beliau (oke, aku juga) inginkan. "Ini bukan hasil PET scan-nya Evan. Pasti ketuker. Evan selama ini sehat, kok. Baru Sabtu kemarin dia pulang malam habis jalan sama pacarnya."
Helaan napas lagi, yang kemungkinan besar berasal dari Dokter Arni. "Tidak, Pak. Ini murni hasil PET scan Evan, tidak tertukar." Beliau berusaha terdengar setenang mungkin, walaupun aku tahu bahkan beliau sendiri merasa cemas melihat apa yang tercetak di kertas film yang mungkin tengah dipegang Mama. After all, Dokter Arni sudah menanganiku selama hampir dua tahun-bisa dibilang beliau sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Somewhat. "Kami akan berusaha melakukan apa pun yang kami bisa. Dan kalau Bapak dan Ibu mau ngasih tahu ini ke Evan...hati-hati. Saya permisi dulu."
Nggak lama kemudian, aku mendengar suara langkah kaki, yang berarti Dokter Arni sudah pergi.
Just like that, aku buru-buru melompat-lompat lagi dengan kaki kananku ke tempat tidur. Mama dan Papa nggak perlu tahu kalau aku barusan menguping pembicaraan mereka. Mereka memakan sekitar dua menitan di luar setelah Dokter Arni pergi, mungkin untuk mendiskusikan apakah mereka harus memberitahuku mengenai berita barusan atau nggak. Yang sebenarnya nggak perlu mereka lakukan, karena begitu Mama masuk ke dalam kamar dan memberitahuku kalau beliau punya kabar buruk, aku menunduk dan berkata dengan nada pelan, "Iya, Ma. Evan udah tahu."
Keluarga kami beranggotakan lima orang-selain Mama dan Papa, aku juga tinggal bersama satu kakak dan satu adik, yang dua-duanya cewek. Oke, secara teknis sebenarnya cuma empat orang. Kakakku, Margaret, kuliah di Singapura, dan baru hari ini dia pulang untuk libur semester.
Kayaknya nggak enak banget rasanya langsung disuguhi berita mengenai kanker adikmu yang menyebar ke sekujur tubuhnya begitu kamu baru pulang dari luar negeri, karena Maggie nggak terlihat begitu senang bisa makan berlima bareng keluarganya lagi. Malam ini, Mama memasak semur daging. Mama,Papa, dan Maggie sedang sibuk membahas hasil PET scan-ku dua hari yang lalu (baru kemarin aku pulang dari rumah sakit), sementara aku, yang menjadi topik utama pembicaraan, malah sibuk membalas Line dari Astrid secara diam-diam di bawah meja. Keluarga kami memangpunya aturan nggak tertulis yang melarang siapa pun memegang ponsel selamamakan malam bersama. Hana, adikku yang baru berumur lima tahun dan nggak ngerti apa-apa, sedari tadi terus-terusan merengek ke Mama minta dibelikan fidget spinner.
Astrid N.
evan
Astrid N.
denger" kamu diopname po?
Astrid N.
kamu tuh kalo ada apa" mbok ya kasih tau dong :(
Evan Alamsyair
ha? kamu tau dari mana aku diopname?
Aku menghela napas. Aku memang belum memberitahu Astrid-pacarku-mengenai penyakitku, dan aku nggak ingin dia tahu. Hal terakhir yang kubutuhkan di dunia ini adalah Astrid mengetahui kalau pacarnya orang penyakitan.
"Tapi Pa, Papa tahu sendiri kan, kalo Maggie nggak bisa drop out kuliah begitu aja?" Suara yang digunakan Maggie saat berdiskusi dengan mereka meninggi, seolah-olah dia nggak terima atas sesuatu yang baru saja dikatakan entah Mama atau Papa. "Maggie tuh udah nanggung di sana, Pa. Dikit lagi selesai skripsi
."
"Kamu sudah bilang itu ke Papa berulang-ulang selama dua tahun terakhir," ucap Papa dengan nada dingin. Maggie, omong-omong, memang bisa dibilang seorang mahasiswi abadi-umurnya hampir 23 tahun, dan saat kebanyakan teman-teman seangkatannya sudah bekerja dan menabung untuk uang nikah, kakakku yang satu itu masih sibuk berkutat dengan skripsinya yang tak kunjung selesai. "Pokoknya, tahun ini kamu harus sudah sidang. Kalo nggak, mendingan kamu nggak usah lanjut."
"Tapi Pa-"
Maggie nggak sempat menyelesaikan kalimatnya, karena Mama buru-buru menimpali, "Ngebiayain kamu kuliah di sana itu nggak murah, Sayang. Apalagi kamu tahu sendiri kan, keadaan keluarga kita sekarang kayak gimana." Dari cara Mama melirikku begitu mengatakan kalimat barusan, nampaknya sudah nggak usah ditebak lagi apa yang beliau maksud dengan keadaan keluarga kita sekarang. Aku menunduk dan memutuskan untuk kembali berkutat dengan Line, saat Mama tahu-tahu memergokiku sedang mengetik sesuatu di ponselku. "Evan, kamu tahu kan kalau ini momen kebersamaan keluarga? Sini HP-nya Mama pegang." Dengan amat terpaksa, aku kemudian menyerahkan iPhone ber-casing Supreme-ku ke Mama.
Maggie menghela napasnya. Terlihat jelas dari raut wajahnya kalau dia kesal. "Maggie capek," gerutunya. "Kenapa sih, Maggie harus selalu ngorbanin masa depan Maggie buat anak yang nggak punya masa depan?" Maggie memelototiku, dan aku kembali menunduk.
"Margaret, kamu nggak boleh bilang gitu-"
Sebelum Mama selesai berbicara, Maggie sudah bangkit dari kursinya dan naik ke kamarnya ke lantai atas. Sangat jelas kalau dia sudah cukup muak dengan percakapan omong kosong mengenai keuangan-keluarga-lagi-susah-dan-adikmu-sedang-sakit-keras ini, dan hal tersebut membuatku semakin merasa nggak enak. Karena itu, tanpa menghabiskan semur daging Mama dan minum obat seperti yang seharusnya kulakukan tiap malam, aku mohon diri sebelum naik ke atas, menyusul Maggie.
"Mama, beliin Hana fijed spinel," rengek Hana sambil menarik-narik lengan Mama.
[1] Dokter yang khusus bekerja di bidang mencegah, mendiagnosis, dan menangani penyakit kanker.
a/n; heya guys ini hilly dan gue memang masih baru di sini wkwk. beberapa dari kalian mungkin mengenal gue sebagai @sweatertowns di wattpad, namun kali ini gue lagi mencoba platform tinlit karena rekomendasi dari temen wkwk. (shoutout to netta @EttaGurl yang koar-koar tentang web ini di gc).
anyways, doakan aku sukses di lomba tinlit x grasindo ini yaps. ehe.


 sweatertowns
sweatertowns