Satu belokan dari SMA Bhakti Negara, ada warung nasi padang yang sering jadi langganan guru-guru dan murid-murid di sana. Warung makan itu selalu ramai saat jam makan siang dan pulang sekolah. Tempat itu beruntung, memiliki lokasi strategis di antara minimarket, Masjid, dan sekolah sehingga jadi salah tujuan utama perut-perut keroncongan.
Laksana pelangi di tengah gurun, gadis cantik itu kontan mencuri perhatian dengan kemunculannya di sana. Di belakang setumpuk kerupuk bawang yang sudah diplastik-plastikan hingga menggunung, ia yang hari itu mengenakan terusan bermotif bunga daisy dan sepatu kanvas hitam, menclok di sana. Tak lupa, kacamata hitam bulat ala John Lennon sudah nongkrong di atas kepalanya, menjadi bingkai untuk poni agung yang di-blow amat rapi.
Sejak sepuluh menit disajikan, seporsi gulai ayam dan es teh manis sudah tenggelam ke dalam perutnya. Dengan ekspresi kekenyangan, Isabel kembali melirik ke arah pintu. Abriel muncul di sana tak sampai lima detik kemudian.
"Aku nerima kertas yang kamu titipin ke Mang Diman, kamu kreatif ya kepikiran kayak gitu." Mang Diman adalah petugas kebersihan SMA Bhakti Negara yang terkenal dekat dengan murid-murid.
Isabel tersenyum puas. "Saya kasih tiga puluh ribu supaya surat itu sampai ke tangan kamu. Berhasil, kan, saya bilang kita bisa kan ketemu tanpa HP."
"Para genius yang udah capek-capek nyiptain berbagai alat teknologi komunikasi canggih harusnya protes tuh sama kamu," dumel Abriel sembari mengulurkan tangan untuk membawakan tas kulit besar yang dibawa Isabel. "Kamu bawa apaan aja? Berat banget. Nggak masukin batu bata ke sini, kan?"
"Kalau nebak tuh kreatif dikitan dong, Mas. Jadi... tas itu tuh isinya setumpuk perkamen paling rahasia dan lima keping hard drive dalam boks terkunci plus antipeluru. Semuanya milik pemerintah United States. Masalahnya, kalau saya kasih lihat kamu bentuknya, kamu bakal dikejar sama FBI dan militer Amerika Serikat seumur hidup kamu. Bahkan kalau kamu nyerah pun pilihannya hanya dilobotomi atau potong lidah," ujar Isabel dengan cepat dan lancar, seolah kalimat itu sudah dikatakannya ratusan kali."So, masih pengin tahu isinya?"
"Selain jadi angsa jadi-jadian, ternyata kamu berbakat juga jadi pengarang. Beneran," kekeh Abriel sungguhan takjub.
"Pengarang itu cuma istilah ningrat untuk pembohong profesional," decak Isabel.
"Kalau gitu, kamu termasuk yang mana: pengarang atau pembohong?"
Isabel mendadak mengamati wajah Abriel untuk beberapa saat sebelum menjawab, "Semuanya."
Mereka sudah berdiri di depan mobil Abriel yang diparkirkan di dekat sana. Dan ketika Abriel sedang membukakan pintu penumpang untuk Isabel, rombongan anak OSIS berpapasan dengan mereka di sana. Dengan canggung, Abriel membalas sapaan beberapa orang yang dikenalnya. Sebelum ia memutari kap depan mobilnya, masuk dan memasang sabuk pengamannya.
"Kapan kamu futsal lagi?" tanya Isabel begitu mobil melaju.
"Belum tahu," jawab Abriel dengan tangan di kemudi. "Aku ke sana kadang-kadang aja, ikut Adit doang. Adit itu temen deket banget, duduk sebangku juga."
"Adit itu yang..."
"Tinggi banget, putih, rambutnya kelimis gitu. Yang pakai baju biru. Badannya paling gede aja kemarin. Nggak gendut, tapi berotot banget."
"Yang sepatunya oranye?"
"Nah, iya."
"Jadi, kamu masih belum tahu kapan mau ke sana lagi?"
"Belum. Mama sama Papa lagi penginnya aku mengurangi kegiatan." Abriel lalu tiba-tiba kembali teringat hari itu, hari di mana ia melihat Isabel di gedung futsal. "Jadi, kamu udah boleh kasih tahu aku kenapa kamu bisa ada di sana kemarin?"
Isabel tegelak. "Sebenarnya nggak penting-penting amat. Kalaupun saya kasih tahu kamu, nggak akan ngaruh apa-apa buat kamu."
"Aku mau nanya sesuatu, boleh?" Ekor matanya mengarah ke Isabel, menatap ekspresi gadis itu yang mendadak tidak nyaman.
"Soal apa?"
"Nggak serius dan nggak maksa untuk dijawab. Aku cuma penasaran, hampir setiap hari, kalau nggak pakai taksi, kamu nunggu dijemput atau pulang diantar seseorang..."
"Saya kerja, cari duit," potong Isabel cepat, nadanya lega dan ceria. Seolah ada pertanyaan lain yang ia waspadai sebelumnya. "Yang jemput saya itu klien-klien saya. Nggak setiap hari sih dapet klien, tapi kadang sehari bisa dua lokasi. Kebanyakan klien saya itu memang cowok. Tapi waktu di Jakarta dalam seminggu saya pernah dapet klien cewek semua. Saya udah begini selama tujuh bulan."
Karena terkejut dengan kelugasan ucapannya, Abriel nyaris mengerem mobilnya mendadak. Bunyi klakson pengendara motor di belakangnya, membuat suasana makin kikuk.
"Klien? Maksud kamu, kamu itu menyediakan jasa... Oh, aku dengar Mama kamu punya tempat katering terkenal banget, apa kamu yang handle bagian ketemu klien Mama kamu?"
"Bukan klien Mama, klien saya sendiri, kok," bantah Isabel langsung.
"Aku agak nggak ngerti." Nada suara Abriel meninggi tanpa bisa ia kendalikan. Ia sendiri sedikit terkejut oleh nada bicaranya itu.
Isabel mendesah setelah terdiam beberapa detik. "Saya ini cewe bayaran, Abriel. Selesai saya lakuin job saya, ya saya dibayar."
Hening seketika. Abriel kehilangan kata-kata. Seakan ada tangan transparan yang memberikan kepingan puzzle terakhir padanya, kemudian tanpa dapat dicegah isi kepalanya mulai mencocokkan setiap ingatan. Semua mobil dan cowok yang menjemput serta mengantar Isabel pulang. Kostum-kostum anehnya, yang mungkin adalah request dari klien-kliennya itu, demi memuaskan hasrat gelap dan liar mereka. Dalam sekejap, semua monolog internal di dalam pikiran Abriel semakin menggila dan tak terkendali.
Abriel merasakan runtuhnya sesuatu dalam dirinya. Ia sedang berusaha meraba perasaannya. Dan di sanalah, di bagian inti dadanya, ia merasakan sebersit kekhawatiran lebih mendominasi kekecewaannya.
"Terus, apa Mama kamu tahu soal itu?" Abriel akhirnya berkata, suaranya terdengar tertahan dan merintih. Ia tidak melirik Isabel, ia takut menemukan fakta lain yang meruntuhkan sesuatu yang lain dari dirinya. Gestur Isabel yang masih tetap tenang dan santai membuatnya tidak nyaman.
Isabel menatapnya meskipun pandangan Abriel hanya lurus ke depan. "Yang di Jakarta sih kayaknya tahu. Cuma selama saya happy... Yang penting kayaknya saya selalu ngabarin aja. Kerjaan saya di Bandung yang saya nggak bilang, soalnya sebelum pindah saya sempet bikin janji. Entah tahun depan atau dua tahun lagi saya mau kuliah. Target saya NYU, saya kepingin banget tinggal di New York. Tapi kalau harus di dalam negeri juga nggak apa-apa. Banyak universitas bagus di sini."
"Aneh," Abriel tidak tahan untuk tidak mengerang. "Kamu tuh serius sama semua omongan kamu ini?"
"Sebenarnya saya sih penginnya berhenti nggak ngelakuin itu lagi, toh saya nggak kekurangan kalau soal materi. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena kepuasan batin aja."
Mata dan alis Abriel sudah naik. Genggaman kemudinya menguat. Perutnya terasa mulas. "Kepuasan batin? Ini hal tergila yang pernah aku dengar. Dan nggak tahu kenapa, kok aku sedih banget ya..."
"Percaya deh, ini terapi buat saya. Dulu hidup saya pernah seribu kali lebih ancur dari ini... Cara terbaik untuk bangkit adalah berdamai dengan masa lalu dan menghadapi sedikit demi sedikit ketakutan saya. Hal positif lain yang saya dapat sebagai bonus, saya bikin orang senang juga. Dan... dapat duit."
Ekspresi Abriel begitu kaku hingga nyengir pun dia enggan.
"Kalau kamu jadi saya, kamu bakal sadar betapa logisnya yang saya lakuin. Job saya sekarang bantu saya banget untuk bisa memindai lagi perasaan saya. Saya nggak mau jadi heartless selamanya," Isabel melanjutkan.
"Iya, logis. Kamu memang 'menyenangkan' orang lain, cowok-cowok itu. Tapi menurut aku itu namanya bukan berdamai dengan masa lalu, bukan terapi, bukan juga membuka lembaran baru. Itu namanya loncat ke jurang, nggak pake parasut-parasutan. Memang, nggak bisa dipastiin seratus persen kamu bakal mati setelah melompat, tapi ingatan itu, trauma itu, sedikit demi sedikit akan ngikis jiwa kamu," Abriel berkata, dongkol karena Isabel tidak memahami situasi yang ia ciptakan dari pengakuannya itu. Abriel merasa ingin melompati bara api, dengan komiknya di genggamannya.
Dicecar dengan kata-kata sinis, Abriel malah mendengar gadis itu terkekeh. "Omongan kamu lucu, ya. Seolah-olah kamu udah pernah ketemu langsung sama jiwa saya aja."
* * *
Heran, Isabel masih melongo tidak percaya waktu Abriel mendadak saja membatalkan acara mereka sore itu, dan malah berbelok ke arah jalan pulang.
Sepanjang perjalanan hingga sampai ke gerbang kompleks mereka, Abriel pun tidak menjelaskan apa-apa selain kalimat "nggak apa-apa" dan "lain kali aja, ya" meski Isabel terus-terusan menanyai alasannya memilih pulang serta bersikap seratus delapan puluh derajat.
"Aku mendadak capek aja," akhirnya Abriel berkata setelah ia mematikan mesin mobilnya. Raut wajahnya keras seperti tanah liat yang seharian terpanggang.
Isabel belum pernah melihatnya seperti itu. Selama ini, Abriel selalu lembut ketika berbicara dengannya dan hangat ketika menatapnya. Nada dan sorotan itu mendadak lenyap. Abriel bahkan beberapa kali menghindari tatapan Isabel.
Isabel sadar, ada sesuatu yang menyentil nuraninya. Ia terkejut menyadari betapa lamanya ia tidak merasakan perasaan seperti itu.
"El, saya boleh nggak, ngomong sama kamu sebentar?" Itulah kali pertama Isabel memanggil Abriel tidak dengan kaku dan lengkap. Tapi hanya dengan "El".
Berkat panggilan yang akrab bagi Abriel itu, cowok itu pun tak kuasa untuk tidak mendongak menatap sepasang mata bundar milik Isabel. Ia mengangguk.
Abriel pun segera memarkirkan mobilnya di trotoar rumahnya sebelum menyeberang menghampiri Isabel di beranda rumahnya. Abriel duduk di salah satu kursi besi tempa bercat putih di sana. Ia masih enggan menatap langsung mata Isabel.
"Kamu marah sama saya, ya?" Isabel mengatakan itu dengan setengah mendesak.
Abriel kembali merasa tidak nyaman. Ia tahu persis bermuara ke mana pembicaraan mereka jika ia mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Ia lelah untuk menjelaskan. Ia merasa tidak punya tenaga untuk melakukan apapun. Ia hanya ingin merobek komiknya, dan tidur.
"Kenapa harus marah?" Abriel memandangi sepatu hitam bergaris putihnya. Saking telitinya ia menatap kakinya, sekarang ia juga sadar kalau ada jaitan yang terbuka di betis celana seragamnya.
"Teknik bolak-balik gitu nggak akan berlaku kalau ngobrolnya sama saya," kata Isabel. "Sejujurnya saya nggak tahu kenapa kamu sampai semarah ini. Apa kamu bisa kasih tahu saya apa yang kamu pikirin sekarang?"
Abriel menggeleng kuat. "Aku nggak bisa jelasin. Cuma, dulu aku ngiranya kamu tuh orang paling... polos, unik sekaligus ajaib yang pernah aku temuin. Sekarang aku baru sadar kamu tuh bener-bener orang paling nggak masuk akal di dunia. Seseorang yang nggak akan pernah bisa aku ngertiin sama nalar aku yang cara kerjanya seperti manusia normal pada umumnya."
Isabel masih menatap Abriel.
"Kamu nggak seperti yang aku bayangin," akhirnya Abriel mengungkapkan apa yang ingin dikatakannya sejak tadi. "Dan aku kecewa." Ia sengaja menekankan kata terakhir itu.
Kali ini Isabel yang tampak mengeras. "Terus tugas saya untuk bikin semua orang di sekitar saya terkesan dan puas sama saya? Salah saya kalau ada sesuatu dalam diri saya yang mendadak bikin kamu wow-oh-so-begitu-kecewanya?"
"Isabel," panggil Abriel, pelan dan lirih. Tapi tidak lembut. "Kamu benar-benar nggak ngerasa ada perkataan kamu sebelumnya ada yang salah? Paling nggak, sedikit aja..."
Isabel mengangkat satu alisnya, berusaha mengingat-ingat. "Ada perkataan saya yang menyinggung kamu secara langsung?"
Abriel bisa merasakan berat di kepalanya. Ia menunduk menatap lantai linoleum di kakinya. "Bel, aku rasa ada yang salah sama kepala kamu. Saran aku sebagai teman, seseorang yang peduli sama kamu, sebaiknya kamu minta rekomendasi untuk ketemu profesional, deh." Ia kemudian bangkit berdiri, menatap Isabel selama dua detik. Tatapannya dingin, Isabel bisa merasakannya. "Aku balik, ya."
Setengah mati Isabel berharap untuk bisa mengatakan semuanya pada Abriel. Bahwa sudah tujuh profesional yang ia kunjungi, hingga ia menemukan satu terapis yang cocok. Bahwa ia tidak pernah absen untuk minum obat jika diperlukan. Tapi lidahnya terasa kelu.
Isabel bisa melihat rambut cokelat Abriel tampak bersemburat keemasan ketika melewati jalanan, dan berubah hitam ketika berpayung kanopi rumahnya. Kemudian, segalanya pun lenyap, tak ada lagi warna bagi Isabel. Pintu rumah tetangganya itu tidak pernah dibanting begitu keras.


 Andrafedya
Andrafedya








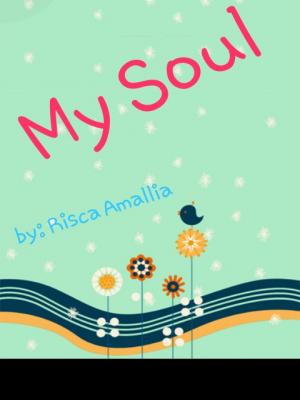





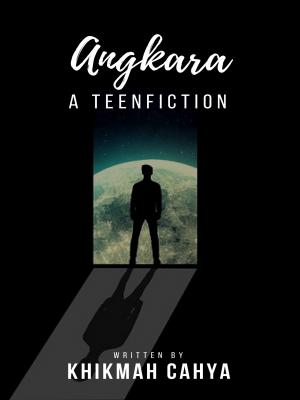

Teenlit namun lbh matang. Metropop namun tidak ngepop amat. Kadarnya pas, bakal lanjut membaca cerita cantik ini. Trims Author untuk cerita ini
Comment on chapter 1. Makhluk MalangKalau suda beres saya akan kasih review.