Hari-hariku di sekolah benar-benar menyebalkan sekarang. Nggak ada yang menarik sama sekali. Ini hari ketiga Arda mengacuhkanku. Dan Rafa, dari kemarin-kemarin dia masih saja mengumbar kemesraan bersama Ralin DI DEPAN UMUM. Lalu, apa arti pelukannya tiga hari yang lalu itu?
Dasar buaya! Apa sih yang aku pikirkan saat Rafa memelukku? Seharusnya aku mendorong tubuhnya sampai terjengkang. Bukannya malah diam dan pasrah. Sampai akhirnya Arda melihatnya. Dan sekarang, karena kebodohanku itu, Arda meninggalkanku.
Tapi, aku merindukannya kebersamaanku dengan Rafa. Aaaargh… Siapa pun, pukul kepalaku sampai itu si Rafa keluar dan nggak lagi menggangguku. Atau kalau ada operasi untuk menghilangkan Rafa dari kepalaku, aku akan melakukannya. Berapa pun biayanya, dehh. Atau ada obat mungkin, yang bisa untuk mengusir Rafa dari pikiranku. Walau pun harus melakukan perjalanan ke Barat untuk mencarinya, akan kulakukan.
Aku mengacak rambutku dengan frustasi.
“Tara?”
Aku menghentikan langkahku, langsung merapikan rambut begitu mendengar namaku di panggil. Kemudian menoleh ke belakang. Rafa mendekatiku dengan wajah suram.
“Bisa ngobrol sebentar?”
“Ya udah, ngomong aja sih.” Aku menjawab dengan sinis. Rafa menoleh ke sekitar. Ya pastilah banyak anak yang seliweran. Ini kan jam berangkat sekolah.
“Kamu sama Arda?” Rafa memulai dengan ragu. Aku jadi teringat cerita Arda soal Rafa yang mengancamnya untuk menjauhiku.
“Ngomong apa kamu ke Arda?” Aku menatapnya tajam. Rafa hanya menatapku dalam diam. Cukup lama. Yang kulakukan juga sama. Aku diam menunggunya menjawab pertanyaanku.
“Arda udah cerita?” Rafa menjawab dengan tampang innocentnya itu. Bikin aku makin muak.
“Raf, kamu yang putusin aku. Kamu yang bilang nggak bisa lanjutin hubungan tanpa perasaan lagi. Itu artinya kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Tapi kenapa disaat aku mulai menemukan kebahagianku, yang ada pada orang lain, kamu menghancurkannya? Apa nggak cukup dengan kamu sakiti aku dulu. Dan lebih pilih Ralin?”
“Aku masih sayang sama kamu, Ra. Ralin, aku nggak pernah sayang sama dia.” Rafa memotong perkataanku. Aku tersenyum sinis.
Melihat anak-anak yang tadinya berjalan tanpa memperhatikan kami, setelah mendengar suara Rafa yang lumayan keras barusan itu, menghentikan langkah dan menatap ke arah kami. Aku bukan artis. Aku nggak mau apa pun yang terjadi padaku menjadi konsumsi publik. Maka tanpa banyak bicara lagi aku melangkah meninggalkan Rafa yang masih saja berdiri ditempatnya.
----
“TARAA?”
Bisa tebak, kan, siapa yang teriak barusan? Ya. Siapa lagi kalau bukan Lyana? Aku memilih pura-pura nggak dengar karena saat ini koridor lagi penuh banget dengan anak-anak pulang sekolah.
“TARA!” Lyana kini sudah berdiri di depanku dengan tubuh membungkuk dan napas ngos-ngosan.
“Apa, sih?”
“Elo kok tinggalin gue, sih? Gue teriakin dari tadi juga.” Gerutu Lyana. Dia mengusap dadanya yang masih naik turun. Aku jadi tertawa geli melihat tingkahnya.
“Emang gue maling pake diteriakin segala?”
“Ikut gue, yuuk?” Kata Lyana setelah napasnya lebih teratur. Aku menatap curiga. Bisa kulihat ada sesuatu yang nggak beres.
“Kemana?”
“Ke PIM.”
“Mau ngapain? Siang-siang bolong begini.” Aku berseru histeris.
Benar, kan?
Kalau aku mengikuti ajakan Lyana, yang ada jam sepuluh malam aku baru sampai rumah dengan badan serasa habis digepuki orang satu sekolah. Asal tahu saja, kalau sudah di mal, tujuan utama Lyana itu pasti shopping.
Dan kalau sudah shopping, seluruh butik atau toko yang ada di mal bakal dia masuki satu per satu. Belum lagi ribetnya pilih model bajulah, model sepatulah. Warna apa yang bagus, mana model terbaru.
Sumpah, aku paling malas. Yang benar saja? Ini itu jam pulang sekolah, lho. Enakan juga pulang, makan, terus tidur siang.
“Mau mancing. Ya menurut lo, kalo anak seumuran kita ke mal mau ngapain sih??” Lyana menatapku seolah baru saja aku bilang, ‘Boleh nggak Molly buat gue?’
Molly itu nama kucing Anggora kesayangan Lyana. Pernah sekali Molly kabur dari rumah. Dari pagi sampai sore Lyana nggak berhenti menangis. Nggak mau makan. Nggak mau ngapa-ngapain. Baru mau berhenti menangis dan mau makan setelah Pak Madun?supir Papanya?menemukan Molly di gapura masuk kompleks rumahnya, dan membawanya pulang.
Gila, kan? Kehilangan kucing saja hebohnya sudah seperti kehilangan orang tersayang.
“Ahh, males gue. Entar ujung-ujungnya lo suruh bawain belanjaan lagi.” Tuduhku.
“Enggak! Cuma mau nyari sepatu doang. Jumat kan, ada jam olahraga. Sepatu olahraga gue udah butut, Ra. Masa lo tega sih lihat gue pake sepatu butut?” Lyana merengek dengan tampang memelas. Kalau sudah begini, mana bisa sih aku menolak?
Dan disinilah aku sekarang. Berada di toko salah satu merk sepatu branded yang paling dicari semua wanita di dunia. Yang sampai sekarang aku nggak tahu, memang penting ya, barang-barang branded untuk anak sekolah seumuran kami? Halooo? Kami baru enam belas tahun, gitu?
Nah, kan? Si Lyana mulai beraksi. Katanya mau cari sepatu sport. Setelah dapat sepatu bukannya pulang, malah nyantol di toko tas. Berani taruhan semua koleksi jersey bolaku, habis ini aku yakin langkahnya pasti berbelok ke toko baju.
“Yuk, Ra. Ke Pamella, ya? Gue mau cari dres buat birthday partynya Nadira. Sepupu gue yang super duper nyebelin itu.”
Kan? Apa aku bilang? Nggak hanya beli sepatu sport saja, kan? Kalau sudah tahu sepupunya itu nyebelin, kenapa harus datang ke birthday partynya coba?
Aku pernah menanyakan soal ini. Dan Lyana menjawab, alasannya datang bukan karena hubungan persaudaraan mereka. Terlebih untuk saling memamerkan koleksi dres, tas, dan sepatu branded terbaru mereka masing-masing. Atau gadget-gadget terbaru mereka yang super canggih itu.
Sebenarnya Lyana itu bukan tipe orang yang suka pamer atau suka memakai barang-barang mewah. Terkecuali di depan sepupunya yang satu itu. Katanya dia nggak mau diinjak-injak harga dirinya sama si Nadira.
Kata Lyana sih, Nadira itu suka menghina orang dengan seenak jidatnya. Lyana pernah dibilang kampungan karena nggak pernah pakai barang mewah seperti dia. Padahal uang orangtua Lyana itu kalau hanya untuk beli tas Louis Vuitton satu truk juga nggak bakal habis.
Itu salah satu yang aku suka dari Lyana. Keluarga dia itu kaya tapi nggak sombong. Papanya?Damar Soenaryo?pemilik Soenaryo Advertising. Belum lagi Soenaryo Resort & Spa yang ada di Bali. Perkebunan teh plus pabrik teh di Bogor. Kekayaan keluargaku sih, nggak ada separuhnya kekayaan keluarga Lyana.
Lyana itu jarang pakai barang-barang mewah bukan berarti dia nggak punya. Tapi dia itu lebih suka hidup sederhana. Nah, jarang kan, ada orang seperti Lyana dan keluarganya itu di zaman sekarang? Makanya, aku suka bersahabat dengan dia.
“Aduuh, Lyana. Mau sampek kapan nih, kita muter-muter Pamella? Gue capek, Yan. Lapeer.” Aku mengeluh dengan hiperbola. Bergaul dengan Lyana membuatku jadi ketularan penyakit drama-nya itu.
“Aduuh, Tara. Gue belum dapet dresnya.” Lyana malah balik mengeluh padaku. Dan kembali sibuk dengan tumpukan dres yang baru dibawa oleh Mbak SPG.
Daripada aku hanya duduk menunggu Lyana yang masih saja sibuk memilih dres, mendingan keluar. Siapa tahu saja ada cowok keren yang ngajak kenalan. (ngarep banget ya?)
Kedua tanganku bertumpu pada railing void. Mengedarkan pandanganku ke lantai paling bawah. Lagi ada bazar buku. Sepertinya ke sana lebih asyik daripada berdiri menunggu Lyana yang nggak tahu kapan selesai memilih dres. Tanpa pikir panjang lagi aku berjalan menuju escalator untuk turun ke bazar buku.
Ini yang aku suka dari bazar buku. Banyak diskon. Ada yang sampai tujuh puluh persen. Sekedar info, aku akan lebih khilaf kalau ada diskon buku daripada diskon baju. Bisa-bisa uang tabunganku habis hanya untuk memborong buku.
Aku berjalan menuju rak novel. Memilih-milih judul yang menarik hatiku. Emm, lebih tepatnya sih cover yang menarik hatiku. Kalau ada kalimat yang mengatakan, don’t judge a book by its cover, itu nggak berlaku buatku. Menurutku, ketertarikan seseorang terhadap buku itu ya berawal dari covernya.
Bayangkan saja, misal judul bukunya LDR. Tapi gambar covernya Kambing. Nggak menarik, kan? Yang ada malah ilfil.
Setelah beberapa saat melihat-lihat, aku menemukan judul novel yang sudah lama ingin kubeli tapi belum juga kubeli. Bukannya nggak ada uang, tapi belum ada waktu untuk ke toko buku.
Yeah, kalian boleh tertawa. Aku baru akan membeli dan baru akan membaca The Cuckoo’s Calling-nya Robert Galbraith. Novel thriller yang kata si Bima ceritanya keren. Penyelidikan tentang kematian seorang model. Ada aksi detektif gitu. Cerita yang aku suka bangetlah. Tapi si Bima pelit banget, nggak mau meminjamkan novel itu padaku. Alasannya malas bawa-bawa buku tebal dari Bandung.
Dan adegan ala-ala sinetron pun terjadi. Tanganku dan tangan seseorang secara bersamaan mengambil novel tersebut. Alhasil, bukannya memegang novel aku malah memegang tangan orang itu. Segera aku menarik tanganku sambil mengucapkan maaf. Aku mendongak untuk menatap pemilik tangan itu. Saat itu juga aku tertegun.
Arda menatapku dengan tatapan yang aku sendiri nggak tahu apa maknanya. Aku terpaku. Diam menatapnya. Dari sekian banyak mal, kenapa dia harus ke PIM? Dan dari sekian banyak tempat di PIM, kenapa dia harus ke bazar buku? Dan bertemu denganku.
-----
Sekarang aku nggak lagi di bazar buku. Melupakan niatku untuk membeli The Cuckoo’s Calling (lagi). Yang ada aku sekarang duduk berhadapan dengan Arda di starbucks. Dan harus rela menerima tatapan aneh dari beberapa pengunjung.
Apa seaneh itu, ya, dua anak berseragam putih abu-abu duduk di starbucks?
Arda nggak juga buka suara. Ya, memang aku sih yang meminta untuk ngobrol. Tapi dia kan cowok. Ngomong apa gitu kek. Tanya soal kabarku mungkin. Atau apalah. Masa sepuluh menit hanya saling diam. Aku yang sibuk menetralkan debar didadaku dan Arda yang sibuk mengamati lalu lalang manusia dari balik kaca jendela.
“Kamu sama siapa ke sini?” Akhirnya aku yang berbasa-basi duluan.
“Sendiri.” Arda menjawab tanpa menatapku. Dengan nada dinginnya yang menusuk. Aku menarik napas perlahan.
“Aku minta maaf.” Kataku pelan.
“Buat apa?”
“Soal…. aku sama Rafa waktu itu.”
Kalimatku itu berhasil membuat Arda menoleh untuk menatapku. Masih dengan tatapan dinginnya.
“Waktu itu…. aku bingung. Kaget tiba-tiba Rafa lakuin itu. Beneran. Rafa yang lakuin itu, bukan aku.” Aku menatapnya dengan hopeless. Sepertinya apapun yang aku katakan, Arda tidak mempercayainya.
Dia kembali membuang tatapannya ke jendela. Tersenyum sinis.
Kemudian Arda berkata, “Oh, ya? Tapi yang terlihat nggak kayak gitu.” Arda berhenti sejenak. “Lagipula, kita kan emang nggak ada apa-apa. Jadi nggak seharusnya kamu jelasin itu ke aku.”
“Aku lihat kamu salah paham. Makanya aku jelasin.”
“Salah paham? Nggak juga.” Arda menjawab dengan nada menyindir.
“Buktinya kamu jauhin aku, kan? Ayolah, Ar. Kalo emang kita nggak ada apa-apa, kenapa kamu harus marah, sih?” Aku menatap Arda. Dia menarik napas berat. Memejamkan mata sejenak kemudian menatapku.
“Harus ya aku katakan lagi alasanku deketin kamu?” Arda menatapku tajam. “Udahlah. Aku pergi.” Arda berdiri kemudian meninggalkanku sendiri.
Dari sikap Arda barusan aku jadi tahu, ternyata cowok itu bisa lebih nggak realistis dari cewek kalau menyangkut soal hati. Konyol. Bukankah dia sendiri yang bilang kalau aku nggak perlu menjelaskan karena kami nggak ada hubungan. Kemudian detik berikutnya dia berkata seolah-olah menyalahkanku karena nggak peka dengan maksudnya mendekatiku. Aneh, kan?
----


 annis0222
annis0222





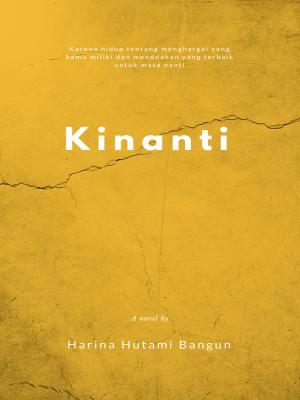




Thank you, kakak.... Cerita kakak lebih keren. Jadi minder... ????
Comment on chapter SATU