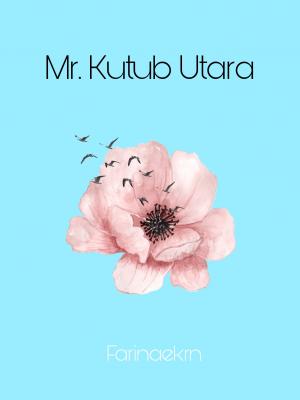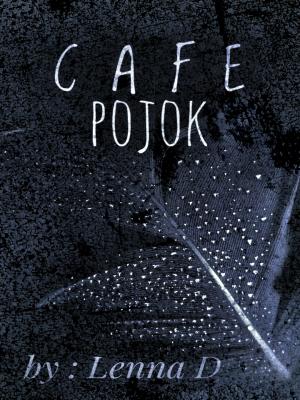Seperti Hujan
Tahukah kamu,
Mengapa hujan semalam meninggalkan kabut pagi?
Ia hanya takut langit kembali patah hati
Karena setelahnya, langit harus kembali merutuki rindu
Entah kapan ia kan kembali menyapa bumi
Menghujamkan setiap derainya
Menebarkan tempias pada tiap lekuk tanah basah
Hingga bumi tahu,
Betapa pedih menahan setumpuk rindu
Abu menutup buku catatan kecilnya. Buku yang selalu ia bawa di manapun berada. Dalam buku itu, ia biasa menulis apapun yang tak sengaja terlintas di kepalanya. Sebagai penulis, Abu tentu tidak ingin melewatkan sekata pun yang ia dapatkan. Dan menuliskannya di buku itu adalah caranya menyimpan. Karena ia sadar bahwa memori di kepalanya tidak akan muat untuk menyimpan tiap ide tulisannya.
Seperti juga pagi itu. Duduk di teras belakang rumahnya, ditemani secangkir cappuccino panas buatan mama. Apalagi, selepas Dhuha, matahari masih saja enggan menyapa. Halaman kecil belakang rumah Abu masih tampak berkabut. Abu baru menyadari, sepertinya, hujan semalam cukup deras. Kebersamaannya dengan Zahra di café hingga mengantarnya pulang, membuat Abu benar-benar tidak peduli pada sekitarnya. Bahkan hujan deras yang telah mengguyur kota kelahirannya pun baru ia sadari pagi ini.
Terlalu bahagia? Mungkin. Mengingat pertemuan semalam, Abu menarik kedua ujung bibirnya, tersenyum. “Astaghfirullah, kenapa gue masih begini aja ya? Zahra. Guna-guna apa sih yang lo mantrakan ke gue?” Sesekali Abu bergumam sendiri. “Astagfirullahaladzim. Mikir apa sih gue? Heghhh!” Abu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya.
Dipandanginya cangkir cappuccino di meja yang terlihat membisu. Seakan ikut merasakan kegelisahan Abu, kepulan asapnya pun kian memudar. Abu menyesapi bibir cangkir berisi cappuccino yang sudah mulai menghangat.
“Sayang…”
“Eh, mama.”
“Mama ngagetin kamu, ya?”
“Ah, nggak kok, ma.”
“Oya, semalem, kamu bilang, kamu habis nganterin Zahra?” Abu memandang mama dan tersenyum. Hanya anggukan kecil yang ia berikan sebagai jawaban. “Lalu? Kalian ngobrol? Ngobrol apa aja? Oya, Zahra apa kabar? Tinggal di mana dia sekarang? Ajak ke rumah donk, Abu. Mama juga pengen ketemu. Mama juga kangen.”
Abu hanya melebarkan senyumnya mendengar interview dari mama.
“Ih, kok malah ketawa sih kamu.”
“Mama sih, lucu.”
“Kok lucu? Harusnya kamu yang buruan ceritanya. Biar mama nggak kepo.”
Abu makin meninggikan nada tertawanya mendengar kalimat mama. Apalagi, melihat ekspresi wajah mama yang terlihat kesal dengan jawaban Abu. Ditambah lagi, intonasi mama yang terdengar sedikit merengek. Mana anak, mana mama, membuat Abu makin melepaskan tawanya di beranda belakang rumahnya itu. Hingga pagi yang masih terasa dingin oleh kabut, tiba-tiba menghangat di antara obrolan mama dan Abu yang saling melepas canda dan rindu.
***
Aroma petrichor makin menghilang, pun cappuccino mereka telah dingin sempurna. Namun, Abu masih menikmati pertemuannya dengan Zahra. Setelah sekian lama mereka tidak berbincang, inginnya Abu menghentikan saja waktu. Berharap malam tak merayap terlalu cepat.
Tapi jarum jam dinding café tak lelah berputar. Waktu sudah cukup larut untuk menutup aktivitas di café hari itu. Beberapa lampu sudah mulai dimatikan. Pengunjung café yang semula enggan bergeming, mulai beranjak meninggalkan bangku mereka masing-masing. Termasuk Abu dan Zahra.
Kali ini, memang waktu tak mau berpihak pada Abu untuk lebih lama lagi memberinya kesempatan bersama Zahra. Lain lagi dengan hujan. Hujan masih saja deras, bahkan tirai langit ini makin merapat saja. Seakan memperpanjang waktu untuk Abu membersamai Zahra malam ini.
“Hujan makin deres, Ra. Gue anterin lo pulang, ya.”
“Ah, nggak usah. Gue bisa naik taksi kok.”
“Udah malem ini, Ra. Diculik sopir taksi tar lo.”
“Hahahahaha. Gokil lo, Abu. Mana ada yang mau culik gue?”
“Kok gitu?”
“Gak ada yang bakal tebus gue, tahu.”
Abu tertawa mendengar kalimat terakhir Zahra. Andai ia tidak sedang bercanda, inginnya Abu langsung menjawab kalimat itu, bahwa Abu lah yang akan menebus Zahra berapapun maharnya.
Tempias hujan seakan tak mau terlewat dari obrolan mereka yang terkesan tiada habisnya. Hijab lebar Zahra mulai basah.
“Ayolah, Ra. Gue anter lo pulang.”
“Beneran lo? Nggak ngrepotin, kan?”
“Apaan sih lo, Ra. Udah yuk. Tapi, gue parkir sebelah sana. Kehujanan dikit nggak pa pa, kan?”
Zahra mengangguk pasti kali ini. Bukan anggukan lembut seperti tadi.
Abu dan Zahra pun berlarian menembus hujan. Tempat parkir café berada beberapa meter dari beranda café. Tawa kecil mereka terdengar lirih di antara derai hujan. Dan tak beberapa lama, Abu telah berada di balik kemudi mobil dan Zahra tepat duduk di sampingnya.
“Rumah lo masih yang dulu kan, Ra?”
“Iya lah. Masih inget kan, lo?”
“Tentu, nyonya.”
Zahra hanya mampu tersenyum menjawab Abu. Mobil melaju menembus hujan menyusuri jalanan kota yang terlihat makin gelap tertutup tirai air langit yang cukup rapat malam itu. Jalanan sudah cukup lengang karena bukan hanya karena hujan, tapi waktu juga sudah cukup malam.
Lima belas menit hujan berhasil memperpanjang pertemuan Abu dan Zahra hingga mereka harus terpisah lagi. Mobil Abu berhenti tepat di depan rumah Zahra.
“Gue langsung aja ya, Ra. Udah malem. Lo istirahat, ya. Thanks untuk hari ini.”
“Gue yang harus terimakasih sama lo, Abu, udah dianterin.”
Abu tersenyum melihat wajah Zahra yang tampak lelah. Mata bulat Zahra mulai terlihat sayu.
***
Setelah pertemuan itu, Abu seakan mendapatkan candunya lagi. Ia selalu berusaha untuk menemukan cara dan waktu berjumpa Zahra.
Sekarang, Zahra yang telah bekerja di salah satu rumah sakit besar di kotanya, hanya memiliki waktu saat senja. Apalagi, saat ini, Zahra juga sedang menyelesaikan pendidikan spesialis bedah. Hal ini menuntut waktu Zahra untuk seharian berada di ruang operasi rumah sakit. Zahra sedang menyelesaikan thesis. Jadi, beberapa tindakan operasi tidak bisa ia lewatkan.
Begitu pun Abu. Ia tidak bisa melewatkan senja tanpa Zahra. Menunggu gadis cantik berhijab itu pulang, adalah rutinitas baru Abu saat senja. Bahkan, ia rela membawa serta tulisannya. Ia tetap sempatkan untuk menulis sembari menunggu datang bayangan bidadari hatinya. Seperti kata penulis idolanya, Abu percaya bahwa segala hal yang ia inginkan, menuntut hal lain untuk ia korbankan.
“Aku sakau tiap kali senja datang dan malam membawamu makin jauh dariku. Aku rindu pagi. Pagi yang kembali mengadirkanmu dengan semangkuk penuh candu itu kemarin. Lalu, apa tujuanmu kemarin itu? Apa maumu dengan menjejali kepala dan hatiku dengan candumu itu? Agar aku merindumu? Atau mencintaimu dengan sekuat urat nadiku? Sudah! Tak perlu lah kamu lakukan itu. Aku sudah menjatuhkan seluruh cintaku padamu, sejak pertama kali semesta mengenalkan bayangmu padaku.
Merindumu? Sudah pasti. Tak perlu lah kamu meyakinkan hatimu lagi. Aku telah merindumu sejak semesta mencipta siang, senja bahkan malam untuk aku menyapamu. Jadi, sayang, sekali lagi aku tanyakan. Apa tujuanmu memberiku semangkuk penuh candu kemarin? Sekarang aku sakau, sungguh sakau pada candumu itu. Lalu, kemana lagi harus kuminta candu itu, kalau tidak darimu?”
Abu menutup kembali buku kecilnya. Sejak pertemuannya dengan Zahra, ia menjadi lebih produktif menulis. Segala ingatannya tentang Zahra seakan terbuka lebar. Bagai sedang menonton layar lebar, segala kenangan saat SMA kembali terbuka tiap lembarnya.
***
“Ayo, Zahra. Ikut gue!”
“Kemana, Abu?”
Abu menarik tangan Zahra. Mengajaknya sedikit berlari.
Siang itu, mereka baru saja mengadakan koordinasi tim majalah sekolah. Sebagai pimpinan redaksi, Zahra selalu menyemangati seluruh tim untuk bekerja sama dan tidak bosan untuk menulis. Minggu depan adalah lomba majalah sekolah. Persiapan sudah hampir delapan puluh persen. Beberapa artikel telah terkumpul. Tinggal proses editing dan layouting. Abu adalah salah satu penulis handal pengisi rubrik cerpen. Tidak jarang juga, Abu mengisi kolom opini. Tulisan Abu cukup readable dengan bahasanya yang ringan dan pas untuk remaja seusia mereka.
“Abu, pelan-pelan donk. Mau kemana sih?” Zahra tergopoh berlari kecil selangkah di belakang Abu. Sedang Abu masih menggandeng tangan kanan Zahra.
“Sudahlah. Entar lo juga akan tahu.”


 FaAli
FaAli