“Sorry, saya jadi ngerepotin, dokter,” ucapnya sembari meletakkan tasnya di kursi untuk penunggu pasien. Dia melepaskan jaketnya kemudian mencium kedua pipi ibunya yang masih dalam masa pemulihan setelah hampir satu minggu di rawat di rumah sakit. Aku tersenyum melihat interaksi antara ibu dan anak itu. Hubunganku dengan Mega juga menjadi semakin dekat setelah malam itu.
“Ngga apa-apa kok. Eh, jangan panggil aku dokter, aku memenuhi permintaanmu bukan sebagai dokter jadi sapaannya biasa aja. Lagian aku juga udah ngga ada kegiatan setelah dinas dan Ibumu enak sekali diajak mengobrol. Kalau gitu, ku sekarang mau keluar dulu. Ibu dan Mega juga perlu istirahatkan?”
“Sekali lagi terima kasih. Kalau ngga ada kamu pasti aku ngga tenang. Ninggalin Ibu sendirian malam-malam.” Aku menganggukkan kepalaku dan berjalan menuju pintu keluar ruang perawatan. Malam ini aku menemukan sosok Ibu yang hangat.
Aku kembali mengingat permintaan Mega kepadaku untuk menjaga Ibunya sebentar tadi siang karena dia ada urusan sebentar dan dia akan pulang terlambat dari hari biasanya. Membuat bibirku tadi siang tidak tahan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi pertanyaan bagiku.
“Aku boleh bertanya sama kamu?” Dia menganggukkan kepalanya. “Aku perhatikan, kamu selalu berangkat pagi-pagi sekali dan pulang malam dengan wajah yang lelah dan kuyu. Sebenarnya kamu ngapain aja seharian? Maaf kalau pertanyaanku lancang. Kalau itu memang rahasia, ngga apa-apa kok kalau kamu ngga mau jawab.” Dia terkekeh. Entah aku tidak mengerti apakah pertanyaanku ada yang lucu?
“Sememprihatinkannya itu ya kalau aku baru pulang?” Aku menganggukkan kepalaku. Memang yang kulihat juga seperti itu kok.
“Kalau ngga sememprihatinkan itu, aku ngga bakal ngomong juga ke kamu dan kepalaku ini ngga bertanya-tanya.”
“Pagi sampai sorenya aku ngampus, sore sampai malam aku kerja part time. Aku sengaja ambil kelas pagi terus biar aku bisa kerja part time di sini. Kalau ada waktu luang, aku langsung ngerjain semua tugas kampus biar malam setelah aku pulang aku bisa full dengan Ibuku.”
“Kerja part time apa?” Aku semakin penasaran.
“Jagain toko bakery sama jadi pelayan. Lumayan bisa buat hidup di kota yang sebesar ini sama Ibu. Aku yang jadi tulang punggung keluarga ngga mungkin kan cuma santai-santai aja duduk di sofa? Sedangkan aku juga harus mempertahankan IPK-ku agar beasiswanya tidak dicabut. Aku juga bukan orang kaya yang punya banyak uang buat belanja sana- sini . Mending buat makan. Mungkin itu yang membuat wajahku cukup lelah. Fisik dan pikiran sudah dikuras habis seharian.” Sekarang aku mengenal bagaimana sosok Mega.
“Lalu Ayah kamu?” raut wajahnya yang semula santai menjadi menegang. Aliran darahnya seperti tiba-tiba naik ke ubun-ubun membuat wajahnya memerah. Tangannya yang di atas meja mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. “Maaf lagi kalau aku kembali lancang. Ngga seharusnya aku tanya seperti itu.” segera aku mengoreksi perkataanku.
“Lelaki itu tidak pantas disebut sebagai Ayah. Dia pengkhianat. Dia selalu berkata kasar, memukul, dan dia yang menyebabkan Ibuku kembali mengalami serangan jantung, tapi entah bagaimana Ibuku tetap tidak mau untuk menceraikannya. Dan alasan itu yang membuatku sangat menyayangi Ibuku. Bukan berarti aku anak mami. Namun, karena sudah banyak penderitaan yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku tahu kalau cinta seorang anak pada Ibunya hanya sepanjang galah sedangkan cinta seorang Ibu pada anak akan sepajang masa. Jadi, ngga ada salahnyakan kalau kita berusaha untuk membahagiakan Ibu kita selagi masih hidup di dunia dengan cara menyayanginya dengan tulus, selalu ada di sampingnya, dan mendengarkan keluh kesahnya bukan hanya dengan menggunakan harta. Mereka ngga perlu uang. Ya, walaupun semua itu memang belum sepadan dengan perjuangannya membesarkan kita,” ucapnya panjang lebar. Aku bercermin pada diriku sendiri. ‘Apa yang sudah ku lakukan untuk Ibuku?’ Aku terhenyak. “Jadi bagaimana? Kamu bisa?” Dia kembali pada tujuannya semula untuk menanyakan kesediaanku.
“Oke, nanti sepulang dinas aku langsung ke ruangan perawatan Ibumu.”
“Terima kasih, maaf kalau merepotkan.”
“Ah, engga kok.”
Aku menekan tombol di remote mobilku untuk membuka kunci pintu mobil. Aku masuk ke dalam mobil dan melajukannya menembus jalanan malam kota New York untuk beristirahat di rumah.
***
Entah kenapa pagi ini aku ingin menemui Ibunya Mega. Aisyah. Aku seperti menemukan teman mengobrol antar wanita selain Vania. Selain itu aku juga ingin membawakan sarapan untuk Mega dan Aisyah.
Hari masih terlalu pagi untuk menemui pasien. Rumah sakit masih sepi. Di depan banyak perawat yang masih menyelesaikan dinasnya dan berjaga di nursing center dan beberapa dari mereka menyapaku hangat. Aku bertanya-tanya sebentar dengan mereka lalu, aku melangkahkan kakiku tampa menimbulkan suara berisik. Ini masih pukul 6 pagi. Aku mengintip dari kaca pintu. Ku lihat Mega masih terbaring di sofanya. Ku buka pintu itu perlahan. Aisyah tersenyum padaku. Aku mendekat dan mencium pipi kanan dan kirinya.
“Bagaimana tidurnya semalam, Bu?”
“Alhamdulillah. Tapi, kayaknya anak Ibu beberapa hari ini tidur tidak nyaman di sofa kecil itu.” Aku tersenyum. Kemudian mengalihkan pandanganku ke arah Mega yang tidur meringkuk di atas sofa. Wajahnya mengkerut. Entah apa yang sedang dimimpikannya. Aku berjalan mendekat kearahnya. Mengambil jaket yang tersampir di kursi untuk menutupi kakinya yang terbuka. Namun, tindakanku itu membuat Mega terbangun dari tidurnya.
Mega mengucek-ucek matanya. Duduk dengan pandangan khas bangun tidur. Rambutnya acak-acakkan. Matanya menyipit ketika sadar akan kehadiranku.
“Jam berapa ini?”
“Masih jam 6 pagi.” Dia menguap. Matanya masih 5 watt. “Kalau masih ngantuk, kamu mending tidur aja lagi.” Dia menggeleng lantas berdiri dari sofa dan berjalan menuju kamar mandi.
“Aku baru ingat, aku belum menyelesaikan tugasku yang dikumpulkan hari ini. Dan aku belum sholat subuh!” Dia menutup pintu kamar mandi. Entah apa yang akan dilakukannya, kencing, BAB, atau hanya sekedar cuci muka yang jelas dari luar terdengar suara kran air yang mengalir.
Dia langsung sholat shubuh walaupun memang sudah bisa dikatakan sudah sangat terlambat. Aku membuka tempat makan susun dan menyusunnya diatas lemari kecil di samping tempat tidur. Aku tadi sempat memasak sup ayam dan tempe goreng. Mungkin lidahku memang lidah Indo yang terbiasa makan-makanan Indonesia atau memang lidahku tidak cocok dengan makanan barat. Jadi, aku selalu memasak kalau aku ingin benar-benar makan.
“Kok kamu jadi repot-repot masak kayak gini, Hassya?” tanya Aisyah. Aku menoleh ke arah Aisyah yang berbaring di atas tempat tidur. Mega yang sedang melipat sajadahnya langsung menoleh ke arahku.
“Ngga apa-apa kok, Bu. Lagian tadi juga Hassya masakannya kebanyakan.” Padahal mana ada yang namanya masak kebanyakan tapi tidak di sengaja? Kan mubazir. Buang-buang makanan. Di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Kata-kata itu selalu teringat dalam pikiranku. Aku memang orang yang berada, tapi aku juga sayang uang. Kalau cuma buat dihambur-hamburkan buat hal-hal yang ngga penting. Mending buat makan. Badan sehat, perut juga kenyang. Aku menyendokkan nasi, sup ayam, dan tempe ke dalam piring. “Meg, ayo ikut makan juga. Otak butuh asupan sebelum kamu nyelesein tugas kuliah kamu. Aku bawa buat dua porsi kok. Sebelum kesini, aku udah makan dulu di rumah.” Mega berjalan ke arahku dia mengambil piring dan makanannya.
Aku memperhatikan wajah Mega. Dia makan dalam diam. Kalau diperhatikan wajahnya bukan lagi mahasiswa S1 tapi lebih cocok sebagai mahasiswa S2. Aku yang sibuk memperhatikan Mega makan langsung terpergok oleh Aisyah.
“Ada apa Hassya? Kok kamu ngeliatin Mega kayak gitu banget? Ada yang mau ditanyain?” Aku langsung salah tingkah karena terpergok memperhatikan Mega diam-diam.
“Eh. I.... bu. Itu Hassya pengen tanya, kan katanya Mega masih kuliah kan? S1 atau S2? Jurusan apa?” Mega yang masih menikmati masakanku langsung meletakkan sendoknya di atas piring. Aisyah hanya senyum-senyum.
“Semuda itu kah muka aku sampai kamu ngiranya aku S1?”
“Eh, kan kamu ngga ngasih tahu kamu kemaren S1 atau S2. Ntar kalau aku bilang S2 langsung, kamu marah-marah.” Mega tertawa pelan.
“Aku S2 jurusan Ilmu Hukum. Bentar lagi wisuda,” jelas Mega
“Iya bentar lagi wisuda, tapi belum punya gandengan buat diajak foto bareng buat wisuda,” sindir Aisyah.
“Kan ada Ibu yang dampingin wisuda.”
“Males ah, udah bosen Ibu jadi gandengan kamu dari wisuda TK.” Aku hanya menahan tertawaku melihat perdebatan anak dan Ibu itu.
“If you don’t want to accompany me, I can come alone. It’s no problem for me,” ucap Mega dengan nada merajuk.
“Please stop, I can accompany you in your graduation,” leraiku.
Mega menyelesaikan acara makannya. Lalu berjalan menuju ke arah kamar mandi sambil membawa piring makannya yang sudah bersih tanpa sisa. Dia mengembalikan piring itu kepadaku dengan keadaan sudah bersih. Dia membuka bukunya lalu menyelesaikan tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Aku merapikan barang bawaanku. Karena hari ini aku benar-benar tidak ada jadwal praktek dan jadwal dinas, aku agak sedikit santai. Ruangan itu tiba-tiba menjadi senyap kembali.
“Oh iya, tadi pas aku mau ke sini, sempet tanya kapan Ibu bisa pulang katanya nanti siang Ibu bisa pulang.”
“Nanti siang?” Aku menganggukkan kepalaku manjawab pertanyaan Mega. Aku sepertinya tahu apa yang ada dipikiran Mega saat ini. Mana mungkin Mega bisa meninggalkan kuliahnya?
“Kalau kamu ngga bisa ngantar Ibu pulang, biar aku aja yang ngantar Ibu pulang. Lagian, hari ini aku juga libur kok.”
“Iya, benar kata Hassya. Kamu kuliah aja.” Aisyah ikut menimpali.
“Tapi, antar ke alamat ini.” Dia menuliskan sebuah alamat di buku tulisnya. Kemudian merobek kertas itu dan memberikannya padaku. Aku membaca tulisan yang tertera di kertas itu. Alamatnya cukup jauh dari rumah sakit ini.
“Ibu mau pulang ke rumah yang dulu. Bukan rumah yang kamu berikan alamatnya pada Hassya!” Entah kenapa Aisyah bisa mengetahui alamat yang diberikan padaku adalah bukan alamat rumahnya yang lama. Mungkin memang insting seorang Ibu itu memang sangat kuat.
“Ibu, still want to go that home again? After what has happened in that house? Is enough, Bu. We need to be happy and calm.” Aku hanya terdiam. Aku tak pantas untuk ikut campur. Ini urusan pribadi mereka.
“Yes, I still want to go that home again. The house is a memory that is impossible to forget. You said we need to be happy and calm? Now, I was already happy and calm in that house!”
“What memory is impossible to forget? Memory about the things you mean? It’s enough, Bu. For what to remember?” Mega meninggikan suaranya. Ini sama sekali tidak dapat dibiarkan.
“Enough, Mega! Remember your mother has high blood pressure and heart disease! These representation aren’t patient for continued!” ucapku dengan nada yang tak kalah tinggi. Mega membalikkan tubuhnya. Memunguti barang bawaannya dan membawanya. Dia tak mengatakan apapun sampai dia keluar dari ruang perawatan.
“Not only the sad memories that exist in the house , but also there is a happy memory that you may not remember,” lirih Aisyah ketika Mega menutup pintu ruang perawatan. Aku hanya mampu mengelus-elus lengan Aisyah. Memberikan ketenangan dan mengajak Aisyah untuk mengatur pernapasannya.
***
Aku yang hanya bertugas untuk mengantar Aisyah dan aku juga tidak memiliki kewenangan apapun untuk ikut campur ke dalam urusan pribadi mereka, aku memilih untuk mengikuti mau kemana Aisyah. Aku mengemudikan mobilku menuju rumah Aisyah. Kota New York siang ini cukup panas. Setelah pertengkaran tadi, Aisyah hanya diam. Dia tak banyak berbicara.
“Bu, mungkin maksud Mega baik karena menyarankan Ibu untuk pindah rumah. Hassya disini tidak memihak siapa pun. Hassya berada di pihak yang netral karena Hassya tidak tahu apa permasalahan kalian, tapi apa tidak sebaiknya Ibu mempertimbangkan saran dari Mega?”
“Sebenarnya bukan masalah untuk pindah rumah, tapi bukannya itu akan menambah biaya pengeluaran? Harus memikirkan tagihan kredit rumah setiap bulan. Sedangkan kami sudah punya rumah sendiri. Kami juga bukan orang yang berkecukupan, buat apa membuang-buang uang untuk hal yang tidak menjadi prioritas utama? Lagi pula, rumah itu bukan hanya menyimpan kenangan buruk tapi kenangan baik juga.” Dia kemudian terdiam. Aku kembali fokus pada kemudiku. “Hassya, baru kali ini Mega bisa dekat dengan perempuan dan dia membawanya ke depan Ibu. Ibu senang karena dia akhirnya mampu dekat dengan perempuan selain Ibunya. Ngga mungkin kan kalau dia terus bersama Ibu terus. Ibu ini udah tua, bau tanah. Sedangkan dia masih muda dan butuh perempuan untuk terus menampinginya. Ada alasan yang membuat dia begitu protektif sama Ibunya. Kalau kamu yang jadi perempuannya, Ibu rela dan Ibu juga bakal tenang kalau ninggalin Mega.” Aisyah mengungkapkan pandangannya. Rona wajahnya senang kala menceritakan hal itu.
“Tapi bu, Hassya cuma....” Ucapanku terpotong begitu saja karena Aisyah keburu menimpali.
“Ibu bilang baru kalau. Ibu ngga berhak buat ngatur hidup kalian berdua. Kalau kejadian ya Ibu bakal bersyukur. Kalau engga ya berarti kalian memang ngga berjodoh.”
Aku menghela napas lega. Aku pikir Aisyah akan sama seperti pemikiran Ibu-Ibu lain yang akan ngotot untuk menjodohkan anaknya dengan orang yang sudah dia sukai terlebih dahulu. Aku memarkirkan mobilku di sebuah rumah yang tak begitu besar dan tak begitu kecil. Cukuplah untuk tinggal tiga orang. Halamannya juga kecil hanya cukup untuk memarkirkan sebuah mobil dan rumahnya di New York juga lebih besar dari rumah ini. Padahal, dia hanya tinggal sendiri. Aku membukakan pintu untuk Aisyah. Dia berjalan perlahan menuju pintu utama. Dia merogoh kantung bajunya untuk mengambil kunci. Yang pertama aku lihat dari rumah ini adalah cukup berdebu seperti rumah kosong.
“Maaf ya kalau banyak debunya. Selama Ibu di rumah sakit kan ngga ada yang pulang ke rumah. Jadi, ngga ada yang bersihin rumah.” Aku maklum. Setiap hari kan Mega selalu berangkat dari rumah sakit dan pulang ke rumah sakit.
Mataku menelisik ke seluruh sudut ruangan ini. Banyak sekali foto-foto Mega ketika masih kecil yang terpajang di dinding. Mega kecil yang sangat manis. Pandanganku terkunci pada sebuah foto keluarga. Seorang ayah, ibu, dan anak. Tanpa sadar tanganku mengangkat pigura itu.
“Foto itu....” Aku segera meletakkan foto itu ke tempat semula dengan gugup seperti maling yang tertangkap basah mencuri karena kaget ditegur oleh yang punya. “foto keluarga Mega. Saat semuanya masih baik-baik saja. Dia lelaki yang merupakan Ayah Mega.” Kalau aku perhatikan dari gambaran wajahnya, dia merupakan lelaki yang hangat. “Kamu pasti berpikir kalau Ayahnya ini merupakan lelaki yang hangat kan?” Entah dari mana Aisyah bisa tahu apa yang ada dipikiranku. “Aslinya dia memang seperti itu dulu, tapi sekarang sudah beda lagi ceritanya.” Tatapan Aisyah berubah menjadi sendu. Karena tak sampai hati, akhirnya aku memilih untuk mengalihkan pembicaraan.
“Bu, boleh menumpang sholat dhuhur?”
“Oh boleh kok. Kamu tinggal lurus aja di situ ada kamar mandi. di seberang kamar mandi ada ruangan sholat.”
Aku berjalan sesuai perintah dari Aisyah tadi. Aku mengambil air wudhu dan menunaikan ibadahku. Aku mengeluarkan mukena yang ada di dalam tas selempangku dan mengeluarkan Al-Qur’an kecil. Kedua barang ini merupakan hadiah dari Mega beberapa waktu lalu. Hadiah yang menurutku sangat luar biasa dan antimainstream yang diberikan oleh laki-laki pada perempuan. Aku melaksanakan kewajibanku. Setelah selesai salam, aku mendengar kegaduhan dari arah depan.
“Kamu itu cewek yang ga bisa diandelin. Udah penyakitan dan bisanya cuma ngabisin uang! Mana pulang bawa mobil lagi! Aku butuh uang!” Bentakan keras dengan bahasa inggris aksen Amerika itu terdengar sampai telingaku. Mendengar keributan yang semakin menjadi itu, aku memutuskan untuk ke arah pusat keributan.
“Aku ngga punya uang dan aku sama sekali ngga megang uang satu sen pun! Itu bukan mobilku!” Mataku melihat lelaki itu. Tangannya sudah mengepal dan hendak melayang ke arah Aisyah. Dengan cepat aku berlari ke hadapannya tepat ketika pukulan itu melayang dan mengenai wajahku. Tubuhku terdorong ke samping hingga terbentur meja dekat jendela. Mataku seketika buram, hidungku mencium bau anyir dan aku merasakan ada sesuatu yang mengalir di wajahku. Beberapa detik kemudian aku tak bisa melihat apa-apa.


 dianakusuma
dianakusuma











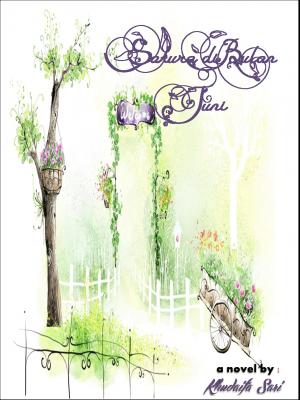
@ShiYiCha terima kasih kritik sarannya
Comment on chapter Independent Woman