BAB 5. PENGAKUAN HANA
HARI KE-3, MEDAN & SAMOSIR
“Horas! Horas! Horas!” seru Harto berulang-ulang saat kami tiba di Medan. Sampai pekak telingaku mendengarnya. Untuk mempersingkat perjalanan, kami naik bus dari Banda Aceh menuju Medan. Kini kami berdiri di depan Istana Maimun, salah satu peninggalan Kesultanan Deli yang dihiasi perpaduan unik gaya arsitektur Islam dan Eropa. Ketika kami melongok ke dalam, kami terkagum-kagum dengan keindahan interiornya yang luas dan dipenuhi berbagai benda unik seperti perabot antik, foto-foto tua dan deretan senjata kuno.
“Istana Maimun dibangun atas perintah Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Deli, pada tahun 1887 sampai 1891,” aku menunduk membaca jurnal Ayah, kemudian mendongak memandang istana di depanku. “Banyak yang bilang istana ini adalah salah satu istana terindah dan termegah di Indonesia. Dan ternyata itu memang benar.”
Saat pertama tiba di kota ini, kami kaget tak kepalang mendengar orang berteriak-teriak lantang. Provinsi Sumatera Utara dihuni berbagai suku, namun yang paling umum ditemui adalah Suku Batak. Dua orang yang sedang mengobrol di dekat kami berbicara seolah jarak mereka seratus meter. Mereka bisa dikira sedang bertengkar kalau tidak diselingi tawa. Logat Batak mereka yang khas terdengar menusuk-nusuk telinga kami yang belum terbiasa.
“Kudengar, orang Batak juga terkenal menyukai lagu-lagu bertema cinta,” komentar Hana saat kami meninggalkan Istana. “Jadi, sepertinya mereka punya sisi lembut juga.”
Sambil duduk, kami menikmati durian medan dan kue bika ambon yang dibeli di sebuah kios dekat terminal. Banyak yang menyangka bika ini berasal dari Ambon, padahal sebetulnya dari Medan. Kue manis yang legit ini menjadi oleh-oleh favorit wisatawan karena cita rasanya yang khas.
Dari Medan, kami meneruskan perjalanan menuju Parapat, sekitar empat jam ditempuh menggunakan bus AC. Saat tiba di Parapat, kami langsung disuguhi pemandangan indah yang luar biasa mengagumkan. Danau Toba, salah satu danau terindah di Asia Tenggara akhirnya terpampang di hadapanku. Rasa penat dan bosan langsung menguap pergi. Danau ini merupakan area wisata yang luar biasa, mencakup wisata alam, spiritual, sejarah, budaya, arsitektur dan tentu saja kuliner. Lingkungan yang sejuk dan menyegarkan, hamparan air yang jernih, kawasan hutan pinus yang tertata asri, serta pemandangan pegunungan hijau yang memesona hanya sebagian kecil saja dari keunikan Danau Toba yang menakjubkan.
“Bagiku danau ini lebih mirip lautan, ujungnya nggak kelihatan,” kataku.
“Tentu saja, karena luas danau ini mencapai 1.145 km persegi,” Igo menimpali. “Selain itu, danau ini begitu tenang dan damai, jauh dari udara panas dan kebisingan perkotaan. Beda banget sama daerah tempat aku tinggal.”
“Yup, bener-bener pas deh buat refreshing,” kata Harto.
Saat hari mulai sore, kami menaiki kapal feri ke Pulau Samosir. Kapal-kapal ini biasanya beroperasi dari pagi sampai sore. Tampak beberapa perahu sewaan berlalu-lalang di sekeliling kami. Aku berdiri di haluan kapal seperti biasa, menikmati indahnya perairan sambil mengamati matahari yang terbenam kemerahan. Menyenangkan rasanya bisa menghabiskan waktu bersama sahabat di penghujung hari ketiga ini.
“Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung api sekitar ribuan tahun yang lalu,” jelas pemandu wisata dengan logat Bataknya. “Danau Toba terkenal sebagai danau terluas di Asia Tenggara dan salah satu yang terdalam di dunia, sekitar 450 meter dalamnya. Danau ini juga dinobatkan sebagai danau berkawah terbesar kedua di dunia, hanya dikalahkan oleh Danau Victoria yang terdapat di Afrika. Seperti yang bisa Anda lihat di sana, di bagian tengah danau terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau vulkanik yang ukurannya hampir seluas Singapura.”
Setelah waktu yang terasa singkat, akhirnya kami mendarat di desa tradisional Tuk Tuk. Jauh di atas sana terdapat pegunungan curam dengan hamparan kabut yang melebar melingkupi tanah. Keindahan alamnya tampak belum terjamah, dan masyarakat setempat yang menyambut kami terkesan ramah dan mudah bergaul. Mereka adalah masyarakat asli Batak Toba dan Batak Simalungun.
Saat hari menjadi gelap, kami menuju pusat hotel untuk beristirahat. Kami memesan tiga kamar seperti biasa, setelah itu pergi keluar untuk melihat-lihat. Di sekitar situ juga terdapat pasar tradisional yang menjajakan berbagai cinderamata seperti kalender Batak kuno yang ditulisi huruf asli Batak, gitar kayu Batak, kain ulos yang terkenal dengan motif dan tenunannya yang halus, dan beragam suvenir unik lainnya.
“Asyik, beli satu yuk,” kata Harto, menimang beberapa gantungan kunci.
Kuliner yang dijajakan juga beragam, mulai dari olahan ikan air tawar Danau Toba yang terkenal gurih, hingga berbagai jenis kue. Kami juga menyempatkan diri mencicipi ikan mas arsik dan na niura, juga bubur sitohap yang merupakan makanan khas penduduk sekitar, berbahan dasar beras dan ayam dengan tambahan daun sitohap dan andaliman—bumbu khas Batak. Tempat itu ramai oleh wisatawan lokal dan asing. Kami duduk bersebelahan dan menyantap sajian dengan lahap. Tak lama kemudian aku sudah kekenyangan.
Aku penasaran dan sudah tak sabar ingin melihat makam Raja Sidabutar yang usianya mencapai ratusan tahun, dan juga Patung Sigale-Gale, “robot” tradisional yang konon bisa diajak menari itu. Jadi, saat yang lain kembali ke penginapan dengan perut kekenyangan, aku memisahkan diri dan melangkah sendirian ke tengah pulau, di mana terdapat Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang, dua danau kecil yang terletak di tengah Pulau Samosir ini. Saat aku sedang asyik sendirian menatap danau, aku kaget karena tahu-tahu ada yang berjalan ke arahku. Langkahnya terdengar ringan. Saat menoleh, kudapati seorang wanita bercelana jeans berdiri di belakangku. Rupanya Hana. Dia tersenyum padaku, dan senyuman itu membuat perasaanku tak enak.
“Eh, kamu ngapain ngikutin aku?” tanyaku.
Gadis itu tertawa. “Dari tadi aku di sini kok, duduk di situ.”
Aku menggaruk kepala, mungkin aku memang tak melihatnya saat datang ke sini tadi. Aku menoleh ke sekitar, mencari siapa saja, tapi tak ada orang lain di tempat ini. Gawat, ternyata aku hanya berdua saja dengannya. Kenapa harus ada dia di saat aku ingin sendirian?
“Eh, aku pergi saja ya, maaf mengganggumu,” kataku, hendak berbalik.
“Tunggu, aku takut pulang sendirian. Temani aku sebentar, boleh kan?”
Aku menghentikan langkahku, ragu sejenak, berdiri agak jauh darinya. Aneh sekali dia ini. Kalau takut sendirian, buat apa dia main ke tempat sepi ini?
“Iya deh, tapi aku di sini saja ya,” kataku tanpa menoleh, duduk di atas batu.
Aku sadar Hana memerhatikanku. Mungkin dia heran kenapa aku menunduk saja. Aku agak tak nyaman, karena jarang sekali aku berkomunikasi dengan wanita, apalagi sampai berdekatan dengan mereka. Sementara itu Hana tampak rileks saja. Meski dia tak memakai kerudung, tapi pakaiannya selalu sopan dan tak pernah pamer aurat selain rambut. Sebetulnya aku ingin pergi saja, tapi takut tidak sopan. Aku juga tak mungkin mengusirnya.
“Oya, maaf, bisa kautangkap ini?” Aku melempar sesuatu.
“Apa ini?” Hana tangkas menangkapnya.
“Pisau lipat. Kalau aku macam-macam, tusuk saja,” kataku serius.
“Ada-ada saja, aku percaya padamu kok,” dia malah tertawa. Setelah hening sejenak, sambil menatap danau, dia berkata pelan, “Boleh aku cerita sebentar? Kau ingat tidak, waktu semester satu dulu, aku seperti apa?”
Aku mengangguk. Tentu saja aku ingat bagaimana penampilan teman sekelasku ini dulunya. Empat tahun lalu—kalau aku boleh bilang—Hana begitu culun, kuper, dan sering dijadikan bahan ejekan anak lain. Para gadis selalu mencibir, meledeknya anak kampungan, dan tak ada pria yang mau dekat-dekat dengannya. Banyak yang menganggap penampilannya buruk karena selalu memakai kacamata tebal dan memeluk buku ke mana-mana.
“Kau tahu apa yang mengubahku menjadi seperti sekarang ini?” Hana diam sejenak. “Saat masuk semester dua, ada seorang pria yang mengubah hidupku. Dia menginspirasi dan memberiku semangat. Dia laki-laki pertama yang membuatku jatuh hati.”
“Eh, apa dia pacarmu?” tanyaku ragu, dan Hana tersenyum geli. Aneh juga dia, tiba-tiba menceritakan hal pribadi begini. Perasaanku semakin tidak enak.
“Aku tak punya pacar,” dia menggeleng. “Lalu, selain pria itu, ada juga Nelly yang selalu berbaik hati mengajakku ke salon untuk merias diri, dan Ruqoyah yang membimbing dan mengajariku tatacara beribadah, memperluas pengetahuanku tentang ilmu-ilmu agama, dan menghiburku saat aku terpuruk.”
Aku mengangguk lagi. Aku tahu itu, tentu saja. Ruqoyah dan Nelly adalah sahabat karib Hana. Merekalah yang mengubahnya dari itik yang jelek menjadi angsa putih cantik, menjadikannya pusat perhatian. Hana bagaikan kupu-kupu yang baru saja menyelesaikan tahap metamorfosis, seperti bidadari yang baru lahir. Sejak saat itu, tak ada lagi ejekan yang terlontar padanya, dan semua mata selalu tertuju padanya.
“Banyak yang mengira aku menikmati semua itu. Namun mereka salah. Aku tak merasa nyaman dengan semua ini. Rasanya aku belum menjadi diri sendiri, seolah aku ini masih kepompong. Aku juga tak tahu siapa yang menobatkanku sebagai wanita tercantik di kampus, karena aku tidak merasa cantik sama sekali. Aku hanya wanita yang biasa-biasa saja, tak punya keistimewaan apapun. Aku bingung dengan diriku sendiri, rasanya masih ada yang kurang dan harus kucapai... tapi aku tak tahu apa itu.”
Aku sadar Hana memandangku. Aku menunduk dalam-dalam, tak tahu harus seperti apa menanggapi ceritanya. Yang jelas dia tak bermaksud pamer. Tiba-tiba, tanpa kusadari dia menggeser posisi duduknya, mendekat ke arahku. Refleks saja, perlahan aku ikut menggeser posisi duduk menjauh, menjaga jarak darinya. Untunglah Hana tak memerhatikan itu.
“Ngomong-ngomong, aku nggak minta izin ke Mama sebelum berangkat,” katanya, kembali memandang danau.
“Ha? Jadi kamu pergi begitu saja tanpa bilang apa-apa ke mamamu?”
“Ya, aku kabur dari rumah. Aku tahu Mama tak akan mengizinkan jika kubilang akan pergi dengan kalian. Sejak kecil, Mama terlalu mengekang, tak pernah mengizinkanku bebas bermain di luar. Kekhawatirannya padaku terlalu berlebihan, mungkin ia lupa bahwa aku sudah dewasa. Mama juga tak setuju aku bergabung di organisasi Bio-Explorer, berbahaya katanya, dan pergaulannya juga bebas. Mama baru mengizinkanku setelah aku berjanji akan menjaga diri baik-baik... Eh maaf ya, lama-lama jadi curhat. Biasanya aku selalu berbagi cerita dengan Ruqoyah dan Nelly, tapi mereka nggak ada di sini. Aku nggak tahan kalau terus memendam itu sendiri.”
“Kenapa kau menceritakan itu padaku?” tanyaku, masih menunduk.
“Karena,” dia diam sejenak, memainkan rambutnya, “kupikir kau orang yang tepat. Kau cucu seorang kiai besar. Sudah lama aku ingin memperdalam ilmu agama. Ilmuku masih dangkal jika dibandingkan kalian. Aku ingin belajar dari kalian. Sejak kecil, aku tinggal di lingkungan yang buruk. Ibuku orang yang paham agama, tapi dia jarang berada di rumah karena tuntutan pekerjaan. Untung aku bisa membatasi diri dalam pergaulan. Aku selalu bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan selalu berhati-hati dalam memilih teman. Makanya aku tidak ikut terseret.” Dia menghela napas, memandang buku di tanganku, lalu bertanya, “Buku apa itu? Kuperhatikan, kau selalu membawanya ke mana-mana.”
“Oh, ini? Jurnal pemberian pamanku. Semacam panduan wisata.”
Hana mengangguk. “Pernah suka sama cewek?”
Aku terbatuk, kaget. “Kenapa kau menanyakan itu?”
“Tidak, aku hanya heran melihatmu betah jadi single. Padahal mudah sekali bagimu menarik perhatian wanita. Kau kan keren, ganteng, baik, juara beladiri tingkat provinsi pula. Kenapa kau tak pacaran? Maaf jika aku menyinggung perasaanmu.”
Aku tak tahu dia bermaksud memujiku atau bukan. Aku diam sejenak, mencari jawaban yang tepat. “Aku tak mau pacaran. Maaf, tapi tak ada wanita yang ingin kupacari, sampai kapanpun. Semua wanita yang tak punya hubungan darah denganku, tak halal bagiku. Aku tak ingin memandang, mendekati apalagi menyentuh mereka, termasuk kamu, maaf. Tak ada wanita yang ingin kusentuh, kecuali wanita yang akan jadi istriku kelak.” Dari sudut mata, kulihat dia bergerak-gerak gelisah.
Aku menatap kedalaman danau yang gelap, lalu menambahkan, “Lagipula sekarang belum ada gadis yang mau denganku. Waktu kuliah dulu aku pernah melamar teman sekelas, gadis alim yang kuidamkan sejak dulu. Kau juga pastinya kenal dia. Waktu itu dia bilangnya mau fokus kuliah dulu, jadi terpaksa kulepas dia dan memilih menunggu sampai kelulusan. Aku tak sabar lagi, karena sudah tak terhitung pengorbanan yang kulakukan untuknya, dan tabunganku juga sudah cukup banyak untuk melamarnya. Anehnya sejak itu dia memutuskan semua kontak denganku. Kutelepon tak diangkat, sms tak dibalas, media sosial diunfriend, kalau ketemu di jalan malah balik arah. Dia seakan menghindariku. Ternyata eh ternyata, beberapa bulan kemudian dia malah menikah dengan orang lain—temanku dari fakultas sebelah yang sudah mapan dan punya bisnis sendiri. Padahal kami sama-sama belum lulus.”
Aku menghela napas dalam, menyeka mata, lalu meneruskan bercerita.
“Aku tak mengerti kenapa dia sampai menyalahi janjinya, malah mengejar lelaki yang lebih baik dariku, membuat penantianku selama setahun itu sia-sia. Aku bahkan tak diundang dalam resepsi pernikahan mereka. Hanya Harto, Igo dan Nasuti yang diundang. Aku merasa tak dihargai, seakan aku ini cuma pengganggu yang berpotensi merusak hubungan mereka. Mengingat gadis itu anggota Rohis, harusnya dia tahu hukumnya dalam Islam, dan harusnya dia memberitahu pria yang melamarnya itu bahwa tidak diperkenankan bagi seorang pria untuk melamar di atas lamaran saudaranya. Tapi, yah... semua sudah terjadi. Memang menyakitkan sekali bagiku, tapi aku harus ikhlas merelakannya. Lagipula aku tahu diri. Saat itu, aku memang hanya pemuda biasa yang tak punya pekerjaan, masih mentah, sedangkan suaminya itu pengusaha sukses. Jika diibaratkan pendaki gunung, gadis itu tipe yang hanya mau menunggu di puncak, bukan yang menggandeng tanganku dan menemani mendaki dari bawah. Atau ibarat petani yang langsung ingin panen tanpa mau menanam.”
Entah kenapa, lama-kelamaan malah aku yang curhat.
“Aku ingat sekali, malam saat aku tahu kabar menyedihkan itu, aku berdiri semalaman di pinggir jembatan yang sepi, melamun menatap sungai di bawah sana sampai air mataku kering. Saat itu hanya rembulan yang menemaniku. Bahkan sampai langit berubah mendung dan hujan turun deras pun aku tak mau pulang, membiarkan bajuku basah kuyup. Jantungku sampai terasa nyeri, dan pada beberapa kesempatan, aku hanya bisa meringkuk memegangi dadaku yang seakan tertusuk-tusuk. Untunglah serangan itu hanya sementara, tidak sampai jadi penyakit serius. Aku hanya bisa berharap, semoga gadis itu bahagia dan tak menyesal atas pilihannya. Toh aku juga sadar kalau di luar sana banyak orang yang lebih menderita dariku. Ujian yang kualami masih tak seberapa, jadi aku harus bangkit dan melupakannya.”
“Ya ampun, tega banget dia, harusnya kan bilang dulu,” Hana tampak bersimpati. Aku mengangguk, memalingkan wajah, tak ingin Hana melihat mataku yang berair. Buru-buru aku mengusapnya. Kurasa dia penasaran siapa teman sekelas yang kumaksud, tapi ternyata malah pertanyaan lain yang muncul. “Memangnya kau ingin istri yang seperti apa?”
Aku terkejut mendengarnya. Untuk apa Hana menanyaiku hal seperti itu? Pikiran aneh terbesit dalam benakku, tapi aku langsung menangkisnya. Hana wanita yang royal, level atas, dan sangat istimewa. Tak mungkin dia suka padaku, mustahil. Aku tahu Hana tidak pacaran, padahal cowok keren yang menggodanya di kampus sudah tak terhitung banyaknya. Kupikir seleranya pasti selangit, jadi tak ada pria yang bisa menjangkaunya. Sangat mustahil jika pria kurus kecil sepertiku terlihat menarik di matanya yang super selektif. Dia adalah wanita soliter dan bukan milik lelaki manapun.
“Aku ingin istri yang penyabar, lembut, dan baik agamanya, seperti Asiah istri Fir’aun yang tabah menghadapi suaminya, meskipun aku tak sejahat Fir’aun sih,” kujawab dengan tenang diselingi tawa. “Nggak perlu cantik, yang penting enak dilihat. Selain itu dia juga harus setia dan mau menuruti kata-kataku. Itu saja sudah cukup.”
Aku menghela napas lagi, berkata lebih serius.
“Tapi... yah, untuk saat ini aku belum tertarik untuk memulai hubungan baru. Aku masih ingin sendiri. Kau tahu, luka hati itu masih menganga, dan sampai saat ini belum ada seorangpun yang bisa menutupinya. Ditambah lagi sebagian temanku bukan penghibur yang baik. Biasa lah, aku malah diledek jomblo dan lain sebagainya. Aku ikut ekspedisi ini pun, salah satu alasannya ya untuk mengubur masa lalu itu. Kuharap aku bisa melupakannya.”
Hana termenung selama beberapa saat, mencerna kalimatku, menatap danau sambil melinting ujung rambutnya. Hening sejenak, yang terdengar hanya desau angin malam. Suara binatang malam terdengar di kejauhan.
Setelah lama membisu, Hana berdiri dan berkata, “Dingin. Pulang yuk.”
Aku ikut berdiri, lega akhirnya dia minta pulang. “Aku antar kau, tapi jangan dekat-dekat ya, nanti kau dikira pacarku.”
“Kau benar-benar pandai menjaga diri ya?” kata Hana, tersenyum. “Eh, maaf ya kalau aku mengganggumu. Aku memang suka begitu orangnya. Kau tak keberatan kan?”
“Nggak apa-apa,” aku tersenyum.
Kami beranjak dan kembali melintasi jalan setapak, kembali ke penginapan. Sengaja aku biarkan dia berjalan duluan, jarak tiga meter memisahkan kami. Tak lama kemudian kami tiba di perkampungan. Hana mengembalikan pisauku, melambai sebelum masuk ke kamarnya, dan aku langsung kembali ke kamarku.
Di depan pintu aku berhenti, merenungi kejadian barusan. Ya ampun, bodohnya aku. Tadi itu kan aku berdua saja dengan Hana, dan meski kami berjauhan, tetap saja itu namanya berkhalwat, berduaan di tempat sepi, dan itu dosa, hampir mendekati zina! Jika aku berdua saja dengan lawan jenis, maka yang ketiga adalah setan. Astaghfirullah, kenapa aku bisa melakukan kesalahan sefatal itu? Aku mengutuki kebodohanku sendiri, geleng-geleng kepala. Tapi mana mungkin kan aku harus marah-marah dan menyuruh Hana menyingkir? Lagipula aku tidak menikmati hal itu, malah menyesalinya. Ah, bertambah lagi dosaku.
Sayup-sayup terdengar ocehan riang teman-temanku. Ketika masuk ke kamar, mereka sudah berganti pakaian tidur. Meski begitu, mereka belum terlihat mengantuk.
“Dari mana saja kau Kapten?” tanya Harto. “Kami mencarimu sejak tadi. Kukira kau diculik dedemit penunggu danau.”
“Cari angin,” jawabku sekenanya, mencuci muka di wastafel.
“Hari yang menyenangkan, dua lokasi dalam satu hari,” kata Igo riang saat kami merebahkan diri di kasur. “Yang bikin capek cuma perjalanannya, lama pula.”
Aku, Harto dan Nasuti mengangguk setuju. Kami saling melirik, memegang bantal masing-masing. Lalu entah siapa yang memulai, tanpa dikomando, tanpa persetujuan, bantal-bantal beterbangan dan kamar dipenuhi keributan saat kami terlibat perang bantal. Aku tertawa girang sambil mengayunkan guling dengan liar, menikmati kegilaan ini. Semua tampak beringas, dengan penuh semangat melemparkan bantal ke arah siapa saja yang terlihat lengah. Kami terpaksa berhenti saat penjaga hotel mengetuk-ngetuk pintu kami. Kami saling pandang, sunyi, kemudian tertawa lama sekali. Mataku sampai berair. Setelah semua babak belur, kami langsung tertidur akibat kelelahan.
Tengah malam aku tiba-tiba terbangun. Aku tak tahu apa yang tiba-tiba mengganggu tidur nyenyakku. Lampu masih menyala. Kulihat Nasuti masih terjaga memandangi foto ayahnya. Aku ingin menegur dan menyuruhnya tidur, tapi mengurungkan diri. Aku merasa melihat genangan air di kedua matanya. Aku mengerti perasaannya. Baginya, ini adalah pencarian seumur hidup. Pasti ia sangat merindukan ayahnya itu. Dia senasib denganku yang harus kehilangan ayah di usia yang masih sangat muda.
“Maaf, kau jadi terbangun,” gumam Nasuti, menyadari tatapanku.
“Oh, iya, nggak apa-apa,” kataku serak. “Kamu nggak bisa tidur?”
Nasuti mengangguk, matanya masih menatap foto. Selama beberapa saat kami berdua terdiam. Kesunyian membentang. Kemudian Nasuti berkata, pelan sekali, “Ayahku pergi saat aku berumur tujuh tahun. Dia meninggalkanku dan ibuku, entah untuk tujuan apa. Aku bahkan tak ingat seperti apa sifat ayahku. Ibuku bilang beliau seorang pakar hukum. Bisa saja ia bekerja sebagai hakim atau pengacara. Satu-satunya kenangan yang kupunya hanya sorban dan selembar foto ini. Kau tahu bagaimana perasaanku kan?”
“Ya, aku mengerti,” kataku. Aku sudah mendengar ceritanya puluhan kali, tapi selalu kudengar dengan penuh minat. “Kau pasti akan segera menemukannya.”
Nasuti menatapku lama, lalu mengangguk dan mematikan lampu. Aku menarik selimut, membalik badan dan merenung. Sesungguhnya, kisah Nasuti tak sesederhana itu.
*****
HARI KE-5, BUKITTINGGI & PADANG
Dari Parapat, kami naik mobil carteran selama delapan belas jam ke Bukittinggi, Sumatera Barat. Kami sengaja memilih perjalanan malam agar bisa tidur di mobil dan menghemat waktu. Itu pun sang sopir sudah ngebut maksimal, lincah menyalip kendaraan lain. Ditambah lagi kondisi jalan yang berlubang-lubang membuat perjalanan semakin molor. Kemarin, pagi-pagi sekali kami harus meninggalkan Samosir. Masih banyak tujuan yang harus ditempuh, jadi kami tak bisa santai-santai. Harus kuakui, perjalanan kilat lintas provinsi ini memang menyenangkan, tapi jika seperti ini terus, rasa-rasanya aku agak kewalahan juga.
Datang ke Bukittinggi rasanya kurang afdol kalau tidak mampir ke Jam Gadang, menara unik yang menjadi landmark kota ini. Jadi pagi itu, setelah tidur yang terasa amat singkat, kami berjalan-jalan sebentar ke Benteng Fort De Cock, sisa-sisa Perang Paderi tahun 1825. Darahku berdesir mengingat dulunya di tempat ini terjadi pertempuran dahsyat antara prajurit yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol melawan tentara Belanda. Jam Gadang yang berdiri di tengah-tengah kota ini dibangun tahun 1926, sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Sekretaris Fort De Cock. Uniknya, angka 4 pada jam yang dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto ini bukannya “IV” malah tertulis “IIII”. Setelah puas berjalan-jalan, kami mampir ke Pasar Atas membeli kain songket khas Minangkabau. Para pedagang yang berbahasa Minang begitu ramah melayani pembeli—meski ada juga yang berteriak-teriak—dan sekali lagi aku dibuat takjub dengan betapa beragamnya suku bangsa di negeri ini.
Setelah agak siang, kami melanjutkan perjalanan ke Kota Padang, sambil disuguhi panorama Danau Maninjau yang elok, ladang-ladang hijau, Gunung Singgalang, dan Ngarai Sianok—tebing cadas eksotis setinggi 100 meter dengan anak-anak sungai di bawahnya. Tiba di Padang, yang pertama kami kunjungi adalah Pantai Air Manis, di mana terdapat Batu Si Malin Kundang yang legendaris—batu berbentuk manusia sedang bersujud yang konon dikutuk ibunya karena durhaka. Malamnya kami beristirahat di sebuah warung makan, memesan sate padang yang empuk dan berkuah kuning, ditambah seporsi itiak lado mudo dan rendang sapi khas Minang—makanan terlezat di dunia, katanya. Semua menu itu pedasnya bukan main, sehingga kami perlu memesan es durian ganti nan lamo untuk menetralisir lidah yang terasa membara. Seharian itu kami hanya mengeksplor dua kota saja di Sumatera Barat, karena besoknya kami punya agenda yang cukup berat dan bakal menguras tenaga.
Aku perhatikan, kebanyakan pengunjung rumah makan adalah pasangan muda-mudi yang tampak bermesraan, dan cuma satu dua yang makan seorang diri. Beberapa terlihat tak malu-malu saling menyuapi. Kulirik Hana yang makan dengan tenang, tak terganggu dengan lirikan om-om di meja sebelah. Meski dia pandai menjaga diri dan terbiasa bergaul dengan laki-laki, tetap saja aku merasa risih karena dia satu-satunya hawa di antara kami.
Tiba-tiba Nasuti terdiam. Ia berhenti mengunyah. Tatapannya lurus ke arah jalan besar di depan restoran. Dia bangkit berdiri, melompat meninggalkan kami, menghambur ke luar restoran dan berlari ke arah jalan raya. Aku dan Harto saling pandang, lalu mengejarnya.
“Ada apa?” tanyaku, ketika berhasil menjajari Nasuti.
“Kalian lihat orang itu?” kata Nasuti, menunjuk seorang pria di seberang jalan, tak menyadari kami. “Aku kenal orang itu. Aku pernah melihat fotonya bersama Ayah, mungkin dia dulunya teman kerja Ayah. Barangkali dia punya petunjuk di mana Ayah berada.”
Pria itu berjalan menjauh. Sebelum sempat kami cegah, Nasuti berlari mengejar, tanpa memedulikan keramaian jalanan. Klakson berdecit-decit. Sebuah mobil mengerem mendadak tepat di depan Nasuti, hampir saja dia tertabrak.
“Woi, kalau jalan lihat-lihat!” teriak si sopir, ngeloyor begitu saja tanpa menunggu maaf. Kami mengejar Nasuti, lalu membimbingnya ke seberang hingga akhirnya berhasil mengejar bapak tadi.
“Oh, waang (kamu) putranya Pak Iqbal? Senang bisa bertemu,” kata si bapak ramah saat kami terengah di depannya. Logat Minangnya terdengar kental.
"Uda (abang) tahu di mana ayah saya?" Nasuti menyambar, tanpa basa-basi.
Bapak itu menggeleng, tampak prihatin. “Saya terakhir ketemu beliau lima tahun lalu.”
Nasuti tampak kecewa, kemudian cepat-cepat bertanya, “Di mana, Uda?”
“Kalau indak salah, di Jogja,” ia mengerutkan dahi. “Coba waang temui orang bernama Sri Murni. Dia pengrajin batik di dekat Malioboro, pernah jadi teman kerja kami saat masih muda dulu. Mungkin dia lebih tahu.” Bapak itu menarik napas, kemudian melanjutkan, “Dulu ayah waang pernah merantau bersama saya. Beliau orang terkenal, seorang hakim yang adil. Dia sering sekali bercerita tentang istri dan anak laki-lakinya. Mendengarnya bercerita, saya tahu dia bangga sekali sama keluarganya. Sayang, waktu dia pulang kampung, istrinya meninggal dan anaknya hilang entah ke mana.”
“Sebenarnya saya tidak hilang, tapi tinggal di panti asuhan atas ajakan teman,” Nasuti melirik Harto. “Ibu saya juga masih hidup. Saya kira… ayah saya tak akan pernah kembali.”
“Oh begitu,” kata bapak itu. “Pak Iqbal terus mencari waang. Dia begitu terpukul dan merasa bersalah telah meninggalkan kalian. Kemudian dia pindah ke Jogja, katanya ada urusan pekerjaan. Sejak itu kami tak pernah ketemu lagi. Kabarnya dia ke rumah Bu Sri atas undangannya dan mendapat tugas memimpin sebuah persidangan di sana.”
Nasuti tak tampak patah harapan, malah justru penuh tekad. “Jogja,” gumamnya. Harapan masih terbuka baginya, meski pasti akan sulit mencari wanita bernama Ibu Sri ini.
“Sabar, nanti juga ketemu. Jangan menyerah,” kami menghiburnya.
Bapak itu tersenyum. “Pak Iqbal itu orang baik. Pasti dia punya alasan sendiri hingga meninggalkan rumah dan keluarganya. Saya tahu dia menyayangi waang. Oh ya, nama saya Alatas. Ini nomor telepon saya, barangkali perlu.” Dia mengeluarkan secarik kertas beserta pena, lalu menuliskan beberapa digit. Kertas itu diserahkannya pada Nasuti. “Kalau ada perlu apa-apa, hubungi saja saya. Dulu ayah waang sering menolong saya, jadi tak usah sungkan.”
Setelah mengucapkan terima kasih, kami merangkul Nasuti kembali ke restoran.
*****


 radenbumerang
radenbumerang


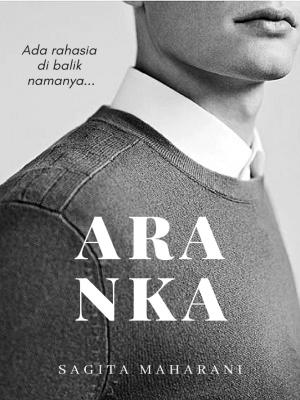


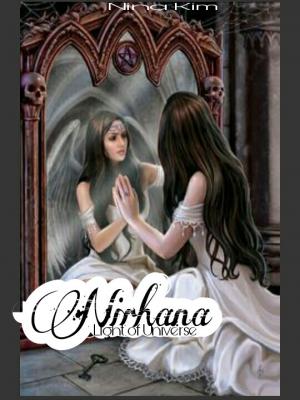
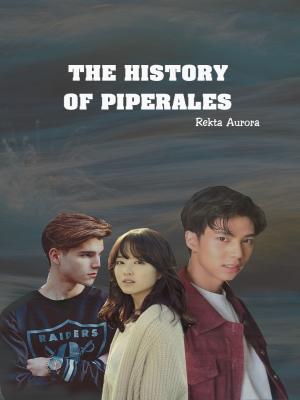

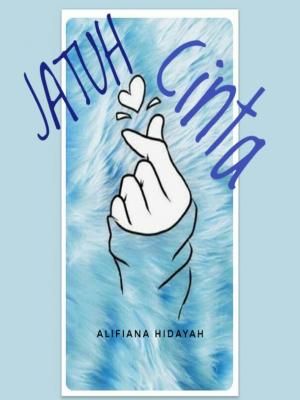

Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.