BAB 6. TARING-TARING PETAKA
HARI KE-6, KERINCI, JAMBI
Setelah menumpang mobil travel selama tujuh jam, dan lagi-lagi kami harus tidur di mobil, akhirnya kami tiba di Desa Kersik Tuo, Jambi. Tak terasa sudah beberapa provinsi kami lewati, dan kami harus berterima kasih pada kru perusahaan travel Zhen yang bertindak cepat dan bisa diandalkan. Di depan kami, Gunung Kerinci setinggi 3805 meter menjulang gagah menggapai awan. Gunung berapi tertinggi di Indonesia ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena menjadi habitat beragam hewan terancam punah, seperti beruang madu, harimau dan gajah Sumatera. Aku sendiri penasaran ingin melihat bunga Rafflesia arnoldi yang tersohor itu, yang katanya ada juga di sini.
“Nah, Guys, besok kita akan mendaki gunung itu,” kata Muqodas. “Ini tantangan berat pertama setelah perjalanan kita dimulai. Buat kalian yang mau ikut, sebaiknya hari ini siap-siap dulu, aklimatisasi suhu tubuh sambil jalan-jalan di kebun teh. Sore nanti kita beli logistik dan malamnya harus istirahat total buat persiapan besok.”
“Oke Bos,” Zhen menyahut, memandang Tugu Macan yang menjadi ikon desa ini. “Perlengkapan mendaki kita juga sudah lengkap. Jadi nggak perlu nyewa.”
“Eh, Hana, kamu ikutan naik juga?” tanyaku, dan gadis itu mengangguk.
Sejak masih kuliah dulu, aku sering mendaki gunung—meski baru sebelas puncak yang kucapai dan itu pun hanya di Pulau Jawa. Harus kuakui jika pendakian ini akan jadi yang terberat, mengingat statusnya sebagai gunung berapi tertinggi dan medannya yang terkenal sulit. Apalagi aku, Harto, Igo dan Nasuti bukan anggota Pecinta Alam, hanya anak Rohis yang hobi bertualang. Setelah menyewa homestay dan packing barang, seharian itu kami berkeliling kebun teh sambil jogging. Penduduk sini ramah-ramah, dan katanya Perkebunan Teh Kayu Aro ini adalah kebun teh tertua di dunia. Adapun teh hitamnya termasuk yang terbaik dan amat tersohor di kalangan ratu Belanda. Kami sempat mencicipinya, dan rasanya memang sedap luar biasa.
Malamnya kami mencoba tidur meski udara terasa dingin menggelitik, dan besoknya pagi-pagi sekali kami berkumpul di pos pendakian untuk mengurus SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi). Masing-masing menggendong tas carrier 80 liter berisi tenda, flysheet, sleeping bag dan ransum untuk dua hari. Igo bahkan membawa trekking pole, tongkat besi untuk mendaki yang bisa dilipat. Setelah registrasi, briefing sejenak dan berdoa, kami memulai pendakian dengan langkah ringan, melintasi jalan setapak melintasi Pintu Rimba, gerbang masuk menuju hutan Kerinci. Saat itu hanya ada dua rombongan yang mendaki, yaitu kami berdelapan dan beberapa mahasiswa dari Jakarta.
“Bagi pendaki, yang terpenting bukanlah siapa yang paling cepat tiba di puncak, karena tujuan utama kita bukanlah puncak, melainkan pulang ke rumah dengan selamat,” kata Zhen. Sama seperti Torik, Muqodas dan Hana, pemuda sipit berkacamata tebal ini juga anggota Mapala Bio Explorer yang terbiasa mendaki gunung, di samping juga atlet Shorinji Kempo yang handal—lawan terkuatku di turnamen se-Jawa Tengah silam.
“Yoi Bro, terkadang kesalahan pendaki pemula adalah menganggap pendakian sebagai balapan, dan yang paling belakang dianggap lemah,” timpal Muqodas.
“Yang terpenting adalah seni mengatur napas, berjalan pelan tanpa buru-buru dan sesekali berhenti jika lelah,” kata Torik. “Tapi jangan kelamaan juga berhentinya.”
Seperti lumrahnya mendaki gunung, langkah-langkah pertama terasa amat berat karena selain medan yang menanjak, kami juga menggendong carrier yang beratnya minta ampun. Namun setelah melewati beberapa tanjakan dari Pos 1 hingga Pos 3, perlahan kami mulai terbiasa, dan napas yang tadinya ngos-ngosan pun kembali ritmis. Udara hutan yang segar dan aroma lumut memenuhi hidung, sesekali kami juga berpapasan dengan hewan-hewan liar yang mengintip dari balik dedaunan.
Sejak dari Pintu Rimba tadi Harto asyik jeprat-jepret dan merekam dengan handycam-nya, sesekali menerbangkan drone untuk mengambil gambar dari atas. Muqodas yang rekor mendakinya paling banyak ditugaskan sebagai leader dan berjalan di depan, sedangkan Zhen diposisikan sebagai sweeper yang berjalan paling belakang, memastikan semua pendaki aman. Keduanya membawa handie talkie dan menggantungkan lonceng kecil di celana.
Selewat pukul empat sore, pendakian mulai terasa berat. Selain fisik kelelahan, suasana hutan mulai tampak mencekam. Tak seperti gunung-gunung di Jawa, hutan di Kerinci sangat rapat dan dihuni berbagai hewan buas. Dengan waspada penuh, aku mengawasi pepohonan besar di kanan-kiriku, tersentak saat melihat kelebatan loreng di balik semak, lalu hilang. Muqodas memberi isyarat agar terus maju, seraya berdoa agar hewan itu tidak mengganggu. Kabut mulai turun mengurangi jarak pandang, kami berjalan berdekatan agar tak terpisah. Jantungku berdegup kencang, dan kami menggigil saat gerimis turun, lalu semakin besar.
“Hati-hati langkah kalian, awas kepeleset,” Muqodas berseru saat kami melewati tanah yang licin dan becek. Sesekali petir menyambar di antara hujan yang kian deras. Genangan air yang meluas membuat kami seakan berjalan di atas sungai. Perutku mulai lapar, carrier yang kugendong seakan bertambah bobot berkali-kali lipat. Di depan kami terbentang jalur supersempit dengan celah-celah pohon rimbun seperti terowongan, dan kami harus melewati jalan setapak yang seperti parit itu untuk sampai di pemberhentian selanjutnya.
Setelah berkasak-kusuk menyibak dedaunan, beberapa kali tersangkut ranting, akhirnya kami tiba juga di Shelter 3. Pukul tujuh malam, artinya sebelas jam kami berjalan dari Pintu Rimba. Ini pun terbilang cepat karena kami jarang berhenti. Adapun rombongan dari Jakarta tadi sudah tertinggal jauh di belakang, memutuskan berkemah di Pos 2. Tubuhku terasa kaku saking dinginnya. Jas hujan yang kupakai agaknya kurang ampuh, bajuku sampai basah kuyup. Mengabaikan fisik yang kelelahan dan pegal-pegal, kami langsung memasang tenda dan flysheet, lalu menyalakan kompor kecil dan memasak air.
Malam itu kami habiskan dengan menyantap bubur instan dan susu jahe, tak ada api unggun. Sejenak bercakap-cakap dan berkelakar untuk mengusir sepi, tak banyak yang dibicarakan. Karena terlampau lelah, kami lantas bergegas tidur, meringkuk di sleeping bag yang nyaman. Para pria tidur berdempetan di tenda berkapasitas 6 orang, sedangkan Hana tidur sendirian di tendanya, ditemani tumpukan tas carrier dan sepatu. Punggungku terasa kram karena hanya mengandalkan matras sebagai alas tidur.
Tengah malam, aku terbangun karena mendengar sesuatu.
Suara geraman.
Aku langsung duduk, menatap sekitar. Gelap, tapi aku merasa ada kaki-kaki besar yang melangkah mengitari tenda. Sesekali, geraman itu terdengar lagi, diiringi bunyi endusan. Mungkinkah itu harimau? Aku semakin waswas, melihat bayangan makhluk itu mendekat ke tenda kami, tepat di sebelahku. Teman-temanku masih tertidur, kecuali Torik yang membuka sebelah matanya, mengawasiku.
“Udah biarin aja, nanti juga pergi,” bisiknya tanpa suara.
Aku mengangguk, merebahkan diri sepelan mungkin, mengawasi bayangan itu sambil komat-kamit berdoa. Perlahan, bayangan itu mulai menjauh dan suaranya tak terdengar lagi, agaknya sudah pergi. Aku bernapas lega, berharap makhluk itu tak kembali lagi.
Rasanya aku baru tidur sebentar ketika Harto mengguncang bahuku. Aku mengucek mata dan melirik jam tangan. Pukul dua dinihari, waktunya summit attack. Yang lain masih menguap, menggulung sleeping bag dengan malas. Hanya Muqodas yang sudah berseragam lengkap, mengenakan jaket gunung, sarung tangan dan headlamp. Sambil berkacak pinggang ia menunggu kami berbenah.
“Ayo, ayo bangun, biar bisa ngejar sunrise. Jangan pada loyo gitu,” katanya. Ia lalu memanggil Hana di tenda sebelah, yang ternyata sudah bangun.
“Kita masak bubur dulu sebentar, biar agak melek,” kata Torik sang koki handal. Dia cekatan merebus air, menuang bubur instan ke mangkuk dan memotong sayuran. Pandai sekali dia memainkan pisaunya. Segera saja aroma sedap menguar di dalam tenda. “Nanti habis ngisi perut langsung berangkat.”
Begitu keluar tenda, udara dingin langsung membuatku menggigil. Muqodas memberi isyarat agar kami bergegas. Aku memasukkan HP, dompet, dan barang berharga lain di tas kecil, sedangkan barang lainnya kutinggal di tenda. Menurut Muqodas, estimasi perjalanan hingga puncak sekitar dua jam. Setelah briefing dan berdoa, kami memulai summit attack dengan langkah kecil, beriringan di tengah gelap sambil menahan dinginnya malam.
Uap putih keluar dari mulutku, lalu lenyap diterpa angin. Mendekati puncak, medan yang kami lewati semakin sulit. Tekstur jalur yang berpasir membuat langkah kami terseok, maju dua langkah terdorong mundur lagi selangkah. Apalagi sumber penerangan kami hanya headlamp dan senter kecil. Harto beberapa kali tersandung. Hana yang berjalan di depanku tampak sempoyongan, terengah kelelahan. Dari gumamannya, ia terdengar seperti ingin menyerah, tapi terus memotivasi dirinya dengan berbisik: Aku pasti bisa sampai ke puncak.
"Break!" Muqodas memberi aba-aba. "Kita istirahat sebentar."
Kami duduk di atas batu, menenggak air mineral sambil mengamati langit jernih yang menampakkan gugusan bintang. Untuk mengganjal perut, aku mengunyah cokelat batangan yang juga berkhasiat sebagai mood booster. Kami pun meneruskan pendakian. Jika siang tadi kami sering bercanda, pendakian malam justru tak ada yang bicara karena kelelahan.
“Hati-hati, jangan sampai tergelincir,” kata Zhen. “Dan waspada juga jika ada runtuhan dari atas. Pokoknya jaga jarak, kalau kalian menginjak batuan rapuh, langsung teriak supaya yang di bawah bisa menghindar.”
“Sebentar lagi puncak kok, ayo semangat,” kata Torik.
Itu kalimat yang diulang-ulang sejak tadi, nyatanya puncak masih jauh. Entah sudah berapa jam kami berjalan, napasku seakan habis. Rasanya hanya batu dan batu lagi saja yang terlihat di depanku. Akhirnya, setelah lututku terasa mau copot, kudapati tak ada tanjakan lagi di depanku. Yang ada hanya tanah datar berbatu dan cukup lapang. Di kejauhan tampak kepulan asap samar dari lubang kawah raksasa yang masih remang. Torik tak berbohong.
“Puncaaak!” Harto dan Nasuti berteriak, mendahuluiku berlarian ke atas. Aku terpana, tak percaya melihat panorama menakjubkan di hadapanku. Akhirnya kami tiba di puncak. Pukul lima pagi, langit perlahan mulai terang, hingga sang surya menampakkan diri dengan gagah, memberi kehangatan pada kami yang kedinginan. Kawah besar itu mulai tampak jelas kesangarannya, mengepulkan uap raksasa yang menjulang tinggi. Di sisi lain, tampak pemandangan kebun teh di kaki gunung yang tampak kecil, beserta Gunung Tujuh, Bukit Barisan dan lautan awan.
“Subhanallah, indah sekali negeri ini,” kataku terharu, seraya bersujud syukur. Kawan-kawanku menunjukkan kekaguman yang sama. Bahkan Hana terlihat menangis.
Meski rasanya betah di sini, kami tak bisa berlama-lama. Setelah berfoto dan merekam pemandangan, kami langsung turun dengan hati puas.
Seperti biasa, perjalanan turun selalu lebih cepat, tapi juga lebih menyiksa karena betis yang ngilu dan tubuh terasa remuk. Tak lupa, sampah berupa botol kosong dan bungkus makanan kami bawa turun untuk dibuang di tempat sampah dekat basecamp. Sebagai pecinta alam sejati, kami selalu sadar untuk tidak corat-coret atau membuang sampah sembarangan. Enam jam berlalu, akhirnya kami tiba di Pintu Rimba. Rasanya puas sekali berhasil menaklukkan puncak tertinggi Sumatera, apalagi tak ada hewan buas yang menghadang di perjalanan turun. Setelah shalat dan makan, kami langsung tidur pulas setiba di homestay, melupakan jaket dan celana yang belepotan. Biar besok saja dilaundry-nya, pikirku.
*****
Seperti yang sudah kuduga, keesokan harinya, kami merasakan perubahan drastis pada fisik kami, suatu penderitaan luar biasa. Sekujur tubuh terasa nyeri dan pegal-pegal. Tulang-tulang seperti remuk, dan setiap jengkal urat rasanya seperti mau putus. Rasanya sulit sekali untuk bergerak, bahkan sekadar berjalan ke kamar mandi pun seperti sebuah penyiksaan. Setidaknya itulah yang dialami Harto dan Igo.
“Aduduh, serangan asam laktat nih, tangan dan kakiku sakit semua,” Harto tertatih-tatih, tangannya gemetar menggenggam sikat gigi. Pasti ototnya ngilu sekali.
"Namanya juga permulaan,” kataku. “Segala sesuatu butuh proses, seperti pembuatan sebuah jembatan, butuh waktu dalam meletakkan papan kayu di atas dua utas tali, setahap demi setahap. Proses yang berat, tapi kemudian akan semakin mudah hingga pada akhirnya akan terbentuk sebuah jembatan yang utuh. Ayolah, baru juga beberapa hari ekspedisi, jangan lesu begitu. Awalnya memang terasa berat, tapi nanti juga terbiasa.”
"Kamu nggak kesakitan, Lutfi?” Tanya Igo. Sejauh ini dia yang paling parah, saking lemasnya sampai beberapa kali menabrak tembok.
“Oh, aku sudah terbiasa berjalan jauh. Tiap minggu aku rutin olahraga ke GOR Satria. Pendakian kemarin sih biasa saja bagiku. Memang capek, tapi nggak sampai bikin pegal-pegal. Makanya, kalau kuajak fitness, lain kali nurut saja.”
“Kalau segini saja kelelahan, gimana nanti kalau sudah sampai di Jayawijaya?” keluh Igo. “Belum setengah pendakian, bisa-bisa aku sudah semamput.”
“Makanya, kita latihan jalan jauh dulu kan, sebelum sampai di sana?” hiburku. “Nanti juga sedikit demi sedikit terasa perubahannya. Latihan yang ringan-ringan saja dulu.”
Hingga pukul setengah enam, Nasuti sulit sekali dibangunkan. Tubuhnya seperti dilem ke tempat tidur. Alarm yang dipasangnya tak berguna. Aku juga sudah mengguncangnya, mencubit, menarik-narik kakinya, percuma saja. Saat Harto menarik tubuhnya, di luar dugaan Nasuti malah meninju pipi Harto, membuatnya terjengkang.
“Males ah, capek!” Nasuti ngelindur, memeluk erat bantal gulingnya. “Jauh-jauh sana, Nenek Lampir!”
Harto bangkit, memegangi pipinya yang berdenyut. Dengan geram, Harto menjitak kepala Nasuti sekuat tenaga. Bagai disengat listrik, pemuda itu langsung loncat, memasang kuda-kuda dengan mata setengah terpejam.
“Sudah bangun?” Harto melipat lengan, lalu menjitaknya lagi.
“Iya iya, aku bangun!” Nasuti meringis. “Kenapa dua kali sih?”
“Bonus!” kata Harto ketus, mengibaskan tangannya. Pasti tambah sakit.
*****
HARI KE-11, LAMPUNG
Meski begitu, perjuangan mati-matian kami mendaki Gunung Kerinci masih terbilang ringan dibanding cobaan yang menimpa kami beberapa hari kemudian. Dari semua petualangan kami di Pulau Sumatera, yang paling menegangkan justru saat kami mengunjungi Way Kambas—tempat pelatihan dan konservasi puluhan ekor gajah Sumatera. Cagar alam seluas 1300 km persegi itu kami tempuh sekitar dua jam dari Bandar Lampung. Untunglah kami diantar mobil pick up Dinas Kehutanan, dan kebetulan tujuannya sama sehingga kami tak perlu keluar ongkos.
Setiba di sana, suara belalai gajah yang mirip trompet bersahutan menyambut kami. Aku terpesona melihat hewan-hewan jumbo itu berlalu-lalang, banyak sekali jumlahnya. Seorang petugas ranger berpakaian khas polisi hutan tampak sibuk mengawasi rekannya yang sedang memasang pelana di punggung gajah. Begitu melihat kami, petugas itu tampak agak terkejut, lalu buru-buru menghampiri kami, tersenyum lebar dan menjabat tangan kami.
“Eh, kalian mahasiswa Biologi Unsoed kan?” sapanya.
“Iya, benar... kok bisa tahu ya?” kataku, agak kaget. Entah kenapa, rasanya wajah petugas ini familiar, tapi aku lupa pernah bertemu di mana.
“Ah, kalian lupa ya? Ini saya, Uki, kakak kelas kalian. Lulusan Biologi juga, angkatan tiga tahun silam. Pasti gara-gara seragam ini, kalian jadi pangling kan?”
“Ooh... iya, iya, saya ingat. Mas Uki yang dulu suka ikut demo itu kan?” kataku, tersenyum lebar. Teman-temanku juga mengangguk-angguk, mendadak ingat, menyapa lebih ramah. “Kalau nggak salah, dulu Mas Uki ini aktivis lingkungan yang rajin menggalakkan agenda menanam seribu pohon kan? Wah, nggak nyangka bisa ketemu di sini.”
“Syukurlah kalian masih ingat. Jadi kangen, dulu saya dan teman-teman aktivis sering keliling di sekitar jalan kampus, bagi-bagi bibit tanaman ke warga, bersih-bersih sampah, sambil mencabuti poster yang dipaku sembarangan ke pohon—merusak alam saja, apa mereka nggak kasihan sama pohonnya? Oya, gimana kabarnya Gunung Slamet? Dulu pas zaman saya kuliah, katanya mau dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di sana.”
Senyumku memudar. “Buruk Mas, meski banyak warga yang menolak, berdemo di depan kantor pemerintah, pembangunan pembangkit listrik itu tetap dijalankan. Padahal menurut undang-undang, pembangkit listrik panas bumi itu termasuk kategori pertambangan, proyek geothermal yang berpotensi merusak keseimbangan alam karena dibangun di atas lahan yang tadinya hutan lindung. Tahun kemarin, sudah dua kali daerah di kaki gunung itu dilanda banjir. Tadinya banyak yang berharap insiden itu mendapat perhatian pemerintah, tapi kasus itu jadi tersampingkan gara-gara isu pilkada. Alhasil, PLTPB tetap jalan, banjir jadi makin sering melanda, tapi pemerintah santai-santai saja menanggapinya.”
“Sangat disayangkan, artinya perjuangan kami dulu sia-sia ya?” Mas Uki mengelus dahi. “Ah, tapi saya tak ingin merusak kunjungan kalian yang berharga ini dengan topik menyedihkan itu. Kalian sedang liburan kan? Mari, saya ajak kalian berkeliling.”
Mas Uki mengajak kami ke sebuah pondok bambu, berbincang hangat tentang berbagai topik. Sambil menikmati ikan bakar dengan saus tempoyak durian, kami disuguhi atraksi menarik saat para pawang menyuruh beberapa gajah berdiri dengan dua kaki, mengangkut kayu gelondongan, bahkan ada juga yang diajari melukis dan bermain bola. Kami juga beruntung bisa ikut patroli bersama petugas ranger, menunggang gajah sambil berkeliling hutan tropis. Patroli ini rutin dilakukan untuk mencegah pembalakan dan perburuan liar. Mas Uki yang memandu kami bercerita bahwa setahun lalu terjadi pencurian kayu besar-besaran di wilayah hutan lindung, tapi para pelakunya selalu meloloskan diri. Sejak itu pengamanan di hutan ini diperketat dan ada wilayah tertentu yang terlarang untuk dimasuki.
“Keren, ini pertama kalinya aku naik gajah,” kata Harto.
“Sama, aku juga,” Nasuti menimpali.
Awalnya kami agak kesulitan saat menaiki punggung gajah, geli rasanya duduk di kulitnya yang tebal. Seorang petugas membantu kami naik. Setiap gajah dinaiki dua atau tiga orang termasuk pawang. Teman-temanku tampak riang saat rombongan gajah bergerak maju, membawa kami menyusuri area konservasi, lalu masuk ke hutan yang semakin lebat. Harto langsung beraksi dengan kameranya, begitu pula para turis lain yang ikut rombongan ini.
“Gimana, asyik kan rasanya naik gajah?” kata Mas Uki. “Dulu waktu pertama kali kerja di sini, awalnya saya juga takut, tapi lama kelamaan mulai terbiasa. Nggak nyesel kerja di sini, berasa seperti mengerjakan hobi yang dibayar. Kalau kalian masih cari kerja, saya sarankan kalian ikut jejak saya. Yah, asalkan pekerjaan itu cocok dengan passion kalian.”
Gerimis perlahan turun saat rombongan melintasi sungai besar. Aku terpukau dengan aksi anak-anak gajah yang masih balita, gemas melihat mereka mandi dan saling menyemprotkan air. Seorang petugas mengingatkan agar tak berlama-lama di sungai itu, karena disinyalir banyak sarang ular dan buaya di sekitar lubuk yang tampak tenang. Sambil bergidik ngeri, kami pun memutuskan kembali ke pos.
Sayangnya, malapetaka justru datang setelah itu.
Entah bagaimana ceritanya, gajah yang ditunggangi Harto dan Zhen tertinggal di belakang. Harto yang duduk dekat ekor tahu-tahu merosot dan tercebur ke sungai. Kaget, sahabatku itu meneriaki Zhen dan tunggangannya yang lebih dulu sampai ke tepi. Bukannya menunggu, Zhen malah tertawa dan meninggalkannya, membiarkan Harto berenang sendiri.
Saat itulah, tiba-tiba terdengar bunyi ceburan keras dan makhluk itu pun muncul. Mula-mula matanya, lalu cuping hidungnya, kemudian tampaklah rahang besar menakutkan dengan deretan gigi tajam. Sejak tadi, makhluk-makhluk ini sembunyi karena tak berani berurusan dengan gajah. Tapi sekarang hewan-hewan jumbo itu sudah pergi, dan ada mangsa empuk jatuh dekat sarang mereka.
“AWAAS! BUAYAAA!”
Zhen tampak pias, berteriak panik saat buaya itu mengejar Harto. Ia meminta pawang membalik arah, tapi si gajah ngotot enggan kembali ke sungai. Jarak buaya itu dengan Harto masih jauh, tapi kecepatan berenangnya tak diragukan lagi. Tanpa menoleh, Harto berlari menyibak air sambil berteriak minta tolong, sadar ancaman maut mengintainya. Reptil itu semakin mendekat. Aku dan para petugas segera kembali untuk menolong, tapi terlambat. Terjadilah insiden mengerikan itu.
Harto meraung kesakitan saat buaya itu berhasil menghujamkan gigi ke betisnya. Harto mengibaskan kaki, namun reptil itu tak mau lepas dan membuatnya semakin kesakitan. Aku dan Igo berseru cemas. Tanpa diduga, Torik nekat terjun ke sungai dan berusaha memiting si buaya, meninju kepalanya, lalu dengan cerdik menutup lubang hidungnya, membuat buaya itu sulit bernapas dan terpaksa membuka mulutnya. Kaki Harto pun terlepas. Zhen buru-buru menarik dan membawa Harto ke tepi sungai. Mas Uki yang kebetulan membawa senapan terpaksa melepas tembakan untuk mengusir buaya itu. Setelah reptil buas itu pergi, petugas lainnya memeriksa Harto dan menggotongnya menjauh dari sungai.
Kami diinterogasi atas siapa yang bertanggung jawab. Harto menunjuk tanpa ragu. Segera saja Zhen kena omelan pedas si petugas. Kami berkerumun mengelilingi Harto yang mengaduh memegangi betisnya. Baru sepuluh hari perjalanan, kami sudah kena musibah.
“Nggak parah kan?” kata Zhen, melongok dari balik bahu Igo.
“Nggak parah gimana? Lihat tuh sampai berdarah-darah!” teriak Igo. Harto mengerang semakin keras. Celananya koyak, betisnya dipenuhi noda gelap. Bisa dibayangkan sedalam apa luka akibat gigitan buaya. Pasti sakitnya tak tertahankan.
“Aduh... kakiku.”
Igo yang mewarisi keahlian medis dari ayahnya segera memeriksa Harto. “Luka di betis kirinya cukup lebar. Banyak sekali darah yang keluar. Untung bekas gigitannya tidak dalam.” Igo cekatan membebat kaki Harto dengan perban yang disodorkan petugas. “Ajaib sekali, atau harus kubilang Harto sangat beruntung bisa selamat hanya dengan luka segini. Padahal yang paling parah kakinya bisa saja buntung. Entah karena dia memakai celana jeans atau buaya yang menggigitnya masih kecil. Tapi tidak, aku melihatnya sendiri, buaya itu besar sekali. Mungkin ada sesuatu yang membuat buaya itu tak sekuat tenaga menggigit Harto. Yang penting lukanya harus segera dirawat.”
“Kita bawa ke rumah sakit, biayanya biar aku yang tanggung,” Zhen menawarkan, wajahnya datar. Segera saja dia menelepon ambulans. Sebetulnya Mas Uki juga sudah menawarkan perawatan, tapi Zhen berpendapat sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja.
“Ada apa? Apa yang terjadi?” kata Hana yang sudah tiba duluan di pos. Muqodas dan Nasuti ikut menatapku penasaran sambil makan es krim. Mereka bertiga tak tahu menahu insiden ini karena ikut rombongan pertama. Saat melihat kondisi Harto yang digotong ke pos, mereka terkejut bukan main. Hana menekap mulutnya, es krim di tangannya terjatuh sia-sia.
“Masya Allah, Harto kenapa?” Nasuti berseru panik.
“Digigit buaya,” Igo menjelaskan singkat. “Kalian cepat siap-siap, habis ini kita ke rumah sakit. Malam ini menginap di sana.”
Aku memandang Torik. “Tadi kau berani sekali, bergulat dengan monster seperti itu. Kalau tidak ada kau, entah apa yang akan terjadi, aku tak berani membayangkannya.”
Dia angkat bahu. “Aku sendiri juga tak tahu kenapa aku menerjang buaya itu. Mungkin insting yang mendorongku berbuat begitu.”
Ambulans datang tak lama kemudian, sirenenya meraung-raung saat mobil putih itu membawa kami ke sebuah rumah sakit di Bandar Lampung. Kami menunggu dengan cemas di ruang tunggu IGD. Nasuti menggigit bibir sambil mondar-mandir. Hana meneteskan air mata, lalu menyembunyikan wajah di balik saputangan. Igo terus mengomeli Zhen yang tampak pasrah. Setelah sekitar setengah jam yang terasa sebulan, akhirnya dokter keluar dan kami segera merubunginya. Dengan raut tenang, Dokter menjelaskan bahwa Harto baik-baik saja. Lukanya tak terlalu parah dan tak sampai menembus tulang, tapi dia harus dirawat inap setidaknya enam hari sampai lukanya kering. Kami lemas sekaligus kecewa mendengarnya.
“Perjalanan kita tertunda dong,” kata Nasuti.
“Tak mungkin kita meninggalkan Harto sendiri,” kataku.
“Kita akan menunggu,” Torik memutuskan, “sampai dia sembuh.”
“Ini semua salahmu, Zhen!” Igo menyembur. Sudah lama tak kulihat sifatnya yang beringas. Bosan terus-menerus dituding tanpa henti, Zhen mulai naik pitam. Ia bangkit.
“Berhentilah mengeluh! Memang benar ini salahku karena meninggalkannya, tapi kau juga tak ada bedanya kan? Kenapa tadi kau diam saja, bukannya langsung menolong?”
“Siapa yang diam saja? Kau tidak dengar tadi aku teriak minta tolong? Lagipula kau yang iseng mendorongnya jatuh kan?”
“Sudah, hei, hentikan!” Torik bangkit dari diamnya. “Pertengkaran tidak menghasilkan apa-apa. Jadi lebih baik tenangkan diri kalian, oke?”
“Ingat, ini rumah sakit, jangan berisik,” Nasuti menambahkan.
Setelah berunding, kami akhirnya memutuskan berpisah jalan lebih awal. Kelompok Zhen akan melanjutkan ekspedisi, sementara aku, Igo dan Nasuti akan menunggu Harto pulih. Torik kuminta ikut kelompok Zhen untuk menggenapkan jumlah anggota, biar sama-sama empat orang. Selain itu aku berpesan agar dia menjaga Hana, barangkali Muqodas atau Zhen berbuat macam-macam. Sore itu kami lepas keberangkatan mereka dengan berat hati.
“Berat rasanya meninggalkan kalian,” Torik merangkulku.
“Hati-hati, jaga diri kalian baik-baik,” aku menyalami Zhen dan Muqodas. Mereka tampak prihatin, tak sanggup melontarkan sepatah kata pun.
“Semoga cepat sembuh,” kata Hana lembut. Di tempat tidur, Harto menanggapinya dengan senyum lemah. Kaki kirinya yang diperban diangkat tinggi-tinggi dan digantung dengan sebatang tiang besi. Jika disentuh sedikit saja pasti dia menjerit-jerit.
“Nanti setiap kalian transit di suatu kota, jangan lupa upload foto di facebook ya, agar kami bisa memantau lokasi kalian,” Zhen memberi ide, dan aku mengangguk. Dia merogoh tasnya, lalu mengulurkan kartu nama padaku. “Ini nomor kontak perusahaan travel kakakku. Kalau kalian butuh tumpangan atau kesulitan mencari tempat menginap, hubungi saja nomor ini. Jaringan perusahaan kami tersebar di banyak kota, berafiliasi dengan beberapa hotel berbintang dan jasa penyedia transportasi darat dan laut. Perusahaan kami bahkan punya pesawat pribadi kalau kalian mau berpindah pulau dalam waktu singkat. Jangan khawatirkan biayanya. Khusus ekspedisi ini, semuanya gratis.”
“Ya, terima kasih banyak,” kataku.
Kami mengantar mereka hingga pelataran rumah sakit, melambai saat bus umum yang mereka tumpangi menjauh. Rasanya ada perasaan aneh yang hinggap saat melihat kepergian empat rekan kami itu, seperti sebuah kekosongan. Akhirnya tinggal kami berempat yang tertinggal di sini. Jika menunggu Harto sembuh, tenggat waktu 80 hari yang kami rencanakan akan berkurang sia-sia. Artinya nanti hanya beberapa kota saja yang bisa kami singgahi.
“Eh, kayak apa sih rasanya digigit buaya?” aku menggoda Harto.
“Kenapa, kau mau coba?” katanya, nyengir jail.
“Kau ini Lut, digigit tokek saja sakit, apalagi buaya,” Igo terbahak.
Malam itu kami menginap di rumah sakit, menggelar tikar yang dipinjam dari pos satpam, meringkuk berdesakan di lantai. Kami tak bisa tidur karena setiap beberapa detik selalu diganggu suara Harto yang mengerang diselingi dengkuran. Entah apa yang ada dalam mimpinya. Selain itu kadang terdengar juga sayup-sayup jeritan pasien sakit saraf di ruang sebelah, di bagian kejiwaan, dan yang paling mengerikan adalah suara rintihan yang lamat-lamat terdengar dari ruang operasi. Karena malam begitu sunyi, suara apapun terdengar jelas termasuk gemerisik dedaunan di kejauhan. Mungkin rintihan itu berasal dari pasien yang kakinya diamputasi, dan mungkin dosis obat biusnya kurang akibat salah perhitungan sehingga si pasien masih merasa sakit.
“Mungkin itu ulah dokter magang atau dokter yang tidak kompeten,” Igo berkomentar. “Ayahku bilang, dokter semacam itu tak memedulikan keselamatan pasien dan hanya mementingkan gaji, sehingga mereka bisa jadi melakukan malpraktek. Kalau aku bertemu dokter semacam itu, ingin sekali kutarik telinganya, lalu kubisiki, ‘Dok, mending sekolah lagi aja sono!’ Nah, puas aku.”
“Guyonannya Pak Aris tuh,” kata Nasuti. “Dosen mikrobiologi, ya kan?”
“Ya, dulu beliau pernah bermasalah dengan dokter magang,” kataku. “Gimana kabar para dosen kita ya? Aku kangen sama Pak Agus Nuryanto, wakil dekan sekaligus dosen serba bisa yang mengajar banyak mata kuliah...”
Kami menoleh saat Harto mengigau, “Ayah... Ibu...” Entah dia bermimpi apa. Sekilas aku melihat segaris air mata mengalir dari matanya yang terpejam. Kami saling pandang. Khawatir mengganggu, akhirnya kami menghentikan obrolan dan tidur.
Esok paginya, perasaan bosan mulai menyerbu kami. Duduk di tempat yang sama selama berjam-jam dan mendengar keluhan Harto membuatku merasa penat. Tiga kali sehari, seorang perawat akan datang mendorong troli yang mengangkut berpiring-piring makanan. Biasanya Harto langsung menjulurkan leher begitu terdengar suara roda yang didorong, meski troli itu masih jauh dan bahkan belum sampai kamar sebelah. Makanan khusus pasien ini biasanya berupa bubur, daging ayam atau ikan, tahu tempe, dan sayuran. Harto makan dengan lahap sambil nyengir menatap kami bergantian. Sikapnya sama sekali tak kelihatan seperti seorang pasien yang menderita. Ia malah senang dilayani dan diperlakukan istimewa, membuat kami jengkel karena dia sering melunjak dan minta dibawakan ini-itu seenaknya.
Siangnya, kami berkeliling rumah sakit untuk mengusir bosan. Saat melihat bahwa mayoritas pasien adalah pengidap penyakit paru-paru, Igo langsung menceramahi kami. “Ini semua gara-gara rokok. Lihat, rumah sakit ini isinya hampir semuanya perokok. Sudah kubilang kan, rokok itu salah satu pembunuh paling berbahaya yang dibiarkan berkeliaran bebas. Ah, andai saja aku jadi presiden, pasti sudah kugulung semua pabrik rokok di negeri ini dan kuganti dengan pabrik permen!”
Selain itu, banyak hal mengharukan yang kami temui di tempat ini. Kami tertegun sejenak melihat seorang gadis terisak di atas tubuh seorang pemuda yang tak sadarkan diri. Dari monolognya, kami tahu sebentar lagi mereka akan menikah, tapi dibatalkan karena si pemuda terserang tumor ganas. Di depan pemuda yang terbaring koma itu, sambil berurai air mata sang gadis berjanji akan selalu menemaninya, tak akan meninggalkannya walau hanya sesaat, dan tabah menunggunya hingga sembuh. Ia berjanji tak akan berpaling pada pria lain dan rela menerimanya walau si pria menjadi cacat sekalipun. Kami meninggalkannya sambil menutupi wajah, malu dan terharu. Aku jadi teringat teman wanita yang kulamar saat kuliah dulu. Aku sih jangankan terkapar di rumah sakit. Selagi aku sibuk mengumpulkan uang untuk modal nikah saja, dia malah cari pria lain yang lebih mapan. Dasar belum jodoh.
Satu lagi yang membuat kami merinding adalah pasien di kamar sebelah kami, seorang nenek tua yang sudah pikun. Kemarin malam, kami selalu menutup telinga karena keluarga yang membesuknya marah-marah gara-gara si nenek sering mengompol. Paginya, si nenek berkelejat saat menjalani sakaratul maut, dan keluarganya baru melolong penuh penyesalan saat si nenek meninggal. Kami berempat termasuk Harto terdiam. Ini pertama kalinya dalam hidupku menyaksikan kematian secara langsung.
“Bagaimana perasaannya, Mas?” sapa dokter berwajah ramah yang merawat Harto. Stetoskopnya mendarat di beberapa titik di dada Harto, dan sesekali ia menekan betis Harto dengan ibu jarinya. Wajahnya bercambang dan pakaiannya yang putih bersih membuat dokter ahli tulang ini tampak gagah. Nama dokter ini Rangga Bambang Kuncoro. Setelah dokter itu pergi, Harto malah meledek namanya yang lucu.
Baru tiga hari terbaring, Harto sudah merasa bosan. Tampaknya dia lelah harus terus terbaring dan selalu dipapah ke kamar kecil. Bekali-kali dia mengeluh ingin segera pergi dari tempat yang mengungkung kebebasan ini.
“Kita kabur saja yuk!” katanya sore itu. Kami terperanjat mendengarnya. “Sudah pegal badanku, tak tahan begini terus. Nanti malam kalau sudah sepi, kita lari lewat tembok belakang. Bagus kan ideku?”
“Kau ini tak sabaran ya,” kata Igo. “Tunggu saja sampai kakimu sembuh.”
“Kalau kelamaan di sini, nanti kita ketinggalan dari kelompok Zhen,” Harto berdalih. “Waktu kita bisa habis percuma.”
“Kabur dari rumah sakit benar-benar ide gila!” kata Nasuti serius. “Tapi fantastis, layak dicoba! Kalau aku, pasti sudah kulakukan sejak kemarin.”
“Kenapa malah didukung? Dasar pemberontak!” Igo melirik kesal Nasuti.
Kami bersikeras memaksa Harto beristirahat, khawatir pada kondisi fisiknya dan takut lukanya akan menghambat perjalanan kami. Tapi karena Harto terus mendesak kami, bahkan mengancam akan kabur sendirian di tengah malam, akhirnya kami kabulkan juga permintaannya. Yah, dengan berat hati. Malam itu, saat nampaknya sudah sepi, diam-diam kami lepas semua peralatan yang menempel di tubuh Harto, termasuk selang infus dan tali yang menggantung kakinya. Kulakukan semua ini dengan perasaan campur aduk.
“Jangan bilang-bilang ya,” bisik Harto pada seorang pasien yang terjaga. Pria yang terbaring terngkurap karena pantatnya bisulan parah itu hanya menatap kami heran. Harto berganti pakaian biasa agar tak terlihat seperti pasien, begitu juga kami yang menggendong ransel seperti keluarga yang sedang menjenguk. Setelah meninggalkan surat di atas ranjang, Nasuti berjalan di depan, menjulurkan leher ke pintu, mengawasi situasi sementara aku dan Igo menopang tubuh Harto yang pincang.
“Aman, jalur bersih,” Nasuti berbisik seraya melambaikan tangan. Kami bergegas ke lorong sambil berjingkat. Tiba di tikungan, kami bersembunyi saat ada satpam dan perawat yang lewat untuk berjaga malam. Kami bersikap biasa dan pura-pura mengobrol, menunggu mereka pergi, lalu kembali mengendap-endap menyusuri lorong. Tak tampak satu orang pun selain dokter yang kelelahan keluar ruang operasi atau pasien tua yang kebingungan mencari kamar kecil. Setelah itu tak ada lagi rintangan yang berarti. Semua pertahanan rumah sakit kami terobos dengan mudah, karena sorenya Nasuti kutugaskan mencari jalur tercepat untuk kabur. Kami baru bernapas lega setelah berhasil mencapai bagian belakang gedung. Nasuti memanjat dinding untuk mencari jalur aman.
“Di bawah ada kebun. Kita bisa lewat jalan kecil yang ada di sana.”
Bersama, kami membantu Harto naik. Hal sama kami lakukan ketika menuruni sisi seberang dinding, lalu mendarat di tanah berumput yang cukup empuk. Setelah itu kami mengendap-endap melintasi pelataran kecil menuju jalan raya.
“Kau yakin dengan ini?” Igo berbisik. “Mereka pasti bakal mencari kita.”
“Iya, kayak maling aja, mengendap-endap begini,” kata Nasuti.
“Biarin aja, biaya pengobatan dan administrasi kan sudah dilunasi Zhen. Kehilangan satu pasien nggak bakal bikin mereka rugi. Mereka malah untung karena tak perlu repot soal jatah makanku.”
Kami berhasil mencapai jalan raya tanpa ketahuan. Tengah malam seperti ini, jalanan sepi sekali, sesunyi kuburan. Tak tampak satu pun kendaraan lewat. Untunglah masih ada taksi yang beroperasi hingga larut malam. Ini pengalaman pertamaku naik angkutan malam. Di mobil, kami tertawa-tawa puas karena berhasil meloloskan diri. Aku tak bisa berhenti tersenyum mengingat pengalaman gila kami kabur dari rumah sakit. Kalau ada yang melihat, tingkah kami yang mengendap-endap tadi pastilah konyol sekali. Ah, bodoh betul memang ide si Harto ini.
*****


 radenbumerang
radenbumerang





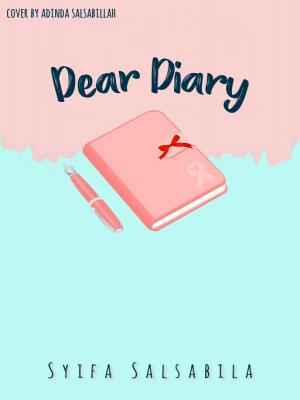




Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.