BAB 4. KISAH LUKISAN BIRU
Paginya, seusai shalat subuh kami langsung mandi dan berganti pakaian. Semua tampak bersemangat menghadapi hari kedua. Dengan menyewa kapal motor kecil, kami meluncur menuju Pulau Weh, pulau vulkanik kecil yang terletak di barat laut Pulau Sumatera, tepatnya di laut Andaman. Saat tiba di sana, aku tak sabar segera menginjakkan kaki di Sabang, kota terbesar di Pulau Weh sekaligus kota yang terletak paling barat di Indonesia. Kami berkumpul dan berfoto bersama di depan Tugu Kilometer Nol yang terkenal itu. Hari itu, impian kami menapaki ujung barat Indonesia telah tercapai.
“Dulunya pulau Weh pernah terhubung dengan Pulau Sumatera, namun kemudian terpisah oleh laut setelah meletusnya gunung berapi pada zaman Pleistosen,” kataku, membaca penjelasan yang ditulis ayahku dalam jurnalnya. “Pulau yang terkenal dengan ekosistemnya ini ditetapkan Pemerintah Indonesia sebagai suaka alam dan satu-satunya habitat bagi katak Bufo valhallae yang statusnya terancam. Berbagai spesies ikan termasuk hiu bermulut besar juga dapat ditemukan di sekitar terumbu karang yang mengelilingi pulau.”
“Ayahmu tahu banyak hal, ya?” kata Harto.
“Ya, beliau orang yang senang bertualang, lulusan fakultas biologi juga seperti kita. Dulu, beliau pernah berkeliling ke berbagai pelosok negeri untuk melakukan penelitian. Sebagai hasilnya, beliau menulis pengalamannya dalam buku ini.”
Saat matahari mulai meninggi, kami kembali ke daratan Aceh dengan perahu yang sama, kali ini menuju Pantai Lhok Nga yang terletak dekat Banda Aceh. Pantai ini tampak memesona sekaligus memilukan, terpaut antara keindahan alam dan trauma tsunami. Igo, Nasuti, dan Torik mendahuluiku berlarian di pantai berpasir dan asyik bermain air. Muqodas dan Zhen berlomba memanjat pohon kelapa, sementara Hana duduk berjemur sambil memandangi laut. Harto menarik-narik tanganku, tak sabar bergabung dengan yang lain. Namun perhatianku tertuju pada seorang gadis yang tengah melukis di pinggir jalan.
Gadis itu sibuk dengan kuasnya, tak sadar ketika aku dan Harto memerhatikannya. Saat kami mendekat, dia mendongak dan tersenyum. Aku menekap mulut, terkejut. Gadis ini tak punya kaki! Dia duduk tenang di kursi rodanya, tampak tak terganggu. Jemarinya yang cekatan melesat kesana kemari, menorehkan warna-warna membentuk pola yang awalnya tak kukenali, kemudian perlahan bisa kulihat sosok lautan biru megah membentang di atas kanvas, lengkap dengan pohon kelapa dan seekor burung camar tengah melipat sayap.
“Mau pesan lukisan Mas?” sapanya ramah.
“Oh, tidak, kami cuma mau lihat,” kataku. “Boleh kami duduk di sini?”
Gadis itu mengangguk. Dia melukis dengan bersemangat, seakan tak memungkiri bahwa dirinya seorang yang cacat. Kuduga dia bertahan sebagai pelukis jalanan untuk menyambung hidup dan meneruskan sekolah. Usianya mungkin hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Ujung jilbabnya bergoyang-goyang saat dia sesekali mendongak menatap laut, lalu kembali ke kanvasnya untuk melukiskan apa yang dilihat.
“Saya selalu mencintai laut,” katanya. “Laut itu indah dan luas. Kadang tenang dan kadang bergelora. Laut menyimpan sejuta misteri yang menarik.”
“Wah, keren. Siapa namamu?” tanya Harto.
Cut Meutia,” jawabnya sambil tersenyum.
“Boleh kurekam? Rencananya kami mau membuat film dokumenter, dan kupikir bagus kalau ada adegan wawancara dengan penduduk lokalnya. Siapa tahu kamu jadi terkenal,” Harto nyengir seraya mengeluarkan handycam. Meutia mengangguk, tak keberatan.
Melihatnya melukis, aku juga tertular ingin melakukan hal sama. Tanpa sadar, segera saja kukeluarkan sebatang pensil, selembar kertas putih kosong dan buku tebal sebagai alas. Begini-begini, aku juga seorang seniman. Bersama-sama, kami melukis dalam diam. Meutia melihat aksiku dan tersenyum. Aku melukis dengan imajinasiku, mencoretkan ide-ide yang muncul dalam benak sejak aku melihat gadis ini melukis. Meutia mencoba melongok lukisanku, tapi tak kubiarkan gadis ini melihatnya sebelum karyaku selesai. Sambil bekerja, kami mengobrol panjang lebar. Meutia dengan senang hati bercerita tentang masa lalunya, dan aku dengan sabar mendengar penuturannya. Kisah ini mungkin sudah ratusan kali ia ceritakan pada para pelanggannya. Mungkin bisa kujadikan pengalaman berharga.
“Akhir Desember 2004, sebelum tsunami terjadi. Cuaca sangat cerah dan tak ada satupun mendung yang tampak di langit. Aku sedang bermain saat itu, bersama adikku yang masih kecil. Ibuku memanggilku dari dapur, memintaku segera menghampirinya. Dulu aku anak yang manja. Aku agak kesal karena merasa terganggu saat sedang asyik bermain. Kami berdua menghampirinya. Ibuku seorang wanita muda yang periang dan murah senyum. Saat kami muncul di pintu dapur, ia tersenyum, tampak menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Aku tiba-tiba ingat, hari itu adalah hari ulang tahunku! Aku melompat girang dengan tak sabar, dalam hati menduga-duga hadiah apa yang akan diberikan ibuku. Ibu menyuruhku menutup mata, lalu meletakkan kotak besar yang dihiasi pita di pangkuanku. Adikku, Dina juga kebagian hadiah. Kutimang kotak itu, menduga-duga isinya, lalu kurobek bungkusnya dengan tak sabar dan segera kubuka.”
Meutia menarik napas dalam, kemudian melanjutkan, “Aku kecewa. Itu bukan boneka yang kuinginkan. Bonekaku jelek dan murahan, rupanya Ibu membelinya dengan uang sisa belanja. Kulihat hadiah adikku. Aku lebih kesal lagi karena bonekanya lebih bagus. Aku menangis. Aku marah pada Ibu, menuduhnya lebih menyayangi Dina daripada aku. Padahal saat itu hari ulang tahunku. Ibu sudah mengacaukan semuanya.
“Aku merobek boneka baruku hingga kepalanya putus, lalu aku berlari meninggalkan rumah, tak memedulikan suara ibu yang memanggil berkali-kali, khawatir. Aku meringkuk di balik dinding tempat biasa kami bermain petak umpet. Aku menangis, tak peduli jika ada yang mendengar atau memergokiku seperti itu. Kulihat Dina datang menyusul, mengepit bonekanya di ketiak. Dengan wajah polos, Dina bilang bersedia menukar hadiahnya denganku. Aku masih kesal, dan aku tak peduli. Kurebut boneka di tangannya, kucampakkan ke tanah berlumpur. Dina menangis melihat bonekanya kotor. Tapi aku tak peduli. Kutinggalkan Dina sendirian dengan bonekanya. Aku terus berlari hingga tiba di pantai. Aku berteriak sekeras-kerasnya, memprotes bahwa dunia ini tak adil.”
Meutia berhenti menorehkan kuasnya, mendongak menatap laut, seakan berusaha menarik ingatan sepuluh tahun silam itu langsung ke hadapannya, dan membagi sensasinya pada kami. Ekspresinya bagai pemain teater kawakan, begitu natural dan memikat, membuat kami penasaran dengan lanjutan kisahnya. Tatapannya kosong dan menerawang.
“Dan kemudian bencana itu datang...
“Aku terbelalak saat melihat laut. Ombak setinggi puluhan meter datang bergulung-gulung. Awalnya aku tak percaya pada apa yang kulihat. Aku tak bisa bergerak karena takut. Aku kira kiamat datang. Dengan ganas, gelombang itu menerjang apa saja yang ada di hadapannya. Gedung-gedung besar, mobil, sawah, rumah-rumah, semua habis dilahapnya tanpa kenal ampun. Aku berlari sekuat kakiku bisa membawaku. Aku menemukan adikku di tempat aku meninggalkannya. Dina masih berjongkok, menutup mata karena takut. Kuajak dia meninggalkan tempat itu, langsung menuju rumah. Namun ibuku tak ada, dan Dina menangis lagi. Aku berteriak memanggil Ibu, tapi tak kutemukan ia di manapun. Mungkin ia pergi mencari kami. Aku sangat menyesal sudah marah padanya.”
Aku dan Harto terkesima mendengar penuturan Meutia. Wajah gadis ini datar namun kami tahu ada kesedihan jauh di dalam hatinya. Mendengarnya berkisah, kami merasa seakan menyaksikan langsung kejadian naas tersebut. Tanpa sadar tanganku berhenti bergerak di atas lukisanku yang hampir selesai. Kami berapi-api, tak sabar mendengar kelanjutan ceritanya yang semakin seru.
“Terus gimana?” pancing Harto, sambil terus merekam.
“Ombak itu semakin mendekat. Orang-orang berlarian panik. Kuajak Dina berlindung di dalam mobil, meskipun tahu akan percuma saja. Kurasakan gelombang itu mengangkat mobil yang kami tumpangi, lalu melontarkannya entah sejauh mana. Aku masih memeluk Dina erat-erat. Mata kami dipejamkan rapat-rapat. Mobil kami terasa berputar-putar, beberapa kali membentur benda keras hingga kami pusing. Kurasakan air memenuhi paru-paru, tapi kami tetap bertahan. Ketika kami merasakan mobil ini terdampar di suatu tempat, kami merangkak melewati kaca mobil yang pecah, mendapati diri berada tak jauh di depan masjid Baiturrahman. Meski limbung dan tergores-gores, sungguh ajaib kami bisa selamat setelah diombang-ambingkan di dalam mobil.
“Aku berlari ke dalam masjid, meringkuk di sudut saat terdengar gemuruh mengerikan monster kelaparan di luar sana. Aku tak mau menyerahkan nyawa padanya, tak ingin menyerah. Dalam hati, aku kagum pada masjid ini yang tak sedikitpun mengalami kerusakan walau menghadapi terjangan tsunami, sementara bangunan-bangunan lain di sekitarnya hancur lebur tak tersisa. Aku menoleh ke samping, terkejut, menyadari bahwa adikku tak ada. Pasti Dina terpisah saat melarikan diri. Tak ingin kehilangan dia, aku pergi meninggalkan perlindungan masjid dan keluar mencarinya.
“Aku memanggil-manggil hingga suaraku serak. Langit begitu gelap hingga aku tak bisa melihat keadaan sekitar. Akhirnya kutemukan adikku bersembunyi di sebuah gudang yang terendam air, gemetar kedinginan sambil menangis. Aku menghampiri dan memeluknya, tapi bencana lain datang ketika gudang bergemuruh dan air membanjir masuk entah dari mana. Beberapa bongkahan beton berjatuhan di sekitar kami, salah satunya memblokir pintu sehingga tak ada jalan keluar. Kami terjebak, dan air yang meluap perlahan semakin meninggi. Guncangan susulan sekali lagi menghancurkan langit-langit, dan aku menjerit kesakitan saat kakiku terjepit lempengan baja. Adikku tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Kucoba mengangkat baja itu namun tak kuasa. Baja bekas penyangga beton itu terlalu berat. Akhirnya aku terpaksa melakukan cara terakhir. Setelah menguatkan diri, kuhentakkan kaki dan kutarik sekuat tenaga. Kedua kakiku terbebas, tapi juga meninggalkan luka menganga yang cukup lebar.”
Aku dan Harto menekap mulut, sungguh kejadian yang amat tragis.
“Adikku menangis melihat kakiku yang berdarah-darah. Air keruh yang mengepung kami berubah warna menjadi merah. Aku pasti mati kalau saja tidak membebat lukaku dengan kain yang kurobek dari jaketku. Kami terjebak selama berhari-hari. Air yang meluap tampaknya tidak bertambah tinggi, namun ketinggiannya hampir mencapai langit-langit. Aku harus menjaga kepalaku tetap di permukaan untuk memperoleh oksigen. Kebetulan beton di atasku berlubang kecil. Aku merasakan kematian semakin mendekat. Kami kelaparan, sesekali bersyukur saat ada sebungkus roti yang mengambang di dekatku. Roti bulukan itu kubagi dua dengan adikku, walau rasanya tak karuan tapi setidaknya cukup untuk mengganjal perut. Aku bersyukur Tuhan masih mengirimi kami rezeki. Kami juga terpaksa minum dari air keruh yang merendam kami. Rasanya asin tak karuan. Perutku sakit, aku mencoba bertahan, tapi adikku tak sanggup lagi.”
Meutia mengusap mata dengan punggung tangan, menunduk dalam-dalam.
“Dia meninggal dalam pelukanku. Tubuhnya dingin dan pucat, namun wajahnya tenang tanpa dosa seperti bayi baru lahir. Aku tahu Dina sudah tiada, tapi tetap saja kupeluk dia, tak kubiarkan kedalaman air yang keruh menelan tubuhnya yang mungil. Aku sangat menyesal sudah mencampakkan bonekanya.”
Tanpa terasa air mataku mengalir. Di sebelahku, Harto terisak dan mengusap mata dengan sapu tangan. Handycam-nya sedikit bergetar.
“Aku terus menunggu, namun tak ada seorangpun yang datang menolong. Tubuhku semakin lemah akibat kelaparan. Aku semakin sulit untuk mempertahankan tubuh agar tetap mengambang. Rasanya aku semakin dekat dengan kematian. Sebentar lagi mungkin aku akan menyusul adikku. Aku berdoa dalam hati, hingga akhirnya di hari kelima kudengar ada yang berteriak-teriak di atas, kemudian suara langkah-langkah kaki. Akhirnya pertolongan datang. Aku mencoba berteriak, namun suaraku terdengar lemah. Tak putus akal, aku membunyikan peluit pramuka yang selalu kubawa di saku. Peluit itu berbunyi lemah, kubunyikan sekali, dua kali, tapi masih belum terdengar tim pencari.
“Barulah setelah perjuanganku meniup kesepuluh kalinya, ada petugas yang melongok dari lubang di atasku. ‘Suaranya dari bawah sini,’ begitu katanya, memanggil tim SAR lain. ‘Ada orang di dalam?’ panggilnya berulang-ulang, namun hanya kujawab dengan tiupan peluit. Saat mengira orang itu akan pergi, aku menjulurkan jariku ke sela-sela lubang, mencoba melambai. Akhirnya petugas itu menyadari keberadaanku dan mencoba membantuku keluar dengan membongkar lapisan beton. Mereka berhasil membawaku keluar dengan selamat, bersama dengan jasad Dina yang masih kudekap erat tanpa mau kupisahkan. Mereka iba padaku dan berbelasungkawa atas nasib Dina. Seseorang menutupi tubuh kaku adikku dengan kain, dan aku hanya bisa menatap pilu. Aku tak bisa berpikir jernih seakan mati rasa. Aku merasa seseorang memberiku makanan, dan langsung kusambar dengan rakus tanpa memerhatikan. Rasa sakit tak tertahankan menjalar dari kakiku yang terluka parah. Seseorang berkata kakiku harus diamputasi untuk mencegah infeksi.
“Kemudian aku teringat ibuku. Tenagaku seakan pulih kembali ketika aku berdiri dan berjalan terpincang-pincang. Tim penyelamat berusaha mencegah, tapi aku menerobos mereka dan memaksa pergi. Ketika keluar dari tenda darurat, aku seakan melihat mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupku.”
Meutia memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam.
“Dunia seakan hancur. Aku ngeri melihat pemandangan kota yang tak lagi kukenali. Semua hancur lebur, tak ada bangunan utuh yang tersisa sejauh mata memandang. Kuseret-seret kaki untuk mencari ibuku. Entah berada di mana ia sekarang. Seorang petugas yang bersimpati membantuku mencari Ibu. Mereka membongkar reruntuhan untuk mencari siapa saja yang masih hidup, namun yang ditemukan hanya mayat-mayat. Hatiku seakan teriris melihat mereka, sosok-sosok tak bernyawa yang wajahnya menyiratkan kengerian mendalam, dengan posisi tangan dan kaki yang menikung ganjil dan sudah kaku. Pakaian mereka basah dan ternoda oleh lumpur dan darah. Sebagian dari mereka dalam kondisi utuh, namun ada juga yang hancur karena tertimpa bangunan, dan bahkan ada yang wajahnya tak bisa dikenali lagi. Aku khawatir ibuku bernasib seperti mereka, tapi kubuang pikiran itu jauh-jauh.
“Pencarian dilakukan selama berhari-hari, namun ibuku tetap tak ditemukan. Aku menangis sejadi-jadinya, tak mau menerima kenyataan. Ibuku tak mungkin sudah meninggal. Kulihat sesosok boneka tersangkut tak jauh di dekat kakiku, hanyut terbawa air. Kuambil boneka itu, yang langsung kukenali sebagai boneka pemberian Ibu. Rupanya Ibu berbaik hati menjahitkannya untukku, memperbaiki robekan yang kubuat. Ibu pasti berharap aku segera pulang dan merayakan ulang tahunku dengannya. Aku memeluk boneka itu erat-erat dan menangis. Aku terus berteriak, aku bersedia menerima apapun pemberiannya. Bahkan aku tak peduli meski Ibu tak memberiku hadiah ulang tahun sekalipun, asal Ibu selalu bersamaku. Aku hanya ingin ibuku kembali. Aku menyesal karena saat terakhir bertemu aku marah padanya. Kini, takkan ada lagi kehangatan Ibu, dan tak ada lagi yang memasak makanan favoritku. Kini aku hidup sebatang kara dan harus berjuang sendirian. Andai saja ibuku tak pergi secepat itu... Adikku juga meninggal gara-gara kesalahanku. Betapa hina dan berdosanya diriku ini. Aku anak durhaka. Aku tak bisa memaafkan diriku.”
Meutia menghentikan ceritanya. Kulihat air matanya merebak, lalu cepat-cepat diusapnya. Kejadian itu telah bertahun-tahun berlalu, namun masih seperti kemarin sore baginya. Ia telah menempuh hidup yang berat seorang diri tanpa merasakan kehangatan keluarga, namun ia tak sedikitpun patah semangat dan selalu melihat ke depan, berusaha sekuat tenaga menghilangkan trauma masa lalunya. Lagi-lagi aku ingin menangis dibuatnya. Meutia memerhatikan itu.
“Maaf, jadi terbawa suasana,” katanya, menunduk sebentar, terlihat menulis sesuatu, kemudian lukisan yang sudah selesai diangkatnya dan diserahkan padaku. “Ini untuk Mas berdua. Sebetulnya ini pesanan orang, tapi saya bisa membuat yang baru. Silakan, ambil saja, gratis dari saya. Anggap saja ucapan terima kasih karena telah menemani saya melukis.”
“Eh, yang benar? Terima kasih,” kataku. Sebetulnya kami ingin menolak, tapi tak bijak rasanya jika menolak kebaikan Meutia yang tampak tulus itu. Bisa dikira aku tak menghargai karyanya. Kujejalkan kain kanvas seukuran kertas A3 itu ke dalam ransel yang sesak.
“Oh iya, kelas berapa kamu sekarang?” tanya Harto.
“Kelas tiga SMA Mas,” jawab Meutia. “Karena saya hidup sendirian dan tak punya kerabat, biaya sekolah saya tanggung sendiri. Alhamdulillah, meski penghasilan saya sedikit, masih bisa mencukupi kebutuhan hidup.” Dia diam sejenak. “Saya tidak mengeluh dengan kondisi ini, meski kadang timbul perasaan rindu. Saya ingin bisa berjalan kembali, dengan kaki saya sendiri,” gumamnya.
Aku dan Harto menatapnya iba, melihat kerinduan teramat dalam di matanya. Harto paling mengerti perasaannya, karena dia pernah mengalami hal yang sama saat kedua orangtuanya dibunuh di depan mata. Harto mengusap matanya lagi. Meutia sedang sibuk membereskan perlengkapan melukisnya. Aku mengamati lukisan buatanku, puas dengan hasilnya. Akhirnya kuberikan lukisan yang sejak tadi kusembunyikan ini padanya. Lukisanku tampak nyata persis model aslinya, salah satu karya terbaik yang pernah kubuat. Saat melihat lukisanku, mata Meutia melebar terharu.
“Lihat, ini kamu, dan kamu punya kaki,” kataku sambil tersenyum. “Anggap saja hadiah ulang tahun dari saya, meski sekarang bukan Desember.”
Kuberikan lukisan itu padanya, yang dibalas dengan beribu terima kasih. Kebahagiaan terpancar di wajahnya, terutama karena melihat lukisan dirinya dalam kondisi fisik yang utuh, lengkap dengan kedua kakinya. Aku juga memberinya beberapa lembar uang sebagai bayaran lukisannya. Awalnya dia menolak, tapi setelah kupaksa akhirnya diterima juga.
“Mas baik sekali, meski baru kenal,” matanya berbinar-binar.
“Anggap saja impas,” aku tersenyum.
“Lukisan Mas bagus, realistis. Mas lulusan sekolah kesenian?”
“Oh tidak juga, pamanku yang mengajari melukis.”
Meutia kembali membereskan peralatannya. Harto berbisik padaku, “Hebat ya dia, hidup serba kekurangan tapi bisa bekerja dengan penuh semangat. Kita seharusnya bersyukur karena diberi kecukupan dan kondisi fisik yang utuh tanpa cacat.”
“Iya, kau benar. Kita harus meneladaninya. Gadis ini seorang pekerja keras. Dia bukan pengemis yang hanya bisa bergantung pada orang lain, tanpa ada usaha sama sekali.”
“Kata-katamu kemarin benar, Lutfi. Baru sehari perjalanan, kita sudah dapat hikmah berharga. Dan kita mendengar kata-kata mutiara itu dari pelukis muda yang hebat ini.”
Aku mendekati Meutia saat gadis itu selesai berbenah dan duduk tenang di kursi rodanya. “Jika melihat kerja keras yang kaulakukan, ibumu pasti bangga dengan prestasimu. Adikmu juga pasti bahagia sekarang.”
Dia mengangguk, tersenyum, lalu berpaling menatap lautan luas. Ombak berdebur pelan menyeret pasir, menghantam karang. Angin berhembus pelan meniup rambut kami. Laut itu tampak indah sekaligus menakutkan. Laut biru yang sama dengan sepuluh tahun lalu. Laut yang dia cintai, tapi juga merenggut nyawa orang yang dikasihinya. Aku ikut menatap laut. Nasib kami sama, memiliki anggota keluarga yang hilang tak diketahui kabarnya. Tapi aku beruntung karena masih memiliki keluarga.
Mendadak aku teringat ibuku di rumah. Langsung saja kuraih HP dan kutelepon ibuku. Beliau kaget karena aku tiba-tiba menanyakan kabar, padahal kami baru satu hari berpisah. Aku senang mendengar suaranya, terasa dekat walau kami berjauhan. Ikatan darah kami tak akan pernah terpisahkan. Tiba-tiba, ingatanku terbang ke masa yang lalu, kenangan indah yang aku sendiri sudah lama melupakannya. Sebuah ingatan samar yang hanya bisa kurasakan lewat batin kecilku, sisa-sisa pengalaman yang meresap dalam pori-pori kulitku saat Ibu mengenalkanku pada dunia. Aku teringat saat sembilan bulan Ibu mengandungku dalam perutnya, menahan sakit luar biasa ketika melahirkanku. Atau saat ia menimangku dalam pangkuannya, dengan lantunan nina bobo dan doa penuh kasih sayang yang masih terngiang hingga kini. Atau saat ia rela kedinginan dan tidak tidur di malam hari, hanya demi menjaga diriku yang sedang sakit. Kasih sayang seorang ibu memang sepanjang masa, tak tergantikan oleh apapun. Dalam hati aku beruntung masih memiliki ibu. Jika Ibu ada di hadapanku, pasti sudah kupeluk dan kucium kakinya saat ini juga.
“Doakan aku terus ya Bu. Assalamualaikum.”
Aku menutup telepon dengan perasaan lega. Dalam hati aku bertekad, sejauh apapun aku merantau, ke manapun aku pergi, aku tak akan pernah menjadi Malin Kundang. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ketika Rasulullah ditanya tentang siapa orang yang paling pantas kita hormati, beliau menjawab, “Ibu... ibu... ibu... dan ayah”. Ibu disebut hingga tiga kali. Artinya, ibu memang orang yang paling besar jasa dan pengorbanannya untuk kita. Jangan pernah sekali-sekali kita berani menyakiti hati orangtua kita. Jangan pernah kita membantah apalagi menghardik mereka, karena dengan berbuat demikian, maka sama saja kita mengundang murka Tuhan dan memesan tiket ke neraka. Sampai kapanpun, aku tak akan lupa tanah airku sendiri, dan aku tak akan melupakan jasa orang yang telah membantuku mengenal dunia. Dialah malaikatku: Ibu.
*****


 radenbumerang
radenbumerang





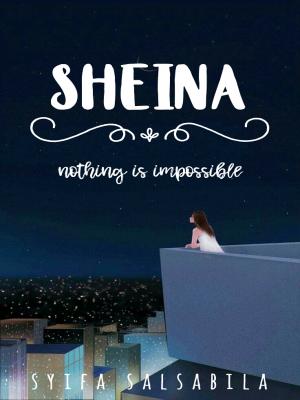

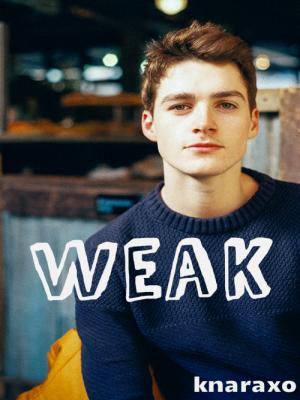


Iya juga yah, satu bab aja sepanjang ini... makasih masukannya Mas AlifAliss, mungkin ke depannya saya bagi per bab aja biar lebih pendek.