Usai berpamitan pada muridku dan orang tuanya, aku bergegas keluar. Ah, membungkukkan badan demi meraih sepatu serasa menekuk usus-usus perutku. Nyeri kembali berdenyut-denyut. Selesai memakai sepatu dengan susah payah, kulangkahkan kaki menyusuri jalan setapak yang kanan kirinya dipagari got. Aih, baunya yang busuk semakin membuat muak perutku. Kalau bisa, kutangkupkan jari-jariku di hidungku biar jadi masker. Namun, muak perutku yang sudah semakin menyetrum kesadaran, membuat dua tanganku menekan-nekan dinding terluarnya. Tekanan yang kuibaratkan belaian diiringi rayuan, "Tenanglah darah-darah di dinding rahimku. Aku tahu kalian ingin keluar sebab tak ada sperma yang membuahi kalian. Kumohon, mengelupaslah dengan santun. Aku masih di jalan. Keributan kalian bisa membuatku terkapar di tengah jalan seperti korban tabrak lari."
Lima menit kemudian, langkahku sampai di Jalan Raya Halimun. Ada pangkalan tukang ojek di pinggiran jalan, dekat gang yang baru saja kulewati. Aku mematung di pinggiran memikirkan berbagai cara untuk sampai ke Stasiun Manggarai. Tidak ada cara lain menuju stasiun kecuali naik ojek. Kopaja dan angkot memang lebih nyaman. Setidaknya, aku bisa duduk bersandar mengistirahatkan perutku. Namun, mereka lama datang. Aku tak sanggup berada di terik terlalu lama sementara kesadaranku low dan tidak bisa dicharg sewaktu-waktu sebab tidak ada powerbank. Baiklah, kali ini aku harus naik ojek, mengorbankan 15.000 berhargaku yang dengannya aku bisa makan ayam penyet terenak di Kober.
Aku melangkahkan kaki menuju pangkalan ojek.
Aish, yang benar saja aku mau naik ojek. Sementara kurasakan ada yang mengalir lembut di tengah-tengah tubuhku, di bawah pusarku. Ingin kutahan. Namun, ini bukan kencing. Aku tak punya saklar untuk menghentikan paksa. Kubayangkan cairan yang berjatuhan dari tempatnya berasal ke celana dalamku, ke celana rangkapku, lalu ke rokku. Tentu saja berjatuhan sebab tak ada penahan yang bisa merembaskan cairan-cairan itu ke rumah empuknya. Mana kutahu tamu-tamuku akan datang hari ini.
Aku tidak bisa naik ojek. Bahkan bila aku punya uang banyak lalu naik taksi pun tak bisa. Ah, tamu-tamuku terlalu banyak. Aku tidak bisa meninggalkan mereka di jok motor atau jok taksi. Tidak semua orang mau menerima kehadiran tamu-tamuku.
Aku memutar badan. Kulangkahkan kaki dengan gontai. Aku harus berjalan dengan kakiku. Kutekan perutku dalam-dalam. Aku bisa merasakan ada yang begemuruh di dalamnya. Setiap kelupasan darah serasa mengirimkan sinyal nyeri ke sekujur tubuhku. Tubuhku bergetar. Keringat dingin mulai membasahi bagian-bagian tertentu tubuhku. Aku mulai merasakan betapa beratnya beban di tas punggungku. Bahkan angin yang lembut pun mampu kusapa lebih lama.
Aku merinding. Kacamata tak lagi bisa memperjelas apa yang kulihat sebab otak-otak di kepalaku terlalu sibuk mengirimkan sinyal nyeri ke sekujur tubuhku. Ah, di hari pertama kedatangan mereka memang selalu seperti ini. Aku terus berjalan menyusuri trotoar. Beruntung, trotoar cukup lebar sehingga aku leluasa untuk memompa udara segar. Biar paru-paru mengirimkan jamuanku ini pada tamu-tamu di rahimku.
Masih 2 kilometer jalan yang harus kulalui untuk sampai di stasiun. Please, aku bukan pelari maraton atau peserta jalan sehat. Aku pasien. Aku pasien, harus menebas jarak sepanjang itu dengan kesadaran yang tidak lagi penuh. Dua kakiku bergetar, tak sanggup menopang tubuhku dengan benar. Ah, sakit ini terlalu pekat. Lebih dalam, kutekankan tanganku di perutku. Getaran-getaran halus itu masih terasa. Aku ngeri membayangkan bagaimana tamu-tamuku mengelupas dari dinding-dinding rahim untuk mencari pembebasan. Pantas saja nyeri dan perih ini berlipat-lipat pekatnya.
Aku terus berjalan. Di sampingku, kendaraan-kendaraan melaju berlawanan dengan arahku. Asap-asapnya mengepul lalu mengangkasa. Beberapa diantaranya menyeruak ke hidungku, memuncakkan mual yang sudah menggunung di perutku. Mata-mata di balik helm atau di balik kaca mobil mereka seperti menghujamiku dengan keheranan yang menggunung. Tentu saja tak ada manusia di trotoar selain aku. Tidak ada yang ingin berjalan di tengah terik siang seperti ini kecuali aku.
Tatapan mereka sekilas memandangiku lekat. Ah, pasien mana yang tidak berwajah pucat. Sementara tanganku masih saja menekan-nekan perutku. Aku merasakan basah di sekujur tubuhku. Rupanya, keringat dingin sudah benar-benar membasahi tubuhku. Udara yang sesak dan panas yang terik benar-benar menguras sisa-sisa daya yang kumiliki.
Nyeri ini semakin pekat. Sakit di rahimku menyebar ke pinggang dan pundakku. Ada pegal yang bersarang di sana. Sementara dua kakiku yang sedari tadi bergetar hebat sebab tak lagi sekokoh saat sehat, terus melangkah, mengangkat dengan berat setiap hentakan pada tanah. Aku harus melangkah menghitung dua kilometer yang masih terhampar di depan mata.
Ingin rasanya berhenti sejenak lalu duduk. Merebahkan diri di teras toko yang pintunya tertutup. Ada toko yang pintunya tertutup. Sepi di sana. Aku bahkan tidak tega meninggalkan tamuku di teras toko itu. Akan jadi aib, bila aku duduk lalu tamu-tamuku tak mau pergi dari bagian belakang rokku. Perjalanan masih jauh. Semua orang bisa memelototiku bila ada satu tamu saja terlihat di bagian belakang rokku. Ah, rok merah jambu terlalu terang untuk warna merah!
Aku terus berjalan tertatih. Sementara di seberang sana, aku melihat kopaja dan angkot berkeliaran melaju ke arah stasiun. Betapa mengenaskannya! Aku bahkan tak bisa menumpaki salah satu di antara kendaraan-kendaraan itu hanya karena tamu-tamuku yang datang tiba-tiba.
Di samping kananku berdiri bangunan-bangunan tinggi, kantor-kantor, dan banyak juga rumah-rumah berpagar tinggi. Ah, andai saja bisa masuk ke salah satu rumah lalu meminta lembaran-lembaran pipih empuk buat tamu-tamuku. Tentu saja aku tak bisa membeli di warung. Tidak ada warung sepanjang yang kulalui. Entah di depan. Aku baru pertama kali melalui jalan ini sebab gadis cilik itu adalah murid pertama sejak aku diterima bekerja sebagai pengajar privat. Lagipula, rumah-rumah di kota tak seramah rumah-rumah di desa. Peduli apa mereka mempersilakan gadis asing sepertiku meminjam toilet mereka dan dengan lancangnya meminta lembaran-lembaran pipih empuk buat rumah tamu-tamuku.
Sungguh aku ingin meronta. Meronta pada Sang Pemilik Kehidupan.
Tuhan, dengan cara apa Kau akan mengantarku sampai ke stasiun? Sampai ke Depok? Sampai ke Kober? Sampai ke kosku? Dengan selamat. Bagaimana? Sementara sakit ini semakin pekat. Daya ini semakin melemah. Sementara badan ini tak punya tempat untuk merebah.
Bahkan sampi kesadaranku yang entah tinggal berapa persen dan sakit yang sudah sedemikian pekatnya, aku terhuyung. Aku merasakan tubuhku hampir terbang terempas angin. Ah, aku sungguh bisa merasakan arah angin. Lalu melalui angin yang teramat akrab di tubuhku, aku mencium wangi tamu-tamuku. Wangi yang khas. Anyir.
Jalanan yang ramai oleh deru motor serasa sepi di telingaku. Mungkin saraf-saraf telingaku pun telah terjerat pada sakit dan nyeri yang pekat. Mata ini tak lagi menghirau bagaimana hujaman tatapan-tatapan heran dibalik helm dan kaca-kaca mobil. Pikiran ini tak lagi menghujati diri atau tamu-tamu lancang yang datang hari ini. Aku benar-benar sudah muak. Muak oleh nyeri dan sakit.
Sudah 1 kilometer aku melangkah. Matahari tak seterik seperti saat pertama aku keluar dari rumah muridku. Namun, asap-asap semakin mengepul dan bunyi-bunyi klakson bersahutan semakin nyaring di telinga. Tangan di perutku mengendur dengan sendirinya. Ah, ya, sakit ini memang masih pekat seperti tadi. Tak ada yang berkurang.
Di depanku, masih sedikit jauh, aku melihat banyak bajaj berjajaran sepanjang jalan. Di satu titik, para pengemudinya berkumpul, merebahkan diri, dan saling berceloteh. Aku melihat banyak pedagang asongan dengan aroma-aroma gorengan, jajanan, hingga rempah-rempah masakan. Aku mulai mendengar gelak tawa dan kebisingan yang dibikin dari artikulator manusia. Mataku menangkap sosok ibu yang membawa tas besar dengan sembulan dedaunan hijau yang biasa kusantap pagi hari. Aku melihat mobil-mobil pengangkut barang menurunkan muatannya. Muatan-muatan yang begitu akrab dengan kehidupanku sehari-hari: berdus-dus minuman soda.
Kepercepat langkahku. Kini aku melihat dengan jelas tempat sumber-sumber apa yang kulihat dari kejauhan. Mataku langsung tertuju pada papan usang, tepat di tengah-tengah bangunan. Aku masih bisa membaca dengan jelas. Kesadaranku cukup untuk membaca dua kata yang tertera di dalam papan tersebut: Pasar Rumput. Tangan di perutku benar-benar telah lepas. Aku bisa merasakan binar mataku membundar dan bibirku sedikit melebar menyunggingkan senyum.
Kini, aku akan menempatkanmu ke dalam rumahmu yang semestinya, tamu-tamuku. Kita bisa pulang cepat ke Depok. Tanpa meninggalkanmu di jok manapun itu.


 Ratihkasturi
Ratihkasturi


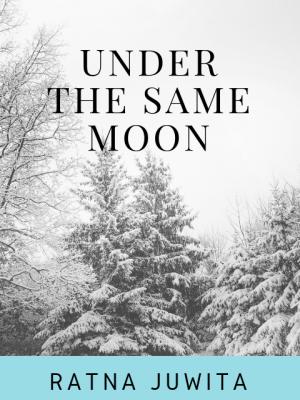




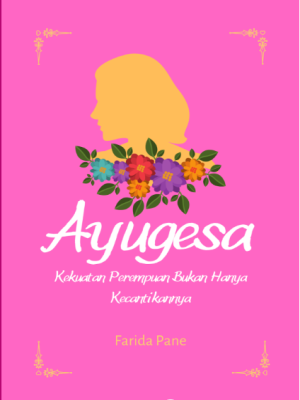
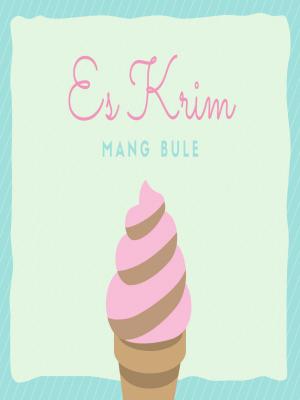
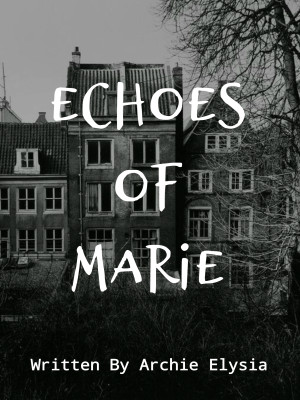
wkwkw. gokilll....