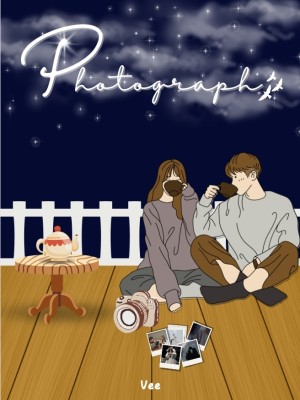Pagi pertama di Istanbul dimulai dengan suara azan subuh yang menggema dari segala arah. Di kamar kecilnya yang menghadap halaman kecil, Ameera membuka matanya perlahan. Ia lupa sesaat di mana dirinya berada, sampai pandangannya menangkap langit pucat Istanbul dan secangkir teh yang ia letakkan di jendela semalam.
Masih ada rasa tak percaya. Kota ini hanya ada dalam layar film dan buku sejarah, dulu. Sekarang, langkah-langkahnya akan benar-benar menginjak ubin-ubin kampus tua yang pernah menjadi saksi para cendekiawan, filsuf, dan penyair masa lalu.
Setelah bersiap dan berpamitan pada Babaanne, ia menaiki trem menuju İstanbul Üniversitesi, kampus yang berdiri gagah dengan gerbang berarsitektur Ottoman dan bangunan ikonik yang terlihat dari kejauhan. Udara pagi masih menggigit, tapi matanya hangat memandangi kota yang perlahan bangun.
Gerbang universitas itu menjulang di hadapannya, seperti babak baru yang menunggu dibuka. Di antara mahasiswa-mahasiswa lokal yang berjalan cepat, Ameera merasa kecil dan asing, tapi juga bebas. Tidak ada yang mengenalnya di sini. Tidak ada yang tahu cerita-cerita patah yang ia tinggalkan di Jakarta.
Di dalam aula registrasi, ia bertemu beberapa mahasiswa internasional lain. Ada yang dari Italia, Azerbaijan, Pakistan, dan satu perempuan berambut panjang dari Bosnia yang langsung menyapanya ramah.
"Kamu dari Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris.
Ameera mengangguk. "Ameera" Ameera mengulur tangannya.
"Lejla. Bosnia." Jawabnya sambil menjabat tangan Ameera.
Mereka saling tersenyum dan seperti biasa, persahabatan antar perantau tumbuh lebih cepat dari biasanya.
Setelah mengurus kartu mahasiswa dan jadwal kuliah, Ameera menyusuri halaman kampus yang sejuk oleh pohon-pohon tua. Ia duduk di bangku taman, membuka jurnal kecilnya, dan mulai menulis.
"Hari pertama. Rasanya seperti berjalan di antara masa lalu dan masa depan. Entah ke mana arah hidup ini? Tapi untuk sekarang, aku cukup duduk di bawah pohon dan menghirup bau tanah tua Istanbul."
***
Siang menjelang sore, langit mulai memudar. Awan-awan menggantung rendah, dan udara makin lembap. Ameera keluar dari kampus dan berniat mampir ke Blue Mosque sebelum pulang. Ia ingin duduk sejenak di halamannya, mungkin menulis satu dua baris di jurnal kecil yang selalu dibawanya.
Namun ketika sampai di pelataran masjid, rintik hujan mulai jatuh. Mula-mula malu-malu, lalu semakin deras. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Ameera mengangkat tasnya dan berlari kecil ke bawah naungan gerbang batu besar di sisi masjid.
Ia baru menyadari seseorang berdiri di sana. Menunduk sambil mengusap lensa kamera dari cipratan air.
Mata mereka bertemu. Lagi.
"Emir?" katanya tanpa sadar.
Pria itu mengerutkan kening sebentar, lalu tampak mengenali wajah Ameera.
"Kamu... yang tinggal di rumah nenek saya?"
Ameera mengangguk cepat. “Kamu di sini?” tanya Ameera, sambil tersenyum kikuk.
“Iya,” jawab Emir, dingin.
Hujan turun deras. Suasana pelataran masjid menjadi magis dalam balutan gerimis. Batu-batu basah berkilau, dan suara hujan berpadu dengan desau angin yang meniup daun-daun kuning jatuh di antara pijakan kaki.
“Kamu suka memotret masjid?” Ameera mencoba membuka percakapan.
Emir mengangguk. “Bukan cuma masjid. Kota ini terlalu cantik untuk dibiarkan lewat tanpa jejak.” jawabnya antusias.
Ameera mengangguk pelan. “Kamu benar. Rasanya seperti setiap sudut kota ini menyimpan cerita yang berbeda.”
Emir menoleh. Untuk pertama kalinya ia tersenyum, sedikit sekali tapi cukup untuk membuat jantung Ameera berdetak lebih cepat.
“Aku suka kalimat itu,” katanya. “Setiap sudut menyimpan cerita.”
Ameera nyaris lupa bagaimana caranya berbicara. Hujan, Istanbul, dan senyum laki-laki yang semalam terlihat seperti bayangan. Semuanya bercampur dalam atmosfer yang anehnya membuatnya merasa hidup.
Mereka berdiri bersebelahan, tak berbicara lama. Tetapi diam itu tidak sunyi.
***
Sore harinya Ameera bersiap untuk ke pasar bersama Hatice hanım, Ia mengenakan jaket krem dan kerudung biru muda, lalu menyusul Hatice Hanım yang sudah menunggu di depan pintu dengan keranjang belanja anyaman di lengannya.
“Hazır mısın, güzel kız?” tanya Hatice ceria.
“Hazırım, Babaanne,” jawab Ameera sambil tersenyum.
Mereka menyusuri trotoar, berjalan santai melewati toko roti kecil yang mengeluarkan aroma simit hangat, dan berhenti sejenak di depan toko bunga yang memajang anyelir dan tulip warna-warni.
"Bunga tulipnya cantik," gumam Ameera
"Kamu mau?" tanya Hatice tiba-tiba membuat Ameera sedikit terkejut.
"Ahhh..... Tidak Babaanne, saya sangat menyukai bunga. Tapi, saya tidak suka memetik bunga atau membeli bucket bunga," jawab Ameera berterus terang.
Pasar berada tak jauh dari rumah. Terletak di antara bangunan tua berwarna cokelat kemerahan, pasar itu ramai oleh suara tawar-menawar, suara pedagang memanggil pelanggan, dan denting timbangan logam. Langit dipenuhi tenda-tenda kain biru dan hijau, sementara aroma buah sitrus, rempah, dan daging panggang bercampur jadi satu.
“Ini namanya pazar. Kalau hari Rabu, sayur-sayur lebih murah,” jelas Hatice sambil menarik Ameera ke dalam keramaian.
Mereka berhenti di kios sayur. Ameera mencari wortel, buncis, kentang, dan bawang merah untuk masakan sayur asem dan perkedel yang ingin ia buat besok.
“Ada yang mirip, tapi bawang merah Indonesia sedikit berbeda dengan bawang merah disini” gumam Ameera sambil memeriksa satu-satu.
Hatice melihatnya dengan penuh perhatian. “Tulis saja semua yang kamu perlu. Nanti kita cari di toko Asia.”
Setelah membeli cabai, wortel, dan jagung muda dan sayur-mayur lainnya, mereka berjalan ke bagian rempah. Seorang pedagang muda tersenyum saat melihat Hatice datang.
“Merhaba Hatice teyze! Bugün ne lazım?”
“Acelem yok bugün. Ama bu kız Endonezya'dan. Ona biraz baharat lazım,” kata Hatice sambil menunjuk Ameera.
Pedagang itu langsung antusias. “Oh! Endonezya? Sambal?”
Ameera tertawa kecil. “Iya! Tapi saya akan membuat sambal yang tidak terlalu pedas, khawatir Babaanne tidak kuat.”
Hatice tertawa, lalu menepuk lengannya. “Buatkan saja yang pedas. Aku ingin mencobanya.”
Setelah itu, mereka mampir ke toko kecil di gang sempit yang menjual bahan-bahan Asia. Ada kemasan kecap manis berbahasa Indonesia, santan kaleng, dan mie instan yang membuat Ameera hampir bersorak.
“Kalau aku masak tempe bacem, kamu mau coba?” tanya Ameera saat mereka keluar dari toko.
“Selama tidak terlalu pedas, aku akan makan semuanya,” jawab Hatice dengan senyum hangat.
Saat perjalanan pulang, keranjang mereka penuh dengan bahan makanan. Mereka berjalan lambat, menikmati sore yang mulai turun. Di tengah jalan, Hatice menggandeng tangan Ameera sebentar, seperti seorang nenek yang tak ingin cucunya tersesat di keramaian Istanbul.
“Aku senang kamu datang ke rumah ini,” katanya lirih.
Ameera tersenyum. Hatinya terasa hangat. “Saya juga, Babaanne.”
Dan di momen kecil itu, di antara jalanan tua dan aroma pasar yang melekat di baju mereka, Ameera merasa: Istanbul mulai menjadi rumah kedua.
***
Langit Istanbul telah berubah menjadi lembaran kelam bertabur bintang. Angin malam bertiup pelan, membawa bau asin dari Selat Bosphorus yang jauh di sana. Di dalam kamar kecilnya, Ameera duduk bersila di depan meja kayu yang menghadap jendela, ditemani lampu meja kekuningan dan secangkir teh yang mulai dingin.
Tumpukan jurnal akademik dalam bahasa Inggris dan Turki terbuka di hadapannya. Ia mencoba memahami materi kuliah Filsafat Pendidikan yang tadi siang baru ia hadiri. Sesekali ia mencoret di catatan kecil, membuat diagram, menerjemahkan istilah-istilah asing. Otaknya bekerja, tapi pikirannya melayang-layang.
Jam menunjukkan pukul 21.47. Di luar, suara trem tua masih terdengar samar-samar, seperti nyanyian tua kota yang tak pernah benar-benar tidur.
Ameera menyandarkan tubuh ke kursi, menghela napas panjang.
Tugasnya malam ini adalah menulis refleksi pribadi tentang "Peran Universitas dalam Pembentukan Identitas Intelektual Mahasiswa." Topik itu terlalu dalam untuk malam yang sunyi.
Ia menulis perlahan:
"Menjadi mahasiswa di negeri asing adalah proses pembentukan ulang. Bukan hanya identitas akademik, tapi juga keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Di sini, aku bukan anak siapa-siapa. Aku hanya Ameera, yang mencari alasan mengapa aku masih bertahan."
Ia berhenti. Menatap layar laptopnya yang kini kosong kembali. Entah kenapa, kalimat itu terlalu personal untuk dikumpulkan sebagai tugas.
Lalu, notifikasi kecil muncul di ponsel. Pesan dari Lejla:
“Sedang belajar? Aku menyerah, otakku beku. Ada café 24 jam dekat Eminönü, kapan-kapan kita kerja kelompok di sana?”
Ameera tersenyum kecil. Ia membalas singkat.
“Boleh. Tapi nanti ya, aku masih mau pura-pura rajin malam ini :)”
Ia menutup laptopnya sejenak, lalu berdiri membuka jendela. Dari luar, suara azan Isya dari masjid dekat rumah menggema lembut, bercampur angin malam dan aroma kayu tua furniture rumah ini. Di kejauhan, lampu-lampu kota Istanbul memantul di permukaan air seperti bintang yang jatuh ke bumi.
Dalam diam, Ameera berbisik dalam hati, “Tuhan… bimbing aku untuk menemukan versi diriku yang baru, di kota ini.”
Ameera menulis lagi di jurnalnya, kali ini kalimat yang ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri.
"Mungkin, beberapa pertemuan memang ditulis Tuhan untuk lebih dari sekali. Dan mungkin, pertemuan tak selalu harus dicari. Kadang, cukup berdiri di bawah hujan, dan semesta akan mempertemukanmu dengan seseorang yang juga sedang berteduh dari luka."
***
Di sisi lain rumah ini, tepatnya di lantai bawah kamar Ameera, Emir sedang menatap layar kameranya, mengedit foto-foto, di blue Mosque lalu berhenti lama pada satu potret Ameera dari yang sedang duduk di pelataran masjid dengan hijab pashminanya yang sedikit basah karena hujan.
"Ternyata Ameera cantik juga, walau tubuh mungilnya seperti anak 12 tahun," Tutur emir tersenyum seraya melihat foto itu. "Çocuk gibi çok küçük," gumam Emir sambil menggelengkan kepalanya.
"Ama o çok güzel," timpal Hatice.
Emir terkejut melihat neneknya sudah berada dibelakangnya, entah sudah berapa lama Hatice memperhatikan cucu kesayangannya itu.
"Babaannem..... Mengapa kamu belum tidur?" tanya Emir seraya memeluk neneknya itu.
"Ameera çok güzel, değil mi?" tanya Hatice.
Emir senyum tanpa menjawab pertanyaan neneknya.
"Emir....."
"Evet, Ameera çok güzel, Babaannem," jawab Emir akhirnya agar neneknya tidak rewel.
"Udah ke masjid sana udah adzan isya tuh," nasihat Hatice kepada cucu kesayangannya itu.
"Tamam Canım, hayatım, aşkım," jawab Emir sambil tertawa kecil.
Hatice meninggalkan kamar Emir, Emir segera menutup pintu kamarnya. "Huft... Sial! Bisa-bisanya babaanne datang disaat aku melihat foto Ameera, lagian bocah itu nggak cantik-cantik amat, tapi ya lumayan manis sih, kulitnya putih bersih," gumam Emir.
Emir menutup laptopnya, berwudhu kemudian berjalan menuju
masjid yang tidak jauh dari rumahnya untuk melaksanakan shalat Isya berjamaah.
***
Note:
Üniversitesi: Universitas
Lejla (Bosnia): dibaca Leyla
Hazır mısın: Apakah kamu sudah siap
Güzel: Cantik
Hazırım: Aku siap
Simit: roti bundar, mirip donat yang biasanya dilapisi dengan biji wijen.
Merhaba: Halo
Teyze: Bibi
Bugün ne lazım: Apa yang Anda butuhkan hari ini?
Acelem yok: Tidak ada
Ama Bu kız Endonezya'dan: Tapi nona dari Indonesia ini
Ona biraz baharat lazım: Butuh sedikit bumbu
Çocuk gibi çok küçük: Sangat kecil seperti anak-anak
Ama o çok güzel: Tapi dia sangat cantik
Çok güzel, değil mi?: Sangat cantik, kan?
Evet: Iya
Canım, hayatım, aşkım: sayangku, hidupku, cintaku


 cha_azra
cha_azra