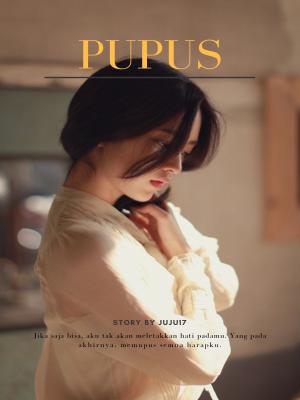Langit Istanbul menjelang senja adalah keindahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Warna jingga yang perlahan terbakar, menyisakan semburat keemasan yang menyebar di antara atap-atap bangunan tua dan menara masjid. Dari jendela pesawat, Ameera menatap panorama itu dengan mata yang nyaris basah. Bukan karena sedih, melainkan karena keindahan itu terasa seperti sapaan lembut dari sesuatu yang telah lama ia rindukan.
"İstanbul'a hoş geldiniz" suara pramugari membuyarkan lamunannya.
Ia merapikan kerudung, meraih ransel, lalu melangkah keluar dari kabin pesawat dengan jantung berdebar pelan.
Ia berjalan menuju imigrasi, setelah melalui antrean panjang dan konfirmasi dokumen, Ameera menyeret koper pinknya ke arah pintu keluar. Langkahnya ragu, tapi wajahnya tak kehilangan semangat. “Bismillah,” gumamnya.
Ia melangkah keluar, menatap langit cerah Istanbul yang baru pertama kali dilihatnya.
Udara dingin segar, dan penuh aroma baru menyeruak ke kulit wajahnya. Di sekelilingnya, suara berbaur menjadi satu, bahasa Turki yang riuh dari pengeras suara, deru kendaraan, dan tawa anak-anak yang berlarian di dekat gerbang. Semua terasa asing, tapi sekaligus menggetarkan hati.
Sebuah taksi kuning berhenti di hadapannya.
“Fatih, lütfen,” katanya gugup, menunjukkan alamat dari pesan singkat yang dikirim oleh pemilik rumah yang akan ia tempati selama satu semester ke depan di distrik Fatih, sebuah kawasan tua yang masih mempertahankan pesona Ottoman-nya. “Kami tunggu kamu di sini,” bunyi pesan itu.
"Tamam, 1500 TL" ujar sopir tersebut.
Ameera mengangguk dan mengiyakan namun di dalam hatinya berguman "satu kali naik taxi Rp 750.000 bisa bangkrut aku kalau begini terus."
Sopirnya tersenyum ramah dan membantu Ameera memindahkan koper ke bagasi. Lelaki paruh baya itu mengenakan jaket kulit cokelat, dengan kumis rapi dan mata jenaka yang memantulkan semangat hidup khas Istanbul.
“Hoş geldiniz, hanımefendi,” sapanya saat membuka pintu belakang.
“Hoş Bulduk, beyefendi. Teşekkür ederim,” jawab Ameera sambil tersenyum sopan.
Setelah duduk di kursi belakang, Ameera menatap jendela dan membiarkan matanya menyusuri kota yang berdenyut itu. Gedung tua bercampur gedung modern, gerobak simit, para turis dari berbagai negara, dan burung camar yang terbang rendah di atas atap-atap.
Istanbul, kota yang dikenal sebagai persimpangan dunia, tempat di mana dua benua bertemu dan sejarah bertaut dengan masa kini. Sebuah kota yang selama ini hanya dia kenal lewat buku dan layar komputer, kini menghampar nyata di depan matanya.
Gedung-gedung tua berdiri berbaris di sepanjang jalan berbatu, dengan kubah dan menara masjid yang menjulang anggun ke langit biru. Di beberapa sudut, pedagang memajang rempah-rempah dan teh aromatik, menarik perhatian siapa saja yang lewat. Angin dari Selat Bosphorus membawa aroma laut dan sedikit wangi kayu pinus, menciptakan harmoni yang menenangkan.
“Pertama kali ke Istanbul?” tanya sopir itu dalam bahasa Inggris patah-patah, namun hangat.
Ameera tersenyum. “Iya. Saya baru tiba hari ini. Akan tinggal di sini untuk kuliah.”
“Ah! Pelajar! Dari mana kamu berasal?”
“Dari Indonesia.”
Sopir itu tertawa pelan. “Jauh sekali! Tapi negara kamu cantik. Saya pernah melihatnya di televisi, Bali?”
Ameera tertawa pelan. “Iya, itu salah satu pulau terkenal. Tapi saya dari Sumatera.”
Sopir mengangguk-angguk, lalu berkata. “Nanti kalau kamu bosan belajar, jalan-jalanlah ke Ortaköy. Makan kumpir di tepi laut. Dan jangan lupa, minum teh di bawah jembatan.”
“Terima kasih. Saya pasti coba.”
“Dan kalau sedang sedih,” lanjutnya, “pergi saja ke Eminönü. Duduk di tepi pelabuhan. Lihat feri datang dan pergi. Angin di sana bisa mendengarkan hatimu.”
Ameera terdiam sejenak. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh. Ia menoleh dan menatap sopir itu lewat kaca spion.
“Bapak sering mengantar mahasiswa?”
“Sering. Mereka datang dengan mimpi, pulang dengan cerita. Kamu juga akan begitu.”
Ameera tersenyum. “Saya harap begitu.”
***
Sekitar empat puluh menit kemudian, taksi berhenti di depan sebuah rumah tua berwarna cokelat kayu. Rumah itu tak besar, tapi tampak terawat dan penuh karakter. Jendela-jendela kecil dengan kaca patri berbingkai putih, balkon sempit yang dihiasi pot-pot bunga kering, dan pintu kayu berat yang tampak sudah berumur puluhan tahun.
Ameera menarik napas, lalu menekan bel.
Pintu terbuka, memperlihatkan sosok seorang wanita tua berjilbab cokelat dengan senyum hangat.
"Hoş geldin! kızım,” katanya pelan.
"Hoş bulduk Hatice hanım, Ben Ameera," ucap Ameera, canggung.
Wanita itu tertawa kecil. “Panggil saja Babaanne. Semua orang di rumah ini begitu.”
Dari belakang, terdengar suara pintu ditutup agak keras.
Ameera menoleh. Seorang pria muda melangkah lewat lorong rumah, membawa kamera tergantung di lehernya. Ia tak bicara, hanya mengangguk singkat, lalu jalan terus.
“Dan itu...” kata Hatice pelan, “cucuku, Emir. Jangan tersinggung kalau dia diam. Dia memang begitu.”
Ameera menelan ludah. “Oke... noted.”
"Mari saya antar ke kamarmu!" ajak Hatice
Ameera menuruti. Di dalam, aroma kayu dan teh hitam menguar dari dapur. Dinding rumah dihiasi lukisan-lukisan miniatur kota tua, dengan langit Istanbul yang selalu menjadi latarnya. Rumah itu sepi, tenang, dan terasa seperti museum kecil yang menyimpan banyak cerita.
“Kamarmu di atas,” ujar Hatice sambil menaiki anak tangga yang berderit pelan.
Ameera mengikuti, melewati lorong sempit hingga tiba di sebuah kamar mungil dengan jendela lebar. halaman kecil dan pohon delima yang belum berbuah.
Hatice Hanım menyerahkan dua kunci logam kecil kepada Ameera. Satu berbentuk biasa dengan label biru muda bertuliskan “Üst Kat”, dan satunya lagi lebih tua, sedikit berkarat, dengan gantungan kain rajut kecil. Ameera menggenggam keduanya dengan hati-hati, seolah sedang menerima sesuatu yang lebih dari sekadar akses pintu.
“Ini kunci kamarmu,” ujar Hatice sambil tersenyum, “dan ini kunci rumahnya. Setelah kamu bereskan barangmu, turunlah. Kita akan makan malam bersama.”
Ameera mengangguk. “Teşekkür ederim, Babaanne.”
Hatice mengusap lengan Ameera sebentar, lalu turun lebih dulu ke dapur.
***
Di dalam kamar kecil itu terdapat kasur single size dengan sprei etnik khas Turki berwarna keunguan lengkap dengan permadani cantik di lantainya, bukan Turki jika tidak ada lampu mosaik di dalamnya. Di kamar ini lampu mosaik besar menggantung di tengah ruangan tepat di atas permadani etnik berwarna denim merah. Tak lupa ada kamar mandi pribadi di kamar ini, sehingga ia tidak perlu berbagi kamar mandi dengan pemilik rumah.
"Alhamdulilah kamar mandinya ada di dalam kamar" batin Ameera.
Ameera membuka koper, merapikan pakaiannya ke dalam lemari kayu tua di pojok kamarnya sambil bersenandung kecil
Fir agar mujhe tu kabhi naa milee
Humsafar mera tu bane, naa bane
Faaslon se mera pyaar hoga naa kam
Tu naa hoga kabhi ab juda
Maine tera naam dil rakh diya
Maine tera naam dil rakh diya
Dhadakegaa tu mujh mein sada
Maine tera naam dil rakh diya
Ameera sangat menyukai lagu India, darah India yang mengalir dari Ayahnya membuatnya menyatu dengan budaya India walaupun selama hidupnya dia sendiri belum pernah mengunjungi negeri Hindustan itu.
"Oke semuanya sudah rapi, sekarang saatnya berbaring sejenak," Ameera membaringkan tubuh mungilnya di atas kasur. "Alhamdulillah, akhirnya bisa istirahat juga." Ujarnya.
Baru saja memejamkan mata Ameera teringat kalau dirinya belum melaksanakan shalat Dzuhur dan Ashar, segera ia bangun kemudian menuju kamar mandi untuk membersihkan badannya. Sekitar kurang lebih 5 menit Ameera selesai mandi dan berwudhu. Langsung ia laksanakan shalat Jamak Takhir Dzuhur dan Ashar.
Selesai shalat Ameera membuka ranselnya, ia menarik jurnal kulit coklat dari dalamnya, lalu duduk di dekat jendela.
Di halaman bawah, Emir duduk sambil memeriksa kameranya. Sinar matahari sore menyorot wajahnya sekilas, rasanya dingin, sejuk dan menenangkan.
Ameera membuka jurnal dan menulis:
Hari pertama di Istanbul. Langitnya biru. Kotanya hangat. Orang-orangnya... campur aduk. Tapi aku suka.
PS: cucu pemilik rumah dingin banget. Fix bukan tipe orang yang suka ngobrol. Tapi kameranya keren.
***
Ameera turun pelan dari tangga kayu, aroma sup dan roti panggang menyambutnya seperti pelukan yang lembut. Lampu gantung tua di ruang makan memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan suasana hangat di tengah hujan yang mulai turun lagi di luar.
Di meja makan, Hatice Hanım sedang menuangkan teh ke dalam gelas kecil. Ia tersenyum ketika melihat Ameera datang.
“Nah, akhirnya turun juga. Duduk, sayang. Kita makan sebelum supnya dingin.”
Ameera duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya. Di seberangnya, Emir sudah duduk lebih dulu membelakangi jendela, mengenakan hoodie gelap dan celana panjang. Ia tidak berbicara, tidak menoleh. Tatapannya tertuju pada mangkuk sup di depannya, seakan itu satu-satunya hal penting di dunia malam ini.
“Teşekkür ederim, Babaanne,” ujar Ameera sambil tersenyum, mencoba memecah kekakuan. Ia melirik ke arah Emir, tapi pemuda itu tetap diam.
Hatice menghidangkan dolma dan börek, lalu duduk di ujung meja.
“Kamu pasti lelah. Besok jangan lupa ke kampus untuk urusan administrasi,” katanya sambil mengaduk teh.
Ameera mengangguk. “Iya, saya sudah cek jadwalnya tadi. Tapi hari ini rasanya ingin istirahat saja.”
Emir menyendok supnya tanpa suara. Gerakannya cepat, efisien, seperti ingin segera menyelesaikan sesi makan malam ini. Ia bahkan belum menatap Ameera secara langsung.
“Kamu sudah bertemu Emir tadi, kan?” tanya Hatice, kali ini dengan nada menggoda.
Ameera diam sejenak kemudian mengangguk pelan.
Emir akhirnya bersuara, tapi suaranya datar, nyaris seperti gumaman. “Kita sempat ketemu.”
Tak ada tambahan kata. Tak ada senyum. Hanya kalimat pendek yang menggantung.
Ameera tersenyum tipis, meski sedikit kikuk. Ia mengambil sepotong sigara böreği dan mencoba fokus pada makanan.
Hatice tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. “Dia memang begitu. Dingin di luar, tapi hatinya hangat kalau kamu sudah cukup mengenalnya.”
Emir meletakkan sendoknya dengan sedikit suara logam. “Babaanne…”
“Apa?” sahut Hatice ringan. “Aku mengatakan itu agar Ameera tidak kaget kalau kamu diam saat diajak bicara,”
Ameera menunduk sebentar, menahan senyum. Ia tahu saat itu bahwa kedekatan dengan Emir tidak akan datang mudah. Tidak ada kalimat ramah, tidak ada basa-basi manis. Tapi justru itu yang membuatnya penasaran. Apa yang membuat seseorang begitu tertutup, bahkan dalam rumah yang terasa penuh kehangatan?
Makan malam itu berjalan tenang tapi penuh jeda. Tak banyak bicara. Hanya denting sendok dan aroma teh yang menari di udara.
Sebelum bangkit dari meja, Hatice berkata lembut, “Besok sore, aku akan ke pasar. Kalau kamu ingin ikut, sekalian kita beli bahan untuk masakan Indonesia yang kamu ceritakan kemarin lewat WhatsApp.”
Mata Ameera berbinar. “Serius Babaanne? Saya senang sekali.”
Emir sudah berdiri lebih dulu. Ia membawa cangkir tehnya dan berjalan keluar ruang makan tanpa sepatah kata pun. Langkahnya tak tergesa, tapi cukup jelas bahwa ia ingin sendiri.
Ameera mengikutinya dengan pandangan, lalu menoleh ke arah Hatice. Perempuan tua itu hanya tersenyum kecil dan menepuk punggung tangan Ameera.
“Jangan diambil hati. Beberapa luka membuat orang memilih diam. Tapi diam bukan berarti tak melihat.”
***
Note:
İstanbul'a hoş geldiniz: welcome to Istanbul
Hoş bulduk: jawaban ketika seseorang menyebut "hoş geldin/ hoş geldiniz
Lütfen: Tolong/Silakan
Tamam : Oke
Hanımefendi: Nyonya
Beyefendi: Tuan
Teşekkür ederim: Terima kasih
Babaanne: Nenek
Üst Kat: Lantai atas
Kızım: nak (anak perempuan)
Dolma: sebuah keluarga hidangan isian sayuran yang umum di wilayah bekas kekaisaran Utsmaniyah
Borek: Sejenis pastri berlapis yang populer di Timur Tengah dan Balkan, terbuat dari adonan tipis seperti phyllo dan berbagai isian, seperti daging, keju, bayam, atau kentang.


 cha_azra
cha_azra