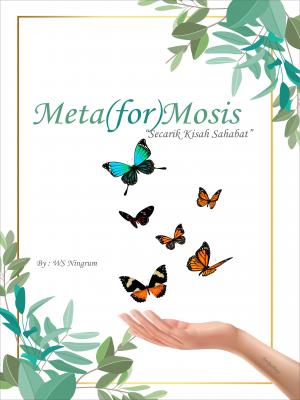Rumah lama kami punya satu tangga pendek yang menghubungkan ruang tengah ke loteng kecil di atas dapur. Hanya tujuh anak tangga. Tapi entah mengapa, tangga itu punya reputasi seperti ujian hidup: hampir semua anggota keluarga pernah jatuh di sana—minimal sekali.
Tangga kayu itu sempit, tidak dilengkapi pegangan tangan, dan selalu terdengar berderit tiap kali diinjak. Sudutnya agak curam, dan kalau kaki kita terlalu besar, tumit pasti menggantung di udara. Tapi justru dari tangga itulah, aku belajar banyak hal—termasuk arti jatuh, dan cara bangkit lagi.
Jatuh pertamaku terjadi waktu aku masih TK. Saat itu aku bersemangat naik ke loteng karena Dira bilang dia menemukan “harta karun” di sana. Tentu saja harta yang dia maksud ternyata cuma celengan ayam dari zaman SD-nya, tapi imajinasi anak kecil tidak mengenal kecewa.
Aku naik terlalu cepat. Kakiku tergelincir di anak tangga keempat. Tubuhku terbanting ke belakang dan—BUGH!—bagian pinggangku membentur kayu dengan suara pelan yang menyakitkan.
Aku menangis. Bukan hanya karena sakit, tapi karena malu. Ibu datang tergopoh-gopoh, lalu memelukku erat sambil berkata,
“Nggak apa-apa jatuh. Justru dari situ kamu belajar hati-hati.”
Itu kalimat sederhana. Tapi aku ingat sampai sekarang.
Karena setelah hari itu, tiap kali aku merasa gagal, kalimat Ibu selalu muncul di kepalaku, seolah berasal dari suara tangga kayu itu sendiri.
Dira juga pernah jatuh. Tapi bukan karena tangganya licin. Melainkan karena dia mencoba naik sambil membawa sepatu roda.
Iya. Sepatu roda.
Dia berdiri di anak tangga paling bawah, lalu sok keren berteriak, “Aku akan menaklukkan duniaaaa!”—dan dalam satu detik kemudian, dunia yang menaklukkan dia. Sepatu rodanya meluncur mundur, dan tubuhnya melayang seperti superhero gagal mendarat.
Kami sekeluarga terdiam. Lalu tertawa keras-keras setelah memastikan dia baik-baik saja.
“Lain kali jangan jadi penemu ide bodoh,” kata Ayah sambil mengoleskan minyak kayu putih ke lututnya yang lecet.
Dira meringis, “Namanya juga eksperimen…”
Itulah Dira. Dan itulah tangga kami. Dua-duanya tidak bisa ditebak. Satu penuh kejutan, yang lain penuh tantangan.
Tangga itu tidak hanya menjadi jalur ke loteng. Ia juga sering jadi tempat “nangis diam-diam”.
Kalau aku habis dimarahi Ibu atau nilai ujianku jelek, aku sering duduk di anak tangga ketiga. Tidak di kamar, tidak di halaman. Tapi di tangga itu. Tempatnya sempit, tapi justru di situlah aku merasa punya ruang untuk berpikir.
Di sana, aku bisa mendengar suara dapur—suara panci, sendok yang jatuh, atau suara kompor menyala. Kadang juga samar-samar terdengar suara Ibu mengobrol dengan tetangga di dapur.
Tangga itu seperti zona netral. Bukan kamar, bukan ruang tamu, bukan dapur. Tapi tempat di antaranya. Dan kadang, saat kita tidak tahu harus ke mana, tempat di antara itulah yang paling menenangkan.
Suatu hari, Ayah berdiri lama di tangga itu. Dia tidak naik, tidak juga turun. Hanya berdiri, menatap kosong ke arah langit-langit.
“Ayah kenapa?” tanyaku.
Dia menoleh, lalu tersenyum kecil. “Ayah lagi mikir, nak. Kayaknya umur Ayah lebih banyak dihabiskan buat jatuh… dan jatuh lagi.”
Aku duduk di anak tangga paling bawah. Menatapnya dari bawah seperti anak kecil menatap pahlawan yang sedang terluka.
“Tapi Ayah masih berdiri.”
Ayah tertawa pelan. “Iya. Karena kalau nggak berdiri, ya ketinggalan hidup.”
Kalimat itu menancap. Bukan karena nadanya dramatis, tapi karena terlalu jujur. Tangga itu benar-benar tahu cara membuat seseorang merenung tanpa harus duduk di atas sajadah.
Beberapa tahun lalu, saat rumah ini mulai jarang dihuni, tangga itu sempat dimakan rayap. Kayunya rapuh, dan Dira pernah hampir jatuh lagi saat mencoba naik.
“Astaga! Tangga ini kayak nahan dendam lama!” katanya kesal.
Akhirnya, kami memanggil tukang untuk memperbaikinya. Tapi kami minta satu hal: jangan diganti dengan yang baru sepenuhnya. Hanya ditambal, dibersihkan, dan dipernis ulang. Karena kami tidak mau kenangan yang melekat di kayu tua itu hilang begitu saja.
Tangga itu memang tidak sempurna. Tapi justru di situlah nilai sempurnanya.
Saat aku kembali ke rumah lama minggu lalu, aku berdiri lagi di tangga itu. Suaranya masih sama. Berderit. Tapi lebih dari itu, ia seperti menyapa:
“Kamu jatuh banyak kali, ya? Tapi kamu masih datang ke sini. Masih berdiri. Masih hidup.”
Aku duduk di anak tangga ketiga, tempat favoritku. Menatap ke bawah, lalu ke atas. Dan di situ, aku menyadari satu hal:
Tangga tidak pernah meminta kita untuk selalu naik. Kadang, ia hanya ingin kita duduk sejenak. Mengatur napas. Menyadari bahwa naik-turun itu biasa, dan jatuh bukanlah kesalahan.
Karena yang paling penting bukan seberapa cepat kita sampai di atas. Tapi seberapa sabar kita menyusuri setiap anak tangga.
Sore itu, aku menulis catatan kecil di buku harian yang kusimpan sejak kuliah. Di halaman belakang, aku tulis:
"Aku pernah jatuh, bukan hanya sekali.
Tapi tangga ini tidak pernah menyalahkan.
Ia diam. Tapi sabar menunggu aku berdiri lagi."
Dan di bawahnya, kutulis kecil:
“Terima kasih, tangga. Kau tidak pernah bicara, tapi kau mengajarkanku banyak hal.”
Refleksi:
Dalam hidup, kita tak hanya butuh tempat untuk berdiri. Tapi juga tempat untuk jatuh… dan belajar berdiri lagi. Tangga di rumah lama itu tak pernah sempurna. Tapi di sanalah aku belajar bahwa jatuh bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang sah.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_