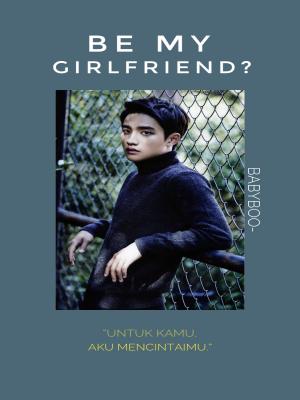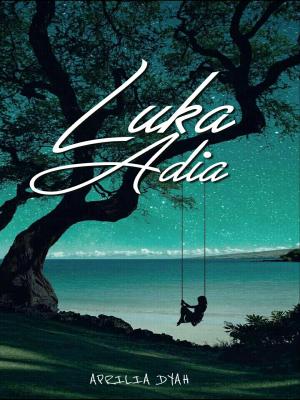Pagi itu, Dina terbangun oleh aroma tanah basah. Hujan semalam masih menyisakan tetes-tetes kecil di kaca jendela. Embun menempel di dedaunan di luar, dan burung-burung seperti belum sepenuhnya sadar bahwa hari sudah mulai berjalan. Rumah itu terasa lebih hidup, lebih berbisik, seolah tahu bahwa seseorang telah kembali.
Dina menggeliat di tempat tidur lamanya, menatap langit-langit kamar yang sudah mulai ia kenal lagi. Bintang-bintang glow-in-the-dark itu memang tak menyala seperti dulu, tapi ia tetap menyukai caranya menyambut pagi. Ia turun dari tempat tidur dan berjalan pelan ke dapur. Hari ini dia ingin membuat teh manis, seperti yang biasa dilakukan ibunya tiap Sabtu pagi.
Rak piring di atas wastafel itu masih menyimpan banyak sekali cangkir. Tapi ada satu yang langsung menarik perhatiannya: cangkir putih dengan motif bunga biru di pinggirannya. Cangkir kesayangan ibunya.
Cangkir itu punya cerita. Ibunya selalu bilang, “Minum pakai cangkir ini, teh manisnya terasa kayak pelukan.” Dina dulu sering menertawakannya. Tapi hari ini, ia mendadak rindu pelukan itu. Namun saat ia mengangkat cangkir itu dari rak, ada suara kecil: krak. Retakan halus di samping badan cangkir terlihat jelas. Garis tipis, tapi cukup membuat teh panas bisa merembes keluar.
Ia terdiam. Cangkir itu retak. Seperti hatinya waktu pertama kali harus meninggalkan rumah ini. Tapi, bukankah benda-benda yang paling disayang selalu menyimpan luka? Seperti manusia. Dina tetap menyeduh teh di dalam cangkir itu. Ia tahu, teh itu mungkin akan menetes sedikit, tapi ia juga tahu: tak semua yang retak harus dibuang.
Ia duduk di meja makan yang dingin. Hujan rintik kembali turun, perlahan mengetuk atap rumah seperti seseorang yang sabar menunggu dibukakan pintu.
Di hadapannya, teh dalam cangkir itu mulai tumpah sedikit. Menetes di taplak meja tua yang bordirannya mulai pudar. Dina memandangnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang bergerak dalam dadanya seperti film lama yang diputar ulang diam-diam.
Dulu, meja makan ini selalu ramai. Ayah duduk di ujung, ibu di sampingnya, dan Dina yang kecil duduk dengan kaki menggantung, tak sampai ke lantai. Mereka makan sambil bercerita. Tentang ayam yang lari ke lapangan sekolah, tentang PR matematika yang susah, tentang tetangga yang pelihara burung kakatua dan suka teriak “PULANG!” tiap sore. Tapi meja makan ini juga menyimpan sunyi. Seperti saat ayah dan ibu bertengkar, hanya terdengar suara sendok beradu piring. Atau malam ketika ibu duduk sendirian, menatap ke luar jendela, tak bicara apa-apa.
Waktu berjalan pelan di rumah ini. Atau mungkin, kenanganlah yang membuatnya terasa seperti itu. Dina menyesap tehnya perlahan. Retakan di cangkir itu meneteskan teh ke jemarinya. Hangat. Ia tidak menyekanya.
Ada rasa yang tidak bisa dituliskan dengan kata. Seperti rasa ketika seseorang yang kamu sayangi sudah tidak ada, tapi semua benda yang pernah ia sentuh masih ada di tempatnya.
Hari itu, Dina memutuskan untuk membereskan lemari di ruang tengah. Lemari besar dari kayu jati, dengan tiga pintu yang engselnya sudah longgar. Ia membuka satu persatu, dan menghela napas saat melihat isinya: buku-buku, album foto, dan kotak-kotak kecil yang menyimpan segala kenangan. Di balik tumpukan buku, ia menemukan satu toples plastik transparan. Isinya bukan kue, tapi potongan-potongan kertas warna-warni, dilipat kecil-kecil.
Ia membuka satu. Di dalamnya tertulis:
"Hari ini Dina belajar naik sepeda. Jatuh dua kali, tapi tetap mau coba lagi. Hebat, ya."
— Ibu
Ia tersenyum. Ini adalah toples kenangan. Ibu memang punya kebiasaan mencatat hal-hal kecil, lalu menyimpannya dalam toples. Katanya, suatu hari nanti, ketika Dina merasa hancur, ia bisa membuka satu demi satu dan ingat: hidup tidak selalu gelap.
Tangannya gemetar saat membuka kertas-kertas berikutnya.
"Dina bilang ingin jadi guru. Alasannya: biar bisa pakai spidol warna-warni."
"Dina belajar bikin telur dadar, gosong, tapi dia makan sendiri sambil bilang 'enak banget'."
Ia tertawa kecil. Tawa yang menetes bersama air mata. Tawa yang menyembuhkan, walau pelan-pelan.
Sore harinya, Dina keluar ke halaman belakang. Ada satu pohon jambu yang masih berdiri tegak, meski sudah kurus. Dulu, dia suka naik pohon itu, duduk di cabang paling rendah sambil membawa buku dan kerupuk.
Ia mendekati pohon itu dan melihat ada ukiran nama: “Dina & Ibu”.
Ia tempelkan telapak tangannya ke ukiran itu. Pohon itu seperti menyimpan semua suaranya yang dulu. Teriakan riang, tawa lepas, bahkan tangis di sore hari saat dimarahi karena main air hujan terlalu lama.
Pulang bukan hanya tentang kembali ke tempat lama. Tapi tentang belajar mencintai semua retakan yang pernah kita benci.
Malamnya, Dina membuat teh lagi. Tapi kali ini ia mengambil cangkir lain. Yang tidak retak.
Tapi anehnya, rasanya tidak sama. Tidak ada kehangatan yang sama. Tidak ada rasa "dipeluk" seperti pagi tadi. Mungkin benar kata ibu: cinta itu bukan tentang sempurna, tapi tentang ketulusan yang bertahan meski retak. Dina lalu kembali ke cangkir yang retak itu. Ia menaruhnya di rak paling depan, paling terlihat. Bukan untuk dipakai tiap hari. Tapi untuk diingat. Waktu tidak pernah benar-benar tumpah, hanya berubah bentuk. Seperti teh dalam cangkir. Bisa tumpah, bisa berkurang, tapi aromanya kadang tetap tinggal di udara.
Dan rumah ini, adalah aroma itu.
Di hari kelima, seorang tetangga lama datang. Namanya Pak Kusno, mantan guru seni di sekolah Dina dulu. Ia lewat depan rumah dan terhenti.
“Dina?” katanya ragu.
“Pak Kusno! Masih ingat saya?” Dina menyambutnya di teras.
“Iya... Wajahmu masih sama. Hanya mata kamu sekarang kayak punya cerita lebih banyak.”
Pak Kusno duduk di bangku teras. Mereka mengobrol sebentar, tentang masa lalu, tentang ibu, dan tentang bagaimana semua orang berubah tapi kenangan tetap nakal dan suka muncul tiba-tiba.
Sebelum pulang, Pak Kusno menunjuk ke jendela kamar Dina.
“Dulu, tiap sore saya dengar kamu nyanyi dari situ. Suara kamu kecil, tapi saya tahu itu suara anak yang bahagia. Teruslah nyanyi, ya. Meski sekarang cuma buat diri sendiri.”
Dina tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang, senyumnya terasa penuh.
Malam itu, ia kembali ke kamarnya, membuka jendela lebar-lebar. Angin malam masuk, membawa aroma hujan dan sedikit kenangan. Ia duduk di dekat jendela, dan menyenandungkan lagu masa kecil pelan-pelan.
Suaranya memang tidak indah. Tapi hatinya terasa damai.
Dan di meja, cangkir retak itu tetap berdiri. Diam. Tapi tidak kalah berarti dari cangkir yang sempurna. Karena dalam hidup, yang kita ingat bukan hanya momen-momen utuh. Tapi juga yang pecah, yang tumpah, yang membuat kita belajar merapikan kembali.
Cangkir itu tidak dibuang.
Karena Dina tahu, beberapa luka tidak untuk dihapus. Tapi untuk disimpan. Untuk diingat. Karena di dalamnya, ada cinta yang pernah dituang dengan tulus.
Dan seperti teh yang tetap hangat meski tumpah sedikit, kenangan juga bisa tetap menghangatkan meski retak-retak.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_