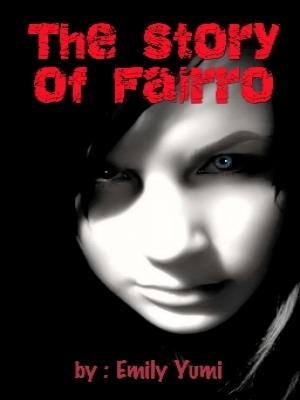Rumah Sakit Tanpa Wajah
Cahaya putih itu menyilaukan. Bukan seperti matahari, tapi lebih menusuk, seperti jarum-jarum neon yang tak mengenal ampun.
Nafa membuka matanya perlahan. Semua terasa asing. Langit-langit ruangan ini bukan langit-langit kamar yang ia kenal. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Tangannya dingin, kaku, dengan selang infus menancap di kulit pucatnya. Ketika ia mencoba bergerak, tubuhnya hanya merespons dengan nyeri yang pelan tapi menyiksa.
Ia tidak tahu di mana ia berada.
Namun suara yang ia cari tak terdengar. Bukan suara ayahnya. Bukan suara suster.
Wajah lelaki itu... seharusnya ada di sini. Tapi tak ada.
---
Hari-hari berikutnya berlalu seperti potongan film yang diputar lambat. Nafa hanya bisa duduk, menatap jendela rumah sakit yang memperlihatkan salju tipis jatuh di luar. Kota ini — tempat ini — adalah Amerika. Begitu kata ayahnya.
“Untuk pengobatan terbaik,” katanya, sambil mengelus rambut Nafa dengan tangan yang dulu begitu tegas, kini penuh keraguan.
Mereka tidak membicarakan kecelakaan. Mereka tidak menyebut nama apa pun dari masa lalu.
Yang ada hanya suster-suster asing, suara mesin medis, dan seorang pria muda bernama Zac yang mulai duduk di ruangan terapi setiap sore.
Zac tidak langsung bicara. Ia hanya duduk. Kadang menggambar di buku sketsanya. Kadang hanya membaca novel. Tapi kehadirannya tenang, seperti air hangat yang perlahan meluruhkan kebekuan.
“Boleh aku duduk di sini?” tanya Zac suatu hari.
Nafa mengangguk pelan. Suaranya belum kuat untuk menjawab. Tapi Zac tersenyum, seolah itu sudah cukup.
---
Suatu malam, setelah Nafa tertidur lebih awal, Zac keluar dari ruang terapi. Ia menemukan Adam menunggu di lorong, duduk dengan tangan terlipat dan kepala menunduk.
“Zac,” kata Adam pelan, seperti sedang menimbang berat di hatinya. “Aku mau bicara sedikit.”
Zac mengangguk, berdiri tegak seperti biasa — tenang tapi waspada.
“Putriku... dia terlihat hidup, tapi hatinya masih di tempat yang tak bisa aku jangkau.” Adam menghela napas. “Aku tahu dia kehilangan seseorang. Kami semua tahu itu.”
Zac menatapnya tajam, tidak menjawab.
“Aku ingin kau menghipnoterapi dia. Hapus kenangan itu. Hapus siapa pun yang membuatnya terjebak di masa lalu.”
Zac menelan ludah. “Pak Adam, proses seperti itu tidak bisa asal dilakukan. Apalagi kalau pasien belum siap.”
“Dia akan hancur kalau terus memeluk kenangan itu. Aku sebagai ayah... aku nggak tahu cara lain buat selamatkan dia.”
Sesaat sunyi. Zac menatap lantai sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, nyaris tidak terdengar, “Kalau aku lakukan itu, dia mungkin akan lupa… tapi dia tidak akan benar-benar sembuh.”
Adam memejamkan mata. “Kalau itu harga yang harus dibayar agar dia bisa hidup... maka biarlah aku jadi orang jahat yang membuat keputusan itu.”
Zac diam. Pilihan itu bukan medis. Itu emosional. Dan dalam hatinya yang mulai terikat pada pasien bernama Nafa, ia tahu — menghapus sesuatu bukan berarti menyembuhkan.
Tapi ia juga tahu... kadang cinta seorang ayah terlalu besar untuk membiarkan luka itu tetap ada.
---
Esoknya, Zac datang ke ruangan Nafa dengan satu tujuan: membantunya melepaskan — meski tahu sebagian dari dirinya sendiri ikut tercerabut dalam proses itu.
Jatuh Pada Perempuan yang Tak Mengingat Siapa Dirinya
Sudah tiga minggu sejak sesi terapi pertama dimulai.
Nafa sudah bisa berjalan sendiri. Pelan, ragu-ragu, seolah setiap langkahnya seperti menyusuri ingatan yang kabur. Ia tidak banyak bicara, tapi Zac tahu... setiap diamnya penuh makna.
Sore itu, Zac duduk di sudut ruangan, mencatat perkembangan pasien lain saat pintu terbuka perlahan. Nafa berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata yang selalu tampak setengah kosong.
“Aku mimpi lagi,” katanya tanpa basa-basi.
Zac menutup bukunya, perlahan berdiri. “Yang sama?”
Nafa mengangguk. “Pantai. Tangan seseorang... dan suara motor.”
Zac tidak menjawab. Ia tahu, memancing terlalu dalam akan menyalakan kembali luka yang seharusnya perlahan padam.
Tapi yang tidak ia duga adalah perasaan yang mulai tumbuh—perlahan tapi pasti. Perasaan yang berbahaya. Yang seharusnya tidak muncul di antara pasien dan terapis. Tapi bagaimana ia bisa tidak tergerak?
Gadis itu duduk di tepi jendela, cahaya matahari sore membingkai rambutnya. Bahkan dalam keadaan rapuh, ada sesuatu yang tenang dan lembut dari cara Nafa mengamati dunia, seperti sedang menunggu sesuatu yang sudah tak akan pernah kembali.
“Zac,” katanya pelan. “Kamu pernah ngerasa... cinta sama seseorang yang nggak kamu kenal?”
Zac tertawa kecil, pura-pura santai. “Kamu nanya gitu karena kamu nggak ingat siapa-siapa, atau karena kamu lagi ngetes aku?”
Nafa tersenyum samar. “Aku serius.”
Zac menatapnya, dan untuk sesaat tak menjawab. Ia tidak bisa jujur. Tapi pikirannya berbicara sendiri:
Ya, aku sedang jatuh cinta pada seseorang yang bahkan tidak mengenal dirinya sendiri.
---
Beberapa hari kemudian, Adam memanggil Zac lagi. Kali ini nadanya mendesak.
“Bagaimana perkembangannya?”
“Baik,” jawab Zac singkat.
“Dan hipnoterapi?”
Zac ragu. Ia sudah mulai menjalankan prosesnya. Perlahan. Membimbing Nafa masuk ke ruang kenangan dengan hati-hati, lalu mengaburkannya sedikit demi sedikit. Tapi setiap ia menghapus satu fragmen, rasa bersalah menyelusup lebih dalam.
“Dia mulai bisa tersenyum,” jawab Zac akhirnya. “Tapi senyumnya... bukan miliknya. Itu senyum yang aku bantu bentuk.”
Adam menatapnya lekat. “Kau mulai terlibat secara emosional.”
Zac tidak membantah. Ia hanya menunduk.
“Aku tidak akan melarang,” kata Adam pelan. “Tapi kalau kau mencintainya, cintailah dia tanpa beban. Jangan buat dia harus memilih masa lalu yang bahkan tak bisa dia lihat jelas.”
---
Malam itu, Zac duduk sendirian di apartemennya. Buku-buku psikologi berserakan di lantai, dan ia membuka halaman sketsanya. Gambar wajah Nafa — dari berbagai sudut, dalam diam, dalam senyum samar, dalam sorot mata kosong — memenuhi halaman demi halaman.
Ia tak pernah menggambar pasien lain.
Hanya Nafa.
Yang Tak Pernah Selesai
Flasback
New York, Dua Pekan Setelah Pemakaman
Dari balik jendela rumah sakit Adam memandangi salju tipis yang turun di luar. Di ruang tengah, mesin infus berdetak pelan di samping ranjang tempat Nafa berbaring. Masih belum sadar. Sudah dua minggu sejak ia membawanya keluar dari Indonesia.
Ia memijit pelipisnya. Lelah, tapi bukan fisik.
Malam-malam belakangan selalu sama—hening, tapi riuh di kepalanya.
Ia menarik kursi, duduk di samping Nafa, lalu menggenggam tangan Nafa yang dingin. Napasnya menggantung, menggenggam tanpa tahu doa apa yang harus diucap.
Ia memejamkan mata, menahan denyut aneh yang selama ini ia pendam.
“kalung itu, luka di wajahnya, dan helm yang hancur. Semua cocok. Tapi waktu lihat tubuhnya di ruang pendingin… kenapa rasanya asing? Kayak aku ngelihat tubuh orang lain, bukan Christian.”
Tangannya bergetar.
“Aku yang tanda tangan surat kematian. Aku yang masukin dia ke liang lahat. Tapi setiap malam, wajahnya datang lagi. Bukan wajah Christian. Tapi… wajah orang yang minta tolong. Minta diungkapkan.”
Matanya menatap ke arah Nafa, yang wajahnya masih tenang dalam koma panjang.
“Kau juga ngerasa, ya?” gumamnya lirih.
Adam meneguk ludah, lalu berdiri. Ia melangkah ke meja dan membuka laptop. Di dalamnya, tersimpan video berlabel “Dashcam – Night of the Accident”. Diberikan oleh kenalan polisi dari Indonesia. Belum pernah ia buka.
Tangannya begetar. Ujung kursor mengarah ke file itu namum Ia ragu untuk membukanya..
Karena jika ia buka… tak ada jalan balik lagi.
Tapi kalau tidak dibuka…
Rasa bersalah ini akan jadi racun yang menggerogoti hidupnya hari demi hari.
Ia menatap layar laptop . Hening. Lalu, satu bisikan dalam hati:
"Kau harus tahu siapa yang benar-benar pergi malam itu."


 choujie
choujie