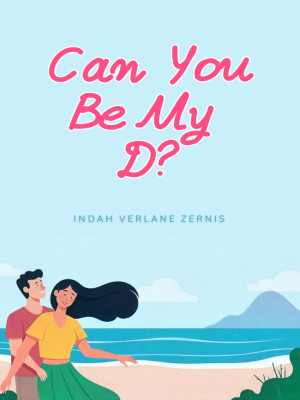Di tengah perjuangan panjang terapi anak, tubuhku lelah, pikiranku kusut, dan hatiku mulai terasa kosong. Hari-hariku penuh—mengantar terapi, bekerja, mendampingi latihan, memantau kemajuan anak, dan menahan tangis diam-diam. Tapi di balik semua itu, ada sisi lain dalam hidupku yang perlahan-lahan retak: hubunganku dengan Radit.
Kami sudah tidak sehangat dulu. Entah sejak kapan. Mungkin sejak malam-malam yang aku habiskan dengan mata setengah terbuka sambil menenangkan anak yang tantrum. Atau mungkin sejak hari-hari yang aku lewati dengan tubuh yang terasa tak utuh karena pikiranku terbagi dua: untuk pekerjaan, dan untuk anak.
Kami mulai menjauh. Tak ada teriakan. Hanya diam. Yang semakin lama semakin dingin.
Kami sempat mencoba memperbaiki. Bertemu konselor pernikahan. Duduk bersama di ruangan berbau bunga lavender yang menenangkan, mendengarkan arahan, mencoba membuka diri. Tapi ujungnya tetap sama—kami tak menemukan titik terang. Seperti dua orang yang berlayar di kapal berbeda, saling melambaikan tangan tapi tak bisa saling naik ke kapal yang sama.
Akhirnya, dengan berat hati, kami memutuskan mengajukan perceraian. Sidang demi sidang kami lewati dengan kepala tertunduk. Bukan karena malu, tapi karena ini adalah keputusan yang tak kami inginkan, tapi pada akhirnya kami sadari mungkin perlu.
Di tengah semua ini, anak kami masih menjalani terapi. Masih belajar bicara. Masih butuh kehadiran penuh. Dan aku tahu, meski hatiku remuk, aku tidak bisa menyerah.
Anak kami tidak tahu kami sedang bersidang. Yang dia tahu hanya satu hal: ibunya harus tetap ada.
Tubuhku lelah. Tapi bukan sekadar lelah karena bekerja, atau karena harus bolak-balik antar terapi. Ini lelah yang lebih dalam. Lelah yang rasanya seperti merayap diam-diam ke dalam tulang. Seperti aku sedang berjalan dalam kabut tebal tanpa tahu kapan bisa duduk dan bernapas lega.
Anakku tidur di sampingku. Nafasnya berat. Kadang masih terisak dalam tidur. Terapi hari ini cukup menguras tenaganya. Aku sempat melihat air mata di sudut matanya saat dia gagal menyusun dua kata. Lalu dia diam. Lagi-lagi diam.
Sakit. Tapi aku tak boleh menunjukkan itu di depannya. Jadi aku peluk dia… erat. Dan diam-diam aku menangis lagi malam ini.
"Apa aku ibu yang cukup baik?"
"Apa aku terlalu sibuk bekerja sampai lupa menengok hatiku sendiri?"
"Apa aku masih bisa menyelamatkan sesuatu dari reruntuhan ini?"
Radit... aku bahkan tak tahu bagaimana menyebutnya sekarang. Suamiku? Teman seperjuangan yang kini hanya menjadi siluet dalam hariku?
Kami seperti dua orang yang menempuh perjalanan panjang dalam satu mobil, tapi tak lagi saling bicara. Hanya menatap jalan masing-masing. Menunggu bensin habis. Menunggu waktu memaksa berhenti.
Padahal dulu, kami punya mimpi yang sama. Kami tertawa membayangkan anak pertama kami, membahas nama, membayangkan akan seperti apa ruang bermainnya.
Sekarang, semua terasa sunyi.
Kadang aku bertanya di malam yang sunyi, saat suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya dan Radit tidur di kamar sebelah. Kapan tepatnya semua jadi seperti ini?
Di sepertiga malam, aku bangun dan duduk diam. Kadang berdoa, kadang hanya menangis dalam hati. Di tengah tahajudku, aku mengingat masa-masa dulu—saat kami masih bisa tertawa bersama di dapur yang sempit, saling bercanda saat mencuci piring, dan memimpikan rumah kecil dengan halaman yang cukup untuk anak bermain. Masa-masa itu terasa seperti milik orang lain sekarang. Jauh. Kabur.
"Apa yang berubah dari kami?" tanyaku dalam sujud yang panjang.
Kadang aku memandang ke arah kamar sebelah, membayangkan Radit yang mungkin juga terjaga, mungkin juga berpikir hal yang sama. Tapi kami tak pernah benar-benar bicara. Tak pernah benar-benar menyentuh luka satu sama lain.
"Apa isi hatimu, Dit?" bisikku lirih, entah kepada siapa.
Apakah kamu marah? Kecewa? Atau hanya lelah seperti aku—lelah karena tak tahu bagaimana harus kembali.
Aku ingin menyelamatkan keluarga ini, tapi aku juga ingin menyelamatkan diriku sendiri. Dan itu… pilihan yang menyakitkan.
***
Aku hampir lupa hari ini hari apa.
Waktu terasa seperti benang kusut sejak kami memutuskan menempuh jalan ini. Setiap minggu berganti tanpa penanda, kecuali jadwal terapi anak dan... sidang demi sidang.
Pagi ini aku mengenakan pakaian yang rapi, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena ingin terlihat wajar. Biar orang-orang di ruang tunggu itu tak perlu tahu bahwa di dalam diriku, segalanya nyaris runtuh.
Pada jadwal sidang ketiga, kami datang bersama.
Tak ada kata-kata selama perjalanan menuju gedung pengadilan. Hanya suara kendaraan di luar jendela, dan detak jantungku yang terasa makin nyaring. Di ruang tunggu, kami duduk bersebelahan, tapi jarak di antara kami terasa seperti samudra yang tak terjembatani.
Aku melirik Radit.
Wajahnya tampak lelah, tapi tegas. Matanya menatap lurus ke depan, seolah ingin segera melewati ini semua. Tidak ada kegamangan di sana. Tidak ada isyarat “masih bisa kita perbaiki.” Hanya ketenangan yang entah datang dari kepasrahan atau keputusasaan.
Aku ingin bertanya, “Kamu kenapa sebenarnya?” Tapi aku terlalu lelah. Terlalu rapuh. Terlalu banyak luka yang belum sempat sembuh untuk membuka lagi ruang bicara yang selalu berakhir sunyi.
Mungkin dia juga sudah kehabisan kata.
Yang tersisa dari kami hari itu hanyalah dua orang asing yang pernah saling mencintai dengan begitu dalam, tapi kini hanya ingin cepat menyudahi sesuatu yang tak lagi bisa diselamatkan.
Aku menarik napas dalam-dalam, menunduk, dan menggenggam tangan sendiri. Di dalam diriku masih ada sisa-sisa harapan yang belum ikhlas sepenuhnya. Tapi aku tahu… kadang cinta juga harus berani melepaskan.
Dan hari itu, rasanya… aku mulai benar-benar belajar merelakan.


 rosadewiita
rosadewiita