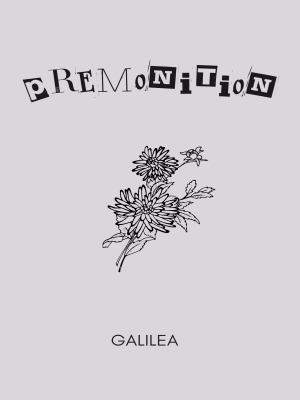Sorry, this chapter has been locked by the author!
Similar Tags
Di Bawah Langit Bumi
4026
1877
87
Romance
Awal 2000-an. Era pre-medsos. Nama buruk menyebar bukan lewat unggahan tapi lewat mulut ke mulut, dan Bumi tahu betul rasanya jadi legenda yang tak diinginkan.
Saat masuk SMA, ia hanya punya satu misi: jangan bikin masalah.
Satu janji pada ibunya dan satu-satunya cara agar ia tak dipindahkan lagi, seperti saat SMP dulu, ketika sebuah insiden membuatnya dicap berbahaya.
Tapi sekolah barunya...
Mimpi & Co.
2724
1517
4
Fantasy
Ini kisah tentang mimpi yang menjelma nyata. Mimpi-mimpi yang datang ke kenyataan membantunya menemukan keberanian. Akankah keberaniannya menetap saat mimpinya berakhir?
Me vs Skripsi
3595
1488
154
Inspirational
Satu-satunya yang berdiri antara Kirana dan mimpinya adalah kenyataan.
Penelitian yang susah payah ia susun, harus diulang dari nol?
Kirana Prameswari, mahasiswi Farmasi tingkat akhir, seharusnya sudah hampir lulus. Namun, hidup tidak semulus yang dibayangkan, banyak sekali faktor penghalang seperti benang kusut yang sulit diurai. Kirana memutuskan menghilang dari kampus, baru kembali setel...
In Her Place
1879
1064
21
Mystery
Rei hanya ingin menyampaikan kebenaran—bahwa Ema, gadis yang wajahnya sangat mirip dengannya, telah dibunuh. Namun, niat baiknya disalahartikan. Keluarga Ema mengira Rei mengalami trauma dan membawanya pulang, yakin bahwa dia adalah Ema yang hilang. Terjebak dalam kesalahpahaman dan godaan kehidupan mewah, Rei memilih untuk tetap diam dan menjalani peran barunya sebagai putri keluarga konglomer...
Resonantia
845
599
0
Horror
Empat anak yang ‘terbuang’ dalam masyarakat di sekolah ini disatukan dalam satu kamar. Keempatnya memiliki masalah mereka masing-masing yang membuat mereka tersisih dan diabaikan. Di dalam kamar itu, keempatnya saling berbagi pengalaman satu sama lain, mencoba untuk memahami makna hidup, hingga mereka menemukan apa yang mereka cari.
Taka, sang anak indigo yang hidupnya hanya dipenuhi dengan ...
Premonition
2099
1016
10
Mystery
Julie memiliki kemampuan supranatural melihat masa depan dan masa lalu. Namun, sebatas yang berhubungan dengan kematian. Dia bisa melihat kematian seseorang di masa depan dan mengakses masa lalu orang yang sudah meninggal. Mengapa dan untuk apa? Dia tidak tahu dan ingin mencari tahu.
Mengetahui jadwal kematian seseorang tak bisa membuatnya mencegahnya. Dan mengetahui masa lalu orang yang sudah m...
Reandra
4232
1872
67
Inspirational
Rendra Rangga Wirabhumi
Terbuang. Tertolak. Terluka.
Reandra tak pernah merasa benar-benar dimiliki oleh siapa pun. Tidak oleh sang Ayah, tidak juga oleh ibunya. Ketika keluarga mereka terpecah Cakka dan Cikka dibagi, namun Reandra dibiarkan seolah keberadaanya hanya membawa repot.
Dipaksa dewasa terlalu cepat, Reandra menjalani hidup yang keras. Dari memikul beras demi biaya sekolah, hi...
UNTAIAN ANGAN-ANGAN
590
476
0
Romance
“Mimpi ya lo, mau jadian sama cowok ganteng yang dipuja-puja seluruh sekolah gitu?!”
Alvi memandangi lantai lapangan. Tangannya gemetaran. Dalam diamnya dia berpikir…
“Iya ya… coba aja badan gue kurus kayak dia…”
“Coba aja senyum gue manis kayak dia… pasti…”
“Kalo muka gue cantik gue mungkin bisa…”
Suara pantulan bola basket berbunyi keras di belakangnya. ...
Kertas Remuk
319
267
0
Non Fiction
Tata bukan perempuan istimewa. Tata nya manusia biasa yang banyak salah dalam langkah dan tindakannya. Tata hanya perempuan berjiwa rapuh yang seringkali digoda oleh bencana. Dia bernama Tata, yang tidak ingin diperjelas siapa nama lengkapnya. Dia hanya ingin kehidupan yang seimbang dan selaras sebagaimana mestinya. Tata bukan tak mampu untuk melangkah lebih maju, namun alur cerita itulah yang me...
Merayakan Apa Adanya
993
727
8
Inspirational
Raya, si kurus yang pintar menyanyi, merasa lebih nyaman menyembunyikan kelebihannya. Padahal suaranya tak kalah keren dari penyanyi remaja jaman sekarang.
Tuntutan demi tuntutan hidup terus mendorong dan memojokannya. Hingga dia berpikir, masih ada waktukah untuk dia merayakan sesuatu? Dengan menyanyi tanpa interupsi, sederhana dan apa adanya.


 rosadewiita
rosadewiita