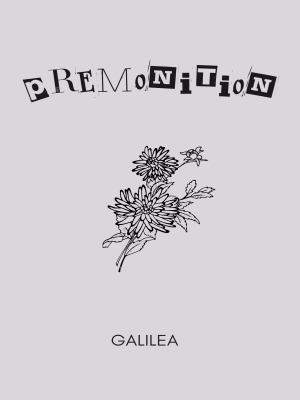Persiapan pernikahan sedang dalam fase paling sibuk—proposal ke vendor, survei tempat, bolak-balik desain undangan. Setiap hari rasanya penuh. Penuh hal-hal yang harus diputuskan, disepakati, dibayangkan.
Tapi semua itu mendadak terasa kabur. Seperti latar belakang yang tiba-tiba di-blur oleh kabar yang datang begitu cepat dan sunyi.
Raya meninggal.
Pesan itu datang saat aku sedang menyiapkan revisi list makanan untuk katering. Tanganku masih memegang pulpen ketika notifikasi muncul. "Nara, maaf, aku tahu ini mendadak… Raya udah nggak ada."
Aku membacanya ulang. Berkali-kali. Tapi otakku menolak. Tubuhku menolak. Dunia menolak.
Aku jatuh terduduk di lantai. Pulpen lepas, napasku tercekat.
Raya…
Sahabatku semasa kuliah. Teman pulang saat hari-hari terasa terlalu berat. Tempatku berbagi tawa, cerita, juga luka yang tak sempat sembuh. Dia yang selalu tahu kalau aku bilang "aku baik-baik aja" tapi sebenarnya tidak.
Dan beberapa minggu lalu… aku baru saja mengirim kabar padanya. "Aku mau nikah, Ray."
Lalu dia membalas dengan emoji senyum besar dan, “Akhirnya! Kamu pantas bahagia, Na. Aku seneng banget.”
Itu terakhir kalinya kami bertukar pesan.
**
Hari-hari setelah itu seperti kabur dalam selimut abu-abu. Aku tidak bisa makan. Tidak bisa tidur. Aku bahkan tidak bisa bicara pada Radit.
Segala hal tentang pernikahan terasa hambar. Terasa tidak penting. Bahkan aku mulai merasa bersalah—kenapa aku bahagia ketika dia justru diam-diam sedang sakit?
Kamar kosku dipenuhi keheningan. Aku hanya duduk memeluk lutut, memandang layar HP yang gelap. Menunggu. Entah apa.
Radit datang ke kos suatu sore, dan dia hanya duduk di sebelahku tanpa bicara. Hanya diam, menemaniku.
Aku menangis. Baru kali itu aku menangis begitu dalam. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang ikut terkubur bersama Raya.
**
“Dia sahabatku, Dit,” kataku akhirnya, suara serak dan gemetar. “Sahabat yang nggak pernah menuntut aku jadi siapa-siapa. Dia cuma… selalu ada.”
Radit mengangguk. “Kamu boleh berduka. Kamu nggak harus kuat terus.”
Kalimat itu pelan, tapi masuk langsung ke dalam rongga yang kosong di dadaku.
Dan untuk pertama kalinya, aku mengizinkan diriku untuk rapuh. Untuk tidak ‘cepat bangkit’. Untuk menangisi seseorang yang benar-benar berarti dalam hidupku.
Karena Raya bukan sekadar kenangan. Dia bagian dari siapa aku hari ini.
***
Beberapa hari setelah kabar itu datang, waktu tidak lagi terasa nyata. Aku bangun hanya untuk kembali menutup mata. Makan hanya untuk menenangkan orang lain, bukan untuk diriku sendiri. Menjawab chat hanya karena merasa bersalah jika terus diam.
Tapi tidak ada yang benar-benar bisa aku rasakan selain hampa.
Radit beberapa kali mencoba mengajak bicara. Tapi aku hanya bisa menjawab dengan lirih, atau tidak sama sekali. Rasanya seperti suaraku tertinggal di dada, tak sanggup naik ke tenggorokan.
Raya bukan hanya sahabat. Dia bagian dari puzzle hidupku yang tidak bisa diganti. Saat aku merasa dunia ini terlalu bising, dia adalah ruang sunyi yang aman. Waktu kuliah dulu, ketika aku tidak pulang dan hanya beralasan "lagi capek", dia yang tahu artinya lebih dari itu. Dia yang diam-diam belikan aku bubur hangat dan duduk di lantai kamar kosku, menemaniku menulis jurnal sampai tertidur.
Semuanya datang kembali seperti kilas balik yang menyiksa.
Aku bahkan tidak ada di sampingnya di hari-hari terakhir. Aku tidak tahu seberapa sakit yang dia tanggung, atau seberapa takut dia. Aku sibuk dengan rencana-rencana masa depan, tanpa tahu bahwa masa depan dia… sudah habis waktunya.
Dan itu menyakitkan.
Karena aku tahu, Raya akan sangat bahagia jika bisa datang ke pernikahanku. Mungkin dia akan jadi orang yang paling sibuk mencari dress dengan warna sesuai tema, yang paling cerewet soal makeupku, atau yang paling keras bertepuk tangan saat aku dan Radit berdiri di pelaminan.
Tapi sekarang, semua itu tinggal bayangan. Dan bayangan itu rasanya terlalu nyata.
Aku menangis lagi malam itu, sendirian di kamar. Perlahan, aku membuka folder lama di laptop—isi kenangan yang dulu selalu bikin tersenyum, kini justru mengoyak dari dalam. Foto-foto kami saat liburan ke Surabaya, Kediri, dan Bali… potret-potret kebahagiaan sederhana. Ada juga video saat dia menyanyikan lagu favoritku—malam itu aku baru saja diputusin pacar, dan dia jadi satu-satunya alasan aku bisa tidur nyenyak.
Aku menutup mata. Menggenggam ponselku erat. Seolah genggaman itu bisa membawaku kembali ke masa ketika dia masih ada.
"Ray…" bisikku ke udara yang kosong. "Aku nikah, Ray. Tapi kamu nggak di sini. Kamu nggak di sini."
Dan itu rasanya seperti ada lubang di hatiku yang tak bisa ditambal oleh apa pun.
Bahkan oleh cinta.
***
Aku tidak tahu sudah berapa kali aku memutar video itu. Suara Raya yang cempreng menyanyikan lagu Sheila on 7 sambil memukul-mukul bantal jadi satu-satunya suara yang kudengar malam itu. Aku tertawa sambil menangis. Rasanya dada ini penuh, terlalu sesak untuk dijelaskan.
Besoknya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala berat. Hari terasa asing. Seperti hidup berjalan tanpa menungguku mengejarnya.
Di meja makan kos, aku duduk sambil memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Jurnal harian yang biasanya selalu kucoret-coret, masih kosong. Aku tidak tahu harus menulis apa.
Radit datang menjelang sore. Dia tidak banyak tanya. Hanya duduk di ujung tempat tidur, sambil sesekali melirikku yang masih diam di dekat jendela.
“Kalau mau cerita, aku dengerin,” katanya pelan.
Aku menatapnya. "Aku udah cerita… kemarin. Tapi ternyata, rasanya nggak selesai-selesai."
Radit mengangguk. Lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil.
“Aku nggak tahu ini bisa bantu apa nggak…” Ia menyerahkan kotak itu. Di dalamnya ada frame kecil dari kayu, berisi kutipan favoritku yang pernah Raya tulis di notes ulang tahunku lima tahun lalu: ‘Perempuan kuat itu bukan yang selalu tersenyum, tapi yang tahu kapan harus istirahat dan menangis.’
Aku menahan napas. Tanganku bergetar saat menyentuh kaca frame itu.
“Terima kasih, Dit…” suaraku nyaris tak terdengar.
Radit masih diam, tapi dia duduk lebih dekat, mengusap pundakku pelan. Kali ini aku tidak menolak.
Malam itu, aku membuka jurnal lagi. Masih dengan mata sembab, aku menulis:
Dear Raya,
Hari ini aku masih menangisimu. Tapi aku juga mulai merelakan.
Terima kasih sudah jadi rumah saat aku nggak punya siapa-siapa.
Terima kasih udah bahagia duluan,
karena kalau aku jadi kamu, aku pun pasti ingin segera bebas dari rasa sakit.
Aku akan terus hidup, terus mencintai hidup ini—karena kamu, bukan meskipun tanpamu.
***
Hari-hari setelahnya berjalan lambat, tapi aku mulai bergerak lagi. Satu demi satu, pesanan mulai kutangani. Kadang sambil menahan tangis, kadang sambil tertawa mengingat lelucon receh Raya dulu. Kehilangan tidak pernah mudah, tapi mungkin begini caranya orang belajar mencintai hidup lebih dalam—ketika tahu bahwa hidup itu rapuh dan bisa berhenti kapan saja.


 rosadewiita
rosadewiita