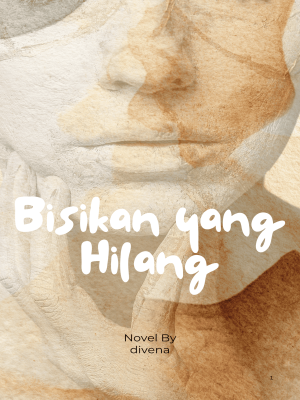Pagi itu, aku bangun dengan mata sedikit berat tapi hati yang lebih tenang. Masih belum ada jawaban pasti dari doaku semalam, tapi entah kenapa, menuliskan isi pikiranku di jurnal membuat segalanya terasa sedikit lebih tertata. Seperti benang kusut yang mulai bisa diurai pelan-pelan.
Aku duduk di tepi ranjang kos, menatap seragam kerjaku yang tergantung di dinding. Kemeja putih dan rok hitam. Biasa saja. Seperti hari-hariku belakangan ini.
Aku berangkat kerja naik angkot seperti biasa. Sambil memeluk tasku, aku menatap jendela yang berembun. Jalanan yang sama, ritme yang sama, tapi pikiranku seperti melayang ke tempat yang entah di mana. Hari ini akan ada meeting rutin divisi, dan aku sudah tahu apa saja yang harus aku input ke laporan surat masuk-keluar minggu ini.
Pekerjaanku sekarang... bukan yang aku bayangkan akan kulakukan setelah lulus kuliah dulu.
"Masuk aja, Mbak Nara," suara salah satu pegawai pria memanggil ketika aku berdiri di depan ruang TU membawa setumpuk map.
Aku tersenyum sopan, mengangguk, dan masuk. Pekerjaan sebagai admin surat membuatku sering mondar-mandir dari satu ruang ke ruang lain. Menginput, mencatat, mengantar dokumen, menerima disposisi. Semua aku kerjakan dengan rapi dan tepat waktu. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa kosong di sela-sela rutinitas itu.
“Kamu kelihatan sering ngelamun, Ra,” celetuk Rina, teman satu angkatan kerja yang duduk di seberangku saat makan siang di pantry.
Aku tersenyum kecil. “Hehe, ya gitu deh. Lagi banyak mikir.”
“Kerjaan baru ya, belum cocok?” tanyanya sambil mengaduk kopi sachet-nya.
Aku menggeleng pelan. “Nggak juga. Cuma... lagi masa transisi aja mungkin. Biasa kan, adaptasi awal.”
Rina mengangguk, lalu tak bertanya lebih jauh. Mungkin karena dia tahu aku memang bukan tipe yang gampang cerita. Aku menghargainya karena itu.
Tapi justru karena pertanyaannya sederhana, aku jadi terdiam lebih lama.
Adaptasi? Iya, mungkin itu alasannya. Tapi bukan cuma pekerjaan.
Aku sedang berusaha menyesuaikan diri... dengan banyak hal dalam hidupku sekarang.
Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi saat sore datang dan aku berdiri sendiri menunggu angkot di halte depan kantor, perasaan itu kembali muncul. Rasa ragu yang menusuk. Pertanyaan yang menggantung di udara.
Apakah aku benar-benar siap menikah?
Atau aku hanya takut mengecewakan orang yang mencintaiku?
Malamnya, aku kembali membuka jurnal. Aku menuliskan hal yang sejak tadi siang memenuhi pikiranku:
“Usiaku 25. Tapi kadang rasanya seperti belum benar-benar memulai apa-apa. Aku belum menuntaskan mimpiku. Belum menemukan pekerjaan yang membuatku merasa ‘hidup’. Lalu sekarang, aku akan menikah?”
“Apa ini waktu yang tepat, atau aku hanya terbawa arus?”
Aku menatap tulisan itu lama sekali, seolah berharap tinta yang kugoreskan bisa memberiku jawaban.
Aku tahu Radit mencintaiku. Aku pun mencintainya. Tapi perasaan sayang tak selalu sejalan dengan kesiapan. Dan di kepalaku yang penuh keraguan ini, ada suara lirih yang berbisik: “Belum sekarang. Aku belum selesai jadi diriku sendiri.”
***
Malamnya, aku duduk di depan meja kosanku yang kecil, menatap buku jurnal yang masih terbuka di halaman terakhir. Lampu meja menyinari kertas putih dengan coretan-coretan yang sudah mulai mengabur di sudutnya. Pulpen di tanganku sudah sejak tadi kuputar-putar, tapi belum satu kalimat pun kutulis.
Aku menunduk, menatap lembar kosong itu seperti sedang menunggu petunjuk dari langit.
Tapi yang kudengar hanya detak jam dinding dan dengung samar kipas angin.
Rasanya aneh. Harusnya aku bahagia. Aku dicintai oleh seseorang yang sabar, baik, dan tidak main-main. Aku tidak sedang patah hati. Tidak sedang sendirian. Tapi kenapa hatiku masih terasa... kosong?
Aku menunduk, menuliskan kalimat pelan-pelan.
“Mungkin bukan karena aku tidak mencintainya. Tapi karena aku belum selesai mencintai diriku sendiri.”
Kupandangi tulisan itu lama. Ada sesuatu yang nyeri saat membaca ulang kalimat sendiri.
Aku masih belajar berdamai dengan banyak hal: kegagalan-kegagalanku, rasa minder yang kadang datang tiba-tiba, dan kenyataan bahwa aku belum bisa menjawab satu pertanyaan penting dalam hidup: aku ini mau jadi apa, siapa, ke mana?
Aku menutup jurnal, lalu berdiri menuju kamar mandi. Wudhu. Lalu kembali duduk, mengambil sajadah, aku sholat istikharah. Pelan-pelan. Dengan doa yang masih sering tertukar antara keyakinan dan keraguan.
“Kalau dia memang baik untukku, untuk hidupku nanti, dan untuk langkah-langkahku menuju-Mu... dekatkanlah. Tapi kalau semua ini hanya membuat aku menjauh dari-Mu, jauhkan, sekuat apapun aku menginginkannya…”
Sujud terakhir malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Bukan karena aku sudah yakin, tapi karena aku tahu: aku sedang butuh dituntun.


 rosadewiita
rosadewiita