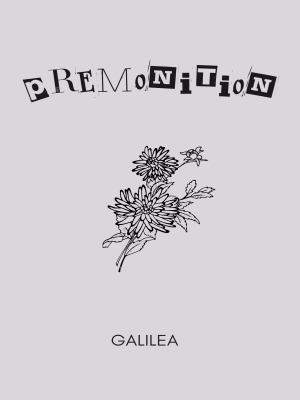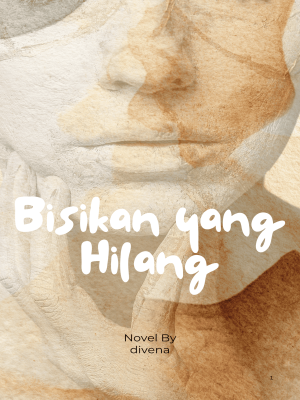Orang bilang, usia dua puluh lima itu peralihan: bukan remaja, belum mapan sepenuhnya. Tapi buatku, rasanya seperti berdiri di tengah lorong panjang yang sunyi—tak tahu harus melangkah ke depan atau kembali ke titik semula.
Banyak hal sudah kupilih. Tapi belum satu pun terasa benar-benar kupahami. Termasuk soal lamaran itu.
Aku sudah bilang ya. Tapi entah kenapa, dalam hati masih terasa ragu. Bukan pada Radit. Tapi pada diriku sendiri.
Setiap pagi, aku bangun dengan rutinitas yang sama: kerja, lembur, pulang, nulis jurnal. Hidup berjalan seperti seharusnya… tapi entah kenapa, tetap terasa kosong di bagian-bagian tertentu.
Sejak Radit melamarku, hidupku seharusnya lebih mudah, kan? Aku tidak sendirian lagi. Tapi perasaan ragu itu tetap ada, diam-diam tumbuh seperti rumput liar di taman yang mulai kutata.
**
Weekend datang seperti jeda yang nggak benar-benar jeda. Di hari libur seperti ini, biasanya aku menghabiskan waktu dengan tidur sepuasnya, mencuci baju, menonton drama Korea favorit, dan kalau sempat, menulis jurnal.
Tapi hari ini terasa berbeda.
Sejak pagi, notifikasi WhatsApp dari Radit muncul beberapa kali. Dia ngajak ketemu sore ini, katanya cuma pengin ngobrol. Aku sempat bimbang—bukan karena nggak mau ketemu, tapi karena aku sendiri belum siap menjelaskan apa yang sebenarnya aku rasakan sejak malam lamaran itu.
Aku jawab “Oke, nanti sore”, dan setelahnya menghabiskan satu jam hanya untuk memilih baju paling netral dan aman. Bukan terlalu cantik, tapi juga bukan terlalu cuek.
**
Kami bertemu di taman kecil dekat kampus lama kami. Tempat yang sering kami lewati dulu waktu masih saling pura-pura nggak peduli satu sama lain.
Radit sudah duduk di bangku kayu yang menghadap kolam ikan. Ia membawa dua gelas kopi take away.
“Aku nggak tahu kamu lagi suka yang mana, jadi tadi ambil yang aman—cappuccino,” katanya sambil menyodorkannya.
Aku tersenyum tipis. “Masih yang itu, kok. Nggak berubah.”
“Berarti kita masih satu frekuensi,” ucapnya pelan. “Meskipun sekarang kita lagi coba jalan bareng ke arah yang lebih serius.”
Kalimatnya membuatku terdiam beberapa detik. Aku mengaduk-aduk kopi dengan sedotan, bukan karena perlu, tapi karena butuh waktu.
“Radit…” akhirnya aku buka suara. “Kamu tahu kan aku… nggak sepenuhnya siap?”
Ia menoleh, menatapku tanpa menginterupsi.
“Aku bukan ragu sama kamu. Bukan. Tapi aku… kayak belum selesai jadi aku. Aku masih sering ngerasa kosong. Masih mikir, ini beneran hidup yang aku mau atau cuma karena harus.”
Radit menatap ke depan, ke arah kolam. Lama. Lalu dia berkata dengan tenang, “Aku tahu, Na. Dan aku nggak minta kamu cepet-cepet selesai. Aku juga tahu kamu lagi cari sesuatu yang lebih dari sekadar jadi pasangan seseorang. Kamu pengin jadi kamu dulu, kan?”
Aku mengangguk pelan, merasa leherku mengeras karena menahan emosi.
“Aku nggak keberatan nunggu, Na,” lanjutnya. “Kita bisa pelan-pelan. Bahkan kalau nanti kamu mutusin mundur pun, aku akan ngerti. Tapi selama ini, yang aku lihat justru… kamu lagi berusaha. Dan aku pengin temenin kamu dalam proses itu. Bukan buru-buru nikah, terus kamu malah kehilangan dirimu.”
Aku tertunduk. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Radit, dengan segala diamnya, ternyata benar-benar mengerti.
“Cinta yang matang bukan soal siapa cepat menikah. Tapi siapa yang mau sabar menunggu sampai kita siap menumbuhkan versi terbaik diri bersama-sama.”
***
Malam itu, setelah lelah mengobrol dan menyibukkan diri sepanjang hari, aku duduk di sudut kamar kos. Mataku lelah, tapi pikiranku masih saja berputar tak karuan.
Dengan perlahan, aku menggulung sajadah kecil yang selalu kuletakkan di sudut kamar. Kubuka Al-Qur’an yang sudah mulai pudar warnanya, lalu bersiap melakukan salat istikharah.
Aku berdoa, meminta petunjuk pada Allah. Memohon agar diberikan jalan yang terbaik—bukan hanya untukku, tapi juga untuk dia yang kurasa mulai mengisi ruang di hatiku.
Setelah sujud terakhir, aku duduk menatap langit-langit kamar yang remang. Aku merasa ada sesuatu yang belum aku temukan jawabannya.
Kuhirup nafas panjang, lalu meraih jurnal kecilku. Di sana, aku menuliskan apa yang aku rasakan, apa yang selama ini aku pendam.
Aku sudah salat istikharah.
Sudah menundukkan kepala di sajadah yang sama, meminta petunjuk dari Tuhan yang sama, yang selama ini kutemui hanya saat aku buntu.
Dan malam ini... aku masih belum menemukan jawaban pasti.
Yang kutemukan justru:
pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dari sebelumnya.
Apakah aku benar-benar mencintainya, atau aku hanya mencintai ide tentang akhirnya ada yang memilihku?
Apakah aku mencintainya karena aku melihat masa depan bersamanya, atau karena aku takut sendirian terus-terusan?
Dan yang paling membuatku takut:
Apakah aku terlalu sibuk mencintai manusia, sampai lupa mencintai Allah?
Tapi bukankah rasa ini juga ciptaan-Nya?
Bukankah aku juga mencintai Radit dengan doa-doaku?
Dengan cara mencoba mengenalnya dengan sabar, dengan menjaga batas,
dengan menyimpan nama kami hanya dalam sepi dan sajadah?
Tuhan, kalau cinta ini menjauhkan aku dari-Mu, tolong ambil.
Tapi kalau cinta ini justru jalan untukku pulang pada-Mu, maka kuatkan aku.
Bimbing aku untuk tetap mencintai-Mu terlebih dulu, baru mencintai dia yang Kau kirim padaku.
Aku nggak mau mencintai siapa pun sampai aku lupa caranya bersujud.
Aku nggak mau mencintai seseorang yang membuat aku jauh dari Diri-Mu.
Tapi aku juga tahu,
cinta seperti ini jarang datang dua kali.
Dan malam ini aku cuma ingin jujur:
Aku takut.
Bukan takut ditinggal,
tapi takut mengambil jalan yang salah karena terlalu sibuk berharap pada manusia.
Kalau boleh memilih,
aku ingin cinta yang mengajakku pulang—
bukan yang membuatku merasa jauh dari rumah utamaku: Engkau.
Kututup jurnal dengan lembut, dan aku merasa tenang.
Meski masih ragu, aku tahu aku belum sendiri. Ada Dia yang selalu ada, mendengarkan segala gelisahku.


 rosadewiita
rosadewiita