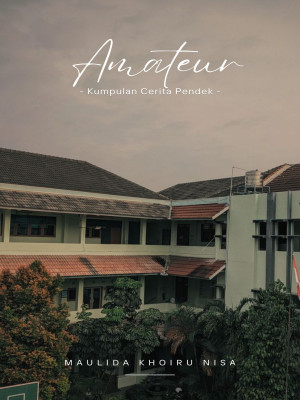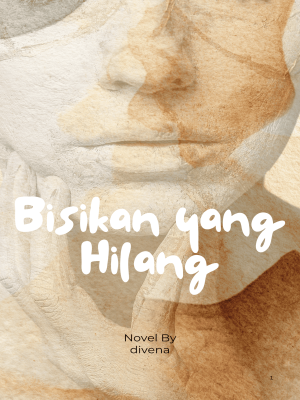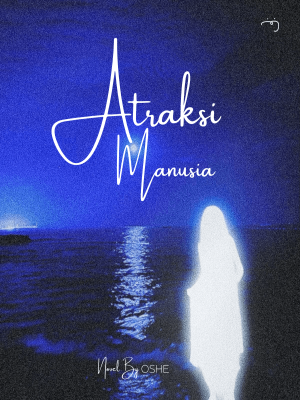Malam itu dilalui Raina dengan gelisah. Ini kali pertamanya bermalam di rumah sakit, menunggui seseorang. Selain tidak punya saudara kandung, Raina juga tidak dekat dengan kerabat mana pun, baik dari pihak bapak atau mamanya. Nenek dan Kakek yang merawat dia sejak kecil juga sudah berpulang. Semua itu membuat Raina terlalu terbiasa hidup sendirian.
Gadis berlesung pipi itu lega karena Sofi bisa tidur pulas. Dia sepertinya juga sudah tidak kesakitan lagi. Sementara, Raina tertidur di kursi dan sedikit-sedikit terbangun. Kesibukannya membantu Sofi tadi kini sudah berakhir, sehingga mau tak mau pikirannya tertuju lagi pada nasib percintaannya yang miris. Sejak tadi, Raina mematikan paket data untuk menghindari Bagas dan Mama. Dia yakin cowok pengecut itu sudah mengadu. Kalau sudah begini, Raina yang jadi pusing sendiri. Seperti berpihak padanya, ponselnya mati kehabisan baterai. Raina jadi punya alasan lain untuk menghindari Mama.
Semburat cahaya matahari mulai tampak. Malu-malu, sinarnya mengangkat percik-percik embun di tanaman yang ada di taman kecil depan ruang VK. Raina menikmati pagi dengan hiruk pikuk rumah sakit yang mulai menggeliat, dan aroma khas obat yang menguar di mana-mana. Dia pergi ke kantin untuk membeli sarapan. Perutnya yang bergemuruh tidak boleh dia abaikan.
Pukul setengah tujuh pagi, bidan jaga mengecek keadaan Sofi. Tekanan darah gadis itu sudah normal, setelah semalam kelewat rendah, wajahnya juga sudah kembali merona.
"Rasanya udah nggak sakit lagi, Bu Bidan," ungkap Sofi.
Bidan kemudian melakukan pemeriksaan dalam untuk mengecek apakah seluruh jaringan janin sudah keluar dari uterus Sofi.
"Alhamdulillah, Mbak. Rahimnya sudah bersih. Perdarahan juga sudah berhenti. Perutnya kerasa keras kan, Mbak?"
Sofi mengangguk. Dia memang merasa perutnya berkontraksi sejak semalam, berdenyut dan seakan diremas-remas.
"Kalau gitu tinggal tunggu dokter visit ya, Mbak. Sepertinya Mbak nggak perlu dikuretase. Tapi nanti lihat keputusan dokter. Kalau memang nggak perlu dikuret, Mbak boleh pulang setelah diperiksa." Bidan menjelaskan.
“Baik, makasih, Bu Bidan.” Sofi tersenyum lega.
Tengah hari, dokter melakukan kunjungan. Benar kata bidan, Sofi tidak perlu dikuretase. Setelah mengurus berbagai administrasi dan menebus obat, Sofi diperbolehkan pulang. Semula gadis itu ingin langsung ke kafe, tapi Raina melarangnya habis-habisan. Kondisi Sofi bahkan belum pulih benar. Akhirnya, Raina mengantar Sofi dengan taksi online. Motornya masih ada di D’Sunset Coffe, yang akan Raina ambil sepulang dia mengantar gadis itu.
"Makasih buat semuanya ya, Mbak."
Mereka sudah berada di rumah Sofi sekarang.
“Sama-sama, Sof. Kamu harus banyak istirahat biar cepat pulih, ya,” saran Raina. Sofi mengangguk penuh arti.
Saat gadis itu beranjak ke dapur untuk membuat minuman, Raina mengedarkan pandang ke sudut-sudut rumah. Duduk di ruang tamu rumah Sofi yang sempit dan berantakan ini membuatnya ingin buru-buru pamit. Jujur saja, dia capai sekali. Kepalanya berdenyut-denyut, dan badannya sakit semua karena tidur dengan posisi tidak semestinya. Belum lagi saat mendengar jerit dan celoteh adik-adik Sofi.
Si bungsu, batita perempuan dengan rambut keriwil dan mata yang bulat menawan, mengganggu kakaknya—yang Raina kira baru masuk SD—merebut pensil warnanya. Alhasil si kakak marah, menarik tangan adiknya keras-keras, dan tangisan kencang pun pecah. Bukannya minta maaf, si kakak justru meninggalkan adiknya begitu saja. Sekarang, tak hanya menangis, batita itu juga sibuk melempari apa pun yang bisa dijangkaunya.
"Syifa, Syifa, jangan dilempar-lempar begitu bonekanya!" Sofi tergopoh-gopoh mendatangi si keriwil sambil membawa nampan dengan dua gelas teh hangat. Kalau sedang berdekatan begitu, keduanya sangat mirip. Raina yakin Syifa akan tumbuh jadi gadis yang cantiknya mungkin melebihi Sofi.
Akan tetapi, tangis Syifa bertambah kencang. Alih-alih menuruti nasihat kakak sulungnya, dia malah semakin membabi buta melempar barang. "Syifa, jangan nangis, ya. Malu, lho, ada teman Mbak yang cantik, masa kamu nangis gitu? Mbak ajak kenalan aja, yuk!"
Syifa langsung merangkul Sofi, beranjak ke gendongannya. Sofi membawa adiknya ke hadapan Raina. Gadis kecil itu menurut. Tangisnya mulai mereda perlahan, menyisakan deguk-deguk kecil. Dia tertunduk malu-malu sambil sesekali curi pandang pada Raina.
"Syifa, cantik sekali kamu, kayak Mbak Sofi, ya. Jangan ganggu kalau kakaknya lagi belajar ya, nanti Syifa kena marah. Syifa main boneka aja sini sama Mbak." Raina berbasa-basi, merentangkan tangan untuk mengajak Syifa. Gadis kecil itu melengos.
"Wah, nggak mau sama Mbak ya, rupanya. Nih, Mbak punya ini. Buat Syifa. Enak, lho. Kakaknya dikasih, ya." Mata Syifa membulat makin lebar saat Raina mengeluarkan sebatang cokelat dari tas dan mengulurkan cokelat itu padanya.
Senyum Sofi merekah. "Ayo, Syifa, bilang apa sama Mbak Raina? Ma-ka-?"
“Sih …” Syifa melanjutkan perkataan Sofi sambil mengerjap-ngerjap. Menggemaskan sekali. Raina tak bisa menahan tawanya. Kalau sedang lucu begini, ternyata batita tidak terlalu menjengkelkan juga, dia membatin.
Si kecil Syifa langsung turun dari pangkuan Sofi, dan lari ke dalam sambil memamerkan cokelat pada kakak-kakaknya. Suara riuh langsung terdengar sampai luar. Raina tertawa lagi. Dia baru tahu kalau ternyata, punya adik bisa membuat rumah semeriah itu. "Kakak-kakaknya dikasih ya, Syifa," ucapnya refleks, setengah berteriak.
Baru sekali Raina ke rumah Sofi, dengan kesan pertama yang semula ingin cepat beranjak dari situ, dalam beberapa menit langsung berganti. Raina sepertinya akan betah berada di rumah ini lama-lama. Matanya memindai tembok ruang tamu yang sudah retak di sana-sini. Cat hijau lumutnya sebagian sudah mengelupas dan luntur termakan usia. Semua itu berbanding terbalik dengan kondisi ruang tamu rumahnya—cat putih bersih mulus, dipadukan dengan sofa beludru yang empuk, dan hiasan lukisan besar mahal. Di rumah Sofi, dia harus duduk di kursi anyaman yang hampir jebol, tidak ada lukisan atau vas mahal. Tapi ada satu hal di sini yang tidak ada di dinding rumah Raina. Foto keluarga.
Raina tersenyum getir saat menatap foto itu lekat-lekat. Meski gambarnya sudah usang, kaca bingkainya penuh debu, namun ada kehangatan di sana. Kehangatan berkumpul bersama keluarga, meski cuma dalam pigura, yang bahkan tidak pernah Raina rasakan. Matanya memanas memandang sosok bapak, ibu, Sofi, dan adik-adiknya yang tersenyum lebar, mengarah ke satu tujuan yang sama—lensa kamera. Dada Raina mendadak sesak. Dia sungguh iri setengah mati pada Sofi, seolah lupa bahwa di balik kehangatan keluarga itu, Sofi juga dirundung pilu. Raina menghela napas panjang. Andai jiwanya bisa ditukar, Tuhan, sekali saja, Raina ingin merasakan hangatnya kasih sayang keluarga.
"Mbak, tehnya diminum." Suara Sofi membuat dunia imajiner Raina lenyap. "Maaf ya, Mbak, rumahnya berantakan banget. Ibu pasti nggak sempat beres-beres sebelum kerja. Tapi beres-beres juga nggak ngaruh sih, Mbak, tetap berantakan. Ya gini, Mbak, kalau di rumah banyak anak kecil. Nggak bisa rapi dan bersih kayak rumahnya Mbak Raina," terang Sofi panjang lebar.
"Tapi enak, kan, Sof, rumah jadi ramai. Nggak sepi kayak rumahku." Raina meringis.
“Ah, Mbak Raina bisa aja. Kalau terlalu banyak jadi kayak Paud, Mbak.” Sofi tertawa kecil. “Kebutuhan mereka juga banyak, Mbak. Itu juga yang bikin aku nggak bisa nolak Ifan. Aku nggak cuma mikirin diriku sendiri. Aku mikir nasib adik-adikku. Nggak apa-apa aku nggak kuliah, tapi aku nggak mau mereka semua jadi sama kayak aku, Mbak. Mereka harus sekolah tinggi. Harus berani punya mimpi tinggi." Kedua mata Sofi berkaca-kaca.
Gadis berambut ombak itu tidak tahu kalimatnya barusan begitu menohok Raina. Dia seperti disodorkan kaca yang bisa bicara, yang meneriakinya untuk bersyukur. Raina mungkin menginginkan keluarga seperti keluarga Sofi, tapi jika Tuhan menukarnya untuk menjadi Sofi, dia tidak yakin sanggup menjalani perannya setegar gadis itu. Sofi. Si tulang punggung keluarga yang rela mengorbankan mimpinya, dirinya, bahkan harga dirinya demi keluarga. Demi adik-adiknya. Sofi yang dipaksa dewasa karena keadaan. Apa kamu pikir kamu sanggup, Raina? Batin Raina bermonolog.[]


 ayufitris
ayufitris