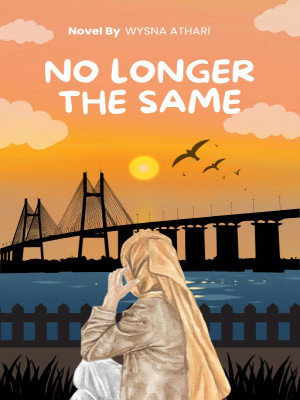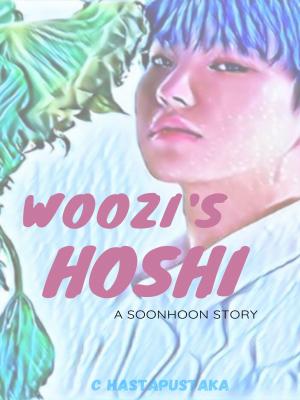Dulu, Sera pernah bermimpi untuk menjadi penari balet terkenal. Melakukan gerakan pirouette[3] di panggung opera, hingga bisa membanggakan ibunya dan Rafa. Ya, Rafa. Sejak duduk di bangku SMP, Rafa selalu ada di dekatnya. Mereka teman satu sekolah, dan pernah berada di salah satu tempat kursus bahasa inggris yang sama. Lalu, entah bagaimana keduanya menjadi sangat dekat.
Mereka masuk di SMA yang sama pula, dan pada tahun pertama ayah-ibu Sera berpisah. Ayahnya pergi entah kemana, sementara ibunya terus berganti pasangan, hingga membuat Sera begitu muak. Sejak saat itu, Sera merasa tidak lagi mengenali sosok ibunya. Ia sering ditinggalkan sendirian di rumah, dan terlihat seperti remaja yang tidak terurus. Lucunya, Sera justru lebih sering menghabiskan waktu dengan Rafa dan keluarganya. Bersama mereka, Sera merasa kembali menemukan ‘rumah’ yang utuh dan bahagia.
Hingga suatu hari, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Kakak perempuan Rafa bunuh diri, tepat ketika Sera dan Rafa sedang bersiap untuk mengikuti ujian akhir SMA. Sejak saat itu, hidup Sera seolah kembali pada ruangan gelap yang menyesakkan. Rafa tidak lagi bisa hidup normal karena traumanya, orang tua Rafa tampak seolah menyalahkannya atas kematian anak pertama mereka. Sama seperti Sera, sejak saat itu Rafa sering ditinggalkan oleh orang tuanya. Mereka hanya memiliki satu sama lain, dan seolah tak terpisahkan.
Setelah kakak perempuannya meninggal, Rafa sering melukai dirinya sendiri. Dan setiap kali melakukannya, Sera menjadi satu-satunya orang yang ia cari. Sejak saat itu, Sera berpikir bahwa Rafa tidak akan bisa menghadapi semuanya sendirian. Jadi, Sera bertekad untuk meninggalkan les balet yang sudah ia ikuti sejak TK, dan melupakan semua mimpinya. Sera mengikuti Rafa ke universitas yang sama, dan mengambil jurusan yang sama. Ia tidak mau kehilangan satu-satunya orang yang selalu menemani ketika ia berada dalam keadaan terpuruk.
Sera tidak sadar, bahwa sejak saat itu ia tidak pernah benar-benar mendahulukan kepentingannya sendiri. Ia seolah hidup untuk memastikan Rafa tetap hidup.
Hari ini, Sera duduk sendirian di sudut ruang seni. Di hadapannya ada sebuah kanvas dengan lukisan yang baru saja ia selesaikan. Dalam lukisan itu, waktu seolah berhenti di dalam laut yang hening. Ada seorang perempuan melayang di batas antara cahaya dan kegelapan laut, dengan tubuh yang membentuk lengkungan anggun— nyaris tampak seperti tarian terakhirnya. Gaun putih yang membalut tubuhnya melambai lembut mengikuti arus air. Salah satu tangannya terangkat, seolah berusaha menggapai permukaan laut yang tampak seperti satu garis tipis.
Apakah ia sedang membiarkan dirinya tenggelam, atau justru sedang berusaha untuk naik ke permukaan? Sejujurnya, Sera sendiri tidak tahu. Ia hanya membiarkan tangannya menari di atas kanvas, dan mengeluarkan apa saja yang ada di dalam kepalanya. Dan ketika akhirnya ia menyelesaikannya, lukisan itu justru tampak seperti sebuah kesedihan yang tidak bisa ia ungkapkan.
Sera tidak lelah, apalagi jengah. Tidak sama sekali. Ia hanya mulai merasa kewalahan. Ia takut dirinya tidak lagi cukup menjadi alasan untuk Rafa melanjutkan hidupnya.
“Sera?”
Mendengar seseorang memanggil namanya, Sera mengalihkan pandangannya dari kanvas di hadapannya. Di dekat pintu masuk, Hilmy berdiri sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Lalu, laki-laki itu berjalan mendekati Sera dengan dua kaleng minuman di tangannya.
“Kok tahu kalau gue ada di sini?” tanya Sera, setelah menerima satu kaleng minuman dari Hilmy.
Sementara laki-laki itu, menarik kursi untuk didekatkan pada Sera dan duduk tepat di sampingnya. “Tadi gue ketemu Rafa di parkiran. Dia bilang kalau lo masih di sini dan nggak mau diajakin pulang. Jadi dia minta gue buat ke sini nemenin lo.”
Sera mengangguk sambil tersenyum tipis.
Begitulah Rafa. Ia seolah tahu kapan Sera membutuhkan sedikit jarak untuk bisa bernapas lebih lega. Rafa tahu, bahwa berada di dekatnya tidak pernah mudah untuk Sera. Namun, Rafa juga tahu persis, bahwa ia tidak akan bisa merelakan Sera untuk melangkah pergi dari hidupnya. Sebut saja Rafa egois, tidak apa-apa. Rafa rela menjadi manusia paling egois di bumi, asal Sera bisa terus berada di sekitarnya.
“Lo udah nggak ada kelas?” tanya Sera, dan Hilmy menjawabnya dengan gelengan.
“Ini lo yang ngelukis?” tanya Hilmy. “Kenapa vibes-nya sedih gini, deh? Apa perasaan gue aja?”
Untuk beberapa saat, Sera sempat terdiam. Alih-alih segera menjawab pertanayaan Hilmy, Sera justru kembali menatap lukisannya dan mengambil napas dalam-dalam.
“Hil,” panggil Sera lirih, lalu ia menoleh pada Hilmy yang menatapnya dalam diam. “Menurut lo, kalau kebahagiaan bisa dinilai dengan uang, berapa banyak yang harus lo punya? Satu milyar? Dua milyar? Seratus milyar?”
Hilmy terkekeh sebentar, lalu membuka kaleng minumannya sebelum akhirnya menjawab. “Hmmm ... sepuluh ribu, mungkin?” Dia meneguk minumannya.
“Sepuluh ribu?”
“Sepuluh ribu udah cukup buat beli dua gorengan dan es teh. Sambil duduk di bawah pohon mangga punya Mang Udin, sambil makan gorengan dan nyruput es teh panas-panas gini juga bisa bikin perasaan bahagia, kan?”
Sera terkekeh pelan. “Andai hidup bisa sesimpel itu, ya ....”
Untuk beberapa saat, tidak ada yang terdengar dari mulut keduanya. Ruangan itu hanya diisi oleh suara detak jam dinding yang menggantung di tembok.
Mencintai Sera tidak pernah mudah bagi Hilmy. Sera selalu punya segudang rahasia yang tidak akan ia ungkapkan pada siapapun, termasuk padanya. Terkadang, ia bisa mendorong Hilmy begitu jauh, seolah ingin menegaskan bahwa laki-laki itu tidak akan pernah bisa memilikinya.
“Lo lagi kenapa?” tanya Hilmy setelah bermenit-menit menatap Sera dalam diam. “Mau cerita, nggak?”
Sera tersenyum, lalu menggeleng setelahnya. “Gue cuma lagi ngerasa kalau hidup, tuh, suka banget mempermainkan gue. Kadang hidup bisa baiiiik banget, tapi kadang bisa jahat banget sampai nggak kasih gue jeda untuk istirahat.”
“Meskipun hidup nggak baik sama lo, Ser, lo tetep harus baik sama diri sendiri. Boleh, kok, istirahat kalau lo lagi capek. Lo boleh nangis kalau emang perlu. Lo juga manusia, Ser. Lo nggak akan terlihat lemah cuma karena nangis.”
Lalu, mereka kembali terdiam. Sera tidak tahu tanggapan macam apa yang harus ia lontarkan untuk ucapan Hilmy barusan. Tidak ada yang salah soal itu— Hilmy sepenuhnya benar. Hanya saja, Sera tidak pernah mengijinkan dirinya untuk menangis, entah sejak kapan. Hingga hari ini ketika Hilmy mengatakan sesuatu seperti itu, Sera merasa seolah dikuliti hidup-hidup. Ia merasa kepalanya sakit, dan matanya memanas tanpa sebab yang jelas. Sera tidak tahu pasti apa yang kini sedang ia rasakan.
“Lukisan lo rame banget, ya.” Hilmy mencoba memecah keheningan.
“Rame? Kebanyakan warna maksudnya? Ini cuma biru gelap, putih, sama—”
“Bukan itu,” sela Hilmy. “Gue rasa ada banyak hal yang pengen lo sampein di lukisan ini, tapi yang kegambar justru kesunyian yang menyedihkan.”
Hilmy terkekeh pelan, lalu menunjuk pada kepala perempuan yang berada dalam lukisan. “Di dalam situ yang rame. Saking ramenya dia sampe cari ketenangan di laut yang gelap itu. Tapi dia nggak sadar, Ser, menenggelamkan diri nggak akan bikin apa yang ada di dalam kepalanya lantas berhenti menyalak. Justru bisa jadi dia malah mati tenggelam bareng pikiran-pikirannya yang rumit itu.”
“Gue ngaco, ya?” kata Hilmy lagi. “Maksud lukisanya pasti bukan itu. Wah ... ini dia alesannya kenapa gue nggak cocok sama seni.” Ia kemudian tertawa pelan diujung kalimatnya.
“Nggak, lo bener.” Sera menunduk dan memainkan ujung-ujung kukunya. “Gue lagi— apa, ya? Gue tuh nggak bisa jelasinnya.” Ia terkekeh sebentar. “Gue takut kalau ternyata diri gue nggak akan pernah cukup untuk orang lain.” Sera turut menunjuk kepala perempuan dalam lukisannya. “Di dalam sana rame banget. Sayangnya, dia terlalu takut buat ngeluarin semua yang ada di kepalanya. Dia nggak mau ditinggalkan lagi.”
“Seberapa sering dia ditinggalkan, sampe dia mikir kalau ngeluarin apa yang ada dalam kepalanya bakalan bikin orang-orang pergi?”
Sera memutar tubuhnya, hingga kini ia menatap Hilmy sepenuhnya. Ia menatap mata Hilmy begitu dalam, sampai-sampai Hilmy dibuat salah tingkah oleh tatapan itu. Hilmy hampir saja mengeluarkan candaan, sebelum akhirnya Sera kembali menunduk dan menghela napas panjang yang terdengar berat.
“Papa dan Mama pisah waktu gue kelas dua SMP. Sebenernya mereka udah lama pisah rumah, tapi pas gue kelas dua itu, mereka bener-bener memutuskan buat cerai. Papa menikah lagi, dan pergi nggak tahu kemana. Gue nggak tahu kabar dia sampe sekarang. Gue nggak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Yang gue tahu, dia ninggalin gue dan Mama demi perempuan lain.”
Sera meremat ujung baju yang ia kenakan. “Waktu gue mau masuk SMA, Mama tiba-tiba bawa laki-laki yang nggak gue kenal ke rumah. Katanya, dia calon papa baru gue. Katanya, dia yang bakalan bayarin sekolah gue dan gantiin Papa. Mama bener, laki-laki itu penuhin semua yang gue butuhin. Bahkan dia bayarin les balet gue setahun penuh. Tapi nggak lama, gue lihat Mama nangis-nangis di dapur. Katanya laki-laki itu juga ninggalin Mama, sama kayak Papa.”
“Gue pikir, Mama udah bakalan nyerah sama laki-laki waktu itu. Ternyata gue salah.” Sera menatap Hilmy dengan matanya yang mulai basah. “Mama justru lebih sering ganti-ganti pasangan sejak saat itu. Mama sering ninggalin gue sendirian di rumah. Sampai akhirnya, gue memutuskan buat tinggal sama Eyang. Baru delapan bulan gue pindah ke rumah Eyang, beliau meninggal karena serangan jantung. Mau nggak mau gue harus balik ke rumah Mama, meski sebenernya pindah ke rumah Mama juga sama aja kayak tinggal sendirian.”
Ada jeda yang cukup lama di sana. Meski begitu, Hilmy tidak ingin mengatakan apa-apa. Ia tahu, Sera masih ingin berbicara lebih banyak. Jadi yang bisa ia lakukan hanya menepuk-nepuk bahu Sera, sambil berharap bahwa tepukan itu bisa memberinya sedikit ketenangan.
“Gue suka Balet, Hil,” kata Sera setelah bermenit-menit diam. “Gue ikut les balet dari TK, dan gue pengen jadi balerina terkenal. Tapi pas gue memutuskan untuk berhenti dan bilang ke Mama kalau gue mau masuk seni rupa, Mama nggak peduli. Mama bahkan nggak pernah tanya kenapa gue tiba-tiba milih untuk masuk seni rupa padahal gue nggak suka gambar. Yang ada di pikiran Mama cuma gimana caranya untuk membuktikan sama Papa, kalau dia juga bisa hidup bahagia dengan laki-laki lain. Dia nggak pernah mikirin kebahagiaan gue.”
“Diantara semua kejadian yang ada dalam hidup gue— Rafa selalu ada di sana. Dia satu-satunya keluarga yang gue punya. Gue sama dia udah bertahun-tahun bareng, dan gue nggak pernah siap untuk kehilangan satu-satunya orang yang peduli sama hidup gue.”
Satu-satunya orang, katanya?
“Gue tahu dia nggak bakalan ninggalin lo, Ser.” Ada banyak hal di dalam kepala, yang ingin Hilmy sampaikan. Namun, pada akhirnya hanya kalimat itu yang mampu keluar dari mulutnya. Ia tidak tahu lagi bagaimana untuk membuat Sera sadar bahwa dirinya juga sama pedulinya dengan Rafa. Bahwa ia juga akan merangkul Sera, bahwa dirinya juga menganggap Sera berharga, sama seperti Rafa.
“Nggak, Hil,” kata Sera dengan suaraya yang bergetar. “Lo nggak pernah tahu apa-apa.”
Ketika mengatakan itu, air mata Sera akhirnya luruh. Ia menangis persis seorang anak yang kehilangan balonnya. Benar. Hilmy tidak tahu apa-apa. Ia tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup Sera, karena gadis itu tidak pernah mengijinkan Hilmy menyentuh hidupnya lebih jauh dari ini. Seolah Sera tidak tahu bahwa Hilmy siap memeluk semua yang ada dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa rumitnya, tidak peduli seberapa sulitnya.
Atau barangkali, Sera memang tidak menginginkan Hilmy untuk ada dalam hidupnya.


 marindya
marindya