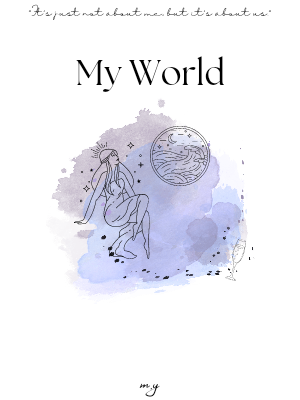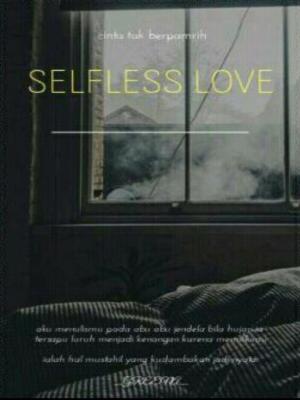Setiap perjalanan selalu dimulai dengan sesuatu yang dikemas. Entah itu baju, kenangan, atau perasaan-perasaan yang belum sempat dibereskan. Dan pagi itu, Aluna duduk di lantai kamarnya, di depan koper terbuka, dengan ekspresi yang tak bisa dipastikan—antara siap dan enggan. Tiket kereta pagi ke Jakarta sudah dipesan sejak seminggu lalu. Tapi tiket untuk meninggalkan rasa bersalah, belum tersedia.
“Baju udah semua, Nak?” tanya Ibu dari balik pintu.
“Udah, Bu… kayaknya.”
“Jangan lupa bawa sweater. Jakarta AC-nya bisa lebih dingin dari desa kita,” ujar Ibu dengan tawa pelan.
Aluna tersenyum. “Iya, Bu. Aku bawa.”
Tapi bukan dingin AC yang sedang ia pikirkan. Ada hawa sepi yang pelan-pelan menyelusup ke dalam dadanya, dan tidak ada sweater mana pun yang bisa menahannya. Tiap kali Aluna menutup ritsleting koper, ia merasa sedang menutup satu bab yang belum benar-benar selesai. Meninggalkan rumah selalu punya dua sisi—lega karena akan kembali ke rutinitas, tapi juga sesak karena belum tentu ada kesempatan berikutnya untuk menikmati hal-hal kecil di rumah: teh hangat buatan Ibu, suara ayam berkokok dari belakang rumah, atau bahkan piring keramik yang retak tapi tetap dipakai karena "masih bisa, kok".
Ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap koper itu.
Koper besar berwarna biru tua yang sudah menemaninya sejak kuliah. Ada stiker lucu di sisi kanan yang sudah mulai mengelupas. Di dalamnya ada baju kerja, oleh-oleh dari pasar, dan sebuah surat dari Ibu yang baru ia temukan tadi malam di meja makan, tanpa nama, hanya tulisan tangan kecil: Untuk perjalanan yang panjang, jangan lupa pulang.
Surat itu seperti peluk yang ditulis. Dan peluk yang ditulis tidak pernah gagal membuat matanya panas.
Di stasiun, suasananya sibuk seperti biasa. Orang-orang datang dan pergi, membawa koper dan rindu masing-masing. Aluna berdiri di dekat pintu masuk, menggenggam tiket di satu tangan, dan ponsel di tangan lain. Notifikasi grup kerja berdenting beberapa kali. Ia abaikan.
Kepalanya sibuk sendiri.
“Kalau kamu udah masuk kerja, jangan terlalu sering begadang,” pesan Ibu tadi pagi sambil menyelipkan bekal kecil di tas Aluna.
“Iya, Bu. Aku usahain.”
“Dan jangan lupa, sesekali telepon. Rumah ini kadang terlalu sepi.”
Aluna hanya mengangguk waktu itu. Sekarang, di tengah kerumunan orang, suara Ibu itu justru paling jelas terdengar di kepalanya. Ia memejamkan mata sebentar. Mencoba menata ulang pikirannya. Pulang selama dua minggu ini telah mengaduk banyak hal dalam dirinya. Hal-hal yang selama ini disembunyikan di balik kerja keras, deadline, dan kafein. Bahwa ia bukan hanya rindu rumah, tapi juga rindu menjadi dirinya sendiri—yang tidak harus kuat setiap hari, yang bisa menangis tanpa merasa lemah, yang bisa diam tanpa dituntut untuk menjelaskan semuanya. Kereta datang, perlahan dan panjang. Suaranya memecah pagi yang mulai hangat. Orang-orang mulai bergerak. Aluna menarik koper, berjalan mengikuti arus penumpang, dan sesekali menoleh ke belakang, seperti berharap melihat seseorang berdiri di sana dan berkata, “Jangan pergi dulu.”
Tapi tidak ada siapa-siapa.
Dia memang harus pergi. Tapi hatinya belum sepenuhnya ikut. Di dalam gerbong, ia duduk di dekat jendela. Pemandangan luar mulai bergeser—sawah, rumah-rumah, jalan kecil tempat anak-anak bermain, semua perlahan hilang dari pandangan. Ia bersandar, membuka bekal dari Ibu—nasi goreng sederhana, dengan telur dadar dan kerupuk.
Di bawah tutup kotaknya, ada catatan kecil:
Makan ya. Jangan cuma kerja, hidup juga harus dinikmati. - Ibu
Aluna menahan napas. Bukan karena nasi goreng itu pedas. Tapi karena hidup kadang terlalu manis untuk ditinggal tergesa-gesa. Beberapa jam perjalanan, Aluna melihat keluar jendela. Langit mulai mendung, dan hujan turun pelan-pelan. Seperti mendukung perasaannya yang sendu. Seperti semesta ingin bilang, "Nggak apa-apa, kalau kamu belum sepenuhnya siap kembali ke rutinitas." Ia membuka buku catatan kecil yang selalu dibawanya—tempat ia menuliskan hal-hal acak. Ia menulis:
Pulang tidak selalu menyelesaikan semuanya, tapi ia memberi jeda. Dan kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi jeda. Untuk duduk. Menangis. Tersenyum. Lalu melangkah lagi.
Ia berhenti menulis, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Betapa anehnya hidup—kita sibuk mencari arti di tempat jauh, padahal rumah menyimpannya sejak awal.
Saat kereta mulai mendekati kota, suasananya berubah. Gedung-gedung tinggi mulai terlihat, jalan-jalan besar, suara klakson, dan wajah-wajah yang seperti lupa cara tersenyum. Kontras sekali dengan desa kecilnya, yang masih punya waktu untuk menyapa tetangga dan mendengar suara jangkrik malam hari. Aluna menghela napas. Ia tahu, kehidupan ini menantinya kembali. Dan ia tidak akan lari darinya. Tapi ia juga tahu, hatinya telah berubah. Ia akan kembali bekerja, ya. Tapi kali ini, ia akan membawa rumah bersamanya. Dalam bentuk teh hangat tiap malam. Dalam bentuk telepon rutin ke Ibu. Dalam bentuk senyum pada orang asing. Dalam bentuk sabar pada diri sendiri.
Karena rumah bukan sekadar tempat, tapi cara hidup.
Sampai di stasiun akhir, ia turun sambil menarik koper. Berat, ya, tapi bukan cuma karena barang di dalamnya. Tapi karena ada bagian dari hatinya yang ingin tertinggal di stasiun sebelumnya. Seorang anak muda di sebelahnya sedang menelepon, suaranya riang, “Iya, Bu! Aku udah sampai. Nanti aku cerita ya…” Aluna tersenyum. Kadang, panggilan telepon itu cukup untuk membawa pulang sebagian dari rumah. Ia berjalan keluar, menatap langit kota yang mendung. Lalu menarik napas dalam-dalam. Dan melangkah. Malamnya, setelah kembali ke kos, ia menata koper dengan pelan. Satu per satu baju ia keluarkan. Di antara lipatan baju, ia menemukan satu benda kecil: kerajinan tangan dari rotan yang dibelikan Ibu dari pasar. Ada catatan kecil yang tertempel: Biar kosanmu ada sentuhan rumah.
Aluna duduk, memegang benda itu, dan akhirnya menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena bersyukur. Bahwa meski hidup kadang melelahkan, kita masih bisa menemukan sudut-sudut hangat seperti ini—dimana pun kita berada.
Sebelum tidur, ia mengirim pesan pada Ibu:
Bu, makasih buat semuanya. Aku udah sampai, dan aku bawa rumah kita di hati aku.
Pesan terkirim. Beberapa menit kemudian, balasan masuk:
Ibu juga makasih. Jangan lupa istirahat. Kalau kamu capek, ingat ya… rumah nggak ke mana-mana. Tinggal pulang.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_