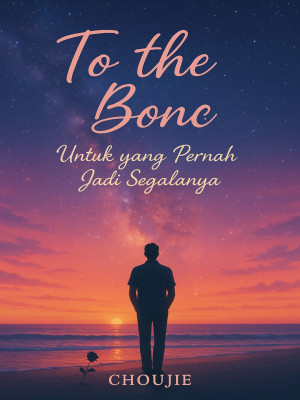Langit sore menyambut kepulangan Kirana dengan warna keemasan yang tenang. Udara di kampung halaman lebih segar, lebih jujur, seakan alam tahu, hati yang pulang tak selalu dalam keadaan utuh.
Sudah tiga hari Kirana di rumah. Ia membantu ibu menyiapkan kue pesanan, mengajari adik-adiknya yang bertanya tentang pelajaran sekolah yang tidak mereka mengerti, bahkan ikut menata ulang warung kecil di teras depan. Ada tawa yang muncul di sela-sela percakapan makan malam mereka, ada kehangatan yang selama ini ia rindukan, tapi lupa bagaimana rasanya.
Namun, di dalam dirinya ada ruang kosong yang belum terisi. Seperti ada satu bagian dari dirinya yang masih tertinggal di kota itu, di antara buku-buku referensi dan jurnal-jurnal yang berdebu, serta laboratorium yang jadi saksi ketidakadilan.
Malam itu, langit menggantung kelabu, tetapi hujan tak lagi turun. Di teras rumah kayu sederhana yang dikelilingi ladang sunyi, Kirana duduk di sebelah ibunya. Tak ada percakapan besar. Hanya secangkir teh hangat, dan bunyi serangga malam yang bersahutan.
Kirana memeluk lututnya, pandangannya kosong ke ujung jalan yang gelap.
Ibu melirik sejenak. “Tadi pagi kamu bantu nyapu halaman ya?”
Kirana mengangguk tanpa menoleh. “Cuma nyoba jalan-jalan, Bu.”
Ibu Kirana tersenyum hangat. Setidaknya Kirana sudah lebih mau terbuka dibandingkan beberapa bulan lalu. Ternyata memang benar, yang anaknya paling butuhkan dari luka itu adalah waktu.
“Akhir-akhir ini kamu kelihatan lebih tenang,” ucap ibu perlahan. “Tapi Ibu tahu… hatimu belum benar-benar pulih.”
Kirana hanya menatap cangkir teh di tangannya. Uapnya mengembun di sekitar bibir gelas, mengingatkannya pada pagi-pagi penuh harapan yang dulu pernah ia punya.
Ibu menoleh ke tanaman di pekarangan rumah mereka yang sederhana, ada beberapa tanaman obat keluarga yang dulu Kirana mulai tanami di sana. Di genggaman tangannya ada beberapa kertas dengan bekas remukan. Beberapa kertas yang Kirana tempel di sisi meja belajarnya sejak SMA. Daftar impiannya. “Jadi apoteker,” “Bikin formulasi sendiri,” “Bantu orang lain lewat ilmu,” kata-kata yang ditulis tangan dengan spidol warna-warni. Kertas-kertas yang 9 bulan lalu Kirana lepaskan dari posisinya dan ia remuk kemudian buang di tong sampah.
“Kamu tahu, waktu kamu nulis semua itu dulu, kamu pernah bilang ke Ibu, ‘Aku mau bikin Papa bangga.’” Ibu Kirana menunjukkan kertas-kertas itu.
Kertas yang ia pungut dan tidak sanggup untuk dibuang karena ia yakin, impian anaknya belum sepenuhnya mati.
Kirana menelan ludah. Menatap remukan kertas, matanya mulai memanas. Ada kenangan berisi semangatnya yang menyala-nyala di sana.
“Dan kamu sudah membuat kami bangga, Nak. Bahkan sebelum kamu lulus. Tapi kamu belum selesai,” lanjut ibu, suaranya pelan tapi tegas. “Kamu punya mimpi. Kamu punya tujuan. Jangan biarkan orang yang menjatuhkanmu merasa berhasil.”
Kirana menggigit bibir. “Bu… aku takut. Kalau nanti aku balik dan gagal lagi? Kalau semua itu cuma bikin luka baru?”
Ibu tersenyum. Ia mengelus kepala Kirana dengan lembut, seperti waktu Kirana kecil dan ketakutan karena petir.
“Takut itu wajar. Tapi menyerah… bukan sifatmu. Kamu Kirana. Anak Ayah yang dulu selalu bilang, ‘Kalau belum nyoba lagi, belum boleh bilang selesai.’ Ayah pasti juga nggak mau kamu berhenti di sini.”
Kirana tak sanggup berkata-kata. Air mata jatuh tanpa suara. Ibu merengkuhnya dalam pelukan hangat, seperti menyatukan kembali kepingan hatinya yang selama ini berserakan.
Ibu tersenyum tipis. “Kamu nggak pernah lemah Kirana.”
Kirana tak menjawab. Ia tahu tubuhnya mulai pulih. Tapi tidak hatinya.
Diam merayap. Lalu, tiba-tiba, Ibu membuka suara dengan nada penuh kenangan. “Masih ingat waktu kecil kamu sering sakit demam?”
Kirana menoleh sekilas. “Ingat...”
“Setiap kamu panas tinggi, Ayahmu panik. Tapi tetap aja, dia yang paling tega maksa kamu minum sirup obat rasa buah itu. Yang kamu bilang rasanya kayak... plastik dicampur karet ban.”
Kirana tertawa kecil, meski matanya masih sayu. “Karena memang aneh, Bu.”
“Tapi selalu berhasil, ya?” Ibu menatap langit. “Besoknya kamu udah main sepeda muterin rumah, seolah nggak terjadi apa-apa.”
Kirana mengangguk perlahan, lalu berbisik, “Waktu itu, aku pikir obat itu semacam sihir. Nggak enak, tapi bisa menyembuhkan.”
“Dan kamu suka nanya: ‘Kenapa bisa begitu?’”
Kirana menghela napas. “Pertanyaan yang lama nggak bisa Kirana jawab.”
Ibu tersenyum pelan. “Pas SMA, kamu makin penasaran, kan? Ibu inget kamu pernah pulang bawa plastik isi daun-daunan aneh. Katanya buat lomba karya tulis.”
“Tanaman herbal. Aku bikin daftar yang katanya bisa bantu turunin gula darah.”
“Cuma daftar?”
Kirana tersenyum kecil. “Ya. Niatnya riset, tapi keterbatasan alat... ya sudah. Nggak menang.”
Ibu menyeruput teh. “Tapi dari situ kamu mulai baca buku. Tanya-tanya ke tukang jamu. Sering ngelamun depan rak obat di apotek. Kamu pernah bilang ke Ayah: ‘Kalau udah gede, aku mau ngerti kenapa obat bisa nyembuhin.’”
Kirana menunduk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak menangis.
“Pas kamu diterima di Farmasi,” lanjut Ibu, suaranya mulai lirih, “Ayahmu bahagia sekali. Katanya, akhirnya pertanyaan anak kecil itu akan terjawab.”
Kirana mengepalkan tangan di pangkuannya. “Tapi Ayah nggak sempat lihat aku bisa jawab pertanyaan masa kecil itu, Bu.”
Ibu menoleh, menatap wajah Kirana yang mulai basah oleh air mata. “Ayah mungkin nggak lihat dengan mata. Tapi dia percaya kamu bisa. Dan itu cukup.”
Hening. Hanya bunyi angin melintasi sela-sela dedaunan.
Pelan, Kirana berkata, “Waktu kuliah, aku mulai ngerti. Obat itu bukan sihir. Tapi ada senyawa-senyawa di balik rasa pahitnya. Yang diam-diam bantu tubuh pulih. Nggak kelihatan, tapi nyata.”
Ia menoleh pada Ibu, suaranya nyaris berbisik. “Dari situ aku sadar… jadi farmasis itu bukan cuma soal campur-campur zat. Tapi soal memahami. Membantu. Jadi jembatan antara ilmu dan harapan.”
Ibu tak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Kirana erat—hangat, seperti dulu, saat Kirana kecil dan demam tinggi, menggigil dalam pelukan.
Beberapa saat mereka diam. Dedaunan bergesek perlahan, seperti ikut menyimak.
“Kamu tahu …” Ibu akhirnya bersuara, lembut dan dalam “… tadinya Ibu memang ingin kamu pulang dulu. Tapi lebih dari itu... Ibu ingin kamu pulih. Benar-benar pulih. Bukan cuma lukanya. Tapi semangatmu untuk bisa memulai lagi.”
Kirana menunduk. Genggaman Ibu menyalurkan sesuatu yang selama ini tak ia sadari ia butuhkan. Pengakuan, penerimaan, dan izin untuk lemah sejenak.
Ia menarik napas dalam-dalam. Ada yang menghangat di dadanya, tapi juga perih. Perih karena ia menyadari betapa lama ia membiarkan dirinya tenggelam. Betapa selama ini ia hidup dalam keheningan, menggantung harapan di langit-langit kamar mess, menunda rasa sakit karena takut tak sanggup menghadapinya. Dan kini, di rumah kecil yang dulu ia tinggalkan, di bawah langit malam yang mulai jernih, ia perlahan mulai mendengarkan dirinya sendiri lagi.
Ia belum sepenuhnya bangkit. Masih banyak luka yang butuh waktu untuk sembuh. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kirana merasa: mungkin ia tidak benar-benar hancur. Mungkin ia hanya tersesat sejenak.
Dan itu tidak apa-apa.
Ia menatap ibunya. Ada mata keriput, tetapi teduh yang menyimpan doa-doa diam.
“Ibu…” bisiknya, nyaris tak terdengar. “Kalau aku coba mulai lagi… dari awal… kira-kira aku bisa?”
Lalu Ibu kembali bicara. Suaranya pelan, tapi kali ini ada harapan di balik kelembutannya.
“Bukan kira-kira. Kamu bisa. Dan Ayahmu pasti percaya itu juga.”
Jeda lagi di antara mereka.
“Nak… kamu sudah memulai ini dengan sepenuh hati.”
Ia berhenti sebentar, seolah ingin memastikan Kirana mendengarkan setiap kata.
“Kamu belajar, kamu berjuang keras, bahkan berusaha berdiri lagi waktu semua rasanya hilang. Ibu tahu itu enggak mudah.”
Kirana tetap menunduk. Matanya mulai basah.
“Jangan biarkan semua usahamu berhenti di tengah jalan.”
Nada Ibu mengeras sedikit, bukan marah, tapi berakar dari cinta yang dalam.
“Jangan biarkan orang yang menyakitimu merasa menang. Jangan biarkan mereka pikir mereka bisa menjatuhkanmu... dan kamu enggak bangkit lagi.”
Ia meremas lembut tangan Kirana. “Ibu tahu kamu luka. Tapi kamu juga kuat, Nak. Lebih kuat dari yang kamu bayangkan.”
Kirana tidak menjawab. Tapi kali ini, ia tidak merasa hampa. Hatinya tak lagi hanya memuat kehilangan. Ada sedikit ruang yang terbuka—untuk percaya, untuk mencoba lagi, meski perlahan.
Dan mungkin, dari bara kecil itu, nyala yang lebih besar bisa tumbuh kembali.
“Ini.” Kali ini ibu Kirana menyerahkan sebuah kartu ATM. “Uang hasil kerja Kirana selama 9 bulan ini ibu usahakan tidak dipakai.”
Mata Kirana Kembali berembun. “Tapi, Bu ….” Ia tahu benar bagaimana keadaan ekonomi mereka yang morat-marit setelah kepergian sang ayah.
“Ibu nggak terlalu mengerti, tapi sepintas yang Ibu tahu, penelitianmu butuh banyak biaya. Ibu … belum mampu bantu kamu. Seenggaknya ini yang bisa Ibu lakukan.” Ibu Kirana menangkupkan kartu itu ke tangan Kirana.
“Ibu yakin, kamu siap memulai lagi.”
Kirana tidak sanggup memberikan balasan. Hanya ada ibu dan anak yang saling berpelukan dan menguatkan. Kirana meyakinkan dirinya lagi, menyalakan bara kecil di hatinya agar makin membara. Kali ini ia tidak akan menyerah semudah itu. Ia tak boleh mengalah pada keadaan atau ketidakadilan.
***
Di kamar kos yang sempit, Kirana kembali memupuk semangatnya. Ia ingat luka yang sudah ia alami terlebih janji pada diri sendiri di malam ia memutuskan untuk kembali memperjuangkan penyelesaian skripsi. Ia tidak akan pasif lagi. Ia tidak akan begitu mudah pasrah menerima keadaan, manipulasi-manipulasi dari Vania.
Kirana tahu, ia mungkin bukan siapa-siapa, tapi ia juga bukan orang bodoh yang tidak bisa melawan.
Tadi ibunya baru menelepon, menanyakan kabar juga perkembangan skripsinya. Kali ini Kirana berusaha jujur, tidak lagi menutupi apa-apa apalagi berkamuflase sok kuat seolah bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Ia yakin, dengan tahu keadaan sebenarnya, ibunya bisa memberikan doa yang paling tepat.
“Mereka mungkin bisa membuat ‘makar’, tapi yakinlah, Nak. ‘Makar’ Allah lebih hebat.” Itu yang dikatakan ibu Kirana.
Kirana menghela napas, melipat sajadahnya. Ia tahu, langkah apa yang harus ia ambil.
Tangannya lihai mengetik di laptop tua pemberian Om Deni, pengganti laptop lamanya yang hancur saat kecelakaan. Ia tahu betapa sulit pamannya menyisihkan uang untuk membeli laptop second itu. Ia tahu, di dalamnya juga terselip harapan dan dukungan nyata dari adik ayahnya itu agar Kirana kembali semangat menyelesaikan studi.
Di ponselnya, Kirana menekan sebuah kontak. Ia akan maksimalkan seluruh bantuan yang bisa ia dapat.
Besok, perjuangan Kirana akan dimulai kembali.


 asih_3a
asih_3a