Terhitung udah tiga hari setelah kejadian itu, gue benar-benar nggak ngobrol sama Ibu atau Selly. Kalau biasanya mereka yang memulai memusuhi gue, kali ini gue yang menghindar. Gue butuh waktu buat sendiri setelah hari yang panjang. Luka itu nyata dan gue sendiri yang melakukannya. Jadi, untuk sementara, sebisa mungkin gue menghindari hal-hal yang bisa bikin gue marah.
Gue pergi dari pagi karena harus ke rumah sakit buat melakukan pemeriksaan seperti yang dijadwalkan. Cuma endoskopi dan cek darah, sedangkan CT-Scan nggak bisa dilakukan di hari yang sama. Kalau nggak salah masih ada lagi, pemeriksaan patologi anatomi atau apa gue nggak ngerti. Gue makin takut. Takut kalau ternyata emang separah itu. Karena rasa sakitnya masih ada, mual muntah juga menetap, rasa nggak nyaman di perut makin aneh-aneh setiap harinya biarpun udah minum obat.
Pas tadi mau diambil darah, petugasnya mungkin lihat luka di tangan gue. Dia langsung tanya, “A, itu tangannya kenapa? Aa ada teman buat cerita nggak? Kalau nggak ada, Aa bisa datang ke profesional. Biar bisa cerita, dan kalau butuh terapi obat nanti pasti dikasih obat supaya Aa lebih tenang."
Tapi, gue memilih buat nggak menjawab dan cuma senyum tipis. Karena jujur gue masih berkubang dalam kebingungan yang sama. Kenapa gue bisa melakukan hal ekstrem kayak gitu cuma karena merasa nggak berguna dan marah? Gue berusaha mengalihkan pikiran dari kejadian itu, karena sakitnya masih jelas. Sangat sakit dan nggak bisa gue atasi sampe gue butuh pelampiasan.
Selesai cek darah, gue diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lain. Harus antre lagi buat endoskopi, beruntung hari ini nggak terlalu rame jadi sedikit lebih cepat. Gue diminta masuk, berbaring dengan posisi miring ke kiri. Petugas menyemprotkan sesuatu yang sepertinya anestesi lokal karena setelah itu area tersebut langsung mati rasa.
"Tarik napas lewat hidung pelan-pelan, ya. Tolong jangan dilawan."
Saat mereka memasukkan alat berupa selang lentur dengan kamera kecil di bagian ujung, tubuh gue tegas menolak, refleks muntah muncul walaupun perut kosong karena diharuskan puasa.
Dokter mengamati dengan saksama, terlihat dari rautnya yang serius, dan nggak lama tiba-tiba aja dia bilang, "Kita menemukan sesuatu yang mencurigakan. Nanti kita kirim sampel jaringannya ke bagian Patologi Anatomi, ya. Hasilnya kemungkinan keluar dalam tujuh hari atau empat belas hari."
Setelah itu gue diminta menunggu tiga puluh menit, dan dilarang minum atau apa pun selama satu jam ke depan setelah endoskopi. Dokter juga menjelaskan soal ketidaknyamanan pasca pemeriksaan itu dan gue cuma mengiakan.
Pas lagi duduk bengong, HP gue tiba-tiba bunyi. Ternyata ada satu pesan masuk dari Lala. Dengan cepat gue membacanya. Dia cukup bawel dari pagi buta.
Lala
Nu, gimana? Udah ada hasilnya? Apa katanya? Jangan bandel lo. Ikutin apa yang dokter suruh oke?
Gue baru tau kalau Lala, tuh, sebawel ini. Terutama setelah tau gue sakit. Alasannya, sih, nggak mau sampai jaga sendiri terus atau berdua sama Cantika, tapi gue merasa ketakutannya lebih dari itu. Tiap kita jaga pagi, dia selalu mastiin gue sarapan. Kalau gue mulai kelihatan pucat di matanya, gue harus banget istirahat, nggak boleh nggak. Kalau gue nggak nurut, dia puasa ngomong sama gue seharian. Dia cewek yang baik, cuma emang agak barbar dan nggak bisa diam aja.
Saya
Gue belum dapat hasilnya, La. Katanya nanti dikabarin lagi kalau hasilnya udah ada. Ini baru mau otw klinik sekarang. Sorry, ya, lo jadi harus nunggu lama.
Lala
Nggak masalah. Hari ini gue nggak pulang rencananya.
Sebenarnya gue nggak enak. Lala jadi harus nunggu lebih dari dua jam karena gue telat. Tadinya gue berpikir kalau pemeriksaan ini bisa cepat, jadi nggak apa-apa gue ke rumah sakit bukan pas jadwal libur, ternyata lumayan lama apalagi antre berkali-kali dari pendaftaran sampai pemeriksaan.
Setelah jam tunggu selesai dan beres ngembaliin berkas, gue langsung ke klinik. Kalau jaga sore udah otomatis ada Selly, gue nggak tau gimana caranya menghindar dari dia. Sakit banget rasanya setiap ingat apa yang dia bilang. Harusnya nggak separah ini, kan? Apalagi gue tau banget Selly gimana. Sayangnya, nggak sesederhana kelihatannya. Setiap kami beradu tatap, semua omongan dia yang terekam hari itu, berputar otomatis di kepala.
Begitu gue turun dari ojek online, Lala langsung lari-larian nyamperin kayak anak kecil. Gue ketawa. Kali ini gue cuma beliin dia es pisang ijo yang ada di dekat rumah sakit, dan itu aja bikin dia heboh banget.
Dia nggak terlihat sungkan sama sekali dan langsung makan dengan lahapnya. Cuma sama dia gue merasakan perasaan sebahagia ini. Mungkin karena Lala nggak pernah melihat gue sebagai orang susah setelah masalah utang obat waktu itu. Gue kasih makanan, dia makan. Ditanya mau apa, dia jawab tanpa basa-basi atau bilang terserah. Es pisang ijo ini salah satu permintaannya. Dia tau cara memperlakukan orang lain dan bikin orang itu merasa nggak rendah diri.
"Nu, perasaan gue aja atau lo sama Selly lagi saling diam? Kalian ada masalah, ya?"
Gue yang sebelumnya diam sambil senyum-senyum lihatin dia makan es pisang ijo sedikit kaget sama pertanyaannya. Dia sadar juga ternyata. Mungkin perubahan sikap gue ke Selly kentara banget perubahannya, jadi Lala sadar. Kalau udah gini, bohong juga percuma, kan?
"La, lo tipe orang yang bisa dipercaya nggak?"
"Harusnya gue tersinggung, ya, ditanya kayak gitu. Tapi, biar lo yakin, ya udah gue iyain."
"Gue takut aja sebenarnya ini bisa memperkeruh keadaan. Tapi, mau jawab bohong juga lo pasti sadar."
Cewek itu menghentikan kegiatannya makan es pisang ijo, kemudian berbalik menatap gue. "Nu, gue nggak tau definisi bisa dipercaya menurut lo, tuh, gimana. Tapi, gue bukan tipe orang yang suka bergosip atau bakal memperkeruh keadaan. Gue juga begini bukan karena sekadar ingin tau, tapi emang peduli."
Jujur, gue terenyuh dengar pengakuan dia. Tapi, sebelum gue sempat menjawab, dia narik tangan gue dan menggulung lengan kemeja yang gue kenakan. Anehnya, nggak ada penolakan. Gue pasrah ketika dia melihat jejak-jejak kemarahan gue di sana.
"Kemarin nggak sengaja gue ngelihat ini setelah lo wudu. Pasti sakit banget, ya, Nu? Tapi, gue nggak tau sesakit apa sampe lo memutuskan buat memindahkan sakitnya ke sini."
Lala nggak menyentuh lukanya sama sekali, cuma mengusap area sekitarnya dengan lembut, dan nggak tau kenapa perlakuan sesederhana itu malah bikin perasaan gue sehancur ini. Ada dorongan yang kuat banget buat nangis, tapi gue nahan diri. Rasanya malu karena gue cowok, dan Ibu selalu bilang cowok itu nggak boleh kelihatan lemah mau sesakit dan sehancur apa pun.
"Dunia dan takdirnya kadang emang jahat, ya, Nu? Gue nggak tau sejahat apa takdir yang lo terima dan sesakit apa lo sekarang, tapi gue harap lo nggak melakukan hal kayak gini lagi. Hidup itu berharga, Nu. Bisa sampe di titik ini aja lo udah hebat banget. Jadi, kalau suatu hari ada yang bikin lo marah, marahin balik, atau kalau nggak bisa, lo bisa melampiaskannya ke gue. Kalau ada yang bikin sedih, lo juga boleh nangis ke gue. Ada yang bikin bahagia, lo bisa bagi kebahagiaan itu sama gue."
Tangan gue refleks mencengkeram dada. Di sana ... sesak dan sakit. Sama kayak waktu itu, gue nyaris nggak bisa napas. Tapi, Lala nggak kelihatan panik. Dia justru menenangkan, dan menuntun gue buat tetap bernapas. Gue melakukan apa yang dia perintahkan berulang, dan cukup berhasil bikin gue kembali bernapas. Walaupun tanpa sadar, di saat bersamaan, air mata gue jatuh. Gue refleks berbalik menatap Lala.
Lala senyum, terus bilang, "Nangis itu manusiawi. Bukan perkara lo cowok jadi nggak boleh nangis sama sekali. Kita sama-sama dikasih emosi, mustahil cowok nggak merasakan itu. Ada sedih, senang, kecewa, marah, takut, bahkan frustrasi. Menangis adalah bentuk validasi dari dari salah satu emosi itu, kan? Jadi nggak apa-apa."
Mati-matian gue berusaha buat nggak bersuara. Walaupun, nggak ada siapa-siapa di sini selain gue sama Lala, tapi sungkan menunjukkan seperti apa perasaan gue saat ini. Jadi, memutuskan buat menyembunyikan wajah gue dengan kepala rebah di atas meja, dan menangis tanpa suara.
Lala nggak berusaha menenangkan atau minta gue diam. Beberapa kali dia cuma menepuk-nepuk punggung gue, pelan banget.
"Gue mungkin orang asing, Nu. Tapi, gue ada kalau lo butuh tempat buat jatuh."
Satu-satunya kalimat yang terlontar dari bibir Lala cuma itu, dan gue mengerti maksudnya. Kita nggak bisa selalu di atas dan berusaha terlihat baik-baik aja. Sesekali jatuh, menenangkan diri, dan kembali ke atas kalau udah waktunya juga terbilang sesuatu yang manusiawi kok.
"Minimal lo harus punya satu alasan buat tetap hidup, Nu. Apa pun itu. Ibu dan Selly mungkin?"
Gue nggak menjawab. Kalau boleh jujur, mereka memang pernah jadi alasan gue buat hidup lebih lama, sampai kemudian alasan itu berubah jadi sesuatu yang mendorong gue untuk pergi lebih cepat.
***
Malam ini pasien cukup rame dan bikin gue sama Lala cukup kewalahan. Biarpun ada Selly, tapi dia nggak bisa leluasa bantu karena memang bukan kerjaannya. Tenaga gue yang mungkin cuma setengahnya dari Lala hampir habis. Dalam kondisi nggak ngapa-ngapain aja gue bisa ngerasa capek banget tanpa alasan, apalagi harus melayani lebih dari lima puluh pasien dengan karakter macam-macam.
Beberapa menit yang lalu gue juga sempat berantem sama driver karena pesanan dari aplikasi Halosehat. Driver tersebut langsung mem-pickup barang sebelum sampe apotek, pas di sini barangnya kosong. Stok di Halosehat emang jarang kami update karena proses keluar masuk barangnya yang cepat. Apalagi, kita cuma bertiga sekarang. Keteteran banget ngurusin semuanya.
"Nu, istirahat dulu, deh. Lo pucat banget."
Padahal, Lala lagi sibuk, tapi dia masih sempat melirik gue dan memastikan kondisi gue. Perut gue emang lumayan sakit dari tadi, tapi nggak berani bilang karena takut fokus cewek itu berantakan. Ternyata, nggak bilang pun fokusnya bukan cuma ke resep, tapi ke gue juga.
Selly cuma melirik, tapi nggak bilang apa-apa. Dia cuma ngobrol sama Lala dari tadi, nggak buka mulut sedikit pun pas berhadapan sama gue.
Nyeri bukan cuma nyeri, mulai muncul sensasi mual yang mengganggu, tapi gue nggak bisa ninggalin Lala dengan kondisi serame ini, kasihan. Jadi, gue berusaha keras menahan diri biar nggak keluar apotek biarpun cuma buat muntah.
Ternyata, semakin lama makin nggak bisa ditahan. Gue refleks menutup mulut dengan sebelah tangan, dan berniat ke kamar mandi. Tapi, pijakan gue goyah. Gue hampir jatuh dan di saat bersamaan, cairan merah pekat kembali menyembur dari mulut gue. Lala menjerit tertahan, sementara Selly menjatuhkan mortir yang mau dia cuci, mungkin karena terlalu kaget dan langsung berdiri kaku di tempat.
Gue yang sebelumnya cuma goyah, tiba-tiba hilang tenaga. Lemas kayak tanpa tulang, dan perlahan ambruk membentur dinginnya lantai. Samar, gue melihat mata Lala yang basah. Dia berjongkok tepat di depan gue, menatap dan memanggil nama gue berkali-kali, tapi makin lama gue nggak bisa dengar suaranya. Jauh dan kabur. Gue kayak ada di ruang hampa, yang cuma ada gue di dalamnya. Sampai kemudian semua berubah gelap. Gue nggak bisa melihat atau merasakan apa-apa.


 purplelight01_
purplelight01_





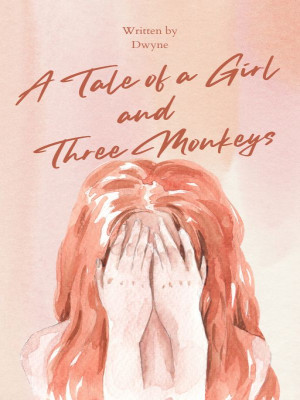




Bahagia selalu ya kalian... Mas Nu udh nemuin kebahagiaan.. tetap bahagia selamanya, skrng ada orang² yg sayang banget sama Mas Nu. Ibu, Icel sama calon istrinya🥰
Comment on chapter Chapter 24 - Penuh cinta