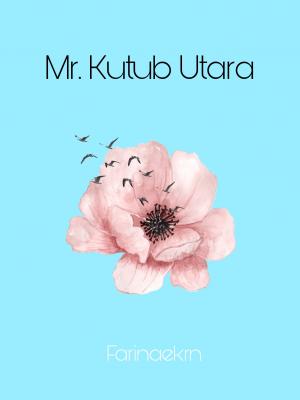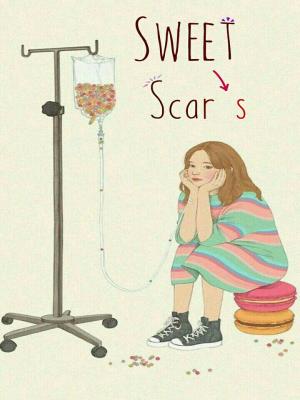“Bang, bangun bang… bentar lagi akadnya mulai.”
Suara Rizal terdengar samar, menggoyang-goyangkan tubuhku. Akad? Akad apa?
Aku mengerjap, merasa berat untuk membuka mata. Setelah beberapa detik, aku berhasil bangun dan langsung menyingkap selimut.
“Hah? Akad apa?” tanyaku setengah sadar.
“Yeee, hari ini kan pernikahannya Rafa sama Fajar! Kalo Rafa tau abang lupa, dihajar kamu bang.” Rizal tertawa kecil sambil merapikan kamar.
Aku menggaruk kepala. Tunggu… kamar?
Aku baru sadar, ini bukan kamarku! Ini lebih luas, lebih rapi, dan terasa asing. Aku segera meraih HP yang tergeletak di nakas. Layar menyala, dan di sana tertulis:
3 Maret 2030.
Aku membeku.
Enam tahun kemudian?
Setelah sekian lama, akhirnya ini datang lagi. Penglihatan Masa Depan.
Aku mengira itu sudah hilang—atau mungkin hanya mimpi belaka. Tapi tidak. Ini nyata.
Seperti sebelumnya, penglihatan ini selalu datang tanpa peringatan. Ia memberiku gambaran tentang skenario terburuk, seolah-olah semesta ingin memberitahuku sesuatu. Aku menelan ludah. Keputusan apa yang salah kali ini? Apa yang harus kuubah?
Dan yang lebih penting… kenapa sekarang?
Aku masih terpaku menatap layar HP, memperhatikan tanggal itu berulang-ulang. 3 Maret 2030.
“Bang, lagi ngelamun apaan?” Rizal memandangku heran sambil berkacak pinggang. “Udah, buruan siap-siap! Masak kita telat di acara nikahan Rafa?”
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diri. Oke, santai, Yudhis. Ini bukan pertama kalinya.
“Ya… ya… bentar.”
Aku bangkit dari kasur—yang entah sejak kapan berubah jadi lebih empuk dan luas dari kamar kosku dulu. Kamar ini terasa asing. Ada lemari besar di sudut, meja kerja yang tertata rapi, bahkan ada rak buku yang penuh dengan tumpukan jurnal dan beberapa foto yang belum sempat kulihat lebih dekat.
“Ayo, jangan lama-lama, nanti kita yang kena omel sama pengantin!” Rizal sudah siap dengan kemeja putih dan celana bahan hitam, tampak lebih dewasa dari yang kuingat.
Aku buru-buru mengambil pakaian dari lemari—aku bahkan tidak ingat sejak kapan aku punya koleksi kemeja sebagus ini. Kemeja putih polos, celana bahan hitam, dan jam tangan yang terasa lebih mahal dari biasanya melingkar di pergelanganku.
Lima belas menit kemudian, kami sudah keluar dari rumah—atau apartemen? Aku belum sempat memastikan. Yang jelas, kami kini berada di dalam mobil yang dikendarai Rizal, melaju menuju tempat akad nikah yang katanya akan berlangsung di Masjid Besar.
Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, mengamati suasana kota yang terasa lebih modern. Beberapa bangunan tinggi tampak lebih banyak dari yang kuingat, papan reklame digital bertebaran di pinggir jalan, dan…
Mataku tertumbuk pada pantulan diriku sendiri di kaca jendela mobil.
Aku berubah.
Rambutku lebih rapi, wajahku tampak lebih dewasa, dan ada tatapan yang berbeda di mataku—seolah aku sudah melalui banyak hal yang tidak kuingat.
“Aduh, semoga kita nggak telat,” Rizal menggerutu sambil mempercepat laju mobilnya.
Aku menarik napas panjang.
Apa yang sebenarnya terjadi selama enam tahun ini?
***
Aku dan Rizal berjalan cepat menuju pelataran Masjid Besar, tempat akad nikah berlangsung. Dari kejauhan, aku bisa melihat dekorasi yang elegan namun tetap sederhana. Ada kain putih dengan sentuhan emas yang menghiasi area pelaminan, serta rangkaian bunga putih dan hijau yang mempercantik suasana.
Orang-orang sudah mulai memenuhi area duduk, menunggu prosesi berikutnya. Aku menyapu pandang ke sekitar, mencoba mencari sosok pengantin—Rafa dan Fajar. Tapi sebelum aku bisa menemukan mereka, seseorang menepuk pundakku.
"Bang Yudhis! Rizal!"
Aku menoleh dan melihat seorang pria yang wajahnya tampak familiar, tapi aku tidak bisa langsung mengingat namanya.
"Eh… kamu siapa ya?" tanyaku refleks.
Orang itu menatapku dengan ekspresi kaget, lalu tertawa. "Gila, Bang. Lupa sama aku? Hilman, woy!"
Hilman?! Aku mengerjap. Hilman yang dulu masih anak bawang di organisasi?! Sekarang dia kelihatan lebih dewasa, dengan jas rapi dan badan yang lebih berisi.
"Wah, iya! Maaf, tadi nggak ngenalin," jawabku canggung.
"Kalian hampir telat, tapi untungnya akadnya udah selesai tadi," kata Hilman sambil mengarahkan kami ke area tempat duduk.
Aku dan Rizal langsung duduk di antara tamu lainnya. Acara berlanjut dengan sesi penyampaian pesan dari teman-teman terdekat mempelai wanita. Seorang perempuan maju ke depan, membawa mic.
Aku masih terdiam, mencoba menyerap semuanya. Jadi Rafa benar-benar menikah hari ini.
“Hahaha, terima kasih atas pesannya, oke karena rangkaian acara sudah -.” Pembawa acara itu dihentikan oleh Rafa yang baru saja berdiri. Ia membisikkan sesuatu.
“Mohon maaf tamu-tamu undangan sekalian, ternyata masih ada yang akan menyampaikan pesannya yaitu dari saudara Yudhistira Wijaya dan Rizal Marzuki, maka kepada mereka kami persilahkan.”
Aku dan Rizal langsung menoleh satu sama lain.
LAH?! SEJAK KAPAN KITA IKUTAN NGISI PESAN?!
Rizal melotot ke arahku, jelas-jelas menyalahkanku seolah-olah ini idenya dari aku. Aku balas melotot, sama bingungnya. Tapi di depan kami, Rafa sudah berdiri dengan senyum penuh arti—senyum yang mengatakan, Berani nolak? Nggak kan?.
Aku menghela napas, mencoba bersikap tenang, sementara Rizal sudah meremas ujung jasnya, jelas panik.
“Bang, kita ngomong apa?” bisiknya panik.
Aku berdiri duluan, berusaha tampil percaya diri. “Santai, improv aja,” gumamku sambil melangkah ke depan.
Mikrofonnya kini ada di tanganku. Aku menghela napas sebentar, lalu tersenyum ke arah Rafa dan Fajar yang duduk di kursi pelaminan. Semua mata tertuju padaku.
Aku melirik Rizal, memberi kode untuk ikut maju. Dia masih ragu, tapi akhirnya berdiri juga di sampingku.
Aku membersihkan tenggorokanku, lalu mendekatkan mic ke mulut.
“Bismillah,” aku memulai, “Sebenernya… aku nggak nyangka sama sekali kalau bakal disuruh maju ke depan kayak gini. Jujur, aku sama Rizal tadinya cuma niat jadi tamu biasa, datang, makan, terus pulang.”
Orang-orang mulai tertawa kecil.
Aku melanjutkan, “Tapi, karena ini pernikahan Rafa dan Fajar, yaudahlah, demi kalian, aku dan Rizal siap kasih pesan terbaik.”
Aku menoleh ke Rizal. “Jal, kamu mau mulai duluan?”
Rizal mengambil mic dengan tangan gemetar. “EHEM. Gini ya…” dia berhenti sejenak, lalu menatap Rafa dengan serius. “Rafa… aku cuma mau bilang, Fajar ini orang baik. Dia bertanggung jawab, sabar, dan… ya, ganteng dikit lah.”
Ruangan kembali tertawa.
“Tapi satu hal yang pasti, dia beruntung banget dapetin kamu,” lanjut Rizal dengan nada lebih serius. “Aku tau kamu orangnya kuat, mandiri, dan luar biasa banget dalam segala hal. Kuharap kalian selalu bahagia dan selalu ada buat satu sama lain.”
Aku menepuk pundaknya pelan. “Eh, kata-katamu keren juga.”
“Aku emang keren,” balasnya bangga.
Aku kembali mengambil mic. “Kalau dari aku…” aku menatap Rafa dan Fajar bergantian, lalu menghela napas pelan. “Kalian berdua adalah orang-orang yang pernah mengisi hidupku. Rafa, kita udah melalui banyak hal dari zaman kuliah sampai sekarang. Fajar, aku nggak banyak kenal kamu, tapi aku percaya kamu orang yang tepat buat Rafa.”
Aku tersenyum kecil. “Pernikahan itu nggak gampang. Akan ada hari-hari di mana kalian bahagia banget, tapi akan ada juga hari di mana kalian diuji. Aku cuma mau bilang, ingatlah selalu alasan kenapa kalian memilih satu sama lain. Jangan lupa komunikasi, dan yang paling penting…” aku melirik ke arah Fajar. “Jangan pernah biarin Rafa kelaperan, itu bahaya.”
Ruangan kembali pecah oleh tawa. Rafa melipat tangan di dada, berpura-pura kesal.
“Terakhir sebelum benar-benar saya tutup, ini pesan khusus buat Fajar, mohon diingat baik-baik,” aku menghela napas, suasana sudah kembali tenang, malah sedikit menegangkan sekarang. “Jangan pernah ketahuan merokok di depan Rafa, karena bukan cuma rokoknya yang bakal dia matiin tapi kamunya juga.”
Semua yang hadir langsung tercengang, lalu tawa meledak. Aku melanjutkan dengan nada serius, “Dan kalau misalnya kamu iseng ngelakuin itu, siap-siap aja disemprot pake air dari botol, kayak kucing yang lagi ngerusak barang. Jangan bilang aku nggak ingatkan!”
Rizal langsung nyelonong, “Iya, Jar, kalo ketahuan, bisa-bisa Rafa bakal ngeluarin jurus ninja-nya, trus langsung ngejewer kupingmu sampe melar!”
Aku melirik ke Rizal, pura-pura kaget. “Jal, itu terlalu jauh, jangan deh.”
“Yaudah, segitu aja dari kita. Semoga hidup baru kalian penuh cinta, makanan enak, dan tentunya… jauh dari asap rokok!” aku menutup dengan senyum lebar.
Aku dan Rizal mengangkat tangan, memberi salam, dan berjalan kembali ke tempat duduk.
Tak lama setelah pesan konyolku dan Rizal selesai, dan tawa para tamu perlahan mereda, suasana kembali tertata. Pembawa acara naik ke depan lagi, kini dengan senyum lega.
“Alhamdulillah, seluruh rangkaian akad nikah telah selesai. Kami mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, Rafa dan Fajar. Mohon doa restu dari hadirin semua agar pernikahan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”
Suara “Aamiin” menggema pelan, khusyuk tapi tetap hangat.
Setelah itu, orang-orang mulai berdiri, sebagian berbaris untuk bersalaman dengan mempelai dan keluarga. Ada yang mulai ngobrol di pinggir-pinggir area, ada juga yang buru-buru ke parkiran—mungkin kejar janji, atau lapar.
Aku dan Rizal ikut berdiri, tapi kami belum langsung maju ke depan. Kami hanya memperhatikan dari jauh. Belum sempat kami kepikiran untuk pulang sebuah chat masuk. HAHAHAHA, KENAPA NAMA GRUPNYA BEGINI DAH.
Trio Penghuni Surga Kecuali Rizal
Rafa : JANGAN PULANG DULU!
Rizal : SIAP NONA, tapi kita mau jemput tante Diana, om Ilham, ama mamakku lho Rap.
Yudhis : Jemput di mana Jal?
Rafa : Oh iyaa, kangen banget sama Tante Diana ama Om Ilham, sama Tante Tata jugaaa, buruan ya jemputnya, mama juga dari tadi nanyain nih...
Rafa : Yud kamu ini amnesia kah? Jangan-jangan kamu juga lupa hari ini kalo aku nikah makanya terlambat.
Yudhis : Wkwkwkwk, Gak kok Rap kan diingatin Rijal.
Rafa : KAN!
Rizal tidak menjawab pertanyaanku lewat grup chat “Abang ini lupa ingatan apa gimana, kita kan harus ke Bandara, emang tante Diana gak telpon?” jelas Rizal.
Sekejap setelah perkataan Rizal Hpku berdering.
YUD MAMAK NELPON! YUD MAMAK NELPON!
Aku menepuk dahi, ternyata Yudhis di zaman ini sama noraknya. Rizal yang mendengarkan tertawa kecil, sepertinya ia sudah biasa mendengarnya, karena kalo pertama kali pasti nih anak bakal ketawa setengah mati. Nada dering itu sukses menarik perhatian beberapa tamu di sekitar kami. Aku buru-buru menekan tombol jawab sambil menahan malu.
“Assalamualaikum, Mak...” sapaku dengan suara setengah pasrah.
“Waalaikumsalam, Yudhis, kalian di mana? Mamak, Bapak, sama Mamanya Rizal udah landing dari tadi. Jangan bilang kamu kelupaan jemput?”
“Enggak, Mak, enggak... Ini Rizal udah ngajakin dari tadi kok,” jawabku sambil melirik Rizal yang langsung pasang wajah polos. Dasar!
“Kalian cepet ya ke bandara. Jangan bikin malu sama keluarga mempelai,” lanjut suara di seberang sana.
“Iya, Mak, iya…” Aku menutup telepon dan langsung mendesah. “Ayo, Jal. Kita kebut ke bandara sebelum Mamak kirim surat teguran resmi.”
Rizal mengangguk cepat. “Aku yang nyetir, Kamu yang jadi navigator. Tapi jangan ngawur ya, jangan kayak waktu kita nyasar ke kandang kambing waktu mau ke kondangan Ustadz Zein.”
Siapa itu? Ustadz Zein? Eh, itu ketum IMM, kan?
“Kak Zein IMM, Jal?” Tanyaku sambil jalan cepat ke parkiran.
“Semuanya aja kamu lupa bang, tadi malam abang abis mabok ya, makanya begini?” Balas Rizal.
“Yeee, kamu kamu gak baca tuh grup ‘Trio penghuni surga kecuali Rizal’, mana mungkin anak baek-baek kayak aku begitu.”
“Sialan, Rapa ketularan kamu itu bang,” HAHAHA, jadi yang buat grup itu Rafa.
Kami berdua tertawa kecil sambil masuk ke mobil. Tapi di dalam hatiku, ada rasa haru yang belum juga reda. Rafa sudah menikah, dan hidup terus berjalan—dengan segala tawa, drama, dan ringtone memalukan.
***
Satu jam kemudian, kami semua sudah berkumpul di rumah Fajar. Ini adalah pemandangan yang cukup langka, menurutku. Bukan hanya aku, Rizal, dan Rafa yang duduk di ruang tamu yang penuh tawa itu, tapi juga orang tua kami. Lengkap.
Seingatku, momen seperti ini hanya pernah terjadi sekali—waktu kami akan berangkat ke Solo untuk kuliah. Kami naik pesawat yang sama, dan secara otomatis keluarga besar ini berkumpul untuk pertama kalinya di bandara. Rasanya seperti reuni keluarga... padahal belum pernah ada "uni" sebelumnya.
Tapi sekarang, semuanya terasa lebih hangat.
Mamak duduk bersebelahan dengan mamanya Rizal, ngobrol akrab seperti sudah kenal seumur hidup. Yah, memang sih, mereka sering video call sejak dulu—Mamak nggak pernah kelewatan kesempatan buat ceritain kelakuanku dan Rizal.
Yang lebih lucu lagi, ternyata mamanya Rafa adalah teman pengajian Mamak juga. Dunia ini kecil banget… atau jangan-jangan, grup pengajian ibu-ibu itu sebenarnya jaringan intel nasional berkedok pengajian. Segala info bisa nyambung ke mana aja.
“Rafa ini kalo udah ngumpul sama Yudhis sama Rizal, aura ibu-ibunya keluar, lho. Jadi makin mirip Bu Dyah,” celetuk Mamak dengan polosnya.
“Hahaha, iya, Rafa juga sering cerita. Dua abangnya itu suka banget bercanda, katanya…” sahut Tante Dyah—mamanya Rafa, sambil melirik kami berdua. Senyumnya manis, tapi pertanyaannya menusuk. “Kalian kapan nyusul Rafa?”
Rafa yang duduk santai di ujung ruangan langsung nyengir ke arah kami. Senyum penuh kemenangan.
“Hahaha, nggak ada yang mau sama Yudhis, Bu,” sambung Mamak dengan tenang. SEDEKET ITU ya beliau menjatuhkan harga diri anaknya sendiri.
“Apalagi Rizal,” tambah Tante Tata dengan ekspresi prihatin pura-pura yang sungguh menyakitkan.
Kami berdua cuma bisa duduk diam. Terlepas dari senyuman lebar Rafa yang jelas-jelas menikmati penderitaan kami, satu ruangan sudah pecah oleh tawa. Suasana jadi kayak acara roasting, tapi tanpa panggung dan tanpa persetujuan.
Aku dan Rizal saling melirik.
“Jal…” bisikku.
“Hmm?”
“Kita duduk di sini tuh kayak lagi jadi korban dokumenter kriminal. Semua saksi hidup ada.”
Rizal angkat alis, “Kita harus keluar sebelum mereka bahas kapan kita terakhir nelpon rumah.”
“Setuju,” jawabku cepat. “Sebelum Mamaku buka aib-aib SD.”
Jadilah kami bertiga duduk-duduk di teras, ditemani dua gelas kopi dan satu gelas susu—buat Rafa, tentu saja. Iya, dia juga ikut-ikutan keluar. Bukannya bermesraan dengan suami barunya itu, malah lebih milih nongkrong sama kami. Mungkin nostalgia lebih menggoda dari pelaminan. Kurasa ini waktu yang tepat buat nyari informasi, apa aja yang udah terjadi selama enam tahun ini.
Kayaknya ini waktu yang tepat buat mulai mengumpulkan informasi. Apa aja yang udah kejadian selama enam tahun ini?
“Kamu nggak sama Fajar, Rap?” tanya Rizal sambil menyeruput kopinya.
“Udah izin mau nemenin kalian bentar,” jawab Rafa santai. “Kan baru akad, belum resepsi. Bonus waktu bebas, gitu ceritanya.”
Aku mengangguk pelan. Lalu, dengan niat memancing obrolan lebih dalam, aku lempar satu umpan.
“Eh, kalian masih inget nggak, enam tahun lalu… waktu aku kejebak di WC?”
Rizal langsung memuntahkan tawanya. “HAHAHAHA, JOROK BANGET ITU KAMU YUD, HUEEKK. Astaga, gue masih trauma visualnya!”
“Hahaha iya! Itu harus kuceritain ke anak-anakku nanti, Bang,” tambah Rafa sambil ngakak. “Legend banget kejadian itu.”
Hadeh. Respon mereka tetap sama seperti dulu—nggak ada belas kasihan, cuma tawa dan ejekan penuh cinta.
“Tapi serius, udah nggak kerasa ya… enam tahun aja berlalu,” lanjut Rizal dengan nada lebih tenang. “Keren banget si Fajar, perjuangin kamu, Rap.”
Rafa tersenyum mendengar itu. Senyum yang dalam, bukan cuma karena pujian, tapi kayak ada cerita panjang di baliknya. “Hahaha iya… Pertama kali ketemu kalian, dia gugup banget katanya. Apalagi liat mukamu, Yud. Katanya kamu juteknya kayak dosen killer.”
Aku ikut tertawa. “Lah, masa iyaa?.”
“Sengaja memang kamu bang,” sambung Rizal sambil nunjuk aku pakai sendok kopi. “Katanya buat ngetes seberapa tangguh si Fajar Rap, kayak tes masuk polisi aja.”
Aku tertawa lagi, kali ini sambil geleng-geleng kepala. Lucu juga denger cerita tentang diri sendiri yang bahkan aku nggak inget.
Di antara tawa dan gelas yang mulai kosong, aku sadar satu hal: meskipun banyak yang aku gak ngerti, ternyata yang aku punya sekarang... masih utuh.
Rafa. Rizal. Cerita-cerita absurd yang nggak akan basi dimakan waktu.
“Itu sekarang Susan gimana, bang?” tanya Rizal tiba-tiba.
Rafa langsung menoleh ke arahku sepenuhnya, ekspresinya kayak anak kecil yang baru denger gosip di depan gerobak gorengan.
Dan aku? Paru-paruku kayak mau copot. SUSAN?? Kayaknya mimpi tadi emang ada hubungannya sama Susan. Dan yang paling penting—AKU HARUS JAWAB APA NIH? SUSAN KENAPA? KENAPA NIH ANAK NANYA SUSAN SEKARANG BANGET??
“Kenapa mukamu berubah gitu, bang? Kalian abis kelai, ya?” Rizal nanya lagi, kali ini lebih hati-hati. Aku buru-buru geleng. “Eh... enggak kok, kita akur-akur aja…”
Tapi... aku sama Susan udah nikah kah? Kok aku tinggal di kos sendiri? OOOHHH. YUDHIS DI ZAMAN INI LAGI SAMA SUSAN PACARAN YA.
“Eh, aku pacaran sama Susan udah berapa tahun, ya, kira-kira?” tanyaku, masih pura-pura waras.
Rafa melotot. “Cowok tuh ya, selalu lupa hal-hal penting! Kalo nggak salah sih udah lima tahun, Yud!”
“Memang gak penting juga,” sahut Rizal. “Apalagi tanggal jadian?”
“PENTING!!” Rafa spontan membentak, suaranya kayak sirine masjid pas subuh.
Selagi mereka berdua ribut sendiri, aku cuma duduk terdiam, mencoba menenangkan diriku. Aku pacaran sama Susan. Udah lima tahun. Dan… kayaknya dia suka juga sama aku, dari awal?
Lima tahun. LIMA. TAHUN. HAHAHA KAYAKNYA AKU GANTENG BANGET YA. Tapi entahlah, aku bingung harus senang atau sedih, karena waktu itu aku memang berniat memacarinya. Kurasa ‘penglihatan masa depan’ kali ini adalah scenario terburuk yang akan terjadi antara aku dan Susan.
“Kapan kamu mau nikahin, Yud? Kasian anak orang nungguin. Padahal dari dulu aku udah bilang, langsung nikah aja, gak usah pacaran. Haram, tau nggak!” Tentu saja itu Rafa. Benar kata Mamak... Rafa memang punya aura seorang ibu.
Tapi kali ini, nada suaranya berubah sedikit lebih tenang.
“Tau nggak, Yud… kadang aku mikir, sebenarnya ya… yang emang udah ditakdirin buat kita, gak bakal ke mana,” katanya sambil mainin ujung gelas. “Sekeras apapun kamu ngehindar, kalau emang buat kamu, ya pasti balik. Dan kalau bukan, meskipun kamu ngejar sekuat tenaga... tetap aja lepas.”
Dia berhenti sebentar, matanya menerawang “Jadi sebenernya, kamu pacaran atau nggak... kalau emang Susan jodohmu, ya bakal ketemu juga, pada waktunya.”
“Siap, Ustadzah Rafa. Denger tuh, Bang.” Rizal nyengir, nimpalin cepat.
Tentu saja aku pernah dengar kata-kata itu.
‘Apapun yang Allah tetapkan untuk menimpamu, pasti nggak akan meleset darimu. Dan apapun yang meleset darimu, nggak akan menimpamu.’ Aku pernah mendengar kata-kata itu entah dari siapa, kayaknya dari reels Ig deh.
Tapi… apakah ini semua mimpi karena aku pacaran sama Susan? Dan kalau iya... Bisakah aku bangun sekarang?
Aku tau kok, pacaran itu salah. Semesta, engkau gak perlu repot-repot kasih mimpi sepanjang ini. Aku janji nggak pacaran. TTM aja, ya? Gitu kan nggak dosa-dosa amat.
Pucuk dicinta ulam pun tiba, lagi ngomongin Susan orangnya malah menelponku sekarang, ternyata selama ini chatnya ada dalam arsipan, aku nggak sadar. Apa Yudhis di zaman ini memang sedang ada masalah dengan Susan?


 saputera
saputera