Langit Amsterdam gelap oleh awan mendung, gerimis ringan membasahi tanah yang mulai dipenuhi bunga dan taburan tanah merah di atas peti yang sudah tertutup rapat. Fabian berdiri paling depan, jas hitamnya lembab oleh hujan, kepalanya tertunduk diam. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras menahan emosi. Oma yang menjadi sahabatnya sejak kecil, orang yang mengajarkannya kecintaan terhadap Indonesia dan mengajarkannya bahasa Indonesia, telah pergi.
Suara doa dalam bahasa Belanda mengambang di udara, diiringi lantunan cello lembut yang dimainkan oleh seorang musisi lokal.
Fabian merasa rintik air di sekitarnya berhenti, seseorang memayunginya. Ia menoleh, di sampingnya Suci berdiri mengenakan gaun hitam sederhana dengan mantel wol gelap. Rambutnya digerai rapi, wajahnya tenang, penuh simpati. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Fabian dengan mata yang dalam dan senyum tipis yang menjelaskan segalanya.
Fabian tergagap, suaranya nyaris tidak keluar. “Suci? Kok kamu di sini?”
Suci menunduk sopan, lalu berbisik, “Aku khawatir. Aku nggak mau kamu sendiri di momen ini.”
Fabian terdiam. Ia sempat menengadah, seakan butuh konfirmasi dari langit bahwa ini nyata. Pupil matanya bergetar haru, teringat jarak dari Bogor ke Amsterdam serta birokrasi yang rumit. Sungguh perlu upaya yang besar mendatanginya ke negeri ini, apalagi bagi wanita yang berangkat sendiri. “Kamu sendiri ke sini?” Fabian yang baru tersadar, sontak khawatir.
Suci mengangguk, lalu mengguratkan senyumnya yang biasa merekah untuk menenangkan orang lain.
-oOo-
Suci Riganna Latief, beberapa hari sebelum keberangkatan.
Suci sampai di kontrakannya, ia mengemas barang-barangnya ke dalam koper dengan tergesa-gesa, berniat menyusul Fabian ke Belanda sesegera mungkin. Kemudian teringat prosedur paspor hijau dan visa untuk bisa mendatangi negeri Belanda yang memakan waktu. Ia terduduk lemas, Sepertinya nggak akan bisa cepat. Pikirnya pasrah.
Ia lalu mengirim pesan ke Surya.
Suci :
Kak, urus visa ke Belanda perlu waktu berapa lama ya? Oma Fabian wafat, aku mau ikut ke sana. Fabian kelihatan syok, aku khawatir.
Surya :
Paspor lu aktif kan? Visa Schengen itu biasanya 7-15 baru jadi, Ci.
Suci :
Lama banget, pembuatannya bisa diwakili nggak?
Surya :
Nggak bisa, lu kesini aja dulu. Tunggu 7-15 hari lagi. Jangan pesan tiket dulu.
-oOo-
Esoknya Suci mendatangi kantor RumahWaktu, berniat mengajukan cuti untuk persiapan ke Belanda, mungkin selama sebulan, demi menemani Fabian yang tengah berduka. Ia datang sendiri, tidak membawa laptop atau menenteng apa pun kecuali tas kecil dan wajah lelah. Ia mengetuk pintu ruangan General Manager RumahWaktu, Arman.
“Suci? Tumben ke sini, ada yang penting?” Arman menyambutnya heran.
“Maaf, Pak. Saya cuma ingin menyampaikan, Fabian harus pulang ke Belanda hari ini. Omanya wafat tadi pagi,” Suci menginformasikan.
Pria paruh baya itu sejenak diam, wajahnya murung. “Saya ikut berduka. Fabian sudah banyak membantu saya,”
“Iya, Pak. Saya ingin menyampaikan juga, kalau boleh saya juga ingin ajukan cuti satu bulan untuk menyusul dia ke Belanda. Saya khawatir dengan Fabian,” Suci berkata jujur. “Meski saya nggak yakin perlu berapa hari mengurus visa di Jakarta.”
Arman menatap wajah pegawai wanitanya itu. Suasana hening, tiba-tiba nada suaranya berubah, lebih dalam. “Saya baru dengar soal apa yang kamu alami di acara kemarin. Saya minta maaf, Suci. Kami semua kecolongan.”
Arman sedikit menunduk dan menghela napas gusar, “Dan saya juga tahu, kakakmu, Surya, bahkan datang langsung ke kantor Sentani Jaya. Harusnya perusahaan RumahWaktu ikut serta menindaklanjuti ini, sebagai bentuk tanggung jawab. Sebagai GM, saya malu telat mengetahuinya.”
“Saya tidak bermaksud memperbesar masalah, Pak. Itu Kakak saya yang ambil sikap sendiri,” Suci berkata pelan.
“Kamu nggak salah apa-apa, kamu korban. Perusahaan ini utang budi kepadamu. Apa yang bisa saya bantu, Ci?” terdengar ketulusan dari ucapan GM itu. “Kamu mau menyusul Fabian ke Belanda, kan? Bagaimana kalau saya urus surat pengantar dari korporat untuk mendapatkan visa kamu. Kamu bisa bekerja dari sana, kan?”
Suci menatap General Manajer itu dengan penuh harap. “Bisa, Pak!”
“Dengan surat dari saya, dan dukungan legal, proses bisa dipercepat. Anggap aja ini penugasan remote jangka pendek,” Arman berdiri, menggapai dokumen. “Saya akan tandatangani sendiri. Ini bentuk tanggung jawab kami. Kamu pantas mendapatkan rasa aman.”
"Terima kasih, Pak,” Suci terharu. Semesta seakan membantunya menyusul kepergian Fabian ke Belanda.
-oOo-
Kediaman keluarga Meijer, setelah pemakaman Oma
Kediaman keluarga Meijer telah sepi setelah pemakaman Oma selesai. Suci memberi salam duka kepada kedua orang tua Fabian. Mama Fabian, seorang wanita berusia akhir 50-an yang elegan, dengan tatapan tajam tapi bersahabat, menyambut kedatangan Suci dengan pelukan ramah. Papa Fabian, pria tinggi dengan perawakan akademisi, ikut menjabat tangan Suci dengan hangat.
“Saya Suci, teman Fabian, sengaja datang ke sini sekaligus ingin mewakili perusahaan kami. RumahWaktu, untuk menyampaikan turut berduka cita,” Suci menggunakan bahasa Inggris sebisanya.
“Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Indonesia,” mamanya tampak sangat terharu.
“Di mana kamu menginap? Kami memiliki kamar kosong di sini. Kalau tidak keberatan, kamu menginap di sini saja selama di Belanda,” Papa Fabian berinisiatif menawarkan dengan bahasa Inggris.
Fabian yang baru turun dari tangga terkejut, mug-nya bahkan hampir terjatuh. “Tunggu! Kalian menawarkan Suci tinggal di sini?” ia terkejut karena tidak dilibatkan dalam perbincangan.
“Dia perempuan, datang ke sini sendiri, dia perlu tempat yang aman,” mama Fabian menekankan. “Apalagi wanita muda selugu ini, kelihatan sekali dia gadis yang baik.”
Suci hanya senyam-senyum, tidak mengerti pembicaraan antara ibu-anak itu.
Suci melirik Fabian. “Jadi, aku boleh tinggal di sini, Fabian?” ia mengulum senyum kesenangan.
Fabian hanya mengangguk pasrah, setengah tidak percaya.
Suci kembali ke hotelnya untuk mengepak barang bawaannya dan check-out. Ia sudah sepakat untuk tinggal di kediaman Meijer selama berada di Belanda. Sementara Suci pergi, Fabian dipanggil ke ruang tengah oleh orang tuanya. Ia duduk di sofa sambil menyipitkan mata heran.
Papa Fabian menginterogasinya, “Fabian, apa hubunganmu dengan gadis itu?”
Fabian bingung menjelaskannya. “Rekan kerja,” ia mencari aman.
“Kamu mau Mama percaya, rekan kerjamu dari Indonesia pergi jauh ke Belanda, 18 jam perjalanan, cuma untuk menyampaikan belasungkawa atas kematian Omamu?” Mama memandangnya dengan tatapan menyelidik.
“Kami… cukup dekat,” Fabian tidak bisa menjelaskan lebih lanjut.
Papa dan mama saling pandang, lalu tersenyum.
“Tuh kan Pa, lihat! Dia sudah menemukan pengganti Akasia. Gadis tadi benar-benar imut, kulitnya kecokelatan, mirip-mirip Akasia,” Mama berkata riang.
“Mama, jangan banding-bandingkan dia dengan Akasia. Mereka berbeda,” Fabian menyela.
“Iya maaf,” mamanya merasa bersalah. “Intinya kamu cukup dekat dengan dia, kan?”
“Sepertinya dia gadis baik-baik, jangan pernah sakiti dia Fabian! Pengorbanannya untukmu besar,” papa memperingatkan putranya itu dengan tegas.
“Nggak akan,” Fabian ciut nyalinya.
“Mama punya teman lagi deh, calon menantu,” mama Fabian kesenangan.
“Belum tentu, Ma,” Fabian mematahkan asumsi Mamanya yang terlalu antusias. Ia menutup wajahnya pasrah.
-oOo-
Mentari bergulir ke ufuk barat, mewarnai langit dengan nuansa jingga keemasan. Daun-daun tua berguguran ditiup angin musim semi, sementara sepasang burung kecil bertengger di dahan. Fabian dan Suci duduk di bangku kayu yang menghadap ke danau kecil. Di taman Vondelpark itu mereka berbagi obrolan.
Fabian sengaja menutup kepalanya dengan hoodie jaketnya dalam-dalam. Ia menyandarkan kepalanya ke bahu mungil Suci.
“Sekarang pinjam bahumu dulu ya, Ci. Gantian,” Fabian berkata singkat, meminta pemakluman. Ia menyerongkan tubuhnya yang lelah secara emosional.
Suci tersentak, “Gantian? Memang kapan aku…”
“Dulu waktu kamu tidur di mobil, perjalanan pulang ke Bogor,” Fabian menjawab sebelum Suci selesai bertanya.
Wajah Suci memerah, malu. Lalu ia menyadari bulir hangat yang berjatuhan dari wajah Fabian, itu air mata. Pemuda itu menangis diam-diam.
“Nggak apa-apa, nangis aja sampai puas. Take your time,” Suci berbisik maklum. Memberinya waktu untuk melepas kesedihannya yang baru saja ditinggal pergi Oma.
Langit Amsterdam terbentang biru lembut, dihiasi awan-awan tipis seperti sapuan kuas cat air. Daun-daun pohon mapel dan ek menari perlahan tertiup angin, menyaring sinar mentari menjadi pola cahaya yang menari-nari di tanah berumput. Aroma segar rumput yang baru dipotong memasuki penciuman Suci, bercampur harum bunga liar yang bermekaran di tepi danau. Suasana alami ini menenangkan jiwa.
Suci melihat di kejauhan, anak-anak bersepeda melintasi jalur berkelok, para pejalan kaki berbincang pelan, dan sepasang angsa putih meluncur tenang di permukaan air. Sesekali gemericik air terdengar ketika seekor bebek menyelam mencari makan, atau ketika angin menyapu riak danau, menciptakan ilusi permukaan kaca yang retak-retak indah.
“Taman ini benar-benar indah ya,” Suci bergumam mengisi keheningan.
“Waktu kecil, Oma sering ajak aku ke taman ini, duduk di bangku ini,” Fabian bercerita di sela isaknya. “Oma bilang, ‘Lihat orang-orang yang lewat, Fabian. Setiap langkah mereka adalah cerita. Nanti kamu jangan lupa menuliskan ceritamu sendiri ya.’”
“Dan sekarang kamu sedang menulisnya, dengan tinta keberanian di lembaran hari-hari hidupmu,” ucapan Suci membuat Fabian mengangkat wajahnya, menatap Suci lebih dalam. Hening menggantung di antara mereka, bukan hening yang canggung, melainkan hening yang menenteramkan hati, hangat, dan penuh pemahaman.
“Kamu tahu cara muncul di waktu yang tepat, Suci,” Fabian berkomentar.
“Aku cuma merasa kamu nggak boleh sendirian menghadapi semua ini,” ungkap Suci jujur. “Oma sepertinya baik sekali, pasti beliau orang yang menyenangkan. Dari cerita-ceritamu, dari senyummu waktu mengenang beliau,” ia menebak-nebak. “Padahal aku mau ketemu, tapi belum sempat.”
“Aku juga belum sempat bawa Oma ke tanah kelahirannya, negerimu. Aku kira aku masih punya waktu,” Fabian menyayangkan, masih terisak. “Oma selalu percaya aku bisa jadi sesuatu, bahkan saat aku sendiri ragu,” suaranya terdengar sengau.
“Oma masih akan selalu ada kok, dia melihat kita, cuma beda alam aja,” Suci menyandarkan lagi kepala Fabian ke bahunya, lalu mengelus-elus kepala di balik hoodie itu. Fabian sempat terkejut, tapi kemudian mengguratkan senyum terhibur.
“Maaf ya, aku pasti kelihatan payah dan cengeng banget sekarang. Menyedihkan,” Fabian menebak imejnya di pandangan gadis itu.
“Nggak apa-apa. Kamu nangis juga masih ganteng kok,” Suci menenangkan dengan candanya.
Fabian mengulum tawanya. “Kamu ya, masih aja bisa bikin aku ketawa,” ia menegakkan duduknya lagi, menatap Suci seakan ia makhluk ajaib. “Aku masih nggak percaya kamu ada di sini,” ungkapnya takjub.
“Jangankan kamu, aku aja nggak percaya,” Suci terkekeh. “Modal nekat aja… dan sepertinya semesta mendukung kedatanganku ke sini,” ia menatap langit luas, membiarkan angin membelai rambutnya lembut.
“Kamu… tahu alamat rumahku dari mana? Tahu pemakaman Oma dari mana?” Fabian bertanya-tanya heran, baru terpikirkan.
Suci mendadak gugup, “Ah itu ya… dari semesta,” ia berusaha menjawab seambigu mungkin. Tentu ia tidak ingin ketahuan menyadap ponsel pria Amsterdam itu diam-diam sejak di Indonesia.
Fabian tersenyum maklum, “Iya ya, kamu selalu punya rahasia.”
“Dari kantor kok.” Suci menepis kecurigaan Fabian. “Sekarang aku lapar, punya rekomendasi tempat makan yang enak?” ia mengalihkan topik.
Fabian tersenyum lalu bangkit dari duduknya. “Ayo ikut.”
Kedua insan itu makan siang bersama di sebuah restoran dengan penuh canda, berbincang riang. Seolah kehadiran gadis itu cukup untuk membuat Fabian lupa akan lukanya.
-oOo-
Suci terperangah saat terbangun pagi hari di rumah keluarga Meijer, masih belum bisa percaya pengalamannya ini.
“Ini bukan mimpi ya? Aku di Belanda?” berkali-kali ia harus meyakinkan dirinya.
Ia menatap seantero kamar itu, baru sadar betapa berbedanya kamar ini dengan kamarnya dan kontrakannya. Apa ini kamar yang dulu ditempati Akasia?’ ikirannya mulai penasaran. Ia sejujurnya iri dan cemburu dengan wanita itu.
Ia mengamati seluruh sudut ruangan dengan detail, memeriksa sisa kehadiran wanita itu. Tangannya menjamah seluruh isi laci meja dan lemari, seaat kemudian ia tersadar dengan kewarasannya. Apa yang sedang aku lakukan sih? ia heran dengan tingkahnya sendiri. Lantas ia memutuskan untuk segera mandi, ia harus membuat kesan baik selama berada di rumah keluarga Fabian.
Setelah Oma tiada, Fabian merasa rumah menjadi jauh lebih lengang, namun sejak gadis itu datang, rumah kembali semarak. Kehadiran Suci meramaikan rumahnya dengan keceriaannya sehingga keluarganya sesaat bisa lupa dengan duka mereka. Ketika sendiri di kamar, Fabian masih sering termenung, terbawa kenangan akan Oma, sehingga kembali sesak dan ingin menangis. Tetapi gadis itu selalu sibuk mengajaknya keluar kamar. Suci kerap memaksanya untuk menemaninya menghabiskan waktu selama berada di Amsterdam. Seperti juga suara bel sepeda yang terdengar nyaring saat ini, itu pasti ulah Suci lagi.
“Fabian, main yuuk! Kita jalan-jalan, naik sepeda. Lumutan loh kalau di dalam kamar terus!” seru gadis itu mengajaknya dari luar rumah. Orang tua Fabian yang mulai terbiasa hanya mengulum senyum menyaksikan tingkah gadis itu yang periang dan berisik, mirip Oma mereka.
Padahal baru kemarin Fabian membawa Suci ke taman Vondelpark, meski ia malah menangis di hadapannya. Bagaimana tidak. Ini bulan Agustus, pemandangan musim panas Amsterdam yang semarak sangat kontras dengan suasana hatinya. Saat matahari akhirnya muncul, suasana kota langsung berubah. Orang-orang berjalan keluar, duduk di taman atau di kafe luar ruangan, membawa keluarganya menikmati mentari yang jarang sekali hadir menghangatkan, menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Semua bahagia, namun tidak dengan Fabian; Oma yang periang dan bersinar secerah mentari itu sudah pergi untuk selamanya.
Suci menekan pipi Fabian dengan telunjuknya. Seketika Fabian tersadar dari lamunannya.
“Apa yang kamu pikirin? Pemandangan di luar lagi bagus banget loh!” Suci menegurnya. Mereka duduk berhadapan di kursi kafe yang menghadap ke kanal.
“Iya, sayang Oma udah nggak di sini. Padahal Oma suka banget musim panas,” Fabian menyayangkan. Ia melemparkan pandangannya pada bunga hortensia yang tumbuh di pot tanaman di dekat sana. “Oma pernah bilang, bunga yang mekar paling lama adalah yang paling sabar menghadapi musim.”
Suci tersenyum tenang, “Dan kayaknya Oma tahu kamu akan tumbuh menjadi orang yang sabar.”
Fabian menarik napas, “Aku sedang mencoba. Tapi hari-hari tanpa Oma rasanya janggal, aku kehilangan arah, seperti Amsterdam tanpa kanal.”
Suci mengangguk, “Kanal bisa surut, tapi jalan setapaknya kan tetap ada. Kadang kita cuma perlu seseorang yang menemani di samping untuk mengingatkan kita arah pulang,” suaranya lembut.
Fabian berbalik menatapnya, tatapannya berat tapi hangat, “Kenapa kamu nekat ke sini, Suci? Sendirian, jauh, meninggalkan semuanya.”
Suci menatapnya balik dengan tenang, “Aku takut kamu sendirian. Aku tahu rasanya kehilangan seseorang tanpa sempat bilang betapa kita menyayanginya.”
Pemuda itu terenyuh, “Jadi kamu datang…untuk memastikan aku nggak sendiri?” suaranya nyaris berbisik.
Suci tersenyum, “Dan untuk memastikan kamu nggak lupa, bahwa hidupmu tetap punya arah, meski orang yang dicintai telah pergi.”
Fabian memejamkan mata sejenak. Angin menyapu rambutnya pelan. Lalu dengan perlahan ia meraih tangan Suci. Genggamannya tenang, seperti seorang pelaut yang akhirnya menemukan mercusuar di kejauhan. “Terima kasih karena kamu datang.”
Suci merengut, “Aku nggak mau ucapan terima kasih. Aku cuma mau kamu tahu, aku ada di sini untuk kamu.”
Dan di kafe yang hangat itu kedua hati pun menghangat. Di tengah aroma bunga dan duka, dua hati berlabuh dalam diam. Dengan kehadiran yang lebih dalam dari apa pun.


 serenarara
serenarara 








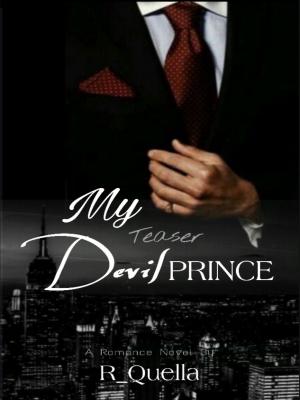

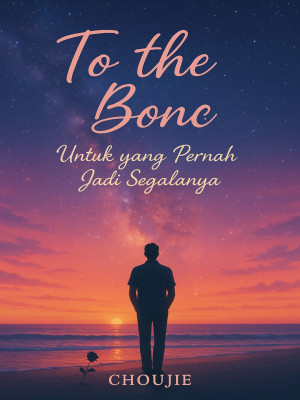

Menarik
Comment on chapter PrologSelalu penasaran kedepannya