Ada kalanya cinta tidak diukur dari seberapa kuat kita menggenggam, tapi dari keberanian melepaskan dengan lembut—karena tahu, menggenggamnya lebih lama justru bisa melukainya lebih dalam.
**
Pagi itu, matahari terasa ramah. Tidak terlalu terik, tidak terlalu malu-malu. Seperti pagi yang tahu caranya bersikap netral saat dua orang sedang pura-pura baik-baik saja.
Nata sudah ada di depan rumah ketika aku keluar, dia duduk di atas motor, helm di tangan, jaket abu-abu kesayangannya dibiarkan terbuka. “Sarapan dulu, yuk,” katanya begitu melihatku.
Aku mengangguk. “Di tempat biasa?”
Dia tersenyum. “Kalau kamu belum bosan.”
Aku duduk di jok belakangnya, seperti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini aku memegangnya sedikit lebih erat. Bukan karena takut jatuh. Tapi.. takut ini jadi kali terakhirnya.
Kami tidak banyak ngobrol selama di perjalanan. Tapi juga tidak hening seperti orang asing. Nata sesekali menunjuk anjing liar yang melintasi trotoar, atau nyelutuk soal tukang parkir yang menurutnya terlalu semangat. Aku tertawa seadanya. Dan itu cukup. Buat pagi itu, cukup.
Kami tiba di warung langganan, tempat yang sama sejak kami mulai dekat.
Pemiliknya menyapa kami dengan senyum lebar “Dua nasi uduk, seperti biasa?” Tanyanya dengan ramah.
“Iya, Bu,” jawab Nata.
Aku duduk, membuka tisu dari saku celana, mulai menyusun peralatan makan seperti biasa: sendok di kanan, garpu di kiri, gelas ditarik sejajar dengan piring. Nata memperhatikanku sebentar, lalu berpaling tanpa komentar. Dia sudah tahu ini bagian dari aku. Dari OCD-ku. Dari cara aku bertahan.
“Kemarin kamu tidurnya nyenyak?” tanyanya sambil menuang teh.
Aku mengangguk. “Lumayan. Mimpi kamu jatuh dari tangga.”
Dia nyengir. “Untung cuma mimpi, kalo beneran gak jadi makan nasi uduk kita pagi ini.”
Aku ikut nyengir. Tapi ada sesuatu yang tercekat di dada. Hari itu kami makan seperti biasa, ngobrol seperti biasa, tertawa seperti biasa. Tapi aku tahu, aku yang duduk di hadapannya pagi itu, bukan orang yang sama seperti kemarin. Dan aku curiga... dia juga menyadarinya.
Kami makan dalam diam yang hangat. Teh manis masih mengepul di gelas kaca, dan suara sendok dari meja sebelah jadi latar yang menenangkan. Pagi itu tampaknya semesta ingin memberi kami jeda.
Sampai akhirnya Nata membuka suara, santai. “Oh iya, berapa kali lagi kamu harus terapi?”
Tangan kiriku yang sedang mengaduk nasi langsung berhenti. Sekilas saja. Tapi cukup terasa.
“Masih beberapa kali lagi,” jawabku pelan “Kenapa nanya?”
“Enggak. Cuma pengen tahu aja. Soalnya kamu makin kelihatan... nggak secemas dulu,” katanya, lalu menyuap tahu goreng ke dalam mulutnya.
Aku tersenyum kecil. Tapi dadaku mulai mengencang.
Dia bilang cuma pengen tahu. Tapi kenapa kalimat itu terdengar seperti pengen tahu kapan semua ini selesai? Kenapa rasanya seperti kami sedang menghitung mundur?
Aku tahu Nata mencintaiku dengan tulus. Tapi aku juga tahu, bahwa cinta bisa lelah, meski kami tak ingin pergi. Pertanyaan tadi mengingatkanku pada seseorang yang berdiri di pintu kereta, menatap jam tangan, bukan karena ingin turun, tapi karena tahu waktunya makin dekat.
Aku mengangguk pelan, pura-pura baik-baik saja. “Mungkin… enam atau delapan kali lagi. Tergantung kondisi ku juga.”
Dia mengangguk, tampak lega. “Oke. Tenang aja, aku akan temani setiap sesi terapi kamu.”
Aku hanya mengangguk lagi. Tapi kali ini lebih pelan. Lebih berat. Karena pertanyaan tadi masih menempel di kepala, tidak mau pergi.
Kami menyantap sarapan tanpa banyak kata. Setelah membayar, kami naik motor dan melaju ke arah kampus. Jalanan pagi mulai padat, tapi tidak bising. Kabut tipis masih menggantung rendah di beberapa sudut kota. Aku duduk di belakang Nata, membiarkan jaketnya menyentuh wajahku, dan aroma sabun mandinya menguar samar. Familiar. Menenangkan. Menyakitkan.
“Udah deh Nat, liat jalan saja. Jangan liatin aku di spion terus, nanti kita nabrak” komentarku ketika beberapa kali mata kami bertemu pandang.
“Enggak kok, aman.. kalo nabrak paling juga cuma kamu yang nabrak hati aku berkali-kali.” Godanya.
Aku menepuk pundaknya. “Udah ah, fokus ke jalan aja.”
Tapi kata kata ku seperti diabaikan. Sepanjang perjalanan, dia masih terus beberapa kali menoleh lewat spion. Mataku menangkap tatapannya yang cepat lalu kembali ke jalan.
“Cantik banget kamu Ra, aku pengen liat itu selamanya”
Aku mengerutkan kening. Pura-pura tidak mendengar ucapan terakhinnya. “Apa Nat?” Jawabku
“Kamu cantik banget, Ra. Bahkan waktu cuma duduk diem kayak gini. Rasanya kayak.., aku pengin lihat senyum kamu selamanya.”
Aku membeku sebentar. Lalu menepuk punggungnya lagi, tapi lebih pelan. “Gombal ih masih pagi.”
“Serius,” katanya sambil melirik spion lagi. “Aku selalu bilang kan, kamu itu versi paling tenang dari badai. Sekali kamu senyum… kayak semua hal yang berantakan di kepala aku ikut tenang juga.”
Aku menunduk. Menyembunyikan wajahku di balik helm, bukan karena malu, tapi karena aku takut pecah. Kata-katanya terlalu indah. Terlalu penuh janji. Dan aku tahu, di dalam diriku, aku sedang mempersiapkan pengkhianatan kecil. Sebuah keputusan yang mungkin akan membuat senyum itu tak lagi dia lihat.
Motor terus melaju, membawa kami ke arah kampus, tempat di mana kami akan kembali sibuk dengan kehidupan masing-masing.
Kami berhenti di depan gerbang kampus. Nata melepas helmnya duluan, rambutnya sedikit acak karena angin. Ia menoleh ke arahku, masih dengan senyum kecil yang entah kenapa hari ini terasa lebih menyakitkan daripada manis.
“Nanti sore jangan ada janji ya,” katanya sambil membetulkan tali jam tangannya. “Aku mau ajak kamu ke suatu tempat.”
Aku mengerutkan dahi. “Tempat apa?”
“Rahasia,” katanya cepat. “Pokoknya abis kelas langsung kabarin aku. Aku jemput.”
Aku mengangguk, berusaha menjaga nada suara tetap datar. “Oke.”
Kami berjalan beriringan beberapa langkah, sebelum akhirnya berpisah di tangga masuk gedung masing-masing. Seperti hari-hari sebelumnya. Tapi langkah kami terasa... lebih hati-hati. Seolah masing-masing takut menginjak sesuatu yang rapuh. Atau mungkin karena kami tahu, hari ini bisa jadi akan mengubah banyak hal.
Aku masuk ke kelas. Tapi pikiranku tertinggal di jalanan tadi. Di spion motor yang menampilkan versi diriku yang tersenyum—padahal di dalam, aku sedang menghitung waktu.
Waktu terus berjalan, jam kuliah akhirnnya selesai. Langit mulai menguning ketika aku keluar dari gedung. Udara sore terasa sedikit dingin, dengan aroma debu dan bunga kering yang ditiup angin. Di seberang jalan, Nata sudah menunggu. Bersandar di motor, dengan helm di satu tangan, dan satu tangan lainnya mengusap wajah seolah mencoba mengusir lelah.
Aku berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas garis di bawah matanya. Rambutnya berantakan, sedikit jatuh ke dahi, dan matanya, mata yang biasanya cerah kali ini terlihat sayu. Tapi dia tetap tersenyum.
“Maaf, nunggu ya?” tanyaku pelan.
Dia menggeleng cepat. “Enggak, baru aja.”
Padahal jelas dia sudah menunggu cukup lama di sana.
Tanpa banyak bicara, dia membuka tasnya, mengambil jaket hitam yang sudah sering kulihat dia pakai. Lalu mendekat dan bukannya menyampirkan, dia merentangkan jaket itu, menyelimutkanku pelan. Tangannya bergerak tenang, mengancingkan jaket satu per satu di tubuhku. Gerakannya hati-hati, nyaris seperti ritual.
“Biar kamu nggak kedinginan,” katanya pelan. Matanya menatap wajahku sebentar, lalu berpindah ke kancing terakhir di bawah daguku. “Aku nggak mau kamu sakit.”
Jaket itu masih hangat. Harum Nata melekat di dalamnya. Waktu dia merapatkan bagian kerahnya, aku merasa seperti dipeluk. Dan mungkin memang itu niatnya.
Kami naik motor, dan perjalanan dimulai. Senja menyapa dengan lembut. Warna langit mencair, jingga berbaur ungu. Jalanan ke arah luar kota mulai sepi. Pepohonan di kiri kanan menggugurkan daun-daun kecil, seperti salju versi tropis. Nata memelankan laju motor, seolah tidak ingin waktu bergerak terlalu cepat.
“Capek nggak hari ini?” tanyanya, suaranya lembut tertiup angin.
Aku mengangguk kecil. “Biasa aja.”
“Kalau aku,” katanya, “Rasanya.. capek banget. tapi pas liat kamu keluar tadi, kayak semuanya reda.”
Aku diam. Ada bagian dariku yang ingin menjawab manis. Tapi di dalam kepala, suara lain sudah terlalu bising.
“Ra?”
“Hmm?”
“Aku nggak tahu tempat ini bisa bikin kamu senang atau nggak,” katanya, “tapi aku cuma pengin kamu punya satu sore yang tenang. Tanpa beban. Tanpa harus mikirin besok. Boleh kan?”
Aku mengeratkan peganganku lalu mengangguk.
"Boleh." Jawabku singkat. Meskipun aku tahu, tenang yang sesungguhnya tidak bisa dibeli dengan pemandangan indah.
Motor mulai menanjak pelan. Jalanan berkelok, sempit, diapit pepohonan tinggi yang mengintip langit senja. Cahaya oranye terselip di sela-sela dedaunan, menari di atas aspal. Angin makin dingin, tapi jaket Nata masih hangat di tubuhku. Dan punggungnya di depanku, jadi satu-satunya hal yang bisa kupegang saat dunia terasa terlalu kosong.
“Ra?” katanya lagi di sela-sela tikungan tajam.
“Ya?”
“Aku pernah kepikiran,” suaranya agak ditinggikan karena angin, “kalau nanti kamu udah lulus… kamu pengin ke mana?”
Aku diam beberapa detik. “Nggak tahu. Kayaknya belum kepikiran.”
Dia tertawa kecil, tapi pahit. “Aku tahu kamu nggak suka mikirin hal terlalu jauh. Tapi... aku sering mikirin kamu di masa depan.”
Motor terus melaju. Suaranya bergema pelan di lembah. Nata melanjutkan, masih dengan nada tenang, seolah sedang bercerita pada langit.
“Aku ngebayangin kamu kerja di studio arsitektur yang kamu suka. Punya project sendiri. Punya ruangan yang kamu desain dari nol. Punya hidup yang kamu pilih sendiri.”
Aku menggigit bibir bawahku. Entah kenapa, kalimat-kalimat itu terdengar seperti puisi perpisahan.
“Dan kalau kamu masih izinin aku ada di situ...” lanjutnya, “aku mau jadi orang pertama yang ngelukis bangunan pertama yang kamu bikin. Aku mau duduk di lantai dua sambil lihat kamu ngarahin pekerja bangunan. Terus pas kamu selesai, aku ajak kamu makan di warung bakso pinggir jalan. Kamu marah karena bajumu kotor. Tapi aku seneng karena kamu senyum.”
Aku tidak menjawab.
Ada rasa panas yang merayap di ujung mata. Tapi tidak tumpah. Karena tubuhku sendiri belum bisa sepenuhnya merasa. Seolah aku cuma menonton hidupku lewat layar tipis, dan semua perasaan hanya suara tanpa gema.
“Nata…”
“Hmm?”
“Kalau semua itu nggak kejadian... kamu bakal kecewa ya?”
Dia tidak langsung menjawab. Hanya ada suara motor dan angin yang makin kencang.
“Nggak,” katanya akhirnya. “Aku bakal sedih. Tapi nggak kecewa.”
Aku mengendurkan peganganku sedikit. Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Aku tahu, tidak kecewa bukan berarti tidak sakit.
“Kadang aku ngerasa kamu terlalu baik buat aku,” kataku pelan.
Nata tertawa, tapi nadanya tidak seterang biasanya. “Kamu tahu nggak, orang yang ngerasa nggak layak dicintai itu... biasanya yang paling butuh dicintai.”
Aku tidak membalas. Karena dia benar. Tapi juga karena aku takut itu tidak cukup.
Kami terus melaju, menembus awan tipis yang menggantung rendah. Ujung jalan mulai terlihat. Di sana, langit terbuka lebar, memantulkan cahaya jingga yang terakhir sebelum malam turun.
Kami sampai di tebing saat matahari mulai tergelincir di ujung cakrawala. Langit seperti kanvas yang dilukis terburu-buru—campuran jingga, emas, dan sedikit biru tua yang mulai menyusup masuk. Angin di sana lebih dingin, tapi jaket Nata masih melindungi tubuhku. Hangatnya aneh. Seperti pelukan yang tahu akan segera dilepas.
Aku duduk di pinggir tebing, menatap cakrawala. Nata berdiri di sampingku, diam, matanya menyapu langit seolah mencari sesuatu yang bisa menjelaskan segalanya. Lalu dia ikut duduk, jaraknya tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat udara di antara kami terasa penuh.
“Kamu tahu, Ra,” katanya pelan, “dulu aku pikir jatuh cinta tuh soal deg-degan. Soal ngerasa nggak bisa jauh dari orang itu.”
Aku menoleh, tapi dia tetap menatap lurus ke depan.
“Tapi sekarang aku ngerti... jatuh cinta juga soal sabar. Soal duduk di sebelah orang yang kamu tahu lagi sakit, dan kamu nggak bisa bantu apa-apa selain tetap di situ.”
Aku menarik napas. Lama. “Aku tahu kamu lelah.”
Nata tersenyum kecil. “Lelah, iya. Tapi lelahnya bukan karena kamu, Ra. Lelahnya karena aku belum tahu gimana caranya jadi tempat aman buat orang yang pikir dirinya ancaman.”
Kata-katanya kena tepat di tempat yang sedang berusaha aku tutupi. Di rongga hampa dalam dadaku yang terus membesar belakangan ini.
Aku menunduk. “Kadang aku ngerasa... semua hal yang dulu bikin aku senang, sekarang datar. Hambar. Bahkan langit seindah ini, cuman aku bisa lihat, tanpa bisa ngerasa apa-apa.”
“Berarti sekarang aku harus ganti jadi langit kamu juga,” katanya pelan. “Supaya walau kamu nggak bisa ngerasa, kamu masih bisa tetap liat aku di situ. Dan kamu tahu aku tetap luas. Tetap nunggu.”
Hatiku seperti ditusuk perlahan dengan jarum tumpul. Tidak langsung berdarah, tapi ngilu yang menjalar ke seluruh tubuh.
“Aku takut, Nat,” suaraku nyaris berbisik. “Kalau suatu hari kamu berhenti nunggu. Atau... kamu nunggu terlalu lama sampai kamu hancur pelan-pelan.”
Dia menoleh ke arahku. Matanya lelah, tapi penuh ketulusan. “Aku bisa nunggu. Tapi aku nggak mau kamu terus-terusan merasa harus pergi demi nyelametin aku. Aku bukan korban dari rasa sayang kamu, Ra. Aku justru hidup karena itu.”
Aku memejamkan mata. Menahan sesuatu yang belum tahu bentuknya—tangis, sesal, atau hanya kekosongan.
Dan di bawah langit yang sebentar lagi gelap, aku hanya bisa berharap.., semoga keputusanku nanti tidak membunuh cahaya yang ada di matanya.
Aku menarik napas dalam-dalam, menatap garis tipis cahaya terakhir di langit. Di sampingku, Nata masih diam, tangannya memeluk lutut, pandangan jauh ke bawah, ke kota yang perlahan menyalakan lampu satu per satu. Rasanya seperti melihat dunia berjalan pelan dari kejauhan. Seolah waktu sengaja memperlambat segalanya agar aku bisa berpikir lebih jernih, atau justru lebih dalam ke arah yang seharusnya tak kusentuh.
Aku tahu ini momen yang damai. Tapi mungkin justru karena itulah aku harus bicara sekarang. Saat kepalaku cukup tenang untuk menyampaikan semuanya tanpa meledak.
“Nata…”
Dia menoleh. “Hm?”
Aku menatap wajahnya yang tertimpa cahaya oranye terakhir. Rambutnya berantakan ditiup angin. Matanya masih sembab, tapi lebih tenang dari pagi tadi.
“Aku sayang banget sama kamu.”
Senyumnya muncul, kecil. “Aku juga.”
Aku menggigit bibir bawahku. “Dan karena itu… aku harus bilang ini lagi.”
Dia menatapku, lama. Tapi tidak menyela.
“Aku… aku tetap ngerasa harus pergi, Nat. Bukan karena aku nggak cinta. Tapi karena aku terlalu cinta. Karena aku tahu kalau aku terus di sini, kamu bakal makin lelah. Dan aku makin hilang.”
Matanya berkaca, tapi tidak langsung pecah. Dia seperti menahannya dengan seluruh sisa tenaganya.
“Jadi kita balik bahas yang tadi malam ya?” suaranya pelan.
Aku mengangguk, pelan sekali. “Tapi kali ini, bukan karena aku nyuruh kamu pergi. Kamu bebas mutusin. Tapi aku harus jujur. Aku ngerasa..., aku nggak bisa jadi pasangan yang layak buat kamu sekarang.”
Dia mendongak menatap langit, lalu mengembuskan napas panjang. “Kalau kamu berharap aku berubah pikiran, aku belum bisa, Ra.”
Aku menoleh padanya.
“Aku belum bisa bilang ‘ya’ ke perpisahan ini. Tapi... aku juga nggak akan maksa kamu buat tetap tinggal kalau kamu benar-benar mau pergi.”
Aku terdiam. Terdengar suara angin menggoyangkan daun-daun kering di sekitar kami.
“Terus gimana?” tanyaku lirih.
Dia menatapku lama. Lalu tersenyum, bukan yang manis seperti biasa, tapi yang terasa seperti menahan sesuatu di dadanya agar tidak meledak.
“Kalau ini yang kamu yakini, kalau kamu butuh ruang... aku akan kasih itu.”
Aku menahan napas.
“Aku sayang banget sama kamu, Ra. Tapi kalau tetap bersamaku justru bikin kamu makin jatuh, aku nggak mau jadi alasan kamu makin hilang.”
Aku meremas ujung jaket yang dia pakaikan tadi. “Maaf…”
Dia menggeleng pelan. “Nggak usah minta maaf. Nggak ada yang salah dari memilih sembuh.”
Kami sama-sama diam. Angin sore mulai dingin, tapi tidak sedingin kenyataan bahwa kami baru saja sepakat untuk berpisah. Bukan karena cinta itu hilang. Tapi justru karena cinta itu terlalu besar untuk terus menyakiti.
Nata menunduk, lalu bangkit pelan. Dia berjalan ke arah motornya, tapi sebelum menyalakan mesin, dia menoleh lagi.
“Aku akan nunggu. Tapi bukan buat kamu balik jadi pacarku. Aku nunggu kamu sembuh. Buat kamu sendiri.”
Aku tak sanggup menjawab. Hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan kembali menanggung jarak.
Langit mulai kehilangan warna. Jingga telah runtuh di balik bukit, menyisakan abu yang menggantung seperti perasaan kami yang tak selesai.
Di motor yang mesinnya belum juga di hidupkan. Tidak ada yang bicara. Hanya deru napas dan semilir angin yang meniupkan dedauan kering yang terdengar. Nata terdiam lama, tangan kirinya memegang helm, tangan kanannya masuk ke saku. Kepalanya menunduk.
Aku menatap punggungnya.
“Nata...”
Dia tidak menjawab.
Aku mendekat pelan, berniat mengambil helm dari tangannya. Tapi dia tetap diam. Bahunya sedikit bergetar.
“Nata,” ulangku, lebih pelan.
Dan akhirnya dia mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Lembab. Sudut bibirnya bergetar menahan sesuatu yang selama ini selalu ia sembunyikan.
“Aku... nggak nyangka rasanya sesakit ini, Ra,” katanya, suaranya parau. Retak. “Ternyata... mengikhlaskan orang yang masih kita cintai itu kayak.., kayak ngelepas separuh nafas.”
Aku menatapnya lama. Ingin memeluk. Tapi tidak berani. Aku hanya berdiri di sana, jadi saksi dari air mata lelaki yang selama ini selalu jadi tempatku bersandar.
Dia mengusap wajahnya cepat. Lalu tertawa kecil, hambar. “Maaf ya, jadi drama. Padahal niatnya ngajak kamu liat sunset, bukan nambah luka.”
“Nggak... jangan minta maaf. Nggak ada yang salah,” kataku. Suaraku pun ikut parau.
Nata akhirnya menyodorkan helmku. Tangannya masih bergetar.
“Boleh aku anterin kamu pulang?”
Aku mengangguk pelan. Kami naik motor dalam diam. Tapi tidak kaku. Angin malam memeluk kami, seperti pelukan terakhir yang tidak sempat diucapkan.
Saat motor mulai menuruni tebing, aku merapatkan jaket yang dia pakaikan tadi. Masih hangat. Masih ada aromanya. Tapi pelan-pelan, aku tahu, semua itu akan menjadi kenangan.
Dan saat itu juga, aku tahu. Aku baru saja kehilangan rumah yang paling hangat dalam hidupku, dengan cara paling lembut yang pernah ada.


 bunca_piyong
bunca_piyong











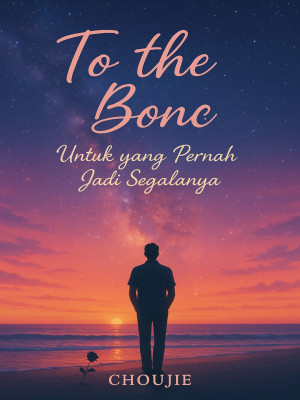






Eh eh eh eh bab selanjutnya kapan ini? Lagi seru serunya padahal.. kira-kira Nara suka Nata juga ga ya??? Soalnya kan dia anhedonia🧐 .