Hari-hariku setelah perpisahan terasa lebih sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan seperti dulu, tapi semacam ruang kosong yang harus kuisi sendiri. Tanpa suara motor di depan gerbang. Tanpa suara Nata yang sering melempar lelucon aneh atau pujian ganjil. Tanpa pelukan di jaketnya. Rindu itu tak hilang. Ia berubah bentuk—menjadi doa, menjadi kekuatan untuk menyambut pagi.
Aku belajar mengenali suara-suara di dadaku, bukan untuk ditekan, tapi untuk dipahami. Aku tak lagi menghitung langkah dari gerbang menuju kelas. Aku bahkan berani memutar jalur, melewati galeri seni hanya untuk menoleh sekilas. Mencari sosok yang dulu selalu menemaniku. Tapi dia tak pernah terlihat. Nata benar-benar menghilang dari kampus dan dari hari-hariku. Namun, karena itu justru membuatku belajar menerima dan perlahan memeluk diriku sendiri.
Beberapa kehilangan memang tak perlu diganti. Cukup diakui. Cukup dihormati. Cukup dirindukan. Aku belum sembuh. Tapi aku mulai tenang. Pikiran yang melompat dan kompulsif masih datang, tapi kini aku menyapanya pelan, seperti berbisik kepada diri sendiri “Aku tahu kamu datang, tapi aku bisa hidup bersamamu.”
Aku kembali ke klinik, duduk di ruang tunggu yang kini terasa sepenuhnya milikku. Kursi di seberang yang dulu diisi Nata, kini kosong. Hanya ada bayangannya yang samar, tertinggal menemaniku di sana. Saat psikologku bertanya, “Rasanya gimana sekarang?” Aku menjawab, “Masih takut. Tapi nggak setakut dulu.” Dan itu cukup.
Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada kabar dari Nata. Tak ada pesan, tak ada like, tak ada jejak. Awalnya aku menunggu. Lalu perlahan… aku berhenti berharap. Sore itu, aku menggambar di teras. Bukan tugas kampus. Bukan sesuatu yang harus dipresentasikan atau dinilai. Hanya… menggambar. Untuk diriku sendiri. Garisnya tak sempurna, perspektifnya sedikit miring, tapi aku membiarkannya. Aku membiarkan sesuatu menjadi nyata tanpa harus sempurna—seperti diriku.
Dan seperti banyak sore sebelumnya, aku tidak berharap apa-apa. Tapi entah kenapa, ketika suara motor berhenti di depan pagar, jantungku melonjak lebih dulu, bahkan sebelum aku melihat siapa yang datang. Tapi bukan Nata. Hanya tukang paket.
Aku berjalan ke pagar, berusaha menenangkan degup yang terlalu cepat untuk harapan yang terlalu kecil.
“Mbak, ini untuk Nara,” katanya.
Sebuah paket kecil. Tak ada nama pengirim. Tapi saat kubuka, aku tahu itu dari Nata. Sebuah lukisan dengan goresan yang sangat familiar. Langit senja yang pernah kami lihat dari tebing terakhir. Tanpa sosok manusia. Hanya langit dan sunyi yang manis. Di belakang kanvas, selembar surat diselipkan.
Untuk Nara,
Aku tahu surat ini akan sampai padamu. Tapi tetap saja, menuliskannya membuatku merasa seolah kita sedang berbicara—meski hanya lewat warna dan kata.
Nara, setelah kamu pergi, aku belajar bahwa beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Bahkan cinta sebesar apapun, kalau akhirnya bikin salah satu dari kita kehilangan diri… ya harus dilepas.
Tapi bukan berarti aku berhenti peduli. Aku masih sering kepikiran kamu, terutama saat hal-hal kecil muncul, seperti gambar perspektif yang meleset, senja di jendela bus, dan lagu yang pernah kita dengar sambil diam-diam saling pandang.
Kamu mungkin sekarang sedang mencoba berdiri sendiri. Dan aku tahu, itu nggak mudah. Tapi aku percaya kamu bisa. Karena kamu selalu berani, bahkan saat kamu sendiri merasa takut.
Ra, lewat tulisan ini, aku ingin kamu tahu kalau aku bersyukur dan nggak pernah menyesal pernah jadi bagian dari dirimu. Kamu ingat kan, dulu aku pernah bilang, aku ingin jadi langit buat kamu—yang selalu ada untuk selalu kamu lihat.
Jadi kalau suatu hari kamu menatap langit dan merasa sedikit lebih tenang… mungkin itu artinya aku masih di situ. Menunggu. Diam-diam menjaga dari jauh.
Jaga dirimu, Nara. Dengan semua luka dan keindahan yang kamu punya.
—Nata
Tanganku gemetar saat membacanya . Tapi kali ini, aku tidak menangis karena kehilangan. Aku hanya diam. Mengizinkan dadaku penuh oleh rasa yang dulu menyakitkan, kini meneduhkan.
Beberapa minggu kemudian, aku membuka buku harianku. Surat dari Nata kuselipkan di dalamnya. Di jendela, senja merayap masuk pelan. Aku menulis, bukan sebagai catatan, tapi sebagai percakapan diam-diam untuk seseorang yang pernah begitu berarti.
Hai, Nata.
Aku baik. Mungkin belum sepenuhnya, tapi cukup untuk hidup tanpa merasa mati.
Aku masih menoleh saat melewati galeri. Masih ingin meminjam jaketmu saat angin dingin. Tapi aku tidak sedih lagi. Karena aku belajar bahwa kenangan yang menenangkan tak perlu disesali. Cukup dikenang—seperti senja yang tak sempat difoto tapi tak pernah hilang.
Terima kasih sudah datang. Terima kasih karena pernah tinggal. Dan lebih dari itu, terima kasih karena pergi dengan cara yang membuatku belajar tinggal di diriku sendiri.
Aku tak lagi menunggumu. Aku berjalan bukan untuk mengejar siapa-siapa. Aku sedang kembali padaku. Menyembuhkan luka yang selama ini tersembunyi, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dari sebelumnya.
Jika suatu hari kita bertemu lagi, aku harap kamu melihatku sebagai seseorang yang telah utuh kembali—meski dengan bekas retak yang kupeluk sendiri.
Terima kasih, Nata. Untuk segalanya. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa diucapkan, dan meski kita tak lagi berjalan bersama, kenangan ini akan selalu jadi bagian terindah dalam hidupku.
—Nara
Dan begitulah, aku menutup buku harian ini dengan hati yang lebih ringan. Kisah kami bukan tentang selamanya. Tapi tentang bagaimana aku belajar menemukan diriku—di tengah perpisahan, di sela rindu yang tak bisa kembali, dan dalam sakit yang tak langsung sembuh.
Aku sempat berpikir bahwa yang menyelamatkanku adalah cinta. Tapi ternyata, yang paling menyembuhkan... adalah keberanianku untuk tinggal. Tinggal di tubuhku sendiri. Di pikiranku sendiri. Di luka yang tak kutolak lagi.
Kini aku tahu: menemukan diri sendiri bukan soal kembali menjadi seperti dulu. Tapi tentang menerima siapa dirimu sekarang—retak, rumit, tapi tetap layak dicintai. Dan meski perjalanan ini panjang, meski aku belum sepenuhnya utuh, aku masih tetap melangkah, bukan untuk mencari siapa pun… Tapi untuk pulang—pada diriku sendiri.
Karena mungkin, menjadi utuh bukan soal tak pernah patah. Tapi soal bagaimana kamu memilih untuk hidup, meski pernah hancur. Dan aku memilih untuk hidup. Hari ini, besok, dan seterusnya. Meski masih terjebak dalam waktu mati, aku tetap memilih merasa dan terus berjalan.


 bunca_piyong
bunca_piyong










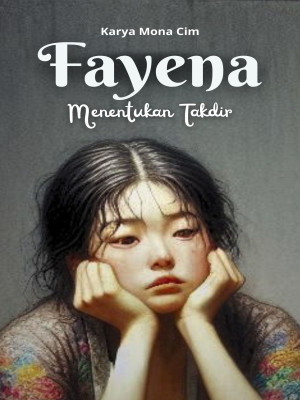







Eh eh eh eh bab selanjutnya kapan ini? Lagi seru serunya padahal.. kira-kira Nara suka Nata juga ga ya??? Soalnya kan dia anhedonia🧐 .