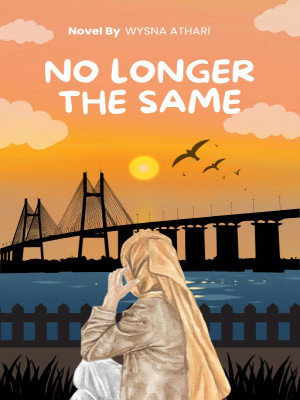Aku tidak tahu, ternyata acara kebudayaan itu dimulai dari malam ini. Bibi Gum-gum menjemputku untuk ikut ke acara terbesar tahunan di pulau ini. Ya, niat hati hanya ikut untuk makan-makan saja.
Acara malam ini adalah doa bersama dan acara adat. Sebelum memulai acara adat, seluruh pengunjung dikumpulkan di lapangan terbuka dan duduk bersama. Saat ingin mencari tempat duduk, aku bertemu dengan Brian yang ternyata ikut dalam acara yang awalnya kupikir akan terasa asing bagiku. Kami mengambil tempat duduk bersebelahan. Aku berharap malam itu aku bisa bertemu juga dengan Nube. Tapi karena terlalu ramai, aku tidak bisa menemukannya di segala penjuru. Entahlah, aku juga tidak tahu di mana dia terselip di antara ratusan orang yang datang.
Kami duduk di tengah-tengah kerumunan. Beberapa pemimpin agama berdiri di atas panggung dan satu per satu secara bergantian memimpin doa. Ada sesi di mana kami berdoa secara pribadi. Semua orang menutup mata dan mengangkat tangan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebenarnya aku tidak punya doa yang benar-benar ingin kupanjatkan. Tapi karena merasa aneh jika hanya diam, aku pun ikut menutup mata. Dalam hatiku, aku hanya berharap... semoga aku bisa sembuh. Bukan hanya luka yang terlihat, tapi juga yang tak kasatmata.
“Tiara...” suara Brian lirih menyusup di tengah keheningan. Seperti doa, tapi terasa menyentuh langsung ke arahku. Aku menoleh pelan, namun dia masih menatap ke depan, mata terpejam, tangan tertangkup.
Kupikir aku salah dengar. Saat aku hendak kembali memejamkan mata, dia berbisik lagi, “Apa doamu sudah terwujud?”
Keningku berkerut. “Hah?” gumamku pelan. Padahal aku belum sempat berdoa. Apa maksudnya?
“Tidakkah kau ingat kalau kita pernah berdoa bersama sebelumnya?”
Aku memandangnya lekat-lekat. “Kapan? Maksudmu... kita pernah?”
Brian membuka mata, lalu menoleh sambil tersenyum lembut. Saat itu, pemimpin agama mengakhiri sesi doa dan MC mulai memandu acara selanjutnya.
“Tidak ingat ya?” katanya pelan.
Aku hanya menatapnya, bingung. “Kita pernah ketemu sebelumnya?”
“Kita pernah dirawat di rumah sakit yang sama. Mungkin dua tahun lalu?”
Aku menggeleng, ragu. “Dua tahun lalu?” Yang aku ingat, aku hanya dirawat karena kecelakaan itu.
“Ya,” katanya, menyesuaikan duduknya. “Aku juga nggak menyangka kita bisa bertemu lagi, di pulau ini pula.”
Aku menggaruk pelipis, mencoba mengingat. “Aku nggak ingat sama sekali. Sungguh. Tapi... kok bisa kau yakin itu aku?”
“Aku baru sadar waktu lihat kamu pertama kali di kafe. Rasanya kayak pernah lihat, tapi aku nggak berani nanya langsung waktu itu.”
“Kau yakin?” tanyaku, setengah percaya.
“Yakin. Kamu dirawat di ruang 308, kan? Korban kecelakaan dari Bandung?”
Aku mengangguk pelan. “Iya... itu aku.”
“Kamu dirawat cukup lama. Aku ingat betul. Kondisimu waktu itu... parah. Tapi lihat kamu sekarang, luar biasa.”
Aku menatap Brian dengan rasa penasaran. “Jadi... kamu sakit apa waktu itu?”
Dia tertawa kecil, canggung. “Kamu benar-benar nggak ingat, ya? Jujur, awalnya aku takut kamu bakal nyebarin soal penyakitku.”
“Tenang saja. Aku bukan tipe orang seperti itu. Lagi pula, siapa sih yang suka penyakitnya dijadikan bahan omongan?”
Dia tersenyum lebar. “Apa aku kelihatan sehat sekarang?”
Aku mengangguk cepat. “Kelihatan. Tapi... apa kamu masih sakit?”
Dia hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Tapi dari sorot matanya, seolah ada kepasrahan yang tulus. Mungkin, sebagian luka hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan keyakinan.
“Brian...” gumamku di sela riuhnya pertunjukan adat di depan. “Aku sungguh tidak ingat. Ceritakan, ya?”
Dia menatap langit malam. “Sepertinya traumamu memang cukup dalam. Kita pertama kali ngobrol waktu kamu tanpa sengaja menabrakku di lorong rumah sakit. Dan sejak itu... kita sering duduk bareng, berdoa bareng. Kamu waktu itu sedang menanti seseorang...”
Aku tercekat. “Seseorang?”
Dia mengangguk pelan. “Kau ingin sekali bertemu dengannya. Tapi waktu itu kamu selalu gelisah... patah hati setiap kali menyebut namanya. Bahkan aku nggak bisa menenangkanmu.”
Aku menelan ludah. “Aku... nggak yakin. Tapi mungkin... aku bertemu dia sekarang.”
“Bagaimana dia sekarang?” tanya Brian.
“Sehat. Bahkan lebih sehat dari kita. Tapi... kayaknya kepalanya ada yang salah.”
Brian tertawa kecil. “Mungkin akibat kecelakaan itu?”
Aku mendecak sinis. “Kecelakaan? Dia itu seperti... psikopat.”
Brian terdiam sejenak. “Tunggu, apa kita bicara tentang orang yang sama?”
Aku menaikkan bahu. “Mungkin saja tidak.”
“Dia... orang yang karyanya akan dipamerkan. Kau bilang, kalau dia menang, dia akan dapat beasiswa, pelatihan, bahkan bisa masuk universitas di Bandung dengan mudah. Tapi kamu nggak sempat melihatnya tampil waktu itu.”
Mataku membesar. “Tunggu... maksudmu... Noah?”
“Noah, ya?” tanya Brian sambil mengamati reaksiku.
Aku menarik napas dalam. “Tapi... bagaimana bisa kamu tahu soal karyanya? Tentang dia datang?”
“Kamu waktu itu terus-terusan menggenggam surat darinya. Dan dia menulis, kalau pun kamu nggak datang, dia tetap ingin kamu tahu kalau dia menang. Bahwa semua itu karena kamu.”
Aku terdiam. Dada terasa sesak. Dunia rasanya mengecil. Aku bahkan sudah jauh dari rumah, menetap di pulau yang asing ini... tapi tetap saja, semesta membawaku bertemu Brian. Dan lebih dari itu, semua kepingan mulai menyatu. Tentang Noah. Tentang diriku. Tentang masa lalu yang ternyata belum selesai kutinggalkan.
Dan di tengah malam yang penuh doa ini, aku hanya bisa membisik dalam hati: Ya tuhan, kuatkan aku. Jika ini bagian dari penyembuhan, maka tuntun aku memahaminya.
***
Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, pikiranku berkecamuk. Bagaimana bisa begitu banyak hal yang terlewati dan terlupakan? Bagaimana mungkin Noah bersikap seolah tak pernah mengenalku? Apakah ini caranya mengujiku? Dan... bagaimana jika teman-teman sekelas tahu ada sesuatu antara aku dan Noah? Tapi, ah—masa bodohlah. Lagi pula, anak itu juga jarang masuk kelas. Barangkali tak ada yang tahu seberapa sering kami sebenarnya pernah bersama.
Mungkin inilah bentuk nyata dari kenyataan yang menyakitkan sekaligus melelahkan. Perasaanku diaduk-aduk seperti ombak yang menabrak karang. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap pada Noah setelah semua ini. Haruskah aku berpura-pura tak tahu? Menjalani hari seakan kehadirannya tidak berarti apa-apa? Tapi... bisakah aku mengingkari getaran itu?
Bukankah sikapnya yang seolah mengenal dan tak mengenalku sekaligus—menyiratkan bahwa dia pernah melihatku, jauh sebelum aku tiba di pulau ini?
Aku melewati taman bermain yang sepi. Dalam keremangan, aku berhenti dan berjalan pelan ke arah ayunan anak-anak. Angin malam menyapu lembut, membawa bau asin laut dan keheningan yang menenangkan sekaligus menyakitkan.
Noah... bagaimana dengan karyanya? Jika benar ia memenangkan seleksi itu, bukankah seharusnya kini ia tengah menjalani pelatihan? Atau bersiap tampil dalam pameran? Bukankah dulu dia pernah berkata ingin melangkah lebih jauh, membawa karya seninya ke dunia yang lebih luas? Dan jika benar ia datang menjengukku—mengapa aku menangis begitu hebat seperti yang dikisahkan Brian? Jika dia tak berarti, mengapa luka ini terasa begitu dalam?
Aku bahkan melupakan surat terakhir itu. Aku yang mengakhiri segalanya. Tapi kenapa... aku bahkan tak mengingat isi dan bentuknya?
“Ini sudah hampir jam sepuluh. Kau belum pulang?”
Suara itu menghentak lamunanku. Aku mendongak pelan, dan seperti yang sudah kuduga, suara itu datang dari orang yang tak kunjung menjauh.
Noah lagi.
Ada perasaan canggung, campur marah, campur tak ingin ditinggalkan. Aku menjadi serba salah. Ia benar-benar seperti bayangan yang menolak padam.
“Rumahku tidak jauh,” jawabku, mencoba bersikap biasa. “Lagipula, belum jam sepuluh, kan?” Aku mengayun pelan, seperti anak kecil yang tak ingin pulang.
Dia berjalan pelan, memasukkan kedua tangannya ke saku jaket. Embusan napasnya panjang, seolah mencoba membuang resah yang tak terlihat. Ia lalu duduk di pagar kayu di depanku.
“Kau pernah bertemu dengan Tiara sebelumnya?” tanyaku, nyaris tanpa sadar.
Dia tersenyum tipis. “Kalau aku pernah bertemu dengannya, kenapa aku harus bertanya apakah kau Tiara atau bukan?”
“Mungkin kau hanya sedang mengerjaiku,” balasku, mengalihkan pandang ke tanah.
Noah menarik jaketnya saat angin menyapu lehernya.
“Apa sebenarnya tujuanmu mendekatiku?” Aku menatapnya dalam. “Aku menemukan suratmu lagi... di kotak pos.”
Dia menatap kosong. “Hanya ingin memastikan,” jawabnya malas.
Aku berdiri. “Kalau begitu, aku pulang.”
“Baiklah... baiklah.” Ia berdiri. “Aku pernah bertemu Tiara sebelumnya.”
Aku terdiam. “Kalau begitu... kenapa aku tidak pernah melihatmu?”
“Hanya sekilas. Dan aku tak pernah yakin melihat wajahnya dengan jelas.”
“Kau yakin itu bukan hanya gambaran yang ada di kepalamu?”
Dia mengangkat alis. “Kenapa aku harus memberitahumu? Bukankah aku hanya menganggapmu seperti Tiara? Bukan berarti aku harus menceritakan semuanya.”
“Oh begitu? Kalau begitu, jangan samakan aku dengan Tiara yang ada dalam kepalamu.”
Dia tertawa kecil. “Tentu. Dia tetap istimewa untukku. Tapi kalau kau merasa terganggu karena aku terus muncul... mungkin sebenarnya kau juga yang tak sadar telah menungguku.”
“Dasar bocah satu ini,” gerutuku pelan, jengkel tapi tak bisa menyembunyikan senyum tipis.
“Aku tidak akan mengikutimu lagi,” katanya, kali ini dengan wajah serius, meski nadanya masih terasa ringan.
Aku mendesis pelan. “Akhirnya kau sadar juga. Kenapa tidak dari awal saja?”
“Karena kalau sejak awal aku yakin Tiara itu kau, mungkin aku tak akan bersikap seperti orang gila. Tapi kami punya janji... dan mungkin, jika pikiranku cukup waras, aku tidak akan lagi berharap pada janji itu.”
Dia tersenyum kecil. Tapi bukan senyum kemenangan. Itu senyum yang menyerupai perpisahan.
Ia pergi.
Aku menatap punggungnya yang menjauh. Ada sesak yang tak bisa kujelaskan. Bukan kehilangan... lebih tepatnya seperti ditinggalkan oleh bagian dari masa lalu yang tak sempat kutuntaskan.
Air mata itu turun tanpa permisi.
Aku menyeka pipi. "Kenapa aku menangis?" bisikku lirih.
Rasanya konyol. Tapi mungkin... di saat seperti ini, tak apa jika hati menjadi lebih rapuh dari biasanya. Mungkin kesedihan ini bukan untuk disangkal, melainkan untuk dimengerti. Karena setiap kehilangan mengajarkan kita bahwa harapan bukan untuk digenggam erat, tapi untuk dilepaskan—dengan ikhlas.
Dan dalam diamku, aku belajar percaya, bahwa Tuhan tidak pernah menjauh. Kadang, Ia hanya menunggu sampai kita bersedia menengadah dan berkata, "Aku lelah... tuntun aku pulang."


 tavxoc
tavxoc