Orang pertama yang Soya cari saat pulang sekolah adalah Sastra. Sebenarnya, keempat anggota yang lain juga. Mereka berpencar, sebab nomor pria itu tak aktif seharian. Tak bisa dihubungi.
Soya menemukan sang guru duduk di tepi panggung auditorium, menghadap para anggota Paskibraka yang duduk di ujung lain aula, membicarakan rencana upacara Hari Pendidikan Nasional dan sebagainya ketika hujan deras mengguyur lapangan.
Cewek itu baru akan mengabarkan kawan-kawannya lewat grup obrolan, tetapi ia mengurungkan niat saat melihat Sastra bengong. Pria itu sekilas tampak seperti gelandangan yang baru saja dicukur bersih dan dikenakan seragam guru. Sejujurnya, kemeja kelabu muda dan celana hitam yang dikencangkan oleh sabuk tampak tak cocok bagi Sastra. Atau, begitulah yang dipikirkan Soya, walau ia juga belum menemukan alasannya mengapa.
“Pak ...?”
Panggilan Soya menyentaknya dari lamunan entah apa. “Oh, Soya.” Ia menyunggingkan senyum lebar. “Ada apa? Mau pinjam kunci rumah saya? Gabus dan triplek tambahan sudah datang kemarin. Saya lupa belum ngabarin kamu.”
Mendengar Sastra begitu riang, Soya merasa liurnya kecut. Apa pria itu tahu kejadian saat jam istirahat tadi siang?
“Pak, sebenarnya ....”
“Gimana perkembanganmu?” tanya Sastra lagi. “Kamu bilang beberapa hari lalu kalau diam-diam latihan akting di kamar, ya? Saya seneng banget dengernya, Soya. Saya dulu juga gitu, biar nggak ketahuan orang tua.”
Ketika Sastra terkekeh pelan, Soya terperangah.
“Bapak dulu juga gitu?”
“Iya. Ibu saya dulu nggak suka begituan. Tapi mendiang bapak saya suka. Malah dulu bapak saya seorang aktor teater. Pernah pentas bersama dengan orang tuanya Nova juga, loh, waktu mereka masih muda. Bapak saya, sih, sudah senior.”
Baru kali ini Soya mendengarnya. Ia mengangguk-angguk kecil.
Menyadari bahwa tampaknya cewek itu siap menampung cerita, Sastra menepuk posisi di sampingnya. Soya menurut.
“Saya dengar Bapak juga bergabung ekskul teater Layar Surya dua puluhan tahun lalu?”
“Iya. 25 tahun, tepatnya.” Sastra tersenyum. “Tahun ini ke-25. Pas, ya? Seperempat abad saya mengabdi di Layar Surya, sebagai murid, sebagai tamu, hingga sebagai pembina sekarang.”
Soya sekarang paham kenapa Sastra sampai menawarkan nilai sempurna kepada Soya, demi menggenapi kuota minimal peserta ekstrakurikuler.
“Nggak bosan, Pak ...?”
“Bosan? Sama sekali nggak pernah.” Sastra menyeringai. “Remaja zaman sekarang nggak pernah bosan main hape, kan? Seperti itu rasanya. Tapi, Layar Surya lebih dari itu. Saya mending nggak makan seharian daripada nggak ngurusin teater ini. Karena ... ya ... Layar Surya yang bikin saya bertahan hidup.”
“Maksudnya, Bapak dapat penghasilan dari situ?”
Lagi-lagi Sastra terkekeh. Namun, belum sempat ia menjawab, Juni muncul. “Nah! Ketemu!”
Segera, ketiga anggota teater yang lain menyusul mereka, dengan sedikit omelan mengapa Soya tak mengabari lewat ponsel.
Sastra mengacungkan jari ke bibir, menyuruh semua diam agar suara mereka tak berbaur dengan diskusi riuh para anggota Paskibraka dan guyuran hujan.
“Anak-anak, mulai sekarang, kita pusatkan latihan di rumah saya.” Ucapan Sastra menegaskan bahwa rupanya dia sudah tahu apa yang terjadi, padahal belum ada satu pun di antara kelima murid itu yang bercerita. Ekspresi muda-mudi di hadapannya pun suram.
“Tapi, teater kita, kan, belum dibatalkan semester ini?”
“Saya tahu,” kata Sastra dengan nada misterius. “Tapi, ini lebih baik. Lagi pula kita mesti fokus menyiapkan properti, dan semua bahan udah tersedia di rumah saya. Perkara audisi peran dan sejenisnya ... bisa dipikirkan lokasinya.”
“Kita tetap butuh panggung.” Nova mengeyel. “Apa arti teater tanpa panggung?”
Keempat anggota lain menggumamkan persetujuan.
“Bukannya Bapak punya pinjaman kunci?”
“Sudah saya kembalikan.”
“Nggak ada cadangan?”
Sastra terperangah. “Kenapa perlu—“
“Ayolah, Pak.” Nova mendesak. Ada kilatan semangat di matanya. “Pinjam lagi, duplikat kunci auditorium! Kita audisi diam-diam di sini waktu lagi sepi. Kan, Bapak punya privilej!”
Sastra memelotot kepada Nova saat mengatakan kalimat terakhir. “Nggak ada privilej. Semua guru sama aja.”
“Tapi buktinya—“
“Sssh.” Sastra mengangkat tangan. “Oke, oke, saya usahakan dulu. Tapi, saya nggak janji! Dan, untuk pertemuan besok, kita adakan di rumah saya. Mengerti?”
**
Keesokan harinya, pada Selasa sore yang mendung seperti biasa, kelima anak Layar Surya menyelinap ke kediaman Sastra. Kebetulan rumah beliau tak jauh. Terletak di belakang sekolah, rumah Sastra tampaknya masih termasuk dari komplek bangunan di zaman penjajahan Belanda dulu. Modelnya serupa, aroma tuanya senada. Kata Kaspian, rumah Sastra memang pernah jadi rumah dinas pejabat sekolah sebelum dijual, dan dibeli olehnya.
Sayangnya, rumput-rumput liar bertumbuh setinggi betis anak-anak, dan potongan-potongan triplek serta gabus berserakan di pojok jalan setapak. Halamannya yang luas teduh oleh bentangan kain PVC yang memuat promosi pentas teater Layar Surya dari beberapa tahun yang lalu, menaungi rongsokan yang mungkin saja masih bisa dipakai, termasuk sepeda tua, kursi yang satu kakinya patah, dan bantal-bantal berjamur. Terasnya, yang juga terdiri dari tegel kelabu dingin, disesaki oleh tumpukan balok-balok gabus baru dan papan-papan triplek besar.
Pada kekacauan itu, sesemakan bunga mawar dan kembang sepatu rupanya masih mencoba untuk tumbuh, walau rupanya terlanjur kerdil. Atau begitu, yang Daru katakan.
Cowok itu menyentuh kelopak mawar yang tumbuh dengan enggan. “Aduh, ini kurang nutrisi,” keluhnya. Saat Sastra membuka pintu dan muncul, ia berseru, “Pak! Mawarnya saya rawat, plis! Sayang banget ini musim hujan malah kayak gini!”
Itu bahkan bukan penawaran. Sastra meringis mendengar Daru mulai mengomel tentang pentingnya memilih pupuk yang tepat. Ia mengaku bahwa itu urusan tukang kebun yang disewanya, lantas teringat bahwa tukang kebun yang dimaksud sudah berbulan-bulan tak muncul lagi. Daru mendengus sebal.
Sementara itu, Soya, Kaspian, dan Nova melipir ke balok-balok gabus yang baru. Mereka menyeretnya ke sisi teras yang lebih lapang dan kosong. Juni merapikan naskah drama Cindelaras yang telah mereka susun selama pekan terakhir liburan di laptopnya. Gerimis meluncur malas dari langit.
Saat Sastra memasukkan kaset koleksi lagu Vina Panduwinata di radionya, memainkan lagu “Kumpul Bocah”, kelima remaja itu spontan tertawa.
“Yang bener aja, Pak!”
Sastra meringis. “Loh, kenapa? Saya dan teman-teman saya dulu senam pakai lagu ini sebelum mulai latihan.”
Kaspian menggeleng dengan senyum di bibir. “Biarin aja om-om ini nostalgia,” katanya. Ia menyeret lembaran triplek ke arah Soya dan Nova yang sedang membicarakan detail properti. “Gimana, guys?”
“Kemarin tuh rencananya butuh tiga pohon, tujuh batu berbagai ukuran, latar bergambar dinding gubuk di hutan, dan dinding ala kerajaan, trus ....”
Nova melipat tangan, otomatis menghentikan penjelasan Soya. “Bentar, deh. Kayaknya tujuh batu tuh kebanyakan, dan tiga pohon? Dua aja kayaknya cukup.”
“Ya, gimana mau gambarin suasana hutan kalau cuma dua pohon?” Kaspian memutar bola mata.
“Tripleknya banyak! Tambah aja latar lukis. Gambar hutan.”
“Heh, kamu kira ada yang pandai melukis di antara kita? Makan waktu banyak!”
“Kamu kira bikin pohon nggak ribet?!”
“Emang kamu maunya pohon bentuk gimana?!”
Soya menghela napas. Kini, ia sudah biasa terimpit di antara perdebatan sang ketua dan wakilnya, masing-masing memiliki pengalaman berbeda di dunia sandiwara.
“Guys ....”
“Jangan sampai kamu mikir pohon yang daunnya cuma bulat-bulat dan ditempel itu, ya!” Nova mengabaikan Soya. “Nggak bakal menang kalau props-nya gitu doang!”
“Nov, bentar—“
“Siapa yang mikir gitu?! Kita bikin semua helai daunnya dari kertas! Kamu kira aku nggak ngerti tata panggung?”
“Emang! Kamu kan cuma aktor cetakan!”
Daru dan Sastra, yang sibuk membicarakan cara merawat mawar di bawah kanopi banner, dan Juni yang sibuk menggumamkan lagu, refleks menutup mulut dan berputar ke arah perdebatan.
Mata Kaspian membulat. Wajahnya memerah padam. Tangannya mengepal. Baru saja ia mengambil langkah maju—memantik seruan dari Sastra—ketika Soya tiba-tiba membanting buku yang dibawanya.
“UDAH!” pekiknya. “Aku yang ngurus tata artistik! Jangan ... jangan debat sendiri!”
Ini bukan kali pertama Soya mengejutkan semua, tetapi baru ini Sastra menyaksikan murid yang satu itu membuat semuanya terdiam. Sastra tersenyum kecil.
Soya ikutan beranjak. Ia menuding buku, gabus, dan triplek bergantian. “Jangan ribut sendiri!” serunya, meski kini nadanya kembali terbata-bata, tetapi ada amarah di sana. Matanya berair. “Dikit-dikit debat, dikit-dikit tengkar! Diomongin baik-baik apa salahnya, sih!”
Kaspian menelan ludah, sementara Nova mengembuskan napas panjang. Cowok itu yang pertama kali bereaksi. Tangannya yang mengepal kini melonggar, dan ia mengusap wajah.
“Udah, udah. Duduk semuanya.” Juni melenggang dengan laptop di tangan. Ia memasuki lingkar ketegangan itu dengan senyum lebar. “Soya bener, loh. Yuk, kita obrolin lagi enaknya gimana. Kas, duduk sini!”
Kaspian mendesah. Ia tak menolak saat ditarik Juni untuk duduk di sampingnya.
Soya pun kembali ke posisi duduk semula. Dadanya berdebar-debar keras. Rasanya seperti melihat kedua orang tuanya berdebat, bedanya Soya merasa bisa bersuara kali ini.
Nova mengawasi Soya dalam diam, lantas merogoh botol berisi air mineral utuh dari tasnya sendiri. Ia menyodorkannya kepada cewek itu. “Sori,” katanya. “Kebiasaan.”
Soya hanya mengangguk saat menerima sodoran botol air. Tangannya gemetaran.
Lupakan soal properti asal-asalan atau bukan. Bagaimana mereka bisa memenangkan lomba kalau perdebatan selalu meletus di antara anggota yang cuma berlima ini?


 andywylan
andywylan

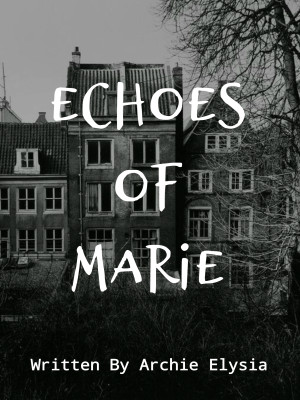








Haruskah kita bertemu lagi dengan efis---
Comment on chapter Prolog: Ambang Batas