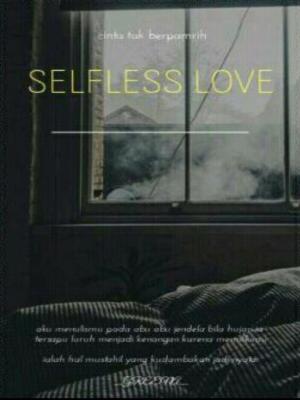Teori atom Dalton dengan model bola pejal. Teori atom J.J Thomson dengan model roti kismis. Terakhir adalah teori atom milik Rutherford dan Niels Bohr dengan model tata surya.
Kalimat itu masih bisa dipahami dan mudah dihafal. Sementara itu konfigurasi elektron? Rumit. Hilang minat Azro melihat berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan konfigurasi elektron. Menurutnya sia-sia semalaman menghafal, paginya ambyar dan soal yang keluar pun ikut ambyar alias berbeda dari kisi-kisi yang diberikan. Double Kill.
Lima belas menit menuju ulangan harian Kimia, kertas ringkasan materi dari Mia dilipatnya menjadi sebuah bentuk kapal. Azro mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, semuanya sibuk menghafal, membaca, dan saling tanya jawab untuk persiapan ulangan harian nanti saat jam terakhir. Seolah udara panas siang ini sama sekali bukan halangan. Ulangan kimia benar-benar mengubah kepribadian teman-temannya.
Azro menghela napas panjang untuk yang ke sekian kali. Tangan kanannya sibuk menjalankan kapal kertasnya di atas meja, membiarkannya mengapung secara imajiner di lautan ketegangan ruang kelas X IPA 1. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti dari ulangan harian Kimia yang diampu Bu Nike, hanya saja waktu yang diberikan sangat singkat. Tiga puluh menit. Bagi Azro waktu segitu tidak cukup untuk mengerjakan soal kimia yang masih sulit dia pahami.
Di sampingnya, Mia terlihat masih fokus membaca catatannya. Sesekali juga menandai beberapa kalimat dengan stabilo kuning. Mata sipitnya menyapu kalimat demi kalimat seperti mesin pemindai.
Mia tahu ini hanya ulangan biasa, tapi baginya tidak pernah ada yang “biasa” dalam dunia nilai. Bahkan satu angka yang tertinggal bisa menggoyahkan peringkat. Dan ketika peringkatnya goyah, posisinya dalam keluarga pun ikut runtuh.
“Ranking satu itu tanggung jawab,” kata Mama beberapa malam lalu.
Kalimat itu seperti doktrin bagi Mia. Karena itu ia tidak boleh kalah. Bukan hanya dari teman-teman sekelasnya, tapi juga dari kakaknya—Azam. Putra kebanggaan keluarga yang kemarin malam kembali menorehkan kesuksesan—diterima fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Mengingat itu membuat Mia kesal.
“Eh, Mia,” suara Tara memecah lamunannya. “Kok kamu bacanya sampe bab 2, sih?” tanya gadis itu tidak sengaja melihat catatan Mia.
Mia menoleh dan menjawab, “Ya emang kenapa? Enggak ada yang larang, kok.”
Tara mendengus kemudian berbalik kembali ke tempat duduknya di barisan belakang. Sementara itu, Azro yang duduk di samping Mia masih menatap kapal kertasnya dengan tatapan malas.
“Andai kita bisa tukeran otak, kali ini aja aku mau pinjem otak kamu, Mi, “ celoteh Azro.
Mie tersenyum geli, “kalo pun bisa, enggak akan aku pinjemin.”
“Pelit!”
“Kan kamu tahu sendiri, Ro. Nasibku bakal seperti apa kalo nilai-nilaiku turun.”
Azro mendecak. Bercanda dengan Mia memang jarang menyenangkan. Salahnya juga membuat nilai menjadi bahan guyonan. Mia sang pemuja nilai tentu sangat keberatan.
Lima belas menit yang diberikan Bu Nike selesai. Suasana kelas seketika berubah. Semua kembali ke tempat masing-masing. Kertas-kertas dilipat, buku-buku disembunyikan ketika Bu Nike memasuki kelas dengan wajah semringah.
“Selamat siang!” sapa Bu Nike ceria sambil meletakkan tasnya di atas meja guru.
“Siang, Bu...” jawab seisi kelas.
Guru Kimia itu berjalan ke depan papan tulis. “Sudah siap?” tanyanya dengan lembar soal di tangan.
“Siap...”
Nada lesu dan pasrah yang terpancar dari beberapa siswa membuat Bu Kartika tersenyum maklum. Jam menunjukkan pukul dua lewat lima belas menit. Udara kelas terasa pengap meski jendela-jendela sudah dibiarkan terbuka lebar. Ketegangan di kelas itu seolah membuat angin enggan untuk mampir. Kipas langit-langit hanya berputar malas, seolah ikut lesu bersama murid-murid X IPA 1.
“Seperti yang Ibu umumkan kemarin, siang ini kita mulai dengan ulangan harian Kimia dulu, ya, sebelum pulang,” kata Bu Kartika sambil menghitung lembar soal di genggaman.
Beberapa suara mengeluh lirih. Mia menyeka pelipisnya yang mulai basah oleh keringat. Sementara itu Azro memejamkan mata dengan kepala di tundukkan. Kedua tangannya terangkat ke depan dada seperti sedang berdoa.
Mia menyikut lengan Azro. “Tumben doa,” ujarnya.
Azro berbisik, “Iya doa supaya ada angin puyuh yang menyapu semua lembar soal itu.”
“Hush! Jelek banget doanya.”
Azro hanya membalas dengan cengiran lebar.
“Ambil satu, oper ke belakang,” perintah Bu Nike.
Mia menerima kertasnya dan langsung menunduk fokus. Tidak peduli dengan terik matahari yang menelusup lewat kaca jendela yang terbuka lebar. Lembar soal itu berisi lima pertanyaan esai dengan tiga sub-soal pada nomer 5.
Soal pertama: Menuliskan konfigurasi elektron dari Argon, Neon dan Kripton
Mia tersenyum tipis. Tidak terlalu sulit seperti ekspektasi Azro. Ia langsung mulai menulis jawaban dengan cepat dan santai. Deretan angka seperti 2-8-8-2 meluncur mulus dari ujung pensilnya.
Di sampingnya, Azro mendesah panjang. Kertas soal tampak seperti puzzle tak bermakna. Pensilnya berputar-putar di tangan, belum menyentuh kertas sama sekali. Pandangannya sesekali terarah ke luar jendela, berharap ada keajaiban—seperti lembar jawaban yang terbang sendiri ke mejanya atau serangan zombie seperti di film. Apa pun yang bisa membuatnya cepat melewati waktu yang sekarang. Tapi yang datang justru sinar matahari yang kian menyengat kulit wajahnya. Keringat mengalir di pelipis, dan suara kipas langit-langit yang berderit tak henti justru menambah panas suasana.
Suasana kelas 10 IPA-1 hampir senyap. Suara gesekan pensil, penghapus, pulpen dan detak jam membentuk simfoni ketegangan. Beberapa siswa terlihat menggigit ujung pena, sementara yang lain menengadah sesaat, mencoba mengingat hafalan terakhir sebelum menuliskannya di kertas.
Tara, dari baris belakang, bahkan sesekali mengipas wajahnya dengan buku catatan. Meski waktu terus berjalan, tak satu pun dari mereka berani melirik jam dinding karena hanya akan membuat panik.
Dalam sekejap Mia sudah sampai pada soal nomer 3. Gadis bermata sipit itu tidak peduli dengan lengketnya lengan yang berkeringat akibat gesekan meja dan udara panas. Baginya, waktu tiga puluh menit adalah ajang pembuktian—bahwa kerja keras semalam tidak sia-sia.
Ketika lonceng tanda akhir jam berbunyi, kelegaan menyebar ke seisi kelas. Beberapa menarik napas lega, lainnya hanya bersandar lemas di kursi.
“Waktu habis! Kumpulkan ke depan sekarang!”
Mia bangkit, menyeka peluh dengan tangan sebelum melangkah. Azro menyusul dengan wajah pasrah dan baju seragam yang mulai melekat di punggungnya karena keringat.
“Yoksi, Peringkat satu emang beda—penuh dan niat banget jawabnya,” gumam Azro sambil melirik lembar jawaban Mia yang penuh.
“Ya iyalah. Ulangan harian kayak gini kan bisa ngaruh ke nilai akhir,” jawab Mia cepat, menyerahkan kertasnya ke meja Bu Nike.
Azro mendengus, lalu meletakkan kertasnya yang hanya terisi separuh. “Aku sih yang penting nyerahin. Hasilnya urusan nanti.”
Mia memutar bola mata. “Makanya, ranking kamu segitu-segitu aja, Ro.”
“Biarin. Daripada maksa banget buat belajar, kayak dunia bakal runtuh aja kalau kelewatan belajar sehari,” balas Azro.
Mia menoleh tajam. “Buat kamu mungkin enggak penting. Tapi buat aku, rangking itu bukti. Kalau aku berhenti berusaha, enggak akan ada yang liat aku.”
Azro tidak langsung menjawab. Dia tahu benar apa yang menjadikan sahabatnya seperti itu. Tatapannya bergeser ke jendela. Langit siang itu biru cerah tanpa sedikit pun gugusan awan.
“Jujur, kamu ngerasa capek enggak, sih?”
“Tentang?”
“Belajar.”
“Capek, lah.”
“Terus kenapa enggak istirahat sebentar aja? Otak juga perlu santai, Mi.”
Mia diam sejenak. “Karena kalau aku istirahat, nanti ada yang nyalip. Dan aku enggak mau itu, cukup kak Azam aja,” jelasnya.
Azro tertawa pelan. “Tahu enggak? Kamu, tuh kayak elektron yang muter terus keliling inti atom, enggak pernah istirahat.”
Mia mengangkat alis. “Daripada jadi elektron valensi yang lepas enggak tentu arah, kan?” balasnya.
Mereka tertawa pelan menyadari percakapan barusan. Mia yang selalu serius harus selalu menghadapi Azro yang menganut sistem hidup santai dan mengikuti arus. Mungkin itu alasan mereka bisa jadi sahabat: karena mereka berjalan di dua garis orbit yang berbeda.
Gerbang sekolah sudah ramai oleh lalu lalang siswa yang menunggu sembari membeli jajanan dari pedagang kaki lima yang berjajar rapi di tepi jalan pintu keluar sekolah. Matahari masih menyengat.
“Aku jalan kaki aja, Ro,” kata Mia sambil menyesuaikan tali tasnya.
Azro menyamakan langkah, kemudian menjawab, “Yakin? Panas banget, loh. Bareng aja. Kali ini Tanteku bawa mobil jadi aman.”
“Oke, deh kalo kamu maksa, hehe.”
Baru beberapa langkah keluar gerbang, suara tawa nyaring memecah udara. Astiya dan Tara berdiri di dekat gerobak cilok, dengan seragam yang dikenakan dengan gaya urakan—kemeja yang di masukan sebelah, kerudung di lilitkan ke leher dan lengan kemeja yang di gulung hingga siku.
“Eh, anak peringkat satu lewat,” ujar Tara setengah berteriak begitu Mia dan Azro melewatinya.
Mia menghela napas, mencoba abai.
Astiya melipat tangan di dada. “Haus validasi banget sampe baca bab 2, Bu Nike juga belum jelasin.”
Azro mendekat sedikit ke sisi Mia. “Udahlah, Tiya. Panas-panas gini jangan mancing masalah. Yang penting enggak nyontek, kan?”
Tawa kecil muncul dari Tara. “Ih, siapa juga yang nyontek. Kita enggak segila itu ngejar nilai kali. Bedalah sama yang hidupnya cuma buat ngejar ranking satu.”
Mia berhenti, menghela napas panjang—meredam kekesalan.
“Enggak usah komentari hidup orang lain, urus aja tuh kemejamu yang belepotan saus!”
Astiya tersenyum sinis. “Kamu pikir semua bisa kamu atur kayak soal matematika?” ketusnya sembari mengusap bekas saus di kemeja.
Mia tak menjawab. Ia memilih melangkah pergi. Di belakangnya, Azro mengikuti dengan diam.
Beberapa meter kemudian, Azro bersuara, “Kamu enggak marah?”
“Hampir.”
“Lah, harusnya lempar aja tas tadi,”
Mia tersenyum kecil. “Aku enggak mau buang energi buat orang yang enggak ngasih aku nilai.”
“Nilai terus,” seloroh Azro diakhiri dengan kikikan kecil.
“Karena kalau enggak mikir kayak gitu, aku...”
Azro menutup mulut Mia sambil menganggukkan kepala tanda bahwa dia sudah tahu alasannya. Tidak perlu dijawab lagi.
***
Pukul setengah lima sore Mia baru sampai di depan gerbang rumahnya. Pagar hitam tua itu sedikit berdecit saat ia membukanya. Setelah melewati ruang tamu yang kosong, Mia lanjut menaiki tangga menuju lantai dua—tempat kamarnya berada.
Sesampainya di kamar, Mia langsung melompat ke atas ranjang. Rasanya lega begitu punggungnya menyentuh lembutnya seprei. Dinding kamar Mia adalah peta mimpi yang ditata rapi. Di atas meja belajar, terdapat menara buku tebal—modul UTBK, soal latihan, dan kumpulan kisi-kisi olimpiade—berdiri berjajar. Di sisi kiri meja, menempel cetakan besar logo ITB dengan tulisan spidol biru: “Target: FTMD ITB.”
Di samping tempat tidur, ada rak kecil yang penuh dengan sticky notes berwarna: rumus cepat, target hafalan, kutipan motivasi, hingga foto bangunan kampus ITB yang pernah ia cetak dari internet. Di langit-langit kamar, Mia menempelkan bintang-bintang glow in the dark, hadiah dari Azro waktu ulang tahunnya—sebagai pengingat bahwa setiap mimpi perlu penerangan, walau sekadar cahaya kecil di gelap malam.
Ia menarik napas panjang, mengubah posisi menjadi duduk, lalu mengamati ruangan 3x3 meter itu dengan angan-angan tentang dirinya yang berdiri di dalam hanggar pesawat.
Lamunannya buyar ketika Mama membuka pintu kamarnya.
“Mama sama Papa mau anter Kak Azam ke kosan. Lusa kan udah mulai orientasi. Jadi kita nginep duluan di sana.” Suara Mama terdengar biasa saja, seperti mengumumkan hal sepele.
“Terus... aku sendiri di rumah?” tanya Mia pelan.
Mama mengangguk tanpa menoleh, tangannya sibuk menekan layar ponsel yang sejak tadi berdering. “Iya, cuma dua malam kok. Di kulkas Mama udah siapin makanan, ada sarden sama selada. Maaf ya, Mama enggak sempat belanja. Tadi buru-buru packing barang-barangnya Kak Azam.”
Mia terdiam. Ada jeda hening yang menggantung di antara mereka.
“Ya udah, Mama pamit. Jangan lupa belajar.”
Mendengar kalimat terakhir itu membuat Mia mendengus. Pintu kamar kembali menutup pelan, menyisakan udara tipis yang entah kenapa mendadak terasa lebih dingin.
Mia menatap pintu yang sudah tertutup. Matanya tidak berkedip, hanya diam sambil menggigit bibir bawah. Di rumah ini, urusan Azam selalu nomor satu. Segala hal yang menyangkut anak sulung itu, selalu diprioritaskan. Dan dirinya? Selalu jadi opsi terakhir. Mia sadar dirinya hanya sebuah orbit kecil yang melingkari pusat yang sama, tapi tak pernah cukup terang untuk diperhatikan.
Ia bangkit dari tempat tidur dengan helaan napas berat. Mia memutuskan untuk mandi sebelum kembali ke meja belajarnya, membuka modul Kimia, dan mulai menulis ulang catatan untuk besok. Satu halaman, dua halaman, hingga larut malam.
Di luar kamar, suara malam mulai terdengar. Jam dinding berdetak lambat, sementara bintang-bintang kecil di langit-langit kamarnya mulai menyala redup. Mia masih terus membalik halaman buku modul—mencoba mengalihkan kesedihannya.


 manusiatepisungai
manusiatepisungai